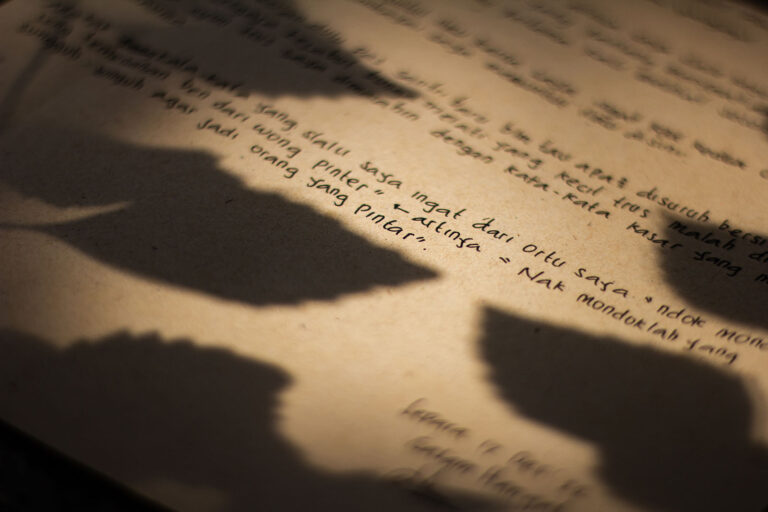Kampung Jejangkit di Kalimantan Selatan tak lagi terkenal dengan kayu putihnya. Jejangkit jadi lebih sering terendam banjir. Kekayaan ekologis hilang, berganti belantara sawit dan bau limbah yang mencemari sungai warga.
EFFENDI sibuk memandangi tanaman padi miliknya yang mulai menguning, Minggu (30/7) siang. Wajahnya semringah. Sebentar lagi, petani berusia 43 tahun itu akan panen dari lahan seluas satu hektare itu.
Ini momen membahagiakan baginya usai beberapa tahun terakhir, sawahnya gagal panen. “Sebenarnya coba-coba aja. Kada kawa behuma (sudah tidak bertani) bertahun-tahun. Jadi tahun ini mulai lagi sedikit-sedikit,” katanya.
Effendi tinggal di Desa Jejangkit Timur, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tanah di kampungnya terkenal subur. Tahun 2018, pemerintah sempat menjadikan kampungnya sebagai tempat pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS).
Sekitar 4.000 hektare lahan rawa disiapkan Kementerian Pertanian dalam Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi), pasca-kegiatan HPS itu.
Namun, tiga tahun terakhir, petani setempat mengalami gagal panen karena banjir yang tak lazim. “Cuma daerah sini yang banjir, kalau ke kecamatan sebelah, kering. Nggak ada apa-apa,” kata Effendi.
Selama periode itu, saban puncak musim hujan tiba, banjir merendam kawasan sawah di Jejangkit dengan durasi dua sampai empat bulan lamanya. Dari Januari hingga April.
Ada tujuh desa yang terdampak: Jejangkit Muara, Jejangkit Pasar, Jejangkit Barat, Jejangkit Timur, Bahandang, Cahaya Baru dan Sampurna. Selain sawah warga, rumah dan fasilitas umum di kawasan perkampungan turut terendam.
Warga awalnya mengira bencana terjadi karena efek panjang dari banjir bandang di Kalsel pada 2021. Kala itu, hampir 13 kabupaten/kota di Kalsel terendam. Jejangkit termasuk wilayah yang terdampak parah banjir karena posisinya berada di kawasan hilir dan tampungan air.
Namun, setelah ditelisik lebih dalam, kemalangan diduga muncul karena drainase yang penuh dengan air buangan dari perusahaan sawit di dekat perkampungan.
Sungai Berbusa dan Hilangnya Kayu Primadona
Selama sekitar satu dekade terakhir, Amat merasa kehidupannya jauh lebih sulit. Demi mencari uang Rp100 ribu sehari saja, nelayan sungai di Jejangkit itu harus pergi sejauh 15 kilometer untuk sampai ke danau tempat ia sehari-hari mencari ikan.
Alih-alih menggunakan perahu mesin seperti nelayan pada umumnya, lelaki berumur 53 tahun ini bekerja dengan mengandalkan motor bebek yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
Setiap hari, ia mesti melewati jalan setapak dan menerobos belantara sawit agar sampai ke danau pemancingan yang lokasinya berada di Kabupaten Banjar, wilayah tetangga.
Di danau yang merupakan kolam bekas perusahaan sawit inilah Amat menggantungkan harapan mencari ikan meski hasilnya tak seberapa.
“Hari ini cuma dapat lima kilo,” katanya sembari memperlihatkan hasil tangkapan ikan gabusnya yang tersimpan di dalam bak.
Setelah dapat ikan, ia harus kembali ke Jejangkit untuk menjual hasil tangkapan ke pengepul dengan harga berkisar Rp20 ribu per kilogram (kg). Dengan kata lain, ia perlu menyisihkan sebagian hasil jual ikannya untuk ongkos pulang pergi.
Semestinya, ia tak perlu kerepotan bekerja sampai keluar desa kalau kondisi kampungnya masih sama seperti yang dulu.
Sebelum ada perusahaan sawit, sungai utama di Jejangkit jernih. Masyarakat setempat dapat mengandalkan air sungai untuk kebutuhan mandi, mencuci, bahkan bisa diminum.

Dulu, Amat dapat hidup lebih dari cukup. Dalam satu hari, ia bisa memperoleh tangkapan hingga 15 kilogram (kg) untuk ikan jenis gabus, sepat, dan papuyu. Hasil tangkapannya itu rata-rata seharga Rp7.500-8.000 per kg.
Masa-masa kejayaan para nelayan terjadi pada tahun 1980 sampai menjelang tahun 2000. Ketika masyarakat setempat masih menggunakan sampan untuk berburu ikan.
Akan tetapi, sejak kehadiran perusahaan sawit, air sungai tak lagi jernih. Airnya berwarna coklat, asam, dan kerap berbusa. Ikan tak tampak, pendapatan merosot.
***
Nasib serupa juga dijalani Anang Aini, warga Jejangkit Timur, yang semasa hidupnya menggantungkan hidup dari usaha jual beli pohon gelam atau kayu putih (Melaleuca cajuputi).
Hutan gelam tumbuh subur di sekitar rawa gambut di Jejangkit Timur. Wilayah ini adalah salah satu wilayah penghasil gelam yang tokcer di wilayah Barito Kuala, selain wilayah tetangga seperti Mandastana.
Bagi masyarakat di sana, gelam adalah primadona. Komoditas rawa gambut ini laku keras dijual karena bisa dipakai untuk keperluan tiang pancang perumahan masyarakat kota yang mayoritas dibangun di atas lahan rawa.
Kayu ini juga bisa bertahan hingga puluhan tahun. Gelam juga tahan apabila dipakai untuk bangunan yang berdiri di atas lahan basah.
Anang mengatakan, sebelum negara sawit menyerang, ia bisa memperoleh lebih dari seratus batang gelam dalam satu hari. Setidaknya, pendidikan anak-anaknya terjamin karena usaha jual beli gelam.
“Walaupun hanya setingkat tsanawiyah (setara SMP), mereka akhirnya bisa tetap sekolah,” kata Anang.
Setiap hari perahu mesin hilir mudik mengangkut hasil dari hutan. Sebagian warga bahkan mendapat julukan juragan gelam karena kayu tersebut mudah dicari di kampung.
Seiring dengan alih fungsi lahan yang semakin masif, warga yang mau bekerja seperti Anang bisa dihitung jari. Bagi warga setempat, mencari galam kini adalah opsi.
“Empat puluh batang aja hari ini,” ujar laki-laki berusia 60 tahun itu.
Anang merasakan betul repotnya mencari gelam beberapa tahun terakhir. Saban hari, ia dan putra bungsunya harus berjibaku mencari kayu tersebut di sela-sela perkebunan PT Palmina Utama dan PT PBB.
“Kalau di dekat-dekat sini sudah nggak ada lagi. Jadi harus dua kilo bawa klotok,” katanya.
“Itu pun cuma ambil sisa-sisanya aja. Kayu yang bagus sudah habis.”

Menurutnya, hasil yang didapat hari itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu batang gelam berdiameter 2-3 cm hanya dihargai Rp1.500. Kalau berukuran lebih tinggi dan diameternya lebih besar, baru bisa dijual Rp 2-3 ribu.
Untuk membuat pendapatan terlihat banyak, mereka biasanya menumpuk kayu-kayu di pinggir jalan desa. Kalau jumlahnya sudah sampai 100-200 batang, baru pengepul dari kota akan mengambilnya. Biasanya, pengepul baru akan mengambil setiap dua sampai tiga hari sekali.
Lantaran kualitas kayu juga menyusut, menjadi berukuran kecil, umumnya mereka hanya mendapat pendapatan berkisar Rp100 ribu.
“Itu belum potong bensin dua liter sama bekal. Mencari duit Rp50 ribu aja sekarang susah,” kata Anang.
Tanah Tali Asih
PT Palmina Utama dan PT Putra Bangun Bersama (PBB) adalah dua korporasi yang menjadi biang dari serentetan kemalangan warga di Jejangkit Timur.
Kedua korporasi ini berada di bawah naungan Julong Group Indonesia, perusahaan multinasional asal Cina di bawah induk usaha Tianjin Julong Group.
PBB lebih dulu beroperasi di Jejangkit dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Batola pada tahun 2006. Menyusul satu tahun kemudian PT Palmina. Bila diakumulasi, lahan mereka mencapai 25 ribu hektare.
Sanusi, tetua kampung di Jejangkit, bercerita bercerita bahwa Julong Group datang ke kampungnya tanpa proses jual beli lahan yang merata. Saat merintis lokasi perkebunan sebelum 2006, ia bilang perusahaan hanya mengganti lahan milik warga dengan “tali asih.”
Seingatnya, besaran uang yang diberi PT Palmina Utama hanya Rp25 ribu per borongan. “Itu kada merata jua (itu juga tidak merata). Sebagian aja,” tutur Sanusi.
Sebagai kompensasi, Julong Group menjanjikan kebun plasma kepada masyarakat. Satu keluarga diberi dua hektare.
Sanusi merupakan salah satu warga yang sepakat dengan perjanjian tersebut. Ia menyebut janji perusahaan, “ada dokumen hitam di atas putihnya.”
Mulanya, khusus warga Jejangkit Timur, yang wilayahnya berada dekat dengan perkebunan, meminta kebun plasma seluas 1.500 hektare ke perusahaan.
Namun, PT Palmina hanya bisa menyanggupi lahan plasma seluas 700 hektare. “Iming-imingnya seperti itu. Dapat plasma. Jalan desa, ujarnya, kami bantu. Sekalinya dikaramputinya (dibohonginya) semua,” katanya.

Sanusi merasa dibohongi ketika perusahaan melarang masyarakat menggarap kebun plasma yang sejatinya merupakan hak mereka. Di lokasi perusahaan, ada plang dipasang yang intinya melarang warga untuk menggarap lahan HGU Palmina.
“Perusahaan justru meminta kami untuk menukari (membeli) lahan di tempat lain,” katanya.
Padahal, Sanusi ingat sekali kawasan kantor utama PT Palmina Utama dan perkebunan sawit dulunya merupakan wilayah sawah warga di Jejangkit Timur. “2002 dan 2004 itu panen raya kita. Ramai sekali. Satu petani itu bisa ada 5 ribu blek dapat berasnya,” ujarnya.
Jengah melihat janji yang tidak ditepati, Sanusi menggugat PT Palmina Utama dan PT PBB ke meja hijau selama tiga tahun terakhir. Ada 175 hektare lahan yang dituntut oleh Sanusi dan kawan-kawan.
“Awalnya di tingkat provinsi, kita menang. Dua puluh delapan kali sidang dan kami menang. Sekarang banding di Jakarta,” ujarnya.
Bau Busuk Dari Parit-Parit Perkebunan
Banjir dan curah hujan tinggi pada tahun 2021, ikut merendam habis perkebunan sawit perusahaan. Kedua perusahaan kemudian membangun pompa untuk mengalirkan air banjir. Seorang warga yang dekat dengan perkebunan mengatakan ada sekitar 100 unit di sekitar area perkebunan.
Untuk menjaga perkebunan sawit tetap beroperasi normal, kondisi air di wilayah perusahaan memang harus seimbang: tidak boleh surut, dan tidak boleh juga terlalu dalam.
Kendati demikian, masalah muncul ketika bukan hanya air limpasan yang keluar dan membanjiri permukiman. Limbah buangan hasil pengolahan sawit juga mengalir melalui pipa-pipa tersebut.
Kami sempat mengecek instalasi pengolahan limbah di belakang pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) PT Palmina Utama.
Alih-alih terjaga di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), limbah yang berasal dari pengolahan minyak mentah sawit itu justru meluber dari kolam hingga ke parit-parit perkebunan. Mengeluarkan bau yang begitu menusuk hidung.

Belum ada hasil uji laboratorium dari pemerintah daerah mengenai dugaan pencemaran sungai di Jejangkit. Namun, seorang warga menuturkan bahwa parit yang dekat sekali dengan kolam pengolahan limbah itu juga terkoneksi dengan sejumlah unit pompa.
Air limpasan berbarengan limbah juga mengalir ke saluran irigasi pertanian dan sungai utama di Jejangkit dan sekitarnya.
Kondisi ini memicu protes warga. Warga berjejaring membentuk gerakan bersama, bertajuk Tabuan, yang berarti tawon atau lebah.
“Seperti namanya, kalau diusik, maka kami pasti menyengat seperti tabuan,” kata Udin, salah satu perwakilan warga.
Sengatan Tabuan
Sejak awal 2023, warga yang tergabung dalam Tabuan melakukan aksi protes, termasuk audiensi bersama pemerintah daerah dan Julong Group.
Tuntutan mereka sederhana: hentikan aktivitas pompa dan buka saluran irigasi yang mengarah ke Sungai Barito, yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Selatan. Mereka juga mendesak Julong Group bertanggung jawab atas rusaknya sawah dan permukiman.
Selama ini, saluran ke Sungai Barito tertutup permukiman warga di desa lain. Masyarakat di wilayah tetangga juga menolak mereka mendapat buangan air sawit. “Jadi airnya tertahan di kampung kami,” ujar Udin.
Selama Maret-Mei 2023, Tabuan juga menemui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan, DPRD Kalsel, hingga untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Pertemuan demi pertemuan itu berbuah kesepakatan yang intinya mewajibkan Julong menyetop sementara aktivitas pembuangan air sawit sampai mereka membuat kajian teknis terkait kegiatan tersebut.
Di sisi lain, penyidik dari Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan juga mencium indikasi pelanggaran hukum dari aktivitas yang dilakukan perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan mereka pada awal tahun.
Penyidik BWS menduga perusahaan telah merusak saluran irigasi di Jejangkit dan mengaliri air perkebunan ke handil.
Perusahaan kemudian dianggap melanggar dua pasal Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Pertama, pasal 68 huruf a yang berbunyi barang siapa melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air prasarananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun.
Pihak yang dijerat pasal ini juga didenda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar rupiah.
Kedua, perusahaan dijerat pasal 70 huruf c yang berbunyi barang siapa melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun.
Adapun denda yang diberikan kepada pelanggar paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.
Walaupun demikian, BWS Kalimantan III hanya merekomendasikan agar perusahaan mengajukan izin pengusahaan sumber daya air dan mengembalikan kerusakan saluran seperti semula, alih-alih menitikberatkan proses hukum.
PT Palmina dan PT PBB lantas sepakat dengan rekomendasi yang diberikan oleh BWS. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki saluran yang telah dijebol dan menutup pompa.
Namun, fakta di lapangan menyodorkan cerita yang berbeda. Pemantauan kami pada Juli 2023, sejumlah outlet pompa masih dioperasikan oleh perusahaan.

Hingga September 2023, saluran irigasi pertanian yang sebelumnya sudah rusak juga belum sepenuhnya diperbaiki oleh dua anak perusahaan Julong Group itu. Kami juga telah menghubungi kedua perusahaan tetapi tidak mendapatkan jawaban.
Warga Jejangkit, khususnya para petani, harap-harap cemas menanti perbaikan saluran itu terealisasi. “Kalau belum, bisa kada bisa behuma lagi kita tahun depan,” kata Udin.
Bolong Kajian
Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan, mempertanyakan dasar perusahaan melakukan pompanisasi. Ia mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang dokumen AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) perusahaan.
“Seharusnya berdasarkan dokumen lingkungan. Salah satunya AMDAL. Di AMDAL-nya ada nggak? Makanya kami selalu mendesak agar ada tinjau ulang dokumen mereka,” kata Kis.
Kis juga mendorong masyarakat Jejangkit terus mengawal masalah pompanisasi karena telah merugikan warga itu. “Kami kemarin kalkulasi, total Rp78 miliar petani rugi karena tidak bisa bertani selama tiga tahun,” kata Kis.
Hitung-hitungan itu belum mencakup kerugian yang diterima warga yang dulunya bekerja sebagai nelayan sungai dan pencari gelam.
Adenansi, perwakilan Sawit Watch di Kalsel, meminta perusahaan menyelesaikan tanggung jawabnya merujuk pada hasil pemeriksaan yang dilakukan BWS Kalimantan III. “Tegakkan itu dulu. Baru kita bicara yang lain. Sampai sekarang kan masih mengambang,” katanya.
Pihak Sawit Watch, kata Adenansi, sampai sekarang juga belum mendapati dokumen lingkungan yang memperbolehkan Julong Group untuk membangun dan mengoperasikan pompa pembuangan air sawit ke permukiman warga.
Ia mengatakan, sedari awal, perusahaan semestinya tidak diberikan izin untuk mengalihfungsikan lahan gambut menjadi perkebunan sawit. Pasalnya, kawasan rawa gambut di Jejangkit juga berfungsi sebagai tempat penampungan air. Ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hulu di Pegunungan Meratus, air akan turun ke hilir, salah satunya ke Jejangkit.
“Salah mereka menjadikan kebun sawit. Bagaimanapun mereka mengelola, pasti akan tergenang,” katanya.

Soal dugaan adanya limbah yang ikut dibuang bersama air sawit melalui metode pompa, Adenansi belum bisa memastikan. Ia menyarankan agar para pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini agar melakukan uji laboratorium dari sungai yang diduga tercemar.
“Kita harus ke lab. Bisa saja itu tumpukan sawit yang terkena hujan dan gugur ke sungai. Biasanya kalau air limbah sawit itu bau, lalu berbuih dan ikan-ikan nggak bisa hidup,” katanya.
Bermalam, Bertahan, dan Berpasrah
Di tengah impitan sawit, warga tak bisa menyerah. Hidup tetap harus berlanjut. Bersiasat menjadi jalan satu-satunya.
“Sebelum ada sawit, cari duit lebih nyaman. Sekarang, di sungai memang masih ada ikan-ikannya. Tapi kecil-kecil. Nggak bisa dijual,” kata Amat.
Amat dan tetangganya, Syarkawi, bahkan rela bermalam di danau untuk mengincar tangkapan ikan yang lebih banyak. Lelaki 40 tahun yang sering dipanggil Awi itu memang punya badan yang masih bugar. Tubuhnya tahan jika harus bermalam agar memperoleh belasan hingga puluhan kilogram ikan gabus.
Awal Juli, Awi nekat menginap selama satu pekan untuk bisa membawa pulang lebih banyak tangkapan ikan di kolam tempat Amat mencari ikan. “Kurang lebih setengah bulan tadi, ada satu minggu bermalam di danau. Itu baru bisa dapat 30 kilo,” katanya.
Meski harus mengorbankan waktu untuk istri dan empat anaknya di rumah, ia merasa ini pilihan tepat ketimbang harus bertaruh mencari ikan seharian penuh dan hasilnya belum tentu maksimal.
“Kalau berangkat sehari lalu pulang, rugi ongkos. Bensin itu paling tidak dua liter. Yang didapat paling cuma tiga sampai lima kilo,” katanya.
Nelayan sungai seperti Amat dan Awi mau tidak mau bertahan dengan keseharian ini karena pilihan pekerjaan semakin terbatas.
“Mau ikut orang kerja di perusahaan sawit, kita nggak biasa. Saya yang tua ini nggak bakal diterima orang juga,” ujar Amat terkekeh.
Awi punya cerita lain. Karena usianya yang lebih muda, ia pernah mencoba peruntungan bekerja sebagai buruh harian di kebun sawit selama satu pekan. Tetapi, itu tidak berlangsung lama karena upahnya yang ia dapat tidak sepadan dengan pekerjaan.
Sementara itu, sejak sawahnya kebanjiran, Effendi bercerita bahwa kehidupannya memang terasa susah. Menanam padi adalah satu-satunya keahlian yang ia miliki, sementara lahannya tak bisa digarap.
“Simpanan (utang) di warung yang justru makin banyak,” kata Effendi terkekeh.
Banjir yang cukup lama juga membuat masa tanam padi di Jejangkit mengalami pergeseran. Biasanya, petani menanam padi pada sekitar bulan Februari, dan memanen pada Juni. Ketika banjir merendam desa, semuanya jadi kacau.
“Kadang bulan empat baru bisa menanam. Panennya di Agustus atau September,” kata Effendi.
Sekilas, ini masalah sepele. Akan tetapi, bergesernya masa tanam padi membuat sawah mereka rentan diserang hama. Alhasil, Effendi memutuskan tidak bertani selama tiga tahun ini karena khawatir terus-terusan merugi.

Kusairi, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Jejangkit, menyebut luas tanam padi di Jejangkit mengalami penyusutan yang signifikan.
Sebagai gambaran, pada 2020, luas tanam padi di Jejangkit berjumlah 2.768 hektare. “Namun, pada tahun 2021, menurun jadi 2.450 hektare dan 2022 turun ke 1.144 hektare,” kata Kusairi.
Kusairi tidak menampik menyusutnya luas tanam padi di Jejangkit karena banjir yang terus berulang tiap tahunnya.
Bersamaan dengan itu, lahan HPS yang sebelumnya dirancang untuk menyokong pertanian di Kalsel juga tak kunjung membuahkan hasil. Kawasan itu kini ditumbuhi rumput ilalang lantaran tak terurus.
Editor: Ronna Nirmala
Artikel ini menggunakan lisensi CC BY-NC-ND 4.0.