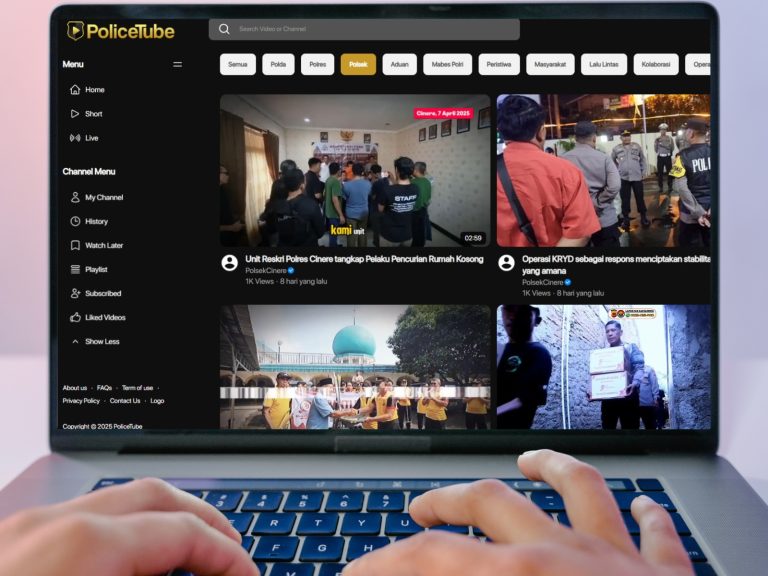DI ARAH barat matahari perlahan angslup, hari bakal menuju gelap. Pada 1 Oktober 2022, kamu masih berada di daerah Situbondo. Agendamu pada hari itu mengambil tebu dari seorang kawan lama. Bersama satu rombongan, kamu memuat puluhan ton tebu di punggung truk yang kamu kemudikan.
Setelah seluruh muatan dinaikan, kamu segera menginjak pedal gas dalam-dalam, memburu waktu agar tak melewatkan laga tim kebanggaanmu, Arema FC, yang tengah bertanding melawan musuh bebuyutan, Persebaya Surabaya.
Kemacetan membuyarkan rencanamu. Kamu hanya menyaksikan pertandingan itu dari gawai yang terpacak di dashboard. Wajahmu tertekuk masam setelah mendengar peluit panjang: Arema, tim kebangganmu, kembali menelan kekalahan; dan yang memalukan, tunduk dari si rival abadi di kandang sendiri.
Tetapi, ceritamu tak berhenti di sini.
Sebuah pesan singkat dari seorang kawan membuat hatimu khawatir. “Om, gak mrene, ta? Stadion lagi goyang.”
Orang-orang mengenalmu dengan nama Sam Devi atau Devi Athok. Kamu telah menjadi Aremania sejak sekolah dasar hingga sekarang usiamu sudah 43 tahun. Kerusuhan dan sepakbola adalah urusan biasa bagimu.
Tetapi, kali ini beda. Kawanmu bilang kekacauan ini tidak biasa. Polisi menembaki penonton dengan gas air mata. Lapangan kisruh. Di percakapan Grup WhatsApp, orang-orang mengutuki aparat.
Kamu bertanya, “Apa yang terjadi?”
Pesan itu tiba tatkala kamu sampai di rumah. Rencananya, kamu memarkir kendaraan lalu melepas lelah setelah seharian bekerja.
Sebelum sempat menjawab pesan dari kawanmu, ada sebuah pesan susulan. Seorang kawan baikmu, yang telah mengarungi perjalanan menjadi Aremania sejak belia, dikabarkan meninggal. Kamu mengetahuinya dari sebuah grup WhatsApp.
“Ojok guyon, rek! Sing temen kon, jancok! Ojok gawe guyonan nyowone uwong,” katamu dengan nada tinggi. Di kalangan suporter, kamu dikenal sebagai seorang pendiam tapi petarung.
“Sumpah, Om. Sam Nawi, gak onok umur,” kata salah satu juniormu.
Selepas memarkir truk, kamu segera meminta seorang tukang ojek pangkalan untuk mengantarmu menuju stadion Kanjuruhan. Jaraknya hanya 15 menit dari garasi pabrik.
Wajahmu tampak bingung di sepanjang perjalanan. Selama empat puluh tiga tahun hidup di kota yang sama, baru kali ini kamu menyaksikan wajah kotamu sedemikian teruk. Malang dalam waktu nisbi singkat, berubah bak palagan: korban-korban luka membawa dirinya sendiri dengan sepeda motor, beberapa di antaranya mengapit kawannya yang terkapar lemas berbonceng tiga. Kamu tak sadar, perlahan air mata meleleh di pipi.
Belum sempat menapakan kaki di area stadion, barisan aparat memblokade jalan. Meminta seluruh orang menjauhi stadion. Kamu terpaksa putar balik. Dari kejauhan, kamu melihat pendar api merah di sekitaran stadion. Hidungmu segera menghirup aroma sangit asap hitam.
Kamu teringat, tadi sore, si sulung berpamitan untuk menonton pertandingan bersama ibu, adik, dan bapak tirinya. Kamu segera ingin menelepon menanyakan kondisi mereka. Tatkala merogoh saku celana, kamu sadar ponselmu tertinggal di kursi kemudi truk. Kepanikanmu berlipat. Kamu berteriak kalang-kabut. Sopir ojek yang menemanimu berkali-kali memintamu sabar.
“Anakku, yo opo iki nasibe, Sam! Ayo wes ndang balik garasi, njupuk HP!”
Begitu sampai garasi pabrik, kamu segera melompat ke atas trukmu. Cepat-cepat kamu meraih ponsel lalu menelepon Tasya dan mantan istrimu, Gebby. Ketika membuka layar, kamu menerima banyak sekali notifikasi. Salah satunya panggilan tak terjawab dari Ubeth, kawan di Curvanord, kolektif suporter Aremania.
Ubeth kembali menelepon. Dengan suara terbata-bata, ia mengabarkan putrimu telah menjadi korban.
“Sam, aku nemu Tasya iki. Arek e gawe klambi Curvanord. Sam, sing sabar, anak sampean wes gak onok umur. Iki digowo nang RS Wava Husada, ditumpakno truk. Aku tak ngiringi nang Wava, yo.”
“Anakku! Anakku mati! Tasya. Ya Allah!”
Kamu meraung histeris. Kamu segera berlari dan melompat ke jok belakang motor orang asing yang kebetulan melintas, memintanya mengantarmu ke rumah.

Di sepanjang perjalanan, kamu memikirkan cara untuk mengatakan kepada bapakmu yang baru saja terserang penyakit stroke. Arloji menunjukan pukul 12 malam. Bapakmu adalah orang terakhir di rumah yang bertemu dengan kedua anakmu, Tasya dan Lala. Kamu ingat, sebelum berangkat ke Situbondo, bapakmu bercerita baru saja menjemput Lala dari sekolah. Bapakmu bercerita Lala begitu manja, meminta membawakan sepatunya, dan minta dicium berkali-kali.
Dengan sisa keberanian yang kamu punya, pelan-pelan kamu membangunkan bapak. Setengah berbisik, dengan air mata tak bisa lagi tertahan, bibirmu mengatakan: “Pak, Tasya, Pak, putumu [cucumu] mati, Pak!”
Kematian Tak Wajar: Jasad Membiru, Tubuh Penuh Luka
Di sepanjang perjalanan, kamu berkali-kali menampar wajahmu. Kamu berharap peristiwa ini mimpi belaka. Seorang anak yang telah kamu besarkan selama 16 tahun meninggalkanmu dalam sekejap. Tubuhmu terkulai lemas di dalam mobil yang membawamu menuju rumah sakit.
Dari percakapan grup WhatsApp, kamu menduga anakmu meninggal karena keracunan gas air mata. Orang-orang membagikan foto dan video yang merekam aksi brutal polisi menembaki tribun secara membabi buta dengan gas beracun. Kamu juga melihat polisi memukuli saudara-saudaramu tanpa ampun.
Kamu melompat dari mobil sebelum terparkir di halaman rumah sakit. Di hadapanmu, ada dua polisi berjaga-jaga. Kamu melayangkan bogem mentah ke arah mereka.
“Kalau waktu itu gak ketahuan anak-anak, sudah saya habisi mereka! Saya ini orangnya besar di jalanan. Cara saya menyelesaikan masalah adalah dengan cara jalanan.”
Di selasar rumah sakit, di parkiran, kamu melihat banyak tubuh terkulai. Kamu mengenal sebagian wajah mereka. Banyak di antaranya tampak membiru, sebagian lain meninggal dalam kondisi mata melotot. Ada ngeri berdesir di hatimu. Hingga kamu di kejauhan, kamu melihat kawan-kawanmu berdiri melingkar. Mereka tampak mengerubungi sesuatu.
Seseorang dengan wajah sembab berbalik arah dan memelukmu. Ia berbisik, memintamu untuk ikhlas dan sabar. Kamu melihat anakmu mengenakan kaos putih yang sudah kumal, meninggal dengan mulut menganga.
“Jancok!” kata itu kamu teriakan berulang-ulang. “Anakku! Anakku mati, cok! Sopo sing mateni anakku cok?”
Kamu tahu itu bukan mimpi. Kamu tahu yang tergolek di lantai dingin tanpa alas itu jasad putrimu, Natasya Debi Ramadhani. Kamu menyaksikan ada darah keluar dari hidung Tasya. Pelipisnya sobek. Ada cairan hijau keluar dari celah-celah bibirnya. Kamu meyakini anakmu mati karena menghirup gas racun. Sebab, selain di area kepalanya, tak ada luka lain di sekujur tubuh anakmu.
Belum tuntas berduka, kamu mendengar kakakmu memekik di belakangmu. Ia pingsan. Kamu menoleh. Kamu melihat putri bungsumu berumur 14 tahun, Naila Debi Anggraini atau Lala, juga terkapar. Bersanding di samping jasad ibunya, Gebby.
Kondisi Lala terlihat lebih parah dari Tasya. Wajahnya lebam sampai-sampai kamu sempat tak mengenalinya. Kamu tercekat. Kesulitan bernapas. Pandanganmu perlahan kabur. Kakimu kehilangan daya. Kamu tersungkur. Kamu dibopong kawan-kawanmu untuk menepi.
Dalam satu malam, kamu kehilangan seorang kawan baik, seorang mantan istri, dan kedua anakmu.
Seketika kamu tak punya alasan untuk melanjutkan hidup. Kamu berencana menghabisi diri sendiri di perjalanan pulang. Kekuatan untuk meneruskan hidup langsung lenyap. Tapi, kamu masih bertahan sampai sekarang. Tidurmu tak pernah nyenyak lagi.
“Aku mengingat malam itu sebagai malam jahanam. Malam pembantaian,” katamu.

* * *
Anakmu dimakamkan pada pukul delapan pagi. Fajar mulai terbit tapi tidak harapanmu. Mereka akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Pathuk, Desa Sukolilo, Kabupaten Malang. Sebelum dimakamkan, kamu melihat jasad orang-orang tersayang untuk kali terakhir di kediaman ayah tirinya di daerah Wajak.
Kamu memasuki bilik berkelir hijau tempat jasad kedua anakmu disemayamkan. Kamu masih ingat, hingga pagi sebelum dikubur, darah terus mengucur pelan dari hidung kedua anakmu. Di hidung Tasya, ada cairan hijau yang terus menetes. Di pelipis kirinya, ada sobekan luka kecil hingga belakang kepala.
Ada aroma gas amonia menguar dari mulutnya. Di kaos bersimbah darah bercampur lumpur yang dikenakan anakmu, aroma gas amonia tercium pekat.
Hal sama pada jasad Lala. Di sekujur tubuhnya, hampir tak ada luka, kecuali kepalanya berwarna ungu kehitam-hitaman.
Kepalamu menengadah. Kamu berusaha air mata tak sampai tumpah di tubuh jenazah. Menurut mitos yang kamu percayai, jika air mata mengenai tubuh jenazah, arwahnya akan merasa kepanasan. Kamu tak ingin anakmu merasakan penderitaannya sekali lagi.
Ketika memandikan anakmu, pikiranmu melayang pada ingatan-ingatan manis si buah hati. Kamu ingat momen pertama kali mengajak Tasya ke tribun Aremania. Sejak itu si sulung begitu menggandrungi tim berlogo Singa, dan selalu turut kemana pun Arema berlaga.
“Tasya adalah anak yang berani, dan keras kepala,” kenangmu.
Tasya bahkan pernah bolos sekolah demi menonton Arema. Ia pernah diancam sanksi dari sekolah. Alih-alih nyalinya ciut, Tasya meminta dipindahkan sekolah. Kamu hanya terkekeh. Bagimu, kebahagiaan putrimu yang utama; sementara pendidikan, sekadarnya saja. Tasya adalah bocah tomboy, dan bercita-cita menjadi polisi.
Sementara anakmu yang lain, Lala, tak begitu suka sepakbola. Ia menonton laga Arema untuk aktivitas eskapis, melepas jenuh dari tugas-tugas sekolah. Biasanya, Lala berangkat ke stadion demi menggenapi kemauan si kakak.
Lala adalah anak dengan hati lembut, katamu. Ia bertubuh bongsor dan pertumbuhannya cepat. Meskipun masih SMP, tinggi Lala telah melebihimu. Kamu kegirangan saat melihat si bungsu menari.
Tetapi, ketika pandanganmu kembali pada kedua jasad anakmu, kebahagiaanmu seketika luruh. Kedua harapanmu telah pergi dalam satu malam.
“Anakku dipateni iki. Anakku dibantai polisi!”

Selepas memandikan putrimu untuk kali terakhir, setelah seorang imam mengumandangkan azan, kamu memilih menepi. Kamu tak punya daya mengebumikan putrimu. Ketika jasad anak-anakmu tertimbun tanah, dan nisan kedua putrimu ditancapkan, kamu berbisik pelan, sebuah ikrar:
Ayah nggak ikhlas kalian dibunuh seperti ini. Sampai di akhirat pun, ayah akan cari keadilan untuk kalian.
* * *
Kamu bisa tidur cuma dua jam. Selama berhari-hari kamu cuma bisa menangis. Lalu muncul penyesalan. Kamu dihantui perasaan gagal menjadi seorang ayah. Kamu tak ada saat kedua anakmu membutuhkanmu di saat sangat dibutuhkan di sebuah tempat yang kamu sangat kenali dan sayangi, sebuah stadion. Dunia cintamu hilang.
Kamu bercerita setiap malam kamu mendengar suara yang begitu kamu kenal, suara putrimu, merintih meminta pertolongan. Kamu bercerita kamu mendengar suara itu, atau kamu mencium anyir darah menusuk hidung. Kamu segera ke stadion Kanjuruhan untuk membaca doa. Jika tanda itu datang tak terlalu malam, kamu menyempatkan membeli sebungkus sempol. Kamu mengingat sempol itu, karena makanan itu yang biasa kamu berikan untuk Tasya sebelum memasuki stadion.
“Saya kemudian meletakan sempol itu di depan Gate-13, lalu membaca doa. Pulangnya, saya mengambil baju terakhir yang mereka pakai waktu kejadian, dan menjadikannya sebagai guling. Dengan begitu, saya merasa mereka masih di sini, bersama saya, menemani saya.”
Di saku celana terakhir yang dipakai Tasya dan Lala, kamu menemukan barang-barang favorit mereka.
Di kantong Lala, ada sebungkus permen, lipstik, dan uang saku darimu. Di saku Tasya, ada uang Rp30 ribu. Aroma pakaian mereka kental aroma amonia dan darah. Kamu sengaja tak mencucinya. Kamu berjanji akan menyimpan itu selamanya.
Kamu juga teringat Tasya ingin merayakan ulang tahunnya pada pertengahan Oktober dengan makan-makan keluarga di sebuah gerai makanan cepat saji. Kamu telah mengiyakan.
Kamu menjanjikannya sebuah mobil untuk bersekolah. Rencananya, pada pertengahan tahun depan, rumah baru yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri untuk kedua anakmu telah siap ditempati.
Tapi, janji dan angan ini menguap begitu saja. Kamu hanya melihat kesia-siaan belaka atas usaha dan kerja kerasmu sebagai seorang ayah.
“Saya hidup sudah tidak ada artinya. Bekerja juga sekarang untuk siapa? Sudah enggak ada lagi semangatnya. Hidup menjadi seorang ayah, nggak ada artinya,” katamu.
Kamu mengatakan sekali lagi bahwa kamu telah siap dengan pusparagam konsekuensi, tatkala melakukan tuntutan hukum, demi memperjuangkan keadilan untuk kedua putrimu.
“Meskipun berat dan bakalan panjang, tapi bukan tidak mungkin,” katamu.
Intimidasi Polisi dan Autopsi
9 Oktober 2022, tekadmu membatu. Kamu berkata kepada pengacara bernama Imam Hidayat bahwa kamu merelakan tubuh anakmu untuk diautopsi, dengan harapan bisa dipakai untuk memberikan bukti penyebab kematian mereka bukan karena terimpit seperti kata polisi.
Kalian bersalaman, lalu kamu menulis sepucuk surat kuasa sekaligus surat pribadi untuk kuasa hukum keluarga Tragedi Kanjuruhan agar mereka melakukan autopsi untuk kedua putrimu.
Dua hari setelahnya, rombongan polisi mulai mendatangi kediamanmu. Pertama-tama mereka datang empat orang, lalu enam orang, lalu bertambah lagi setiap hari. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama, tentang keyakinanmu melakukan autopsi. Keluargamu gemetaran. Kamu mengkhawatirkan nasib bapak dan ibumu. Di hari-hari lain, polisi terus datang tapi kamu enggan membuka pintu rumahmu, memilih melipir lewat belakang untuk menghindar. Kamu ketakutan, seperti sedang diintimidasi.
Suatu siang saat kamu menimang keponakanmu di pinggir jalan, seseorang berperawakan tegap, berjaket hitam, menghampirimu tanpa memperkenalkan diri. Ia merogoh sebuah benda dari saku celananya. Kamu merasakan besi dingin mendarat di kepalamu. Setelah kamu melirik, itu sebuah pistol. Dengan nada setengah berbisik, si orang itu berkata, “Ojok macem-macem kon.”
Lalu si orang itu mengoceh soal autopsi. Alih-alih nyalimu menciut, kamu menantangnya,
“Sampean tembak ae, Pak. Ben mesisan mari.” Bapak tembak saja saya, biar semuanya selesai, katamu tanpa rasa takut.
Kematian tak menjadi momok menakutkan lagi bagimu. Sebab, selepas kehilangan kedua putri, kehidupan menjadi hampa. Melihat dirimu bergeming, si penodong pun berlalu.

Mendapat intimidasi berkali-kali, membuatmu merasa menanggung permasalah ini sendirian. Ketika polisi tiba, kamu mencoba menghubungi salah satu utusan pengacaramu, tapi teleponmu tak juga diangkat. Kamu juga meminta bantuan dari kolektif suporter Aremania, tapi teleponmu tak kunjung dijawab. Sampai kemudian polisi mengumumkan bahwa autopsi akan digelar pada 20 Oktober 2022.
Tiga hari sebelum autopsi digelar, seorang polisi kembali mengunjungi rumahmu. Sebab kamu merasa ditinggal sendirian, kamu pun terpaksa menandatangani surat pembatalan.
“Aku merasa sendirian. Aku nggak takut mati. Cuma takut kalau orangtuaku juga jadi korban. Mereka sekarang satu-satunya yang aku punya, yang masih tersisa,” katamu.
Harapanmu kembali runtuh, sekali lagi. Kamu mengunjungi pusara kedua putrimu. Di sana, kamu menangis dan memohon ampun. Kamu merasa tak sanggup menunaikan janji. Kamu merasa terlampau lelah.
Kamu kemudian menceritakan kepada seorang pengacara dari Federasi Kontras, Andy Irfan Junaedi. Sontak, surat-surat kabar memuat kisahmu. Pada 18 Oktober, teleponmu kembali berdering dari nomor asing: “Lapo kon kok wadul nang Andy iku? Ojok macem-macem kon, yo!” kata orang itu yang menuduhmu bikin perkara karena mengadu ke Andy.
Tetapi, kamu tak menggubris. Kamu menjawab dengan santai, “Memang itu yang terjadi.”
Kamu tak sepenuhnya rela saat menandatangani surat pembatalan autopsi. Demi mencari keadilan, kamu kembali bertekad mengajukan autopsi untuk jasad kedua putrimu pada 22 Oktober 2022.
Saat keluargamu tahu kamu kembali mengusulkan autopsi, mereka mengusirmu dari rumah. Kemarahan mereka meledak. Mereka membayangkan teror yang sama kembali mengetuk rumah mereka. Tapi, tekadmu lebih besar melampaui segala ketakutan. Kamu bersikeras dan bersedia angkat kaki dari kediaman orang tuamu.
Demi menempuh perjalanan mencari keadilan untuk kedua putrimu, kamu hidup berpindah-pindah saban hari. Alasannya, aparat masih mengintai kediamanmu. Kamu kerap mendapati orang asing di depan rumah. Setelah kamu berada di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kamu mulai agak merasa tenang tinggal sebuah rumah aman hingga proses autopsi digelar pada 5 November 2022.
Kecewa pada Hasil Autopsi
Hari yang kamu tunggu telah tiba. Setelah seharian terjaga, dan hanya terlelap selama satu jam, kamu melaju menuju makam kedua putrimu. Kamu mengenakan kaos hitam dan memegang potret kedua putrimu.
Kamu menyembunyikan matamu yang sembab di balik kacamata hitam. Langkahmu pelan, tapi tampak yakin saat melangkah menuju pusara. Kamu diapit orang-orang berperawakan tegap.
Di depan pintu pemakaman, air matamu tiba-tiba pecah. Kamu kembali histeris. Kamu ragu saat memasuki tenda berwarna hijau tua, tempat jasad kedua anakmu akan diautopsi. Ketika memasuki bilik itu, seseorang dengan hazmat putih menjabat tanganmu. Ia adalah dr. Nabil Bahasuan, Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia wilayah Jawa Timur, yang memimpin prosesi autopsi.
“Pak, kita bersumpah di depan pusara anak saya. Kalau sampai ini tidak transparan dan jujur hasilnya, mungkin Bapak dan kawan-kawan Bapak akan lolos dari hukum. Tapi bersumpahlah sebagai seorang bapak, bahwa Bapak siap untuk diazab Tuhan?”
Dr. Nabil mengangguk.

Dr. Nabil memintamu mempercayakan seluruh proses kepadanya. Kamu diminta keluar. Selama proses autopsi, tak satupun perwakilan keluarga diberi kesempatan mengawasi. Kamu duduk di kursi plastik, lalu meladeni para wartawan.
Kamu diminta kembali ke bilik saat autopsi selesai. Di sana, kamu melihat dua jenazah anakmu sekali lagi. Kamu diminta memandikan mereka sebelum dikembalikan di liang lahat. Kamu berkali-kali jatuh pingsan, lalu bangkit kembali. Hatimu sedikit lega karena kondisi mayat masih sama seperti saat kamu memandikan mereka pada 2 Oktober 2022. Jasad anak-anakmu masih utuh. Kain kafan dan papan kayu masih baik.
Selepas memandikan, kamu membisikan permintaan maaf terakhirmu kepada kedua anakmu.
“Maafkan ayah. Tolong bantu ayah untuk mencari keadilan buat sampean, ya, Mbak,” katamu
Kamu melihat kedua anakmu duduk di atas pusara seraya tersenyum saat kamu hendak memakamkannya lagi. Saat itulah hatimu kembali rontok. Kamu kehilangan daya menyanggah tubuhmu. Pandanganmu kabur. Lamat-lamat menjadi gelap. Lalu tersungkur. Kawan-kawanmu membopongmu menuju ambulans.
* * *
Dari dr. Nabil, kamu mengetahui proses autopsi membutuhkan paling lama dua bulan.
Sepanjang menunggu itu, kamu harap-harap cemas. Kamu begitu yakin bahwa kematian anakmu disebabkan gas air mata. Kamu berharap polisi yang membawa maut pada anakmu dihukum seberat-beratnya, bukan dengan dakwaan lalai menjalankan tugas, melainkan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana.
Hasil autopsi rupanya rilis lebih cepat. Tapi, kamu mengetahuinya justru dari kawan-kawanmu.
Pada 30 November, kamu mendapatkan pesan dari seorang kawan. Dari pesan itu, kamu membaca berita. Dr. Nabil baru saja mengumumkan hasil autopsi di Surabaya. Ia mengatakan kematian kedua anakmu murni karena berdesakan. Ada tulang yang patah di area sekitaran leher dari anakmu.
Kemarahanmu memuncak. Kamu mengumpat. Kamu merasa upayamu mencari keadilan, sekali lagi, dirobohkan oleh mereka yang punya kuasa.
Imam Hidayat, pengacaramu, mengatakan kepada para wartawan bahwa hasil autopsi patut dipertanyakan. Ia sudah mengendus keganjilan karena selama proses autopsi, tak satupun pihak darimu diperkenankan turut mengawal.
“Dengan kondisi seperti ini, patut diduga ada rekayasa. Karena secara fisik kasat mata kita melihat ada busa dari hidung dan mulut korban. Air kencing dan kotoran juga keluar,” kata pengacaramu.

Kamu berkata kamu rela mengautopsi ulang jenazah anakmu, sekali lagi. Demi mencari fakta, demi keadilan, demi menuntaskan ikrarmu sebagai ayah.
“Ini adalah janji seorang ayah kepada anaknya. Saya akan terus dan mengorbankan segalanya demi keadilan untukmu, Tasya dan Lala. Sampai nyawa pun rela kupertaruhkan untuk mereka,” katamu.
Kamu tak pernah rela para pembunuh Tasya dan Lala bisa cuci tangan dan bebas begitu saja.
Artikel ini bagian dari serial #PercumaLaporPolisi