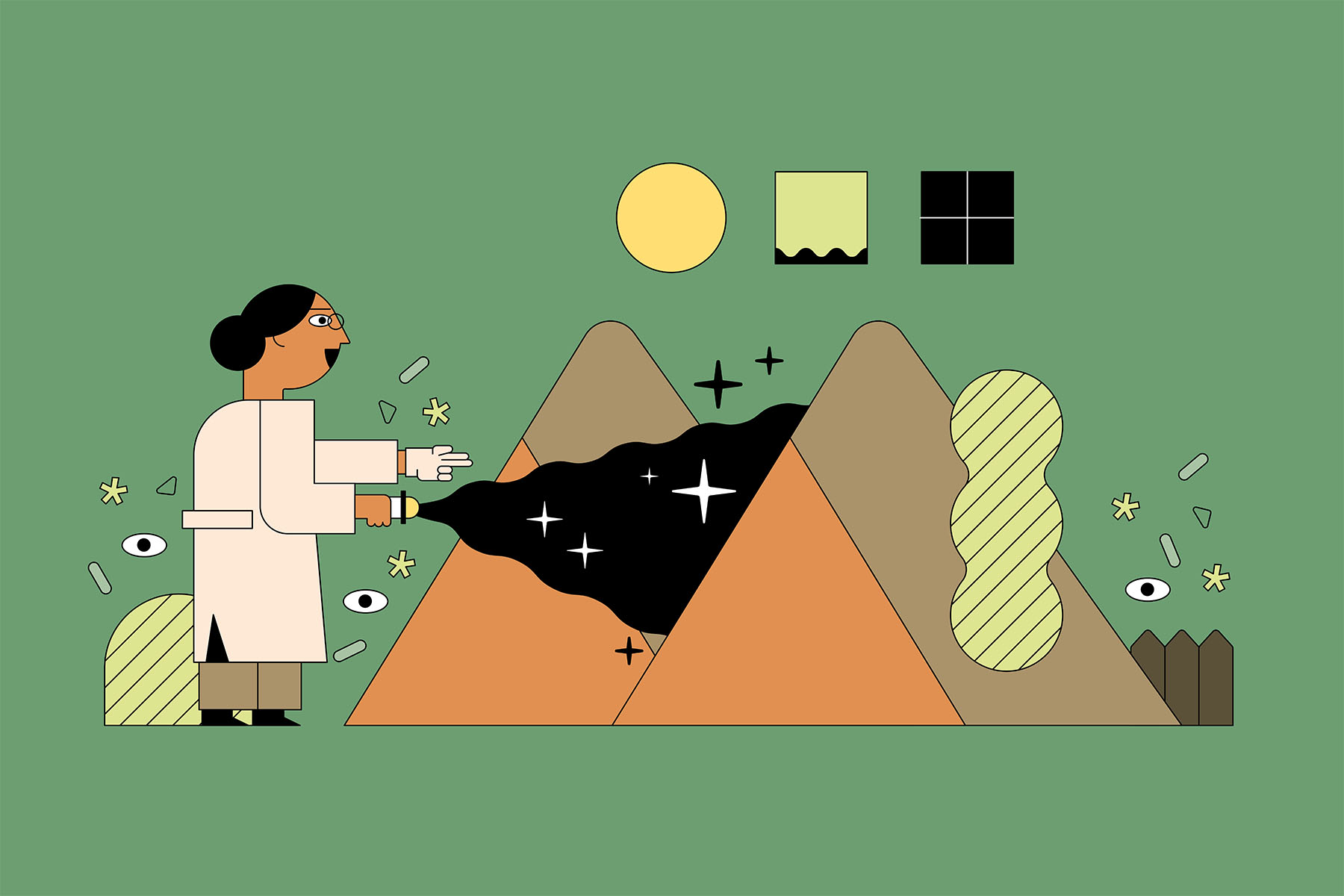Pada 2017, saya bicara di konferensi mengenai perdagangan anak di hadapan anak-anak SMA di Jakarta. Saat itu, saya telah bergiat melawan perdagangan anak melalui Yayasan Rumah Faye, dan kami baru mulai membuat “safehouse” di Batam. Pengalaman saya di Rumah Faye dalam memfasilitasi pendampingan bagi korban perdagangan anak membuat saya paham bahwa ada isu struktural yang meminggirkan kelompok minoritas.
Konferensi itu akan selalu saya ingat sebagai suatu peristiwa di mana sebuah perjuangan baru, yang personal, mulai terukir di hati saya: “tes keperawanan” terhadap calon tentara perempuan dan calon istri tentara. Di konferensi itu saya bertemu kenalan baru, Latisha Rosabelle, yang membuat petisi pertama untuk melawan “tes keperawanan” di Indonesia.
“Kamu tahu tidak?” tanyanya kepada saya. Saya tidak tahu.
Bagi saya ketidaktahuan ini terasa lebih parah karena saya berasal dari keluarga militer, dan saya bangga akan kenyataan itu. Ayah saya adalah seorang perwira baret merah Kopassus. Mungkin ini optimisme buta, tetapi saya sudah lama mengagumi militer karena disiplin dan komitmen mereka terhadap bangsa.
Kami hafal Hymne Komando, dan saya ingat, hari itu saya menggumamkan lirik lagu itu dalam perjalanan pulang ketika saya berusaha mencerna bahwa ada sesuatu bernama “tes keperawanan”.
Mungkin untuk sebagian orang tes itu bukan hal yang mengejutkan, tapi untuk Faye yang saat itu berusia 15, dunia seperti luluh lantak. Bagaimana bisa kita mengatakan “rela binasa membela Ibu Pertiwi”, ketika perempuan di militer tidak mendapatkan hak asasi mereka yang paling dasar?Click To Tweet“Tes keperawanan” sudah lama dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tes seperti itu “tidak memiliki validitas ilmiah” dan “tidak memiliki tempat” dalam praktik medis modern. Karena tidak valid, Andreas Harsono, seorang peneliti dari Human Rights Watch (HRW), meminta kepada para wartawan dan penulis untuk selalu menuliskan “tes keperawanan” di antara tanda kutip, karena keperawanan tidak dapat diuji.
Tapi banyak tokoh yang mendukung tes tak valid itu. Figur-figur ini memiliki kekuasaan, dan mereka mengklaim bahwa dibutuhkan suatu ukuran “ideologi mental” dan keperawanan adalah “tolok ukur penting” untuk moralitas perempuan.
Kelompok advokasi seperti HRW telah bertahun-tahun bekerja melawan “tes keperawanan”, namun saat itu belum membuahkan hasil. Jika Pak Andreas Harsono belum bisa menjangkau mereka, lalu siapa yang bisa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Namun, saya pikir, upaya terbaik adalah dimulai dari rumah.
Mungkin banyak yang tak percaya, tapi meski saya lahir di keluarga militer, saya tidak takut membicarakan “tes keperawanan” secara terbuka dengan orang tua saya. Waktu itu, saya tidak ragu bahwa mereka akan setuju tes itu tidak manusiawi. Meski saat itu saya sudah siap bertarung, tetapi saya tahu pertarungannya bukan dengan orang tua saya, yang telah lama mengajari saya bahwa peluang bisa diperjuangkan menjadi kemenangan.
Sudah sejak lama ayah saya menaruh perhatian pada pengembangan masyarakat, perubahan jangka panjang dan berkelanjutan. Dia menyadari dia dapat menggunakan posisi strategisnya—membimbing prajuritnya untuk menjadi ujung tombak bagi pengembangan masyarakat yang ia cintai. Sama halnya dengan ibu saya, yang memberikan fasilitas untuk taman kanak-kanak (TK) dan program pemberdayaan perempuan untuk istri perwira militer. Orang tua saya membentuk pandangan saya terhadap dunia, melalui hal yang mereka kerjakan—di setiap tempat mereka diposisikan, mereka melakukan renovasi asrama dan sekolah militer, membangun kembali pusat pertanian untuk memberdayakan komunitas lokal, dan menciptakan pusat rekreasi.
Amarah saya direspons dengan pengertian dan ketenangan dari kedua orang tua saya. Meskipun awalnya ragu-ragu, kedua orang tua saya akhirnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tes keperawanan” dan mengapa itu diterapkan.
Saya ingat ketika menangis karena frustrasi, tidak memahami mengapa tes macam itu masih diberlakukan. Saya meminta kedua orang tua saya untuk segera memikirkan kampanye macam apa yang paling efektif untuk menghapuskan “tes keperawanan”. Orang tua saya menjelaskan bahwa saya, bagaimanapun juga, memiliki posisi yang unik untuk melakukan hal lebih dari sekadar kampanye dari luar. Memang saya selama ini kampanye “dari luar” mengenai perdagangan orang melalui Rumah Faye, tapi orang tua saya menunjuk hal lain: meski organisasi non-profit memiliki kekuatan tertentu, tetapi saya juga dapat melakukan sesuatu (walaupun mungkin kecil) “dari dalam”.
Saya lalu membicarakan “tes keperawanan” dengan dua teman saya di kompleks militer. Keduanya segera mengajak orang tua mereka diskusi mengenai hal tersebut. Satu orang kena marah paling besar sepanjang hidupnya; yang satu lagi mendapatkan penegasan singkat bahwa “tes keperawanan” adalah hal terbaik: mereka bilang, memangnya ada cara lain untuk membuktikan bahwa seorang perempuan benar-benar bermoral?
Saya melihat banyak pergerakan dari luar untuk melawan tes ini, tetapi saya melihat hampir tidak ada diskusi di internal militer mengenai ini (setidaknya dari apa yang saya lihat).
Orang tua saya benar: perubahan harus dimulai dari dalam, dari orang-orang yang bisa mengambil tindakan dengan segera untuk perubahan secara kelembagaan.
Hal ini berarti bahwa kami harus memulai sebuah diskusi dengan tujuan akhir: (1) mengakui “tes keperawanan” bukanlah ukuran moralitas yang valid, (2) menekankan ketidakakuratan medis dari “tes keperawanan”, (3) mendorong terbitnya dokumen untuk melarang “tes keperawanan” seperti itu terjadi lagi, dan (4) memastikan implementasi yang tepat atas perubahan kebijakan tersebut.
Implementasi ini harus dibarengi dengan meminta pertanggungjawaban para pencetus/pendukung “tes keperawanan” pada masa lalu dan membuka kesempatan untuk para perempuan yang pernah mengalaminya (baca: “tes keperawanan”) untuk mendapatkan konseling atau layanan penting lainnya.
Tujuan akhir ini harus dimulai dari pekerjaan akar rumput, yang menuntun saya pada pembicaraan intensif dengan Korps Tentara Wanita (Kowad) untuk mempelajari pengalaman mereka.
Pertama kali saya membicarakan tes itu dengan korban adalah dengan seorang teman, sebut saja Marel, yang pernah bekerja dengan ayah saya dalam suatu penempatan tugas. Kalau dipikir-pikir, harusnya saya mungkin tidak langsung bertanya tentang “tes keperawanan” tapi bertanya dulu mengenai keseluruhan proses seleksi militer. Karena saya langsung bertanya tentang tes itu, ekspresi wajahnya langsung ketakutan. Lalu ketika dia sudah berhasil mengontrol ekspresinya, dia mengangkat bahu, seolah-seolah mengatakan kepada saya, “memangnya kita bisa apa?”
Setiap orang yang saya ajak bicara menunjukkan reaksi yang kurang lebih sama. Sebagian orang marah, tetapi kebanyakan pasrah, menerima “tes keperawanan” sebagai syarat pendaftaran. Tetapi belakangan saya juga mendapatkan cerita bisik-bisik tentang pemeriksaan yang menyakitkan, ruang tunggu yang kosong, air mata, kebingungan. Dan rasa malu.
“Tes keperawanan” berdampak jangka panjang bagi para penyintas. Mereka masih ingat peristiwa itu bahkan lebih dari satu dekade kemudian. Saya ingat, saya sempat frustrasi: jika banyak perempuan merasakan seperti ini, mengapa mereka diam? Tapi saya sadar, kekuatan dinamika kekuasaan dalam militer dan budaya kita membuat sangat sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Struktur hierarkis yang ada, terutama di lembaga-lembaga militer, hanya memberikan sedikit ruang bagi reformasi kecuali jika ada dukungan tokoh-tokoh berpengaruh.
Akhirnya saya memulai sebuah kampanye rahasia, dan saya sadar saya tidak dapat mengharapkan perubahan jika mengajak orang-orang di militer berdebat bahwa moralitas perempuan bukanlah terletak pada keperawanannya, atau bahwa “tes keperawanan” secara medis tidak akurat. Jika saya memilih berdebat soal itu maka saya akan cuma disambut ejekan dan tuduhan bahwa saya mendukung perzinahan atau bahkan mereka akan mempertanyakan moral saya.
Saya mulai dengan gaya gerilya remaja gila (crazed-teenage-guerrilla-style ambushes) kepada siapapun, kenalan saya yang berhubungan dengan militer. Melalui Rumah Faye, saya menjelaskan dampak dari “tes keperawanan”, berbekal pengalaman saya yang hampir delapan tahun bekerja dengan korban perdagangan seks, eksploitasi, dan pelecehan. Tapi, beberapa kali saya didebat bahwa laporan WHO “terlalu baru”, atau percakapannya “terlalu modern”, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa.
Jika saya pikir-pikir, kalau saya bukan anak dari orang tua saya, mungkin saya tidak akan melangkah sejauh ini. Saya berpikir banyak tentang privilese saya; bahwa saya bisa memulai dialog karena saya berada dalam posisi istimewa. Penting untuk dicatat bahwa saya bisa melakukan ini karena dukungan dari orang tua saya dan juga reputasi saya yang dikenal karena kegiatan saya di bidang anti-perdagangan manusia. Tanpa dua hal itu, saya pikir banyak orang tidak akan mau mendengarkan seorang remaja perempuan usia belasan tahun.
Saya terus ngotot melawan dari dalam karena saya pikir terlalu banyak peristiwa kelompok minoritas dipinggirkan justru oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Artinya, jarang perubahan terjadi hanya melalui kampanye eksternal---harus ada dukungan dari dalam agar perubahan kelembagaan dapat terjadi.Click To TweetSaya sebenarnya sadar harusnya bukan suara saya yang diberi ruang lantang, karena saya sendiri tidak pernah mengalami “tes keperawanan”. Harusnya suara penyintas yang dilantangkan, tetapi bagi mereka menyuarakan hal ini sangat sulit karena hampir semua penyintas tak ingin bicara lalu identitas mereka terungkap. Ini bisa dimengerti karena sifat hierarkis dalam Angkatan Darat.
Bahkan dengan privilese (baca: hak istimewa) saya sendiri, pekerjaan ayah saya dan pekerjaan saya sendiri masih bisa terancam. Saya harus akui, privilese adalah sesuatu yang terjalin erat dalam kisah ini; bahwa kampanye saya dimungkinkan oleh privilese saya. Ini kenyataan yang saya sayangkan, karena saya yakin mestinya setiap suara harus didengar, dengan atau tanpa hak istimewa.
Kejutan dari AD
Seiring berjalan waktu, gerakan untuk mengakhiri “tes keperawanan” mulai berkembang, baik secara eksternal maupun internal. Dari luar, yang paling menonjol, paling tidak sepengetahuan saya, adalah Pak Andreas Harsono dan Latisha Rosabelle.
Pada 2017, ibu saya memperkenalkan saya kepada bu Ninik Rahayu dari Ombudsman Indonesia. Ibu Ninik berbicara panjang lebar kepada saya tentang “tes keperawanan”, mengenai pekerjaan yang telah dia lakukan, dan pekerjaan yang perlu dilakukan. Saya terus berkomunikasi dengan Bu Ninik. Dia bekerja tanpa lelah untuk bicara kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk melarang “tes keperawanan”.
Saya diam-diam bertemu dengan istri tokoh militer yang memiliki posisi kuat serta telah lama mencoba untuk memulai percakapan seputar “tes keperawanan”. Anggota militer perempuan berbagi pengalamannya dengan kami. Sebagian besar menolak untuk mengambil langkah tindak lanjut karena takut gerakan kecil mereka akan berbalik menyerang mereka. Kami sangat memahami. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada terlihat tidak bermoral di negara ini; seorang perempuan bisa kehilangan segalanya gara-gara tuduhan ini.
Meskipun ada upaya-upaya untuk membentuk koalisi melawan “tes keperawanan”, tapi tidak ada satu pun yang terbentuk. Dalam diskusi terakhir kami pada Mei 2021, ibu saya, bu Ninik, dan saya telah merencanakan untuk mengumpulkan sekelompok perempuan untuk mengirim lagi surat resmi ke Komando Staf Angkatan Darat. Sayangnya, beberapa perempuan berpengaruh menolak permintaan untuk bermitra dengan kami. Alasannya, mereka khawatir melawan “tradisi” atau khawatir suami mereka dihambat promosi jabatannya.
Gerakan kecil kami adalah proses panjang yang sejarahnya tidak dapat saya lacak dengan baik; separuhnya karena panjangnya durasi kampanye, dan separuhnya lagi karena semuanya sangat informal. Saya tidak kenal semua orang yang tergabung dalam gerakan internal ini. Saya juga tidak dapat secara terbuka menyebutkan nama-nama perempuan yang saya tahu terlibat karena berbagai alasan. Kami melakukan pertemuan dan agenda secara sembunyi-sembunyi dan dibungkus sebagai agenda informal karena topiknya terlalu sensitif.
Bulan Agustus, artikel-artikel media yang mengutip Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, bahwa AD telah menghentikan “tes keperawanan”, mengejutkan saya. Sebelum pengumuman itu saya mendeteksi hanya sedikit gerakan sehingga saya tidak sadar akan ada peristiwa besar. Saya memang mendengar ada pertemuan-pertemuan antara beliau dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tetapi saya tidak mendapatkan kabar lagi. Pengumuman dari Pak Andika pun tidak terlalu kencang gaungnya, terjadi hampir dalam diam. Pidato Pak Andika pada awal Juli baru tersebar pada akhir Juli, karena dikutip oleh Pak Andreas Harsono dalam laporan dia untuk Human Rights Watch.
Begitu mendengar berita itu, saya menangis. Sebagian dari diri saya masih kecewa mengingat perubahan ini terjadi baru sekarang meski sudah bertahun-tahun dibicarakan dan dikampanyekan. Tetapi juga, ada rasa lega luar biasa.
Sekarang kita harus menjaga akuntabilitas lembaga negara kita dalam memastikan bahwa perubahan akan diterapkan secara memadai di seluruh negeri, dengan pengawasan dari Pak Andika. Selain itu, harus ada pertanggungjawaban dari mereka yang ikut mendukung “tes keperawanan” di masa lalu, disertai permintaan maaf mereka kepada semua orang yang pernah mengalami pelecehan struktural ini.
Langkah Angkatan Darat ini baru permulaan. Angkatan Laut dan Angkatan Udara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melarang diskriminasi struktural terhadap perempuan ini.
Setelah kabar dari AD, saya mendapatkan banyak pesan dari teman-teman yang menyatakan rasa tidak percaya bahwa hal ini akhirnya terjadi. Marel, setelah bertahun-tahun jarang berkontak, mengirim “direct message” ke inbox saya, membahas tentang penghapusan tes. Ada perayaan singkat, kemudian diikuti keraguan, yang naluriah dan tertanam di diri banyak perempuan: Akankah ini benar-benar terjadi?
Penerjemah dari Bahasa Inggris: Giovanni Alvita Diera, mahasiswa magang dari Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.
Faye Simanjuntak adalah mahasiswa tahun kedua yang telah kurang lebih delapan tahun bekerja untuk memberantas perdagangan anak, eksploitasi, dan pelecehan di Indonesia melalui program jangka panjang di Rumah Faye. Faye juga bekerja untuk mengangkat diskusi sosial politik Indonesia melalui What Is Up, Indonesia? (WIUI) di Instagram. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Jordinna Joaquín atas bantuannya untuk penulisan artikel ini.