“Mbak, udah makan? Cobain bihun sisa jualan saya tadi pagi, ya,” ujar seorang ibu.
“Mau nasi juga nggak, Mbak? Ini saya bawa dari rumah,” kata ibu yang lain sambil menyodoriku kotak plastik yang padat berisikan nasi.
Siang itu, sekitar pukul 11.30, aku sampai di sebuah komplek ruko di bilangan Jakarta Utara. Wiwid, seorang buruh garmen yang membagikan lokasinya dan buruh-buruh lain berkumpul, menghampiriku di depan gang kecil yang terimpit di antara dua bangunan ruko. Menengok ke dalam gang, melewati sebuah warung kopi, aku melihat sekitar 30-an perempuan, usia 40-an tahun ke atas, sedang duduk-duduk di jalanan gang yang dialasi terpal.
Sekilas mereka terlihat tak ubahnya ibu-ibu yang sedang arisan. Beberapa mengobrol satu sama lain, beberapa mengeluarkan bungkusan-bungkusan makanan untuk dibagikan ke kawan-kawannya. Ada juga yang menyuapi anaknya makanan. Mereka menyapaku dengan ramah dan mempersilakanku duduk di alas terpal.
Bihun, nasi uduk, dan berbagai macam lauk hingga air putih mereka tawarkan kepadaku. Berbagi makanan adalah tanda kasih sayang. Aku belajar itu pertama kali dari ibuku yang selalu menyiapkan makanan untuk dibawa pulang setiap aku hendak kembali ke kos. Aku kembali menemukan makna itu dari interaksiku dengan para ibu di gang sempit itu.
Hanya saja, di tengah suasana yang hangat itu, mereka bukan sedang bersantai. Mereka sedang memperjuangkan hidup mereka.
Wiwid telah bekerja lebih dari 20 tahun di PT Trinitas Mulia Abadi, sebuah perusahaan konveksi, ketika kabar pemecatan itu ia terima. Saat itu April 2020. Selang sebulan setelah kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia, pihak perusahaan mengumumkan kepada para pekerjanya bahwa mereka akan tutup. Klaimnya, perusahaan telah merugi selama dua tahun berturut-turut, dan pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Ada sekitar 150 buruh garmen yang terdampak. Rata-rata dari mereka telah bekerja selama 20 tahun di perusahaan itu, bahkan ada yang telah bekerja sejak 1992. Sebagian besar di antaranya adalah perempuan.
Meski perusahaan mengklaim kerugian telah terjadi selama dua tahun terakhir, para buruh yang dipecat tak pernah menerima laporan keuangan yang membuktikan itu. Perusahaan juga menghindari dari tanggung jawab uang pesangon dan penghargaan masa kerja yang sesuai, dengan menawari para buruh mengundurkan diri dengan imbalan uang.
Undang-undang Ketenagakerjaan lewat Pasal 164 telah menyatakan secara tegas bahwa perusahaan hanya bisa melakukan PHK jika perusahaan telah mengalami kerugian selama dua tahun terakhir, dan mesti dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Perusahaan yang melakukan PHK juga wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang besarannya bergantung dengan lama mereka bekerja. Buruh yang telah bekerja lebih dari delapan tahun berhak atas uang pesangon sebesar sembilan bulan upah. Buruh yang telah bekerja lebih dari 21 tahun juga berhak atas uang penghargaan sebesar delapan bulan upah.
Dengan upah buruh yang sebesar UMP DKI Jakarta 2020, yaitu sekitar Rp4,2 juta, maka perhitungannya:
Jumlah uang pesangon: 9 bulan x Rp4,2 juta = Rp37,8 juta
Jumlah uang penghargaan masa kerja: 8 bulan x Rp4,2 juta = Rp33,6 juta
Total jumlah uang: Rp37,8 juta + Rp33,6 juta = Rp71,4 juta
Jika perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian atau dalam keadaan memaksa, maka uang pesangon yang berhak didapatkan oleh buruh menjadi berjumlah dua kali lipat, atau sekitar Rp75,6 juta. Besaran total ini juga belum termasuk uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil, ongkos berangkat dan pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
Kenyataannya, para buruh dipaksa untuk menerima uang ganti yang besarannya jauh di bawah itu, yaitu sekitar Rp10-20 juta, dengan pembayaran yang dicicil hingga 10 kali.
Proses bipartit dan mediasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat telah mereka lakukan, tetapi hasilnya nihil. “Kalian egois,” kata pihak perusahaan kepada para buruh yang menuntut hak mereka.
Bagi Wiwid, salah satu korban pemecatan, tidak bekerja dan tidak ada pemasukan berarti ia mesti merelakan anak sulungnya tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Gaji suaminya yang sebesar upah minimum DKI Jakarta terbilang pas-pasan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan kedua anak mereka.
Nurchasanah, buruh perempuan lain, sedang menjadi tulang punggung keluarga ketika dirinya mendapatkan kabar pemecatan dirinya. Suaminya kena stroke pada 2012, dan belum pulih benar hingga kini, sehingga ia jadi satu-satunya yang bisa diandalkan untuk bekerja. Saat itu, langsung terbayang di kepalanya kebutuhan sehari-hari yang tak bisa ia dapatkan tanpa ada pemasukan tetap. Selain suami, ada dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang mesti ia nafkahi. Ada kebutuhan makanan, biaya sekolah, listrik, cicilan motor, dan kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang bisa saja muncul mendadak.
Kini, mereka sedang dalam proses persidangan. Proses perjuangan yang menguras energi dan waktu itu membuat sebagian dari mereka perlahan-lahan menyerah dan menerima “tawaran” pengunduran diri dari perusahaan. Tersisa 40 orang yang menolak dan masih berjuang hingga kini.
Kena Pecat Dua Kali: Setelah Melahirkan dan Saat Covid-19
Perjalanan hampir dua jam dari daerah Jakarta Selatan, ke daerah Setu, Bekasi, Jawa Barat, melewati gunung sampah Bantargebang mempertemukanku dengan Dwi. Begitu sampai di rumahnya, ia menyapaku dengan hangat, sembari berseloroh bahwa rumahnya “mewah”.
“Mepet sawah maksudnya,” katanya sambil terkekeh.
Pukul 11 pagi itu, Dwi baru saja selesai mengukus jualannya, bakso, dan bakso tahu. Sembari duduk di teras rumahnya ditemani anaknya yang paling kecil, ia menceritakan pengalamannya.
Dwi telah bekerja selama lima tahun di PT. Sinar Prima Plastisindo (PT SPP), sebuah pabrik suku cadang kendaraan bermotor di kawasan Bekasi ketika ia di-PHK sepihak oleh perusahaannya di awal pandemi. Perusahaan beralasan bahwa mereka sedang merugi sehingga mesti memecat karyawan-karyawannya.
Kabar mendadak itu menimpa Dwi bagai langit runtuh. Dwi punya tiga anak—yang paling muda masih berusia dua tahun, dan dua lainnya masih bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Ia juga punya tanggungan tiga keponakan dan dua orang tua yang sudah sepuh. Dengan tambahan cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya, pemasukan suaminya yang tidak lebih dari Rp4 juta membuat Dwi kelabakan.

Masalah lainnya, perusahaan tidak bisa mempertanggungjawabkan alasan mereka melakukan PHK. Perusahaan tidak gulung tikar—setelah lebih dari 60 orang dikeluarkan, perusahaan mempekerjakan orang-orang baru yang diupah lebih rendah. Selain itu, Dwi dan kawan-kawannya juga tidak mendapatkan pesangon dengan alasan bahwa mereka bekerja dengan sistem kontrak yang bisa diputus kapan saja.
Ini bukan pertama kalinya Dwi dipecat sepihak oleh perusahaan. Pada 2018, Dwi sedang hamil. Ia tidak mendapatkan cuti hamil dan juga dipekerjakan di shift malam—membuat Dwi berangkat kerja pada malam hari dalam keadaan hamil besar dan pulang pagi hari setiap harinya seorang diri.
“Kamu yakin masih mau kerja shift malam di saat hamil besar seperti ini?” seorang staf HRD menanyakannya suatu hari.
“Iya, yakin, pak.”
“Mending resign aja. Suratnya bisa langsung saya bikin.”
Tentu Dwi menolak. Tidak bekerja berarti tidak ada pemasukan untuk keluarganya. Ia juga tidak ditawarkan untuk berganti ke pekerjaan yang tidak perlu pakai shift malam—sebutannya “non-shift”. Satu-satunya penawaran adalah mengundurkan diri.
Undang-undang Ketenagakerjaan telah menyebutkan secara spesifik bahwa perempuan, utamanya yang sedang hamil, tidak bisa secara sembarang dipekerjakan pada jam malam. Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan buruh perempuan hamil antara pukul 23.00-07.00 yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya.
Bagi perempuan, jika tetap dipekerjakan pada waktu tersebut, pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman, menjaga keamanan di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput.
Peraturan ini tidak berlaku bagi Dwi. Hingga usia kandungan masuk bulan ke-9, Dwi tetap bekerja di shift malam seperti biasa, pukul 11 malam sampai 7 pagi. Dwi juga tidak mendapatkan jatah cuti ketika melahirkan. Ia memanfaatkan waktu libur yang saat itu kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.
Ketika aku bertanya tentang status kerja Dwi selama masa hamil, Dwi tergelak dan bilang, “Saya juga bingung.” Pada 2015, saat Dwi pertama kali bekerja di perusahaan tersebut, Dwi tidak mendapatkan surat perjanjian kerja dan ia digaji harian sebesar Rp80 ribu dengan waktu kerja 8 jam.
Ia baru mendapatkan surat perjanjian setelah tiga bulan bekerja di perusahaan tersebut, tetapi ia tetap digaji harian dan tak mendapatkan jatah cuti. Setelah setahun berakhir, kontrak Dwi tak kunjung diperbarui. Sebagai orang yang masih awam dengan hak-haknya sebagai pekerja, Dwi saat itu masih takut untuk mempersoalkan perihal kontrak dan hak cutinya karena khawatir perusahaan justru akan memberhentikannya.
Perusahaan memanfaatkan ketidaktahuan ini dengan memperlakukan pekerjanya secara semena-mena. Mereka hanya diberikan waktu setengah jam setiap harinya untuk beristirahat. Karyawan-karyawan yang izin sakit dipotong gajinya meski mereka telah memberikan surat keterangan sakit dari dokter.
Beberapa hari setelah Dwi melahirkan, atasannya mengabarkan secara sepihak bahwa ia telah diberhentikan. Dwi dianggap tidak lagi mampu untuk bekerja karena ia baru saja melahirkan dan mesti mengurus anak.
Inilah saat pertama Dwi kena pemecatan sepihak. Saat itu, ia tidak punya tenaga untuk memprotes. Ia masih dalam proses pemulihan dan sedang sibuk-sibuknya mengurus anak bayinya. Setelah tiga bulan tidak bekerja, atasannya kembali menghubunginya dan mengatakan hendak mempekerjakannya kembali. Dwi juga tidak menolak. Ia membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya.
Beban Mengurus Anak dan Rumah Tangga
Wiwid, Nurchasanah, dan kebanyakan buruh perempuan lain di Jakarta Utara mencari alternatif pemasukan dengan cara yang paling mereka pahami: menjual hasil masakan mereka. Tidak memungkinkan bagi mereka mencari pekerjaan tetap di tengah kesibukan berangkat ke pabrik atau ke pengadilan setiap hari. Jarak dari rumah ke pabrik sudah memakan banyak waktu, seperti Wiwid yang jarak dari rumahnya di Cibitung ke pabrik adalah sekitar 50 km.
Nurchasanah mencoba membuka lapak kecil di depan rumah. Ia membuat nasi uduk, mi goreng, bihun, hingga berbagai jus buah dini hari, kemudian langsung menjualnya di pagi hari. Jualan itu lebih sering sepi pembeli. Tak banyak orang yang berlalu lalang di sekitar rumahnya. Ada masa-masa ia tak punya uang sama sekali. Selama dua minggu, sisa uang Rp200 ribu mesti ia cukupkan untuk kebutuhan anak-anak dan suaminya.
Berjualan makanan juga menjadi siasat Dwi di Bekasi untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Dwi akan bangun pukul 4 pagi setiap harinya. Ia akan membuat adonan bakso, tahu bakso, dan mi ayam, dan lainnya, untuk kemudian ia masak. Ada sekitar 100 porsi yang ia buat, yang lalu Dwi jual via grup WhatsApp ke para tetangga dan kawan-kawannya.

Sembari melakukan itu semua, Dwi juga mesti bebersih rumah dan menyiapkan makan untuk anak-anak dan suaminya. Anak keduanya yang sedang duduk di bangku SMP akan sekolah secara daring. Suaminya akan berangkat kerja pukul 08.00 di sebuah bengkel.
Dwi menceritakan pengalaman-pengalamannya itu kepadaku sembari menenangkan anaknya yang paling kecil. Si anak sedang merengek minta diajak main di luar rumah dan meminta dibelikan jajanan. Aku menanyakan apakah pekerjaan rumah tangga sehari-hari itu, menjaga dan mengurus anak, menyiapkan makanan, beberes rumah, dan berdagang juga dibagi kepada suami dan mungkin anak-anaknya. Dwi merespons dengan terbahak.
“Suami saya bangun tidur pukul setengah 8 pagi,” katanya. “Setelah itu, ia langsung siap-siap berangkat kerja.”
Apakah ia tidak kewalahan mengerjakan semuanya sendiri?
“Kalau saya sudah capek banget, suami akan bantu cuci baju. Mengepel,” jawab Dwi. “Kalau saya sudah kecapekan banget. Kalau belum, saya gas terus.”
Sarinah, biasa dipanggil Sherin, selaku pengacara buruh dan juru bicara di Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) mengungkapkan bahwa buruh perempuan kerap menanggung beban ganda: mereka bekerja sembari menanggung tugas-tugas rumah tangga seorang diri. “Biasanya, mesti suaminya tidak bekerja, mereka tidak mau membantu.”
Sherin menemukan sejumlah kasus serikat buruh yang masih memalingkan muka dari situasi ini. Masih ada serikat buruh yang tidak responsif gender, tidak menganggap kesetaraan gender itu penting, dan justru mendorong perempuan mengakomodir beban ganda.
“Ketika serikat buruh sudah paham isu ketimpangan gender, mereka akan membangun narasi yang mendorong agar keluarga atau buruh perempuan itu mau menegosiasikan agar pekerjaan rumah tangga dengan suami. Tapi, masih ada serikat buruh yang bilang bahwa perempuan tidak boleh melupakan tugas mereka sebagai seorang ibu ketika mereka aktif berserikat.”
Dalam situasi Covid-19, beban perempuan ini semakin bertambah. Jika ada anggota keluarga mereka yang terinfeksi Covid-19 dan jatuh sakit, beban perawatan akan ditimpakan kepada perempuan. Fenomena belajar secara daring juga membuat mereka mesti mendampingi anak mereka yang masih sekolah belajar dari rumah.
Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam laporan “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” yang disusun oleh UN Women, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dan Indosat Ooredoo: perempuan lebih banyak mengalami penurunan pendapatan selama Covid-19 dibandingkan laki-laki, dan pada saat yang sama perempuan juga kena beban pekerjaan rumah tangga lebih besar.
Berserikat dan Bersolidaritas
Ketika Dwi kembali dipecat pada awal 2020, ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dwi bersama sesama korban pecat sepihak lainnya mulai merencanakan untuk membuat serikat buruh. Didampingi oleh pengacara serikat buruh selama prosesnya, mereka mulai menyadari hak-hak pekerja mereka yang selama ini terabaikan: bahwa perusahaan tidak bisa sewenang-wenang memecat karyawannya dengan alasan efisiensi tanpa memberikan bukti laporan keuangan. Bahwa jam istirahat adalah hak. Antar jemput bagi buruh perempuan yang bekerja di malam hari adalah hak. Cuti haid dan cuti hamil adalah hak.
Berbekal pengetahuan itu, Dwi lewat serikat buruhnya mulai melakukan proses perundingan dengan pihak perusahaan. Suatu siang, ia bersama seorang kawannya menghampiri pihak HRD yang saat itu sedang makan siang di sebuah warung. Di situlah proses bipartit berlangsung untuk pertama kalinya. “Kami nggak melakukan proses bipartit di dalam kantor, atau tempat-tempat lain yang lebih ‘resmi’. Kami lakukan itu di warung depan kantor,” cerita Dwi.
Saat itu, pihak HRD menyayangkan sikap Dwi dan korban-korban pemecatan lainnya yang meminta keadilan atas kasus mereka.
“Ngapain kalian begini?” kata pihak HRD. “Sudah enak-enak kalian.”
“Enak-enak bagaimana? Saya di-PHK,” respons Dwi.
Pihak perusahaan menawarkan untuk mempekerjakan kembali Dwi dan kawan-kawan jika mereka bersedia untuk menandatangani surat pengunduran diri. Mereka akan dipekerjakan dengan status percobaan atau probation selama tiga bulan, dengan upah yang masih dibayar harian. Padahal, setelah bekerja selama lima tahun di perusahaan tersebut, Dwi telah punya posisi sebagai leader sebelum dipecat.
Proses perundingan selama sebulan tidak membawakan hasil. Perusahaan masih bersikukuh untuk memecat mereka. Para buruh korban pemecatan kemudian melakukan mediasi selama tiga bulan bersama dengan pihak federasi serikat, pengacara perusahaan, dan pihak dinas ketenagakerjaan Jawa Barat. Proses ini juga tidak membuahkan hasil.
Dari sinilah para korban berinisiatif untuk berunjuk rasa di depan kantor Yamaha, Honda, hingga Toyota yang mendapatkan pasokan komponen dari perusahaan tempat Dwi bekerja. Aksi unjuk rasa itu juga mendapatkan solidaritas dari buruh-buruh di tempat kerja lain yang juga kena pecat sepihak, hingga totalnya terdapat empat bus berisikan anggota serikat mendatangi kantor-kantor perusahaan otomotif itu.
“PT SPP tidak patuh hukum,” tulis sebuah poster yang dibawa oleh seorang buruh.
“PT SPP harus patuh hukum!!! Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.”
“Yamaha, tegur PT SPP!”

Setelah tiga sampai empat bulan mereka berunjuk rasa, aksi itu akhirnya membuahkan hasil. Akhir April 2021—tepat satu tahun setelah mereka dipecat—perusahaan mengalah dan memutuskan untuk mempekerjakan Dwi beserta lebih dari 40 orang lain sebagai pegawai tetap atau berstatus PKWTT. Mereka kini digaji bulanan, dan berhak atas cuti, termasuk cut hamil.
“Mungkin mereka takut kena tuntutan,” kata Dwi. “Kemarin mereka menyepelekan kami. Ternyata mereka salah. Undang-undangnya sudah jelas.”
Serupa dengan kisah Dwi, para buruh perempuan di Jakarta Utara juga terpantik untuk bergabung dengan serikat buruh semenjak mereka melihat gerak-gerik perusahaan yang mencurigakan. Perjuangan mereka belum tuntas. Masih ada beberapa sesi persidangan di pengadilan. Mereka mesti menyertakan dokumen-dokumen ke pengadilan yang membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan di luar hukum: mereka dipecat dengan alasan perusahaan mengalami rugi dan terdampak pandemi, tetapi setelah itu perusahaan masih beroperasi dan justru merekrut orang baru.
Untuk mendapatkan bukti bahwa perusahaan masih beroperasi, para korban pemecatan masih berjaga di sekitar pabrik setiap harinya, mereka akan memotret pegawai-pegawai yang masih berlalu-lalang keluar masuk pabrik. Begitu pula dengan truk hingga ojek online yang membawa pergi pakaian-pakaian yang telah jadi untuk dikirimkan ke toko atau langsung ke konsumen.
Tetap berdiam di pabrik juga merupakan bentuk protes mereka—bahwa mereka masih bagian dari tempat kerja itu selama perusahaan belum membayarkan hak-hak mereka.
Aku menghubungi kontak PT. Trinitas Mulia Abadi, perusahaan yang memproduksi baju bermerek Lee Vierra, tempat Wiwid, Nurchasanah, dan buruh-buruh garmen lain bekerja. Di Google Maps, tertera keterangan bahwa perusahaan sudah tutup permanen, tetapi nomor teleponnya masih aktif. Ketika pihak perusahaan mengangkat telepon, aku bertanya apakah aku sedang berbicara dengan pihak PT. Trinitas Mulia Abadi. Mereka menjawab, “Bukan. Tapi benar ini perusahaan yang memproduksi Lee Vierra.”
Saat aku memperkenalkan diri sebagai jurnalis dan ingin meminta komentar pihak perusahaan tentang pemecatan para buruh PT. Trinitas Mulia Abadi, pihaknya menolak. “Tidak ada yang bisa diwawancarai. Mbak salah sambung,” katanya. Setelah pemecatan karyawan-karyawannya pada awal 2020, PT. Trinitas Mulia Abadi telah berganti nama PT. Busana Aktif Mandiri. Mereka sebagai PT. Busana Aktif Mandiri juga menolak untuk diwawancarai.
Sementara kontak PT. Sinar Prima Plastisindo, tempat Dwi bekerja, tidak bisa dihubungi.
Memberdayakan Sesama Perempuan
Proses perjuangan selama lebih dari 1,5 tahun yang menguras energi itu tidak mengurangi rasa peduli para buruh perempuan di Jakarta Utara ke satu sama lain. Di sela-sela waktu mereka mengawasi pabrik, mereka yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga akan saling berbagi makanan. Ini cara mereka untuk saling menjaga dan mendukung.
Sembari duduk di terpal yang mereka gelar di sebuah gang kecil di sebelah bangunan tempat pabrik beroperasi, mereka mengeluarkan berbagai camilan dan lauk. Ada onde-onde, pisang, dan keripik pedas yang mereka bawa sebagai camilan. Nasi bungkus, mi goreng, bihun, hingga jengkol mereka bawa untuk makan siang. Sekardus air kemasan gelas juga telah mereka sediakan.
“Kami makan ramai-ramai, yang nggak bawa makanan, kami bagi.”
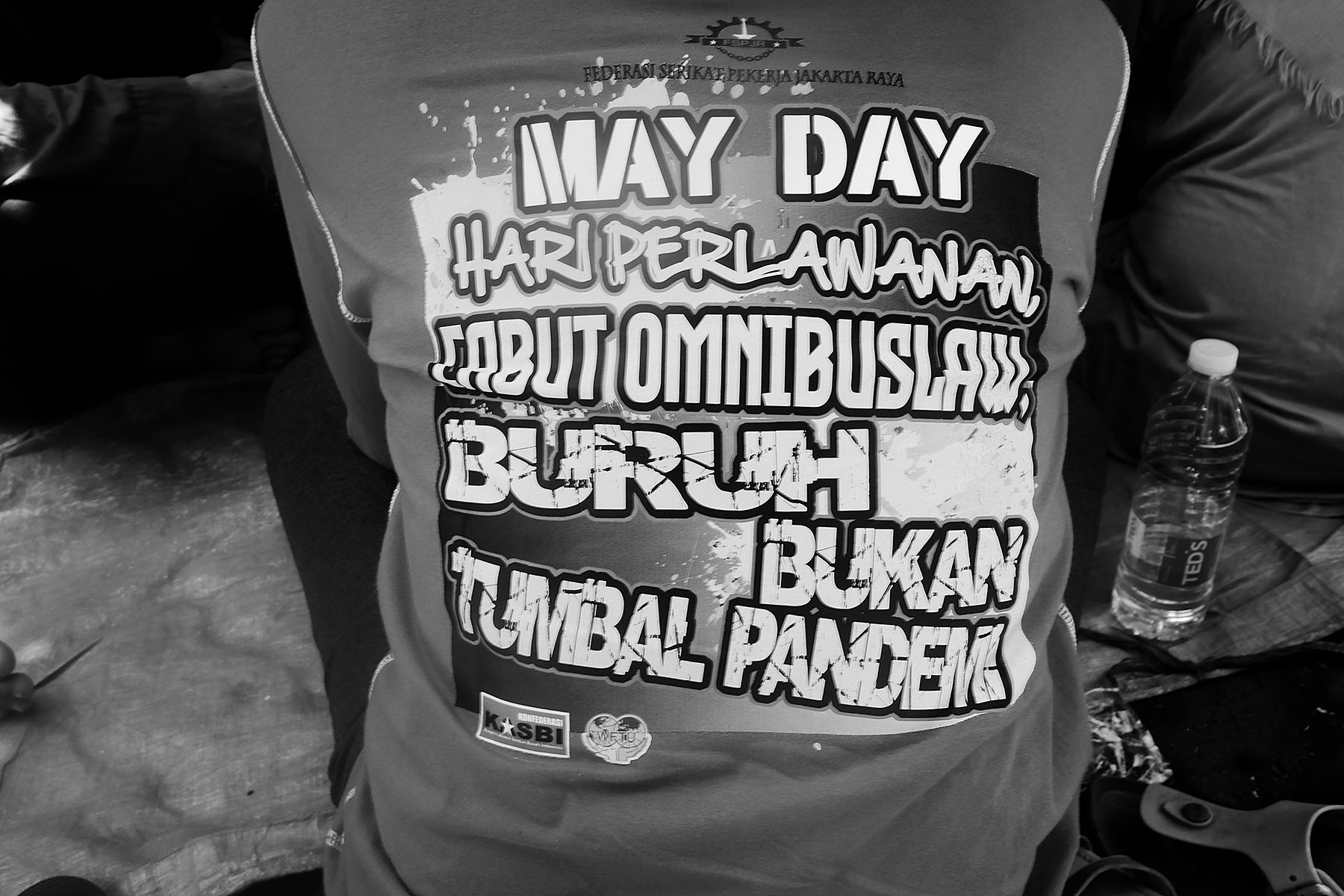
Meski pekerjaan Dwi telah aman, usaha sampingannya berdagang makanan itu tetap ia pertahankan. Ini adalah bentuk jaring pengaman Dwi. Jika suatu saat ia dipecat kembali, ia dan keluarganya tetap bisa bertahan hidup lewat dagangannya. “Jadi saya nggak takut lagi di-PHK. Istilahnya, sudah ada lubangnya untuk usaha,” kata Dwi.
Ia juga tetap aktif berserikat hingga saat ini, dan mereka sedang memperjuangkan hak para buruh perempuan untuk mendapatkan cuti haid. Dwi melihat pribadinya yang berubah signifikan sebelum dan setelah bergabung dengan serikat. Dulu Dwi merasa tak berdaya untuk melawan tindakan sewenang-wenang atasannya, tetapi kini berbeda.
“Dulu saya nurut aja sama atasan, sekarang nggak,” katanya.
Berserikat telah membuatnya mendapatkan kembali pekerjaannya dan memastikan hak-haknya yang lain terpenuhi. Pengalaman ini yang Dwi pegang dan ia hendak teruskan ke para buruh perempuan lain demi saling memberdayakan satu lama lain.
Kami sedang duduk di teras rumah Dwi. Wawancara telah selesai. Dwi menyajikan cemilan-cemilan hasil dagangannya ke diriku. “Semuanya saya bikin sendiri,” kata Dwi.
Ia ikut mencicipi sedikit sembari mengawasi anaknya bermain di depan rumah. Saat itu juga Dwi teringat masa-masa ketika atasan dan beberapa rekan sesama pekerja meremehkan usahanya untuk mendapatkan status pegawai tetap.
“Manajer saya, teman-teman saya, semua pada mengejek,” ujar Dwi.
Saat Dwi sedang bipartit di warung, atasan-atasannya menertawakannya. “Elo mimpi. Masa iya, zaman pandemi gini elo mau diangkat jadi karyawan,” kata mereka.
Dwi hanya tersenyum. “Dalam hati saya—lihat saja nanti. Kalau nanti saya masuk lagi, jadi karyawan tetap, Anda yang malu.”
Tulisan ini adalah bagian dari serial #Perburuhan. Permata Adinda mendapatkan fellowship liputan Citradaya Nita 2021 yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.










