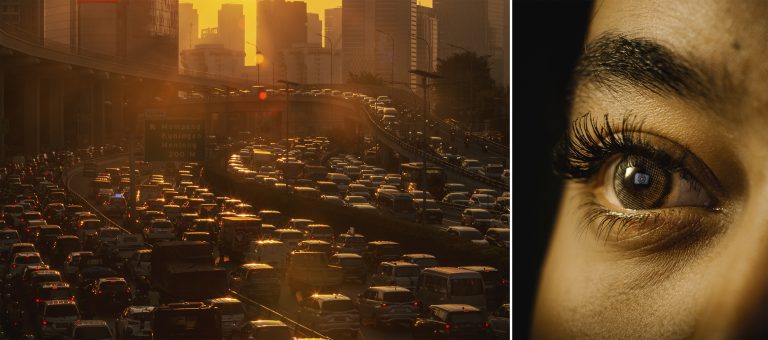I—Rumahku Digusur, Warungku Hilang
Dusun itu telah tiada. Rumah-rumah telah rata. Lahan seluas 364 ha di antara gunung dan laut berganti muka. Dua sumber mata air dengan kicau burung-burung Gelatik Jawa tinggallah cerita. Rerimbun pepohonan pun tinggal warita. Sebelum 1985, lokasi itu jadi tempat meneduh para pelancong saban melintasi ruas jalan raya pantai utara (Pantura).
Dulu, ada sembilan warung makan milik warga di sana. Cabai, tomat, dan sayur-sayuran untuk masakan warung tinggal dipetik dari kebun. Ranting dan batang kayu untuk sumber tungku dapur tinggal diambil dari hutan.
Dusun itu bernama Sumber Gelatik. Terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sekilas dari namanya dusun itu menggambarkan suasana romantis antara sumber mata air dan burung Gelatik Jawa. Sekarang dusun ini cuma jadi sejarah tutur warga sepuh di Desa Bhinor.
Dusun yang dalam bahasa Madura disebut bherghete itu berubah jadi kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. Dulu, sebelum perusahaan produsen listrik itu berdiri, dusun ini dihidupi 13 keluarga pegawai Perhutani. Keluarga Martini adalah salah satunya.
Rumah Martini dulunya menempati yang sekarang jadi lokasi cerobong PLTU. Ia menghidupi keluarganya dengan berjualan warung makan. Pembelinya adalah para sopir dan kernet truk. Dalam sehari warung makannya bisa membutuhkan 20 kg beras dan 6 ekor ayam kampung.
“Jadi pembelinya banyak,” kenangnya. “Tempatnya ada sumber mandi. Ada dua sumber mata air. Ada tempat teduh yang biasa orang berhenti untuk istirahat.”
Di tempat itulah Martini menghidupi separuh usianya. Saat kecil, saban bulan gelap, ayahnya suka mengajaknya untuk nyolo alias mencari ikan di malam hari.
Laut di dekat Sumber Gelatik tak cuma berlimpah ikan tapi juga masih banyak kuda laut dan bintang laut. Mangrove tumbuh rapat di sekitar pantai. Terumbu karang masih lestari, yang jadi titik pencarian ikan.
Ayahnya pun biasa mengajak Martini mencari madu hutan. Mereka biasa pulang membawa 2-4 botol madu hutan untuk selanjutnya dijual.
Saat remaja, Martini mulai belajar membuat kerajinan tangan dari kulit kerang berkat pernah berkunjung ke Pantai Pasir Putih di Situbondo. Ia membuat bermacam hiasan seperti bunga anggrek, burung dara, hingga merak.
Tapi peruntungannya saat membuka warung makan. “Warungku ramai,” katanya.
Meski begitu, peruntungannya cuma sebentar. Lima tahun kemudian, pada 1985, keluarga Martini mesti angkat kaki dari Sumber Gelatik. Mereka tahu bahwa tanah dan rumahnya berdiri di atas lahan Perhutani. Lahan itu akan dipakai untuk PLTU Paiton.
Keluarganya diberi kompensasi untuk relokasi warung makan sebesar Rp2.950.000. Mereka juga diberi janji.
“Orang PLN, enggak tahu PLN pusat atau mana, katanya kalau ada proyek, anak-anak di sini diutamakan,” ujar Martini, saat ini berusia 64 tahun.
* * *
Usia 26 tahun, pada 1985, Martini pindah ke Dusun Krajan, Desa Bhinor. Ia membeli sepetak lahan di tepi ruas jalan Pantura Paiton seharga Rp3.000/meter. Ia kembali membuka warung makan. Namun, lokasi warung tidak sestrategis dulu karena tak ada air dan tak ada tempat parkir.
“Di Krajan aku enggak dapat pembeli.” katanya.
Putus asa dan jengkel, ia sempat sewot kepada sembarang polisi yang dilihatnya di depan Balai Desa Bhinor.
“Saya hanya disuruh makan debu apa gimana?”
“Loh, Bu, jangan ngomong gitu. Kan, dapat kompensasi.”
Protesnya masih berlanjut. Ia wira-wiri ke kompleks proyek PLTU Paiton. Mencari peluang membuka warung bagi para pekerja. Tapi, ia dilarang berjualan apa pun di dekat proyek.
“Yawis, sing kuaso siapa?” katanya.
Ia akhirnya membuka warung di ruas jalan Pantura yang hari ini dikenal dengan sebutan Puncak. Tapi, polisi mendatanginya.
“Siapa yang nyuruh di sini?”
“Nggak ada, Pak,” jawab Martini.
“Kenapa mendirikan?”
“Ya namanya pengen makan, enggak ada yang nyuruh.”
“Pokoknya harus dibongkar besok. Kalau enggak, saya panggil alat berat.”
“Nggak usah, Pak. Alat berat larang (mahal). Sampeyan tendang ambek sepatumu, paling yo wis ambruk warungku,” kata Martini menyebut warungnya terbuat dari bambu ala kadarnya.
Kali lain, petinggi PLN memanggilnya. Ia datang bersama suami.
“Dari mana saudara?”
“Dari Bhinor, Pak.”
“Oh ini yang jualan di Puncak. Saudara itu PKI.”
“Hah, Pak, kalau ngomong yang bener. Saya nggak takut mati. Saya cuma takut lapar,” jawab Martini.
Kengototan Martini sampai dibawa ke suatu pertemuan yang melibatkan camat, komandan militer dan kepala polisi di tingkat kecamatan.
Di pertemuan itu, Martini diomeli Kapolsek, “Kalau kerja itu mbok yang halal.”
“Terus menurut Bapak, kalau saya jualan nasi itu halal apa enggak?” jawab Martini.

* * *
Peruntungan Martini datang saat ada tawaran berjualan di kantin yang disewa salah seorang pekerja proyek pembangunan PLTU Paiton. Di kantin itu Martini tinggal menempati saja. Peralatan dapur, tempat tidur, hingga kursi dan televisi sudah tersedia. Ia datang hanya bermodalkan tenaga dan sedikit uang tabungan.
Kantin itu ramai. Setiap Jumat, ia menyembelih 2 ekor kambing untuk para pekerja. Ia mendapatkan kontrak dengan lima perusahaan untuk menyediakan katering, yang pernah melayani 1.200 bungkus nasi dalam sehari.
Pada 1989, pendapatannya Rp6 juta dalam seminggu. Saat itu ia memiliki delapan belas pembantu dengan upah bulanan Rp300-Rp400 ribu.
Lagi-lagi, masa keemasan itu cuma bertahan singkat. Manisnya proyek PLTU untuk Martini hanya sampai tiga tahun. Kontraknya diputus.
“Setelah itu sudah enggak lagi,” kata Martini.
Suatu hari mantan bosnya di PLTU Paiton mengajaknya bekerja di Krakatau Steel di Cilegon, ujung barat Pulau Jawa. Di sana ia disewa untuk menyediakan katering bagi para para pekerja perusahaan penghasil baja tersebut.
* * *
Berkat usaha warung makan pula Martini mengenal seorang pekerja PLTU Paiton yang kemudian jadi suaminya. Suaminya bekerja di sana sejak 1989.
Anak bungsu mereka sempat bekerja di PLTU tapi bukan pekerja tetap. Disebut pekerja overhaul atau outage, warga Bhinor menyebutnya autit alias pekerja musiman saat PLTU butuh perawatan. Biasanya pekerjaan ini cuma sebulan, kadang bahkan cuma seminggu.
Martini menyebut bekerja “jungkir balik” demi anaknya bisa bekerja di PLTU Paiton. Keluarga ini menyekolahkan anaknya hingga lulus pendidikan tinggi di Malang. Setelahnya, anaknya mencoba melamar ke PLTU Paiton.
Maksud Martini, ia mengingat dan ingin menagih janji dulu bahwa proyek PLTU Paiton akan mengutamakan para pekerja dari warga sekitar.
Namun, pihak perusahaan menolak sebab saat itu membutuhkan pekerja yang memiliki pengalaman bekerja selama lima tahun.
Martini masih jengkel jika mengingat janji perusahaan itu. “Orang sini yang brebeken (kebisingan), yang bledukan (kena debu),” katanya.
II—Karena Batubara, Pukat Harimau, dan Jurung
Pada 2018, sebuah kapal tongkang batubara kandas di sekitar pesisir Desa Bhinor. Cuaca buruk. Gelombang menghantam tongkang. Pagar-pagar tongkang pecah. Batubara tumpah.
“Pagarnya keropos, kena ombak rusak, batubara berjatuhan,” kata Zarkasi, nelayan Dusun Pesisir, yang menaksir tumpahan batubara itu seberat 6.000 ton.
Tumpahan batubara itu tidak segera dibersihkan. Dan butuh usaha penyedotan memakai mesin dan penyelam hingga setahun setelah kejadian.
Awalnya penyelam yang terlibat warga sekitar. Setiap hari, dua penyelam mencari titik lokasi tumpahan batubara.
“Tapi lama-kelamaan orang sini nyerah,” kata Zarkasi. “Siapa yang kuat setiap hari selama berjam-jam [menyelam] pakai kompresor?”

Meski tak tumpah di titik terumbu karang dan rumpon (rumah ikan buatan) nelayan, Zarkasi menyebutkan bahwa tumpahan batu bara itu berdampak serius. Ia sempat mendapat keluhan dari salah seorang temannya yang kerap mencari ikan-ikan seperti kakap dengan jaring di pinggiran. Teman Zarkasi itu biasa bekerja di malam hari. Namun beberapa hari setelah tumpahan batu bara itu, ia mengeluh tidak dapat ikan.
“Kalau saya lokasinya agak ke tengah. Tumpahannya itu di pinggiran. Yang berpengaruh itu yang jaring di pinggiran. Banyak yang ngeluh. Banyak nggak dapat. Biasanya ngejaring malem-malam, di dekat karang-karang. Itu banyak mengeluh, sudah beberapa hari nggak dapat,” ujar Zarkasi.
Secara jarak tangkap, Zarkasi mengaku bahwa tak ada perubahan berarti. Ia memang kerap mencari ikan agak ke tengah, berbeda dengan nelayan lainnya. Namun ia mengaku bahwa dulunya di wilayah pinggiran itu, dulunya, banyak ikan. Sebelum ada PLTU, dulu nelayan kerap mendapatkan hasil banyak dengan memancing dan menjaring.
“Sekarang sudah nggak ada. Itu teman saya buktinya. Air panasnya itu yang dibuang ke laut, itu yang unit 9. Unit yang lain juga dibuang ke laut, tapi jadi satu di timur. Itu langsung mengalir ke tengah. Kalau yang unit 9 itu mengalir ke sini. Wong kalau malam air di sini hangat,” ungkap Zarkasi.
Di titik itu, nelayan Bhinor mengalami dampak ganda yang berkepanjangan. Ruang hidup mereka rusak dan mau tak mau beberapa warga juga mesti bekerja menjadi penyelam untuk menyedot batu bara dengan mempertaruhkan kesehatan. Mereka menyelam menggunakan kompresor dan mencari titik tumpahan batu bara.
***
“Kalau hasil tangkapan lebih enak dulu daripada sekarang. Kenapa? Ya gara-gara batu bara itu lagi. Proyek PLTU. Ikan itu nggak begitu, sudah jarang. Kan kotoran debu batu baranya itu berserakan sampai ke tengah laut. Ikan akhirnya nggak kayak dulu lagi,” kata Zarkasi.
Zarkasi mengisahkan tatenger (penanda) yang biasa ia lihat untuk mengetahui keberadaan ikan-ikan besar adalah ikan teri yang ngaton muncul ke permukaan. Biasanya ikan-ikan besar itu akan mengejar dan memangsa ikan-ikan kecil itu. Zarkasi dan Suaidi akan mematikan mesin perahunya dan melempar kail saat melihat rombongan ikan teri itu.
Hanya saja, kondisi itu berubah. Suaidi dan Zarkasi tak lagi memiliki tatenger. Ikan-ikan teri tak lagi muncul. Akibatnya, ikan-ikan besar susah terdeteksi. Musababnya adalah adanya paparan abu-abu halus debu batu bara yang mengapung, memanjang, dan bertebaran di laut Bhinor.
“Kalau sekarang sudah enggak ada. Biasanya ngaton. Itu jadi tatenger adanya ikan besar. Kalau sudah banyak ikan-ikan kecil itu ada ikan besarnya berhenti. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi. Paling ikan cakalang saja. Ikan terinya gak ada,” kata Suaidi menimpali.
“Makanan sehari-hari itu [debu batu bara] sudah. Wong itu aja, di perahu itu, cuma berapa hari gak kerja, itu sudah hitam semua. Perahu markir itu. Pas nggak kerja berapa hari itu ya hitam,” kata Zarkasi.
Debu-debu itu, kata Zarkasi, tak hanya berasal dari tempat penampungan batu bara. Namun juga disebabkan pemindahan batu bara dari tongkang yang diangkut menggunakan crane. Tak jarang, Zarkasi melanjutkan, batu baranya justru berjatuhan.
“Banyak sebenarnya jatuhnya batu bara itu di sekitar dermaga,” ungkap Zarkasi.
Penurunan hasil tangkapan ikan bukan penyebab tunggal dari PLTU. Zarkasi menyadari penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan seperti pukat harimau, dan jurung turut menyumbang merusak terumbu karang dan rumpon nelayan di laut Bhinor.
Padahal, kata Zarkasi, terumbu karang itu lunak dan mudah patah. Ketika sudah patah, untuk tumbuh lagi butuh waktu yang tidak sebentar. Kerusakan itu musababnya adalah saat alat tangkap yang digunakan oleh kapal jenis sleret, maupun jonggrang itu mencari ikan di perairan pinggiran.
“Jaring nyangkut di terumbu karang. Akhirnya ikan takut. Ikan yang nyangkut di jaring akhirnya busuk, bau. Kalau sudah bau, ikan jadi nggak kerasan,” kata Zarkasi. “Kan di situ (karang) tempatnya ikan-ikan besar itu di Karang itu.”
Tak hanya sekadar merusak terumbu karang dan rumpon, penggunaan alat tangkap tersebut juga membuat ikan berkurang. Kata Zarkasi, ikan kecil pun pasti terjaring dengan pukat hariman dan jurung.
“Kalau sekarang yang kena jaring saja sudah berapa ton itu. Habis sudah. Yang mau nunggu besarnya masih lama,” imbuh Zarkasi. Kayak kapal seleret itu sekali ngejaring itu sudah berapa dapat berapa ton.”
Zarkasi menuturkan bahwa overfishing di laut Bhinor bukan karena alat tangkap pancing yang biasa digunakan oleh nelayan di desanya. Ia dengan tegas menyebutkan bahwa sekalipun mau memancing seharian, selagi tidak dijaring, ikan tak akan habis. Sebab ikan yang mereka cari adalah ikan besar. Jika kailnya dimakan ikan kecil, Zarkasi mengaku, akan melepasnya.
Sedari awal, Zarkasi menjelaskan, nelayan Bhinor bukan diam saja dengan penggunaan alat tangkap tersebut. Ia cukup sering mewanti-wanti untuk tidak menebar jaring di wilayah pinggiran. Bahkan nelayan Bhinor dan nelayan luar Bhinor pernah duduk bersama dan meneken perjanjian untuk berhenti menebar jaring di pinggiran. Bila ketahuan, jaringnya akan diambil.
“Bahkan sampai dibakar [jaringnya]. Sering sudah. Sampai dibuatkan ranjau juga,” ujar Zarkasi.
* * *
Di barat, matahari perlahan surup. Ombak-ombak kecil di Pantai Dewi Harmoni, sore itu, menggerakkan sampan-sampan nelayan. Di timur, lampu-lampu PLTU Paiton berpendar di permukaan air laut. Cerobong besi itu mulai mengeluarkan asap. Gemerlap perusahaan produsen listrik tersebut menyimpan cerita-cerita sedih akibat perubahan kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
“Tadi kerja dapat tiga. ikan tenggiri satu ukuran dua kilo satu ons, ikan talang ukuran satu kilo delapan ons, dan ikan giant trevally (GT). Dan itu kecil,” kata Zarkasi.
Zarkasi sudah menjadi nelayan dengan alat tangkap pancing sejak tahun 1996, sedangkan bapaknya, Suaidi telah akrab dengan laut Bhinor sejak tahun 1970-an, jauh sebelum PLTU Paiton berdiri. Malam itu di rumahnya mereka mengisahkan perubahan-perubahan yang terjadi di Bhinor. Termasuk perubahan hasil tangkapan ikan. Suaidi dan Zarkasi biasa mencari dan memancing ikan-ikan besar.
Suaidi masih ingat, saat tahun 1995 ia berhasil menaklukkan ikan kerapu dengan berat 1 kuintal 4 kilo. Kala itu umpan yang ia gunakan adalah ikan putihan hidup seberat dua kilogram. Saat disambar ikan kerapu itu, Suaidi tak menariknya sendirian. Ia dibantu oleh tiga orang temannya. Perahu yang ia tumpangi sampai miring ketika menarik ikan tersebut.
“Kalau ikannya ngelawan terus ditarik sudah. Jangan mengikuti ikan. Kalau mengikuti ikan kalau nggak ditarik, ikannya masuk kedalam terumbu Karang. Ya tarik tambang sudah kalau dulu itu kuat kuatan. Untung-untungan sudah,” kenang Suaidi.
“Pernah juga dapat marlin 5 kilo. Kalau yang kerapu itu tahun 1995. PLTU masih baru. Kalau yang marlin 50 kilo itu, setelah dapat kerapu. Itu pake alat tangkap pancing, kailnya 5,” imbuh Suaidi.
Di lain cerita, suatu waktu, sampan Suaidi juga pernah diseret marlin. Sekira pukul 09.00 pagi umpan dimakan. Suaidi cukup kelelahan meladeni ikan itu. Tangannya panas. Ia pun mengikat senar pancing di perahunya. Ikan itu masih terus menyeret sampan Suaidi hingga ke tengah laut, sekitar 10 kilometer. Hingga akhirnya senar pancing Suaidi putus.
Kenangan lain yang masih kental dalam ingatan Suaidi saat memancing di sekitar terumbu karang Kranji. Kala itu, Suadi dan Zarkasi memancing bersama. Sekira pukul 11.00 siang, umpan Suaidi disambar ikan. Ia pun menarik. Serupa dengan kejadian sebelumnya, ikan itu pun menyeret sampan Suadi hingga ke tengah laut. Hingga sore, ikan itu belum bisa ditaklukkan.
“Sampai saya disusul itu sama ponakan, saya dikirim. Pas bulan puasa waktu itu,” kata Zarkasi menimpali cerita bapaknya.
“Putusnya senar itu Jam 9 malam.”
“Kalau dulu ikan enak masih besar besar. Sekarang kan ikan resoreh (ikan marlin) kan kecil-kecil semua. Kalau dulu 30 kilo, setengah kuintal, 40 kilo. Itu satu ikan. Itu dulu tapi sekarang sudah nggak ada,” imbuh Zarkasi.
Saat ditanya apakah ukuran-ukuran ikan itu masih ada hingga saat ini, Zarkasi tegas menjawab, “Siah, Kaemma. Sobung. (Mana ada. Nggak ada).”
“Paling sekarang lima kilo, enam kilo. Ikan ukuran 10 kilo sudah jarang.”
“Saya masih pernah dapat 15 kilo, 10 kilo kerapu. Umpan kepiting hidup. Itu tahun, berapa ya, lupa saya. Kisaran tahun belasan muda. 2011, 2012,” tegas Zarkasi.
Padahal dulu, saat musim ikan tiba, Zarkasi dan Suaidi mudah mendapatkan ikan-ikan besar. Bahkan tak jarang mereka kekurangan umpan. Mereka biasa menggunakan umpan ikan-ikan hidup. Sebelum menuju spot ikan-ikan besar, mereka terlebih dahulu mencari umpan ikan-ikan kecil ke tengah laut. Setelah umpan terkumpul, mereka akan ke wilayah pinggiran di perairan dangkal.
“Nggak kayak dulu melaut sekarang itu. Dulu dapat Ikan Talang itu kuintalan, setengah kuintal, 70 kilo, sekali nyujuk (umpan dimakan ikan) itu seru. Nggak usah pakai umpan, kailnya saja itu dimakan kalau dulu,” ungkap Zarkasi.

Perubahan itu tak hanya dari alat tangkap pancing. Nelayan Bhinor juga kerap menggunakan bubu (perangkap ikan) untuk mencari ikan. Zarkasi biasa melempar bubu di kedalaman 35 meter di sekitar rumpon. Dulu, sekali pun melempar bubu tanpa umpan, dalam sehari hampir pasti ada ikan yang ia dapat.
“Dilepas pagi, besok diambil. Nginep semalam. Kadang ada yang diambil setelah dua hari kemudian,” kata Zarkasi.
Jika bubu menggunakan umpan ubur-ubur, dalam sehari bisa panen dua sampai tiga kali.
“Sekarang, bubu itu sampai nginep dua hari nggak ada apa-apa. Kadang ada yang nyuri.”
Kondisi itu kian parah karena cuaca yang sulit ditebak. Kata Zarkasi biasanya di bulan Oktober-November itu sudah mulai musim hujan. Namun, pertengahan November, hujan belum juga turun. Kondisi itu juga berpengaruh terhadap musim ikan yang juga tak bisa ditebak.
“Ini nggak hujan. Nggak bisa diprediksi. Kalau dulu bisa, sekarang musim ikan apa, musim ikan apa. Sekarang nggak bisa. Waktunya musim ikan marlin gitu, atau ikan apa, itu nggak ada,” kata Zarkasi.
“Biasanya bulan 7, bulan 8 itu musimnya ikan meladeng, ini ngga ada. Harusnya musim. Tahun sekarang ini sepi,” Suaidi menimpali.
“Mulai musim paling bulan januari ini. Mulai angin barat. Cuma hujannya ini gak ada sekarang,” Zarkasi menegaskan.
Zarkasi menyebutkan bahwa secara penghasilan memang lebih banyak hari-hari ini meski hasil tangkapan terus berkurang. Sebab, dulu, ketika jumlah ikan banyak dan besar, harga ikan murah. Bahkan dulunya tak dikenal konsep jual-beli dengan metode timbangan, melainkan ikan nelayan dihargai per ekor.
“Kalau penghasilan dari segi pendapatan uang lebih enak sekarang ketimbang dulu karena dulu nggak ada timbangan dibeli bijian. Seandainya sejak dulu sudah ada timbangan, ya lumayan banyak dapatnya. Wong sampai nggak kuat mikul orang dulu itu. Besar-besar ikannya,” ujar Zarkasi.
Namun kondisi itu tinggal kenangan. Suaidi dan Zarkasi berkali-kali menegaskan bahwa kondisi laut Bhinor telah berubah drastis. Kini, tangan Suaidi dan Zarkasi tak lagi panas karena menarik ikan-ikan babon. Suaidi tak akan pernah mengalami kisah diseret ikan hingga ke tengah laut. Mereka kompak menjawab bahwa hasil tangkapan ikan lebih banyak dan besar dulu, sebelum PLTU berdiri.
“Berkurangnya itu pelan-pelan.”
* * *
Suaidi memulai berkenalan dengan laut Bhinor sekira tahun 1970. Usianya baru lima tahun, kala itu. Mulanya, ia hanya ngojhur (minta ikan ke nelayan) lalu menjual. Uang itu bukan Suaidi pakai untuk sangu sekolah maupun jajan, tapi ia memberikannya kepada emaknya. Saat menginjak kelas tiga Sekolah Dasar (SD), Suaidi memilih tidak melanjutkan sekolah. Ia pun mulai ikut tetangganya dan belajar mancing.
“Sampai saya pernah dicari sama kepala dusunnya. Padahal saya mancing. Dapat ikan, dijual, dapat uang dikasi ke emak. Buat beli jagung. Kalau sekarang kan beli jagung sudah diselip. Kalau dulu masih bulat itu. Masih buah. Jadi pulang mancing itu saya ndak nemu nasi. Melas. Jagung itu sek digilis. Kadang ikan itu ditukar tape, jagung, tales, orang dari gunung itu turun. Jadi ya makan itu saja. Sehari makan sekali ya sering,” kenang Suaidi.
Seiring berjalannya waktu, ia mulai akrab dengan laut Bhinor. Di tahun 1985, PLTU Paiton mulai proses pembangunan. Suaidi sempat kerja kasar di proyek tersebut. Ia bekerja untuk membabat lahan. Dengan gaji Rp1.000-1.500 per hari. Namun pekerjaan itu tak lama, hanya lima bulan.
Tahun itu, Suaidi sudah memiliki perahu. Setelah berhenti dari kerja proyek itu, pekerjaan selain memancing, Suaidi menyewakan sampannya untuk ojek pekerja kapal barang. Dalam sehari harga sewanya sebesar Rp20.000. Namun bonus yang ia dapat Rp.40.000. Ia bekerja hanya lima bulan, dan hasil pekerjaan itu Suaidi tabung dan terkumpul sebesar Rp1.300.000. Ia
“Lama kelamaan karena saya nggak punya tanah akhirnya beli tanah ini. Minta 1.300.000 dulu. Pindah ke sini tahun 1997-98,” kata Suaidi.
“Saya ngojek orang di kapal besar, kayak servisan sekarang ini.”
***
LAUT yang tak bisa diandalkan membuat Suaidi dan Zarkasi memutar otak mencari alternatif pemasukan. Salah satu adaptasi dan alternatif yang dilakukan nelayan Dusun Pesisir, Desa Bhinor adalah menyediakan jasa ojek perahu bagi pekerja tongkang.
Bagi masyarakat setempat pekerjaan itu kerap disebut sebagai servisan. Biasanya mereka akan membawa pekerja tongkang ke daratan dan membantu membawakan belanjaan. Zarkasi dan Suaidi pun melakukan hal serupa. Kata mereka, setiap nelayan pasti memiliki pelanggan masing-masing.
“Biar nggak rebutan,” kata Zarkasi.
Tarif nyervis ia akan mendapatkan tiga jeriken solar, yang jika diuangkan, kata Zarkasi, sebesar Rp400.000 dalam sehari. Ongkos tersebut bisa untuk dua-tiga kali turun. Tarif lain yang ia terapkan adalah ongkos per orang, yakni Rp150.000 dalam sekali turun ke darat. Harga itu belum termasuk fasilitas membawakan barang belanjaan, berbeda dengan tarif pembayaran dengan solar.
“Orang sini ya servisan itu. Tapi nggak tiap hari.”
“Tapi kebanyakan bayar pakai solar. Kalau selama 2 hari turun orang-orang kapal tongkang dapat enam jeriken. Kalau nggak turun ya nggak ada,” ungkap Zarkasi.
Servisan memang menjadi salah satu pemasukan Suaidi dan Zarkasi. Namun hal tersebut tak setiap hari ada. Pelanggan mereka berdua saja, sudah lebih sebulan tak datang. Sebab, kapal-kapal tongkang itu memang tergantung jadwal, terlebih pelanggan mereka bukan perusahaan yang dikontrak PLTU.
“Kalau nggak dikontrak itu kayak siluman itu. Ya kalau datang, datang. Sekalinya hilang, ya hilang. Kadang 7 bulan kemudian baru mau datang lagi. Itu pun kalau datang. Kadang setahun. Namanya juga siluman.”
Zarkasi mengatakan bahwa ia pernah memiliki pelanggan dua perusahaan yang dikontrak PLTU. Kala itu, servisannya cukup lancar. Dalam sebulan bisa tiga-empat kali. Namun itu tak bertahan lama. Suaidi dan Zarkasi hanya merasakan kondisi itu hanya satu-dua tahun. Setelah itu pelanggannya kembali siluman.
“Di sini banyak yang siluman. Pokoknya kapal-kapal baru itu datang. Dan itu ya untung-untungan datang lagi.”

Suaidi dan Zarkasi juga pernah memiliki alternatif pekerjaan mengantar pemancing. Sistem yang mereka lakukan bukan hanya sekadar mengantar pemancing. Jasa ojek pemancing ini di Desa Bhinor ada dua jenis.
Pertama mengantar-menjemput pemancing ke kapal tongkang tarifnya Rp25.000; kedua mengantar berkeliling dan dibantuin memancing, tarifnya kisaran Rp700.000-Rp1.000.000 sekali memancing dengan maksimal empat orang.
Suaidi dan Zarkasi menerapkan sistem jenis kedua. Ia dibayar untuk mengantar berkeliling bahkan membantu mencarikan spot mancing yang gacor dan membantu memancing. Biasanya mereka berangkat sejak pagi dan pulang di sore hari. Spot yang biasanya mereka tuju adalah rumpon. Namun sebelum itu, biasanya mereka akan mencari umpan hidup terlebih dahulu.
“Saya bantuin mancing juga. Nggak diam aja. Meski dapat banyak, saya nggak ngambil. Paling cuma 1-2 aja. Jadi semua hasil mancingnya dibawa semua. Saya cuma bantuin aja. Sekalipun dapat ikan marlin, kerapu yang besar, ya mereka bawa.”
Namun pekerjaan itu sudah lama tak Suaidi dan Zarkasi lakukan. Sebab, mereka berdua merasa pemancing yang pernah mereka antar justru pindah ke nelayan lain setelah mendapatkan spot gacor. Tak sekali dua ia mengalami pengalaman itu.
Selain itu, Zarkasi mendapatkan pemasukan lain dari jasa sopir mobil. Namun itu pun tak sering. Ia hanya menerima pekerjaan itu dari tetangga-tetangganya.
Saat ditanya pemasukan sehari-hari, Zarkasi menjawab, “Ya, mancing itu dah. Dan hasil mancing sulit sekarang.”
Perubahan hasil tangkapan bahkan membuat Zarkasi menyuruh keponakannya yang juga melaut untuk mencari kerja di tempat lain. Zarkasi menyebut bahwa laut tak lagi bisa dipastikan. Selepas wisuda, berkat bantuan salah satu saudara yang lebih dulu bekerja di PLTU, keponakan Zarkasi juga bisa bekerja di perusahaan produsen listrik tersebut.
“Kalau di laut, sama kayak ayam cari makan dengan mencakar sisa makanan kerja di laut itu,” ungkap Zarkasi. “Dulu juga gitu. Kalau sudah bukan rezekinya, ya berhari-hari nggak dapat.”
III—Kenangan dari Dusun Klompangan
DENGAN celana tiga perempat berwarna krem dan singlet merah, Sutarji menarik tuas gas sepeda motornya. Ia mengajak saya menuju sawahnya yang terletak di Blok Sokonan, Dusun Klompangan, Desa Bhinor. Pria berkacamata itu hendak menunjukkan bahwa tembakaunya gagal panen karena paparan debu jalan tol dan debu batubara.
Sore itu kami melintasi pembangunan proyek jalan tol Trans Jawa Probolinggo-Banyuwangi. Sepanjang jalan debu-debu berterbangan. Truk-truk fuso mondar-mandir mengangkut tanah. Di kanan-kiri dedaunan tak lagi hijau. Semua berubah warna menjadi abu-abu, kotor karena debu.
Kami pun tiba. Kami memarkir motor dan berjalan menuju sawah milik Sutarji. Selama berjalan, Sutarji tak henti-henti merutuk. Truk fuso yang mengangkut tanah itu menjadi objek kekesalan Sutarji karena sawahnya rusak. Tahun ini ia menanam sebanyak 30.000 pohon, yang terdampak debu proyek tol sekitar 18.000 pohon.
“Itu, Cong, sawah saya langsung bersebelahan dengan jalan truk.”
“Ini debu proyek tol, dan debu batubara. Rusak nggak bisa dipanen,” kata Sutarji sembari memegang daun tembakau yang kotor.
Sutarji mengungkapkan bahwa kerugian masyarakat itu banyak. Hanya saja, mereka tak berani bersikap. Mereka memilih diam, sebab urusannya bisa panjang.
“Wah ini proyek negara. Ini proyek tol. Mau menuntut? Ya nggak bisa,” kata Sutarji menirukan pernyataan intimidatif yang pernah ia terima ketika protes.
“Ini kan harusnya nggak boleh. Bukan seperti ini,” imbuhnya.
Sutarji mengaku bahwa paparan debu batubara memang kasat mata dan tipis. Tak setebal debu dari proyek jalan tol. Ketika hinggap di daun, warnanya pun berbeda. Debu batubara hitam, sedangkan debu proyek jalan tol lebih abu-abu kecoklatan. Namun, ia menegaskan bahwa keduanya berdampak pada penurunan produktivitas pertanian miliknya.
“Iya, debu batubara dan ditambah debu jalan tol. Seperti ini kan mutlak. Apalagi tembakau, nggak bisa. Kesuburan ini beda ketimbang tidak ada PLTU,” kata Sutarji.
* * *
Keberadaan PLTU Paiton berdampak ke lahan pertanian milik Sutarji. Komoditas utama yang biasa Sutarji tanam adalah tembakau, padi, dan jagung. Namun hasil panen Sutarji kini semakin menurun, baik secara kualitas dan kuantitas. Ia menyebutkan sejak sebelum ada PLTU ada banyak perubahan mulai dari proses rajang, jemur, hingga hasil panen yang tak sebanyak dulu.
Ketika proses perajangan Sutarji mengaku lebih susah karena pisau rajang mudah tumpul. Sejak ada PLTU setiap 15 menit merajang, pisau mesti diasah. Terlebih diperparah dengan debu pembangunan jalan tol. Perubahan juga terlihat saat proses menjemur tembakau. Ia menyebutkan dari segi warna tak sebagus dulu.
”Kalau dulu itu warnanya kuning bagus dan juga untuk beratnya itu lebih berat dan normal sampai satu plastik itu bisa memperoleh 20 sampai 25 kilo. Ya kalau sekarang dapat 12 kilo itu pun sudah sulit. Paling hanya 10 kilo, 11 kilo,” aku Sutarji.
“Ya jauh, Mas. Jauh banget. Apalagi ada proyek tol. Merusak tembakau,” kata Sutarji.
Secara harga jual, dulu 1 kg tembakau seharga Rp15.000, bahkan kata Sutarji, 1 kg tembakau setara dengan 10 kg beras. Jika dilihat hari ini, harga tersebut memang murah. Namun bila dibandingkan dengan harga beras hari-hari ini, harga tersebut terbilang cukup mahal. Sutarji menyebut bahwa di tahun ini harga tembakau tembus Rp65.000. Hanya saja, ia tak turut merasakan “manisnya” harga tersebut, karena tembakau miliknya gagal panen.
”Karena gara-gara dampak debu PLTU dan sekarang ditambah debu jalan tol. Ya tambah parah.”
Saban musim tembakau, Sutarji menerapkan sistem tumpang sari. Di sela-sela tanaman tembakaunya ia juga menanam cabai. Cara itu ia lakukan untuk menambah pemasukan. Setiap sehabis panen tembakau, ia akan memulai panen cabai. Hanya saja, buah cabai milik Sutarji kecil. Padahal dulu sekalipun cabai rawit buahnya besar.
Sutarji mulai menyadari penurunan hasil panen tembakaunya sejak dua tahun setelah PLTU Paiton beroperasi. “Dapat tiga tahun itu tambah parah.”
Bahkan dulu pernah ada kejadian saat petani panen tembakau, mereka harus membasuh dan membilas daun-daun tembakaunya ke sungai karena hitam terpapar debu batubara. Setiap petani membawa dua timba besar. Satu timba untuk membersihkan. Timba satunya untuk membilas. “Rowwet (ruwet), Cong,” katanya.

Tak hanya tembakau, komoditas jagung dan padi kondisinya tak jauh berbeda. Perubahan hasil panen yang Sutarji alami semakin menurun dari tahun ke tahun. Misalnya, ia mengilustrasikan, di luas lahan 350 m2, sebelum ada PLTU berhasil panen jagung seberat tiga ton. Sedangkan hari-hari ini hanya dua ton. Di lahan dengan luas yang sama, hasil panen padi pun menurun. Dulunya tiga ton setengah, kini hanya dua ton.
”Mau dapat dua ton setengah itu susah. Satu ton setengah hilang.”
Sutarji menuturkan bahwa menurunnya hasil panen itu disebabkan oleh menurunnya tingkat kesuburan tanah. Imbasnya, petani mau tak mau menambahkan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Padahal dulunya petani terbiasa membawa hewan ternaknya ke lahan saat seusai panen.
Kondisi itu membuat biaya produksi semakin tinggi. Salah satunya biaya pupuk kimia. Saban tanam tembakau, Sutarji menghabiskan pupuk sebanyak delapan kuintal. Harga satu kuintalnya Rp600.000. Namun tak jarang, Sutarji kerap mengalami kelangkaan pupuk. Akhirnya, kata Sutarji, jika dulu biaya pupuk tidak banyak tapi hasil panen banyak.
“Sekarang, modal banyak ngeluarkan, hasilnya ngurangi. Dulu, modal dikit, hasilnya banyak.”
* * *
“Pohon kelapa saja, semoga saya nggak selamat, misal saya nggak tanam pohon kelapa, banyak saya punya kelapa. Nemu terus. Berangkat ke sawah, kadang nemu empat. Itu dulu. PLTU masih belum ada.”
SABAN pulang dari sawah, Sutarji kerap menenteng minimal dua buah kelapa. Semua kelapa itu ia temukan tergeletak di tanah. Sebab, sepanjang pematang nyiur-nyiur itu tumbuh menjulang. Pohon kelapa subur di Dusun Klompangan, Desa Bhinor. Saking suburnya, tak sekali-dua ia membawa pulang kelapa empat hingga enam buah.
Sutarji memiliki sekitar 30 pohon kelapa yang tumbuh di sawah, tegal, dan di belakang rumah. Saat ingin kelapa muda, Sutarji tak pernah bingung, ia tinggal memanjat pohon kelapa miliknya. Kelapa-kelapa itu biasa jatuh di kala sore hari. “Kalau nggak bisa naik bisa pakai galah, enak,” kata Sutarji.
Tapi, “Itu dulu. Kalau dulu itu pohon kelapa itu subur, dari tegalan ini ngereyep (banyak). Pohon kelapa semua. Termasuk di belakang rumah saya ini,” kenang Sutarji.
“Sekarang, sejak ada PLTU, kena dampaknya batubara, jangankan pohon kelapa, tanam tembakau rusak, kurang bagus. Kalah dengan dulu.”
Sekira tahun 1970-an, pemasukan Sutarji dari pohon kelapa lebih dari cukup. Ia mengaku kebutuhan sehari-hari dapat teratasi dari menjual kelapa yang ia panen dari pohonnya sendiri, atau yang ia dapat di saat menuju sawah. Setiap bulan Sutarji bisa memanen puluhan buah kelapa. Dari 30 pohon yang ia punya, setiap pohonnya bisa mencapai 20 buah. Harga setiap buahnya tak sampai Rp500. Kala itu harga 1 kg beras sekitar Rp250.
Tak hanya melego buahnya, Sutarji juga kerap menjual pohon kelapanya sebagai bahan bangunan. Namun, biasanya, sebelumnya ia telah terlebih dahulu menyiapkan penggantinya. Pohon kelapa yang dijual merupakan pohon yang telah berusia tua dan tak lagi produktif lagi. Setiap pohon dihargai Rp250.000 hingga Rp400.000.
“Nah kalau dulu, zaman belum ada PLTU, semuanya, petani-petani itu paling samporna (sempurna/sejahtera). Tanaman apa saja itu, samporna. Jadi saya itu kerja tanpa ngambil penghasilan saya. Kelapa yang nemu itu yang dijual buat belanja harian. Sampe sekarang, alhamdulillah bisa sehat, bisa menikahkan anak, kan termasuk samporna sudah. Beda dengan sekarang.”
“Loh, sampeyan ini, Mas. Saya ini kalau bicara yang nggak benar, dipermasalahkan sama orang,” kata Sutarji jengkel saat kembali ditanya tentang kondisi pertanian sebelum ada PLTU Paiton.
Hanya saja, kondisi itu kini menjadi dongeng belaka. Sebab, pohon kelapa tak lagi terlihat di sekitar Bhinor. Bahkan di Kecamatan Paiton, pohon kelapa tak lagi tumbuh subur. Pohon kelapa itu habis perlahan. Satu persatu mulai mati. Sutarji menduga matinya pohon kelapa itu karena dampak debu-debu yang menempel di dedaunan kelapa.
”Ketika debu-debu itu nempel di daun kelapa ini akhirnya mati total,” tegas Sutarji.
* * *
Dulu, Sutarji menjadi petani penggarap sembari anggaduh hewan ternak milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Kala itu Sutarji anggaduh sapi dua ekor dengan perjanjian, sebagai perawat, ia berhak mendapatkan dua anak sapi dan si pemilik juga dua sapi.
Ia menjadi petani penggarap di lahan dengan 2000 tanaman tembakau. Namun si pemilik lahan, kata Sutarji, judes. Ia kerap dimarahi. Pernah suatu ketika Sutarji dimaki, karena tembakaunya tak disiram. Ia bukan tak mau menyiram, tetapi airnya tak ada. Sekalipun ada jaraknya cukup jauh. Akhirnya mau tak mau ia mesti berjalan kaki dan memanggul wadah air.
”Akhirnya ya bolak-balik, nyiramnya pake cangkir. Ngimbal (memikul) jauh ngambil air di sungai, terus disiram pake cangkir. Karena dulu itu nggak ada mesin air, nggak ada pompa air.”
Selain menjadi petani penggarap, Sutarji juga kerap mendapat pekerjaan menjadi buruh tani bagian membajak sawah. Di tahun 1980-an ia mendapatkan upah sebesar Rp1.000. Upah itu ia buat beli beras seharga Rp250,00 dan sisanya ia tabung. Di masa itu ia juga mendapatkan penghasilan dari menjadi blantik sepeda motor.
Semua keuntungan itu ia tabung, baik dari hasil menjual kelapa, pohon kelapa, hingga memburuh. Kemudian Sutarji terus menambah tabungan dengan membeli anak sapi dan mulai menggaduh sapinya. Di tahun itu, harga anak sapi masih Rp700.000.
Hingga suatu ketika, Sutarji mengambil gadaian sawah seluas 350 m2. Ia menanam padi di lahan satengnga ereng (satuan luas sawah). Keuntungannya pun ia tabung, sebab kebutuhan sehari-hari dapat dicukupi dengan pohon kelapa. Tabungannya terus bertambah. Sapi-sapi yang Sutarji gaduh ke orang lain dijual untuk membeli sawah.
“Ya tahun 1980-an saya bisa dapat tambahan, sampai mampu beli sawah,” ungkap Sutarji.
* * *
PERUBAHAN kondisi pertanian yang kian menurun itu Sutarji atasi dengan menjual arit. Sekitar 15 tahun Sutarji telah berdagang arit. Cara berdagangnya ia berkeliling menjajakannya. Sutarji mengulak arit itu langsung ke pandai besi. Sutarji membeli dengan harga Rp25.000 dan dijual Rp70.000. Sebelum itu ia juga pernah bekerja menjadi buruh kasar di PLTU, hingga saat ini ia kerap menjadi pedagang sapi dan menjadi blantik (makelar) sepeda motor.
“Sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga,” kata Sutarji.
Sejak PLTU dibangun, Sutarji telah menjadi pekerja di PLTU. Cukup lama ia bekerja menjadi buruh industri, tetapi ia tak ingat pasti tahun berapa berhenti. Alasannya kala itu, pihak perusahaan menganggap Sutarji sudah tua. Di saat menjadi pekerja PLTU ia masih menjalankan profesinya sebagai petani. Biasanya sebelum berangkat kerja, ia terlebih dahulu menyelesaikan urusan di sawah. Bila ada keperluan di sawah dan belum waktu jam pulang, Sutarji akan pulang pada jam istirahat.
Kata Sutarji, bekerja di PLTU dan menjadi petani sama-sama menambah pemasukan. Dari PLTU ada harapan setiap bulan ketika hasil panen tak menentu. Namun Sutarji menegaskan bahwa dampak dari PLTU itu bukan omong kosong. Debu-debu batubara itu juga hinggap di rumah-rumah warga di Dusun Klompangan.
Sutarji menekankan, ”Debu ini bukan hanya berdampak kepada orang-orang miskin namun semua orang termasuk orang kaya itu juga terdampak.”
IV—Dampak Kesehatan, Perikanan, dan Pertanian
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) Paiton berdiri sejak tahun 1994. Ada tiga perusahaan yang memiliki dan mengelola pembangkit listrik. Pertama, milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Unit 1 (400MW), Unit 2 (400MW), yang telah beroperasi sejak tahun 1993 dan 1994 dan Unit 9 (660MW) beroperasi sejak tahun 2012; Kedua, PT Paiton Energi, Unit 3 (800MW) beroperasi sejak tahun 2012, Unit 7 & (615MW), dan Unit 8 (615MW) beroperasi sejak tahun 1999; Ketiga PT Jawa Power Unit 5 (610MW) dan Unit 6 (610MW) beroperasi sejak tahun 2000.
Dikutip dari Harian Kompas, dalam sehari limbah dari proses pembakaran batubara, PLTU Paiton menghasilkan debu kasar dan debu halus sekitar 400 ton. Selama satu tahun total volume limbah itu sebanyak 110 ribu ton.
Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan, fly ash dan bottom ash memang dikeluarkan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun pusparagam perubahan baik di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial-budaya terus berlangsung.
Martini, Suaidi, Zarkasi, dan Sutarji hanya empat orang dari 2.737 warga Desa Bhinor yang merasakan dampak dari kehadiran PLTU dan debu-debunya. Debu-debu itu akan berterbangan ke lahan-lahan warga, ke teras-teras rumah, ke laut, hingga mengendap di paru-paru manusia. Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) adalah penyakit yang acapkali diderita oleh warga di sekitar PLTU.
Martini sendiri tak merasakan ada kendala kesehatan. Hanya saja, Martini sadar bahwa lingkungannya tak sehat. Itu sebabnya ia tak mengizinkan cucunya yang baru berusia sebulan setengah keluar rumah. “Takut polusi. Kesehatan,” tegasnya.
Sedangkan Sutarji, ia mengaku saat bekerja di PLTU Paiton tak pernah melepaskan masker, karena dia sadar akan bahaya debu batubara. Sutarji menegaskan bahwa kondisinya yang semakin berumur, ia sesekali sesak nafas. Sutarji tak pernah memeriksakan kesehatannya.
“Saya kadang takut gitu-gitu. Selain rongent juga mahal,” katanya.
Saat ditanya apakah kondisi kesehatannya itu akibat rokok, Sutarji menjawab, “Bukan. Karena kebanyakan debunya batubara ini kan lebih halus daripada debu tol. Debu tol kan kasar, Cong. Kalau debunya PLTU itu halus tapi debunya ke mana-mana.”
“Bahaya tetap, cuma agak samar karena sudah terbiasa terlalu lama.”
Temuan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI JATIM) dalam bukunya berjudul Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah: PLTU Paiton, PLTU Pacitan, dan PLTU Cilacap, menunjukkan data dari Puskesmas Paiton bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2019-2021 ada penurunan, yaitu di tahun 2019 sebanyak 482 pasien; 2020 sebanyak 200 pasien; dan tahun 2021 sebanyak 190 pasien.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa ISPA di tahun 2020 ada 494 pasien rawat jalan di Puskesmas Paiton. Sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 337 penderita ISPA. Masih di dokumen yang sama disebutkan juga pasien Acute Upper Respiratory Infection, Unspecified yang rawat jalan di Rumah Sakit Rizani–sebuah rumah sakit yang berjarak 5,3 KM dari kompleks PLTU Paiton–sebanyak 278 di tahun 2020, dan naik menjadi 359 di tahun 2021.
Sedangkan catatan dari Rumah Sakit Rizani, Paiton, di Januari 2022 tercatat ada 100 kasus ISPA di poli rawat jalan rumah sakit. Sedangkan pada bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 252 kasus ISPA. Pada tahun 2013 Dinas Kesehatan merilis data 10 besar penyakit di Kabupaten Probolinggo. ISPA menempati posisi pertama sebanyak 44.744 penderita. Pada tahun 2022, ISPA turun ke posisi tiga yakni 20.425.
Pada tahun 2011, Cyntia Galuh Puspita, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pernah meneliti kesehatan para pekerja kontrak PLTU bagi coal handling. Respondennya sebanyak 51 orang. Hasilnya adalah sebanyak 50 persen responden memiliki keluhan pernapasan berupa batuk kering, 35 persen responden mengeluh sesak napas, dan 15 persen responden mengeluh banyak dahak.
Ia menulis bahwa bahaya dari debu batubara bagi pekerja apabila terpapar dalam waktu lama dan tanpa perlindungan adalah Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) atau yang sering disebut penyakit paru kronik obstruktif yang dapat dihubungkan dengan 2 penyakit yaitu chronic bronchitis dan emfisema. Gejala-gejala yang dapat ditemukan yaitu sesak nafas dan batuk kering.
Bahkan, Hasil riset Harvard University-Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia tahun 2015 menyebutkan bahwa polusi udara dari PLTU telah menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Penyebab utamanya karena stroke 2.700 jiwa, penyakit jantung iskemik 2.300 jiwa, penyakit paru obstruktif kronik 400 jiwa, kanker paru-paru 300 jiwa, serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan lainnya sebanyak 800 jiwa.
Dalam catatannya itu, mereka menerangkan bahwa PLTU batubara menyebabkan masyarakat terpapar bahan beracun, ozon dan logam berat. Dampak kesehatan yang berat disebabkan partikel mikroskopik (PM2.5) yang terbentuk dari emisi sulfur, nitrogen oksida dan debu. Partikel halus ini menembus ke dalam paru-paru dan aliran darah, menyebabkan kematian dan berbagai masalah kesehatan.
Batu bara yang dibakar memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO2, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2.5. Masyarakat ilmiah dan medis telah mengungkap bahaya kesehatan akibat partikel halus (PM2.5) dari emisi udara tersebut. PLTU batu bara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen.
“PLTU batu bara adalah mesin penebar maut. PLTU mengeluarkan polusi yang membunuh, meracuni udara, menyebabkan gangguan kesehatan dan kerugian yang luas untuk pertanian, perikanan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat,” tulis mereka di laporannya.

Namun, Dewi Korina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo menyebutkan bahwa kondisi lingkungan hidup di Desa Bhinor cukup baik. Kesimpulan itu ia lihat dari dua aspek, yaitu kualitas udara dan air laut.
Kualitas udara, selain evaluasi dari hasil pantau kualitas emisi PLTU yang secara otomatis dan real time melaporkan hasilnya, Dinas Lingkungan Hidup, kata Dewi, juga melakukan pemantauan kualitas udara ambien salah satunya di sekitar kawasan PLTU yang nantinya dihitung sebagai IKU.
“Dan IKU di Kabupaten Probolinggo saat ini tergolong baik, bahkan di tahun 2023 naik dari 82,82 menjadi 83,64 (70 < Baik ≤ 90),” kata dia melalui keterangan tertulis.
Di samping itu kualitas air laut, indikasinya adalah kondisi biota laut dalam hal ini terumbu karang di perairan Bhinor yang berdekatan langsung dengan kegiatan PLTU, berdasarkan hasil pemantauan dari beberapa titik pantau kondisi terumbu karang masih masuk dalam kategori baik s/d baik sekali, mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan terumbu Karang.
Namun, penelitian Dian Saptarini dan Farid Kamal Muzaki pada tahun 2009-2010 yang berjudul Study On Coral Lifeform And Species That Susceptible Of Bleaching In PLTU Paiton Water, ada indikasi kasus coral bleaching ditemukan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton. Coral Bleaching dapat didefinisikan sebagai hilangnya warna dari terumbu karang yang disebabkan oleh berkurangnya suplai energi untuk karang yang berasal dari Zooxanthellae.
Penelitian tersebut dikuatkan juga dengan riset Pratiwi Fudlailah, Mukhtasor, dan Muhammad Zikra, Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2012, berjudul Pemodelan Penyebaran Limbah Panas di Wilayah Pesisir (Studi Kasus Outfall PLTU Paiton).
Temuan mereka menyebutkan coral bleaching salah satu musababnya dipengaruhi oleh limbah air bahang yang keluar dari outlet discharge canal mendominasi penyebaran kenaikan suhu air laut. Dari jarak kurang lebih 125 meter dari mulut kanal kenaikan suhu pada air laut sebesar 4.21°C. Sedangkan jarak kurang lebih 250 meter dari mulut kanal, kenaikan suhu air laut sebesar 3.07 °C.
Pada jarak kurang 500 meter dari mulut kanal, terlihat pengaruh kenaikan suhu air laut berada pada angka 2.17°C. Sedangkan di titik pada jarak kurang lebih 1 km dari mulut kanal, kenaikan suhu yang terjadi adalah 1.61°C.
Dalam riset tersebut menghitung nilai kerugian akibat kerusakan ekosistem terumbu karang di PLTU Paiton. Setiap kenaikan temperatur 33°C kerugian ekonominya sekitar 81 sampai Rp130 juta per tahun. Sedangkan dengan temperatur buangan 38°C sebesar Rp3,4 miliar hingga Rp4,5 miliar, dan di temperatur buangan 40 °C sebesar Rp6 miliar hingga Rp7,3 miliar per tahun.
Riset lain yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Muhamad Jaelani dan Zulfahmi Afifi menunjukkan bahwa pemutihan terumbu karang seluar kurang lebih 726 meter persegi. Dalam penelitian yang berjudul Studi Pemetaan Pemutihan Terumbu Karang dengan Citra Resolusi Tinggi (Studi Kasus: Perairan PLTU Paiton Probolinggo), menyebutkan pemutihan terumbu karang itu disebabkan oleh dua faktor, yakni pemanasan suhu permukaan air laut dan aktivitas dari PLTU Paiton.
“Adanya aktivitas pengerukan untuk pembangunan unit pembangkit baru dan aktivitas pembuangan air hasil proses PLTU turut menyumbang penyebab pemutihan selain disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan air laut sebesar kurang lebih 2 °C,” tulisnya.
Dewi mengatakan setiap industri memang berdampak terhadap lingkungan hidup. Namun, kata dia, ada tolok ukur untuk melihat apakah dampak itu mengarah kepada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ukurannya adalah baku mutu lingkungan dan baku tingkat kerusakan lingkungan.
“Selama kedua kriteria tersebut tidak terlampaui, maka dampak tersebut dapat dikatakan terkendali,” kata dia.
Di samping itu, kerusakan terumbu karang diduga juga disebabkan oleh tumpahan batubara. Dewi mengakui pernah terjadi kejadian tumpahan batu bara pada tahun 2018. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor cuaca akibat hantaman gelompang saat kapal tongkang pengangkut batu bara melakukan pengiriman batu bara ke salah satu unit PLTU Paiton.
“Selanjutnya kapal tersebut dikandaskan di sekitar perairan Bhinor. Sehingga kejadian tersebut belum menjadi tanggungjawab PLTU, melainkan masih menjadi penanggung jawab pemilik kapal tongkang, karena kejadian tersebut terjadi diluar area pelabuhan/jetty PLTU,” ungkapnya.
Sedangkan dalam dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 18-20 November 2020 juga disebutkan tumpahan batu bara di perairan Bhinor, akibat tenggelamnya kapal tongkang PG Nautica 21 bermuatan batu bara milik PT Nusantara Tri Bahari.
Kisah yang dialami Suadi dan Zarkasi menegaskan kerusakan terumbu karang yang mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan. Namun, Achmad Aruman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo berdalih bahwa tidak ada penurunan hasil tangkapan nelayan Desa Bhinor merupakan dampak dari PLTU Paiton.
“Adanya hanya laporan aktivitas penangkapan ikan dari daerah lain menggunakan alat tangkap jaring di atas wilayah perairan berterumbu karang,” kata Aruman dalam keterangan tertulis.
Ia juga mengatakan bahwa alat tangkap yang digunakan nelayan di Desa Bhinor ramah lingkungan yakni berupa pancing dan bubu dengan wilayah konservasi sehingga sumber daya ikan di wilayah tersebut relatif baik. Terkait tumpahan maupun ceceran batubara, Arman menyebut bahwa itu bukan merupakan kewenangannya.
“Tidak ada informasi tentang tumpahan batu bara yang berdampak di sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya.
BPS Kabupaten Probolinggo tak memiliki data spesifik per desa seperti di sektor perikanan. Mereka hanya mencatat data per kecamatan, itu pun hanya empat tahun terakhir, dari 2019-2022. Di tahun 2019, produksi perikanan tangkap penangkapan laut di Kecamatan Paiton sebanyak 7.149,82 ton, tahun 2020 sebanyak 8.340,81 ton, tahun 2021 sebanyak 9.624,91 ton, dan tahun 2022 sebanyak 9.509,75 ton. Dari data tersebut ada peningkatan dari 2019-2021, tetapi menurun di tahun 2022. Sebagai informasi, nelayan di Kecamatan Paiton tidak hanya ada di Desa Bhinor, melainkan juga di Desa Sumberanyar, Desa Pondok Kelor, dan Desa Karanganyar.
Di sektor pertanian, kondisinya tak jauh berbeda. Sutarji dengan gamblang mengisahkan perubahan yang signifikan. Pohon-pohon kelapa telah banyak mati. Produksi padi di Desa Bhinor pada tahun 2000 dengan luas panen 110 ha, yaitu 550 ton. Delapan tahun kemudian dengan luas panen 106 ha, produksi padinya yakni 712 ton. Setahun kemudian kondisi itu mulai berubah perlahan. Di tahun 2009 luas panen 99 ha, menghasilkan 665,28 ton padi. Di tahun 2013-2015 produksi meningkat, kemudian turun lagi di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2020 luas panen menjadi 90 ha dengan produksi padi 585 ton.
Sedangkan komoditas jagung di Desa Bhinor juga mengalami penurunan produktivitas. Di tahun 2000 luas panen jagung 34 ha dengan produksi 159,8 ton. Di tahun 2008 produksi jagung sebanyak 858,4 ton dengan luas panen 160 ha. Di tahun 2014, di luas panen 116 ha mampu memproduksi jagung sebanyak 638 ton. Di tahun 2020 produksi jagung 420 ton dengan luas panen 82 ha.
Tembakau menjadi komoditas unggulan bagi petani di Kecamatan Paiton, termasuk di Desa Bhinor. Bahkan tak jarang mereka menyebutnya sebagai daun emas. Untuk di Desa Bhinor, pada tahun 2001, produksi panen sebanyak 2,565 kuintal di luas 150 ha. Di tahun 2004 menurun menjadi 124 ton di lahan panen seluas 40 ha. Empat tahun kemudian, di tahun 2008 di atas luas panen 72 ha hanya mampu produksi tembakau 8,64 ton. Data BPS Kabupaten Probolinggo hanya mencatat hingga tahun 2015, yaitu di luas 38 ha memproduksi 45,6 ton.
Data tersebut memang tidak bisa menunjukkan bahwa penurunan produktivitas padi itu disebabkan tunggal oleh PLTU Paiton. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo ada penurunan luas panen, yang jika dibandingkan dengan hasil produksi memang terlihat ada peningkatan produktivitas.
Namun pengalaman Sutarji menunjukkan hal yang berbeda. Di lahannya, penurunan hasil panen itu nyata. Musababnya, kata dia, karena unsur hara tanah menurun. Imbasnya, ia mesti menambah biaya produksi dengan membeli pupuk kimia. Bagi Sutarji kondisi itu, petani kian buntung, karena biaya produksi bertambah sedangkan hasil panen menurun. Di sisi lain, Sutarji menegaskan juga ada perubahan secara kualitas hasil panen.
Mahbub Zunaidi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo menegaskan tak pernah ada laporan kerusakan tanaman pertanian akibat limbah batu bara selama lima tahun. “Tidak ada keluhan,” katanya melalui keterangan tertulis.
Saat ditanya matinya pohon kelapa, Mahbub mengatakan bukan karena PLTU Paiton, melainkan akibat serangan OPT Kwangwung atau kumbang tanduk pada 2017.
Faiq El Himmah Kabid Sarana, Penyuluhan, dan Pengendalian Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo saat dihubungi melalui sambungan telepon mengamini pernyataan Mahbub. Kata dia polusi udara dari PLTU Paiton itu tak ada berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Bila ada beberapa orang yang mengeluh, Faiq mengaku tidak tahu karena tidak pernah ada laporan.
Ia juga menerangkan bahwa penurunan produktivitas pertanian itu musababnya macam-macam. “Tidak hanya karena PLTU Paiton saja,” kata Faiq. Namun bisa disebabkan oleh hama, pestisida berlebihan, penggunaan pupuk kimia dan organik yang tidak seimbang hingga benih tidak unggulan.
“Bisa karena unsur tanahnya yang kandungan hara ada di tanahnya itu berkurang tanpa sepengetahuan dari petaninya itu sendiri,” kata Faiq.
“Jadi kalau misalnya kita langsung bilang bahwa produktivitas itu turun karena laporan satu dua orang karena PLTU Paiton. Wah jelas Kita harus melakukan penelitian,” imbuh Faiq. “Di Bhinor itu nggak ada penurunan produktivitas pertanian.”
Saat ditanya tentang penyebab menurunnya unsur hara tanah, Faiq menegaskan bahwa tidak serta merta karena PLTU Paiton. “Penurunan unsur hara tanah yang pasti bukan karena PLTU,” tegasnya. Bahkan saat wawancara via telepon, Faiq meminta salah seorang temannya, Analis Pembenah Tanah untuk menerangkan tentang unsur hara tanah.
“Oh enggak. Kalau umpama unsur hara yang terkandung di tanah daerah Bhinor sana itu karena bisa berbagai faktor. Jadi bukan hanya dari limbah saja. Jadi penggunaan pestisida yang melebihi dosis terus penggunaan obat-obatan yang terus menerus itu bisa mengakibatkan perubahan unsur di dalam tanah,” katanya.
Di sisi lain, ia juga mengatakan bila pemerintah telah mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait limbah, termasuk ada instalasi pengelolaan limbah. Kata dia, bila PLTU Paiton tidak sesuai SOP, pemerintah tidak akan mengizinkan.
“Kalau memang perusahaan itu dari segi pengolahan limbahnya sudah memenuhi SOP memang tidak ada pengaruh ke lingkungan sekitar,” ujarnya.
“Jadi intinya petani ini walaupun ada PLTU berdiri di situ itu gak ngaruh. Sehingga yang namanya petani ya tetap bertani, produktivitas mbako juga baik-baik saja malah tahun ini produktivitas tembakau itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Faiq menimpali dan langsung pamit untuk mengakhiri telepon.
Pelbagai perubahan tersebut membuat indeks kualitas lingkungan hidup di Desa Bhinor menurun. Dalam penelitian berjudul Village Development Index of Probolinggo Coastal Villages Case study: Bhinor Village, Paiton District, Y.E Prasetya, A.R.T Hidayat dan D. Dinanti, menyebutkan bahwa aspek lingkungan hidup mempunyai nilai yang rendah, yaitu 0,33, karena banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan tersebut, terutama dari kegiatan PLTU Paiton.
Raudlatul Jannah, Dosen Sosiologi Universitas Jember menuturkan perubahan adalah sebuah keniscayaan di dunia ini, terlebih di sekitar tapak industri. Biasanya, kata Ana perubahan-yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat, potensi konflik sosial, partisipasi masyarakat, lunturnya identitas lokal, struktur sosial, kesenjangan dan kerusakan lingkungan.
Ia menilai perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan negara atas nama pembangunan nasional. Bagi perempuan yang akrab disapa Ana itu, diksi “membangun” memiliki konsekuensi mengekslusi kelompok sosial tertentu.
“Saya sih percaya bahwa hampir semua kebijakan pemerintah ya itu selalu ada praktik eksklusi pada kelompok yang lain terutama yang yang sifatnya industrialisasi ya,” kata Ana.
Ana melihat semua “keputusan” dalam rangka “pembangunan nasional” pasti ada dua konsekuensi, untung dan rugi. Dalam konteks keberadaan PLTU, sebagai sumber energi yang menyuplai kebutuhan listrik se-Jawa Bali tentu ini adalah bagian dari upaya “membangun” yang berarti adalah upaya yang terencana atau disengaja untuk memenuhi kebutuhan akan listrik yang memiliki dampak ikutan yang luar biasa untuk menggerakkan ekonomi dan membangun/mendorong kesejahteraan masyarakat luas.
“Meskipun, kita tidak boleh menutup mata pada dampak sosial ekologis yang menyertainya. Secara umum, industrialisasi memberikan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya dan ekologis. Mari kita menghitung mana yang lebih banyak dampak positif atau negatifnya,” kata dia.
Secara sosiologis, kata Ana, kondisi tersebut bisa dilihat sebagai fenomena masyarakat risiko. Ia mengutip pendapat sosiolog Jerman, Ulrich Beck, bahwa masyarakat modern telah memasuki fase baru yang disebut sebagai “masyarakat risiko.”
“Ini bukan berarti bahwa risiko tidak ada sebelumnya, tetapi Beck menyoroti bahwa karakteristik risiko telah berubah secara signifikan. Risiko saat ini tidak lagi terbatas pada tingkat lokal atau nasional tetapi bersifat global dan melibatkan dampak jangka panjang,” tuturnya.
“Perubahan yang terjadi di suatu komunitas apabila ada industri ya sudah pasti kesejahteraan masyarakat bisa jadi meningkat meskipun ada kelompok yang akan tereksklusi. ya kan kawasan ekonomi itu banyak loh pendatang ya kan masyarakat lokal apa kabar.”
Perempuan yang sedang menjalani studi Doktoral Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan perubahan-perubahan lain yang terjadi itu salah satu musababnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Padahal dengan konsultasi publik, kata dia, minimal mampu mengurangi risiko inequality.
Salah satu risiko yang paling mengkhawatirkan atas dampak sosial ekologis yang menimpa masyarakat lokal, kata Ana, adalah hilangnya mata pencaharian. Ia menilai kerentanan dan kemiskinan akan meningkat karena ketidakmampuan masyarakat lokal melakukan adaptasi atas perubahan sosial ekologis yang dihadapinya.
“Oleh karena itu, jika masyarakat mampu beralih profesi ke sektor jasa maka itu baik dan bagian dari upaya adaptasi masyarakat. Meskipun, pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan isu ketahanan pangan? di saat nelayan dan petani beramai ramai beralih profesi pasca hilangnya lahan atau sulitnya mencari ikan,” jelasnya.
Ana menegaskan masyarakat miskin menjadi korban yang paling terdampak dari krisis iklim. Pasalnya, hilangnya mata pencaharian membuat kerentanan masyarakat meningkat. Mereka, sebelum ada PLTU, telah rentan karena ancaman kerusakan sosial-ekologis dan kemiskinan. Kemudian kerentanan bertambah dengan adanya PLTU.
“Ya terutama komunitas yang sangat bergantung pada alam.”
Itu sebabnya, Ana menekankan, adaptasi masyarakat dengan perubahan sosial-ekologis yang terpaksa harus mereka hadapi. Bagi Ana adaptasi yang dilakukan harus berbasis ekonomi, karena mata pencaharian itulah yang menjadi basis dari kerentanan masyarakat yang paling tinggi.
Amalya Octaviani, Manajer Program Bioenergi Trend Asia menyebutkan bahwa pengetahuan-pengetahuan lokal petani kerap dianggap tidak memiliki legitimasi untuk bicara saintifik. Perempuan yang akrab disapa Amel itu mengisahkan saat bertemu salah satu petani di Paiton yang menyebutkan bahwa matinya pohon kelapa karena PLTU Paiton. Namun beberapa pihak, baik perusahaan maupun dinas terkait seolah mendelegitimasi argumentasi petani.
“Masalahnya adalah mereka mengalami itu pelan-pelan gitu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kemudian PLTU tidak merekognize pengetahuan lokal mereka gitu,” kata Amel. “Ketika masyarakat menuntut, didelegitimasi. Itu yang terjadi.”

Kata Amel, perusahan harusnya bertanggung jawab, seperti ganti rugi terhadap kehilangan yang dialami komunitas masyarakat di sekitar PLTU dan melakukan pemulihan lingkungan. Ia juga menyitir tentang program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak mempengaruhi pemulihan lingkungan.
“Itu enggak fair gitu. Pada akhirnya itu (CSR) menjadi alat kontrol.”
Di sisi lain, Amel juga menyinggung tentang standar baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya memperbolehkan air bahang dibuang ke laut dengan suhu maksimal 40 celcius. Padahal, kata Amel, air dengan suhu tersebut itu membuat ikan tak lagi betah untuk menerap. Itu sebabnya, setting standarnya rendah. Hal tersebut, bagi Amel, merupakan akar masalah.
“Jadi pada akhirnya sulit untuk mengklaim bahwa ada dampak-dampak yang dialami karena ya kita sudah sesuai standar kok gitu ya kan,” jelas Amel.
Amel juga menyoroti perubahan yang terjadi itu membuat gap ketimpangan kian lebar, baik di sektor perikanan maupun pertanian. Ia mencontohkan di sektor perikanan, ada ketimpangan alat produksi. Kata Amel, hanya nelayan-nelayan yang memiliki kapal dan modal besar yang bisa melaut jauh.
“Tapi kemudian, nelayan yang hanya punya alat produksi, kapal-kapal kecil otomatis sulit kemudian untuk melaut. Karena kalaupun mereka melaut mereka bisa melautnya di tempat yang di situ-situ aja tidak terlalu jauh,” kata Amel.
“Nah itu ketimpangan struktural yang harus kita notice gitu dan itu memperparah dampak krisis iklim yang dialami.”
Wahyu Eka Setyawan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI Jatim) merespon pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dan Dinas Pertanian yang menyebut bahwa masih dalam baku muku dan sesuai SOP. Kata Wahyu, pernyataan tersebut merupakan scientific denial yang membuat pengendalian dan penanggulangan dampak PLTU semakin sulit kontrolnya.
Bagi Wahyu, harusnya bukan sekadar dari batas aman, melainkan harus melihat bahwa paparan hasil residu PLTU itu akumulatif. “Seperti paparan fly ash dan bottom ash atau limbah lainnya. Memang tidak terlalu tampak, tetapi permasalahan satu persatu muncul, seperti ekosistem laut mulai perlahan menurun kualitasnya, pertanian juga bahkan sampai kualitas kesehatan,” kata Wahyu.
Wahyu juga menerangkan, penurunan hasil pertanian memang cukup berkorelasi dengan adanya aktivitas PLTU, meskipun bukan satu-satunya faktor penyebab, karena ada banyak faktor seperti masalah pupuk, obat-obatan, cuaca yang tidak menentu, dan adanya paparan PLTU seperti debu hasil pembakaran atau dikenal sebagai fly ash.
“Ini ditemukan sendiri oleh petani yang saya temui. Dinas Pertanian memang tidak seharusnya mengatakan hal tersebut, tetapi lebih banyak mendengarkan cerita petani, cross check tanpa dalih dan melihat sesuatu secara proporsional. Bukan malah mendiskreditkan temuan petani dan seolah-olah petani keliru, karena yang bertani bukan dinas tetapi para petani, tentu siapa yang lebih paham? Kepala Dinas yang jarang ke ladang atau petani yang setiap hari ke ladang?” tegas Wahyu.
Di samping itu, terkait tumpahan batu bara, Wahyu menilai, pertanggungjawaban mutlak itu harus ada dalam pendekatan pencemaran ekosistem. Meskipun tongkang yang mencemari atau perusahaan penyedianya, tetapi yang memanfaatkan jasanya adalah PLTU. Tentunya PLTU pun harus turut tanggung jawab karena ia memanfaatkan jasanya.
“Sehingga seharusnya ikut tanggung jawab. Meskipun tidak ada aturan baku, tapi secara etika saja.”

Kata Wahyu pengecekan berkala yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu menjadi cukup penting untuk tahu tingkat emisi dan cemaran yang dihasilkan dan untuk mengkomparasikan secara tahun dan pembangkit.
“Sehingga tahu gerak perkembangan dari cemaran dan emisi PLTU untuk mendorong kebijakan phase out atau pengurangan “pemensiunan” pembangkit sebagai bentuk mendorong komitmen transisi energi ke EBT,” jelasnya.
* * *
Menurut laporan bertajuk Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia pada 2019 mencapai 59 gigaton setara karbon dioksida. Penyumbang terbesar emisi itu adalah sektor energi, yakni sebesar 34 persen; 24 persen dari industri; 22 persen dari pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan; 15 persen dari transportasi; dan 6 persen dari bangunan.
Catatan Endcoal.org menunjukkan sejak tahun 2006-2020 setidaknya ada 171 PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas 32.373 megawatt. Pembangkitpembangkit ini ikut menyumbang CO2 yang dihasilkan oleh seluruh PLTU di dunia yang mencapai 258.394 juta ton dengan rata-rata emisi tahunan sekitar 6.463 juta ton. Hal ini sejalan dengan laporan harian Reuters yang menyebutkan jika PLTU adalah sumber emisi terbesar kedua di Indonesia setelah deforestasi, menyumbang sekitar 35% dari 1.262 gigaton setara dengan CO2 per tahun.
Hal tersebut sejalan dengan laporan dari IPCC pada tahun 2014 pada chapter 7: Energy System yang mengungkapkan konsumsi batu bara masif untuk kebutuhan listrik, pada akhirnya akan mendorong peningkatan emisi baik dalam proses menghasilkan listrik maupun saat melakukan penambangan untuk menghasilkan batu bara.
Laporan dari International Energy Agency (IEA) 2021 menegaskan bahwa sektor energi dan proses industri merupakan penyebab utama perubahan iklim dengan kontribusi emisi sebesar 89% dari total emisi global selama tahun 1990-2021.
Dalam melihat musabab krisis iklim dari PLTU, Amel menjelaskan, bahwa hal tersebut mesti dilihat secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Terlebih, kata Amel, jejak karbon dari transportasi pengiriman batu bara mendominasi emisi dari transportasi laut. Di hilir, keberadaan industri-industri yang masih menggunakan energi kotor juga turut menyumbang terhadap krisis iklim.
EMBER merilis laporan terbarunya pada 5 September 2023 terkait lonjakan emisi batu bara per kapita dari negara-negara anggota G20. Dalam riset berjudul G20 Per Capita Coal Power Emissions 2023 menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan kenaikan emisi per kapita tertinggi, yakni 56 persen dari tahun 2015-2022 (+0,2tCO2).
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 dan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025. Salah satu strategi yang digenjot saat ini yakni dengan pensiun dini sumber energi dengan emisi karbon tinggi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memiliki daftar 33 PLTU yang hendak dipensiunkan, salah satunya adalah PLTU Paiton.
Namun, dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dirilis sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), 1 November 2023 lalu menyebutkan bahwa tidak akan ada pemensiunan PLTU sebelum tahun 2030. Pemensiunan paling awal akan dilakukan pada tahun 2035/2036.
Sedangkan, rilis IESR menyebutkan PLTU Paiton merupakan satu dari 12 pembangkit yang semestinya dipensiunkan dalam waktu 2022-2023. Seluruh unit PLTU ini, kecuali unit 3, berstatus subcritical sehingga menjadi prioritas untuk segera dipensiundinikan.
Namun di dokumen CIPP JETP PLTU Paiton bukan merupakan pembangkit listrik yang termasuk dalam proyek pensiun dini. Hanya tercatat ada dua PLTU yang masuk skema pensiun dini, yaitu PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu.
Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dewi menyebutkan, berdasarkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang instansinya evaluasi, secara performa PLTU Paiton masih memenuhi baku mutu lingkungan, baik aspek pengendalian pencemaran air, udara, dan laut. Indikator yang dijadikan rujukan, kata Dewi, adalah tingkat ketaatan perusahaan dan terpenuhinya baku mutu lingkungan.
“Bahkan dari 9 unit PLTU yang ada, 3 (tiga) unit memperoleh predikat Proper Emas. Artinya kondisi PLTU saat ini masih layak beroperasi dan mampu memenuhi kewajiban dan ketentuan di bidang Lingkungan Hidup,” kata Dewi.
Namun, ia mendukung bila ke depan PLTU akan transisi ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan, karena itu tidak hanya menjadi cita-cita negara, tetapi dunia.
“Namun tentunya tidak akan segera dan secepat itu. Pemerintah Pusat sudah memiliki grand strategy terkait dengan program transisi energy, Pemerintah Daerah akan mengikuti dan mendukung setiap tahapan kebijakan yang telah ditetapkan.”
Amel menyampaikan PLTU Paiton sudah selaiknya pensiun. Ia mengutarakan argumennya bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan transisi energi dari energi kotor ke energi bersih. Termasuk agenda phasing out coal.
“Komitmen kita terkait transisi energi untuk mereduksi emisi, ya, terkait perjanjian paris komitmen kita untuk melawan krisis iklim di bawah 1,5 derajat, harusnya itu sudah cukup kuat. Salah satu caranya adalah pensiun PLTU, terutama yang memang sudah umurnya. Tapi kita sampai sekarang nggak tahu mekanismenya seperti apa dari negara untuk pensiun itu,” imbuh Amel.
Pemensiunan PLTU Paiton, kata Amel, tidak termasuk skema pensiun dini, melainkan pensiun alami karena usia pembangkit yang sudah tua. Perbedaan pensiun dini dan pensiun alami terletak di skema pendanaan dan usia beroperasi PLTU.
“Nah pensiun alami berarti ketika kontraknya memang sudah selesai dia harus mulai masuk skema untuk pensiun alami, sudah waktunya selesai nih, tidak bisa beroperasi lagi gitu. Di situ tuh ketika kita katakan pensiun alami,” kata Amel.
Oversupply listrik di Jawa menjadi argumentasi lain dari Amel terkait pemensiunan PLTU Paiton. Meskipun, Amel mengatakan data transmisi jaringan listrik tak pernah dibuka. Namun, Amel menduga produksi listrik dari PLTU Paiton mengalir ke industri.
“Jangan-jangan banyak ke situ. Jadi kita nggak tahu nih listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton mereka salurkan ke mana saja itu kita tidak tahu. Jadi argumen pemerintah selalu ini kan backbone-nya Jawa Timur kalau ini ditutup terus kemudian banyak masyarakat tak bisa dapat akses listrik. Ya dibuka dong data transmisi jaringannya, ke mana saja Paiton itu menyuplai listrik. Tapi itu nggak pernah dibuka,” jelas Amel.
Hal senada, Wahyu menjelaskan alasan PLTU Paiton sudah layak pensiun karena usia pembangkit tersebut sudah tua dan secara teknologi sudah tidak mumpuni. Daripada diremajakan dengan biaya tinggi lebih baik dipensiunkan dan beralih ke EBT. Hal itu sangat terkait dengan emisi yang dihasilkan yang melebihi rata-rata daripada pembangkit yang lain.
Emisi PLTU Paiton, kata Wahyu, setara dengan 3,4 juta ton Co2 sepanjang Januari-Desember 2022, atau sekitar 284 ribu ton per satu bulan. Sementara emisi dari industri itu sekitar 10 juta ton dalam setahun, artinya sekitar 833 ribu ton per bulannya. Jika ditotal ada sekitar 1,117 juta ton per bulan.
“Ini belum sektor lain. Artinya mengurangi emisi PLTU juga akan sejalan dengan berkurangnya emisi pada unit usaha yang selama ini menggunakan energi kotor. Karena dengan pembaruan energi, otomatis juga ada itikad untuk pembaruan produksi untuk ke yang lebih hijau,” jelasnya.
Namun, Wahyu belum melihat ada skema pasti dari pemerintah terkait pemensiunan PLTU. “Hanya sebatas wacana sementara ini. Karena belum ada aturan teknis maupun komitmen mendorong pemensiunan dini.”
Direktur Utama PT PLN Nusantara Power (PNP) Rully Firmansyah, dalam sebuah acara bertajuk Business and Risk Perspective Energy Transformation Talk 2023 menyebutkan PLTU Paiton memang menjadi salah satu pembangkit yang akan dipensiunkan. Namun ia mengaku tak diam saja. Ia mengatakan optimalisasi co-firing menjadi salah satu upaya untuk menghindari upaya pemensiunan.
“PLTU Paiton termasuk PLTU yang direncanakan early retire. Kami nggak diam begitu saja, kami coba melakukan kajian-kajian, kami melakukan diskusi-diskusi dengan manufaktur, dalam hal ini, dengan manufaktur jepang untuk memastikan bahwa PLTU Paiton itu bisa menggunakan biomassa 100 persen,” kata Rully.
Rully menyebutkan telah menyiapkan lahan untuk stok tanaman energi di Nusa Tenggara Timur seluas 50.000 ha. Kata dia, itu menjadi salah satu langkah konkrit untuk menuju net zero emission. Ia mengklaim, PNP di tahun 2022 telah memanfaatkan 230.000 ton biomassa dan berhasil mengurangi emisi karbon setara 251.000 ton co2.
Meskipun, kata dia, penggunaan batu bara masih menjadi primadona. Rully mengklaim bahwa program co-firing 100 persen lebih masuk akal ketimbang pemensiunan PLTU, karena pembiayaan dan investasi yang cukup besar untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan. Ia pun mencontohkan apabila PLTU Paiton diganti dengan panel surya, maka diperlukan kebutuhan lahan yang lebih besar dan luas dalam prosesnya.
“Untuk mengganti 300 mw PLTU batu bara dibutuhkan area sebesar 1500 ha. Bisa dibayangkan Pulau Jawa akan ketutup kalau seluruh PLTU harus diretire atau harus dimatikan,” katanya.
PLTU Paiton menjadi salah satu dari 52 lokasi pembangkit yang dikelola PLN yang menjalankan metode co-firing. Melalui anak usahanya, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menggunakan co-firing biomassa sebagai pencampur batu bara pada PLTU Paiton 1 dan 2. Rata-rata, biomassa yang dibutuhkan sebagai campuran batu bara sebesar 1.000 ton-1.5000 ton per bulan.
Tahun 2022, PLTU Paiton dinilai sukses menerapkan penggunaan biomassa sebesar 20 persen. Biomassa yang digunakan di PLTU Paiton adalah serbuk kayu (sawdust). Namun Executive Vice President (EVP) of Engineering and Technology PLN Zainal Arifin menuturkan bahwa permasalahan co-firing biomassa adalah ketersediaan pasokan.
Zainal mengatakan di PLTU Paiton, untuk tambahan tiga persen itu saja pasokan biomassa harus didapatkan di luar daerah hingga Lumajang. Dia menambahkan, apabila seluruh PLTU di Indonesia mulai menerapkan co-firing, setidaknya kebutuhan biomassa yang diperlukan sebesar 6 juta ton per tahun. Hal tersebut kemudian yang menurut Zainal menjadi masalah sekaligus tantangan di Indonesia.
“Meskipun kita sudah tanda tangan dengan PTPN, dengan Perhutani, tapi kita belum dapat gambaran. Masih bertanya-tanya juga apakah itu nanti cukup dan berlanjut,” jelas Zainal dikutip dari Kumparan.com.
Selama ini PLTU Paiton 1-2 mendapatkan bahan baku biomassa itu dari pengepul sawdust pohon sengon di wilayah Probolinggo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Namun, mereka juga terus berupaya mencari sumber lain. Salah satunya, penanaman pohon kaliandra.
“Tahun ini kita menanami 20 ribu pohon dan tahun lalu juga ada penanaman Kaliandra 20 ribu. Bila membuahkan hasil, bisa menjadikan best material yang bisa digunakan. Namun itu masih jauh ketika membutuhkan target bauran 50 persen. Untuk 1 unit PLTU kira-kira dibutuhkan 1,2 juta hektare lahan,” ungkap Pelaksana Harian General Manager PLTU Paiton 1-2 Anggoro Hadi Novianto.
* * *
Penggunaan biomassa berbasis hutan tanaman energi (HTE) bukan tanpa masalah. Dalam laporan riset Trend Asia yang berjudul “Adu Klaim Menurunkan Emisi” menyebutkan bahwa klaim PLN soal co-firing biomassa pelet kayu sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi energi ternyata tidak terbukti.
Perhitungan matematika yang dilakukan Trend Asia menemukan emisi karbon dihasilkan mulai dari hulu hingga hilir. Emisi dari saat pembangunan HTE dengan cara deforestasi sampai pembakaran pelet kayu di PLTU, itu lebih tinggi dari stok emisi yang bisa dihasilkan seluruh HTE.
Study serupa juga dilakukan Solutions for Our Climate (SFOC). Mereka menyebutkan biomassa pelet kayu justru memiliki faktor emisi yang lebih besar dibandingkan batu bara. Faktor emisi ini dihitung berdasarkan seluruh aktivitas terkait biomassa, mulai dari pembukaan lahan, pemanenan, hingga distribusi dan pengolahan.
Dengan asumsi praktik co-firing biomassa pelet kayu sebesar 10 persen, maka kebutuhan biomassa untuk 107 PLTU yang berkapasitas total 18,8 GW akan mencapai 10,23 juta ton per tahun dan berpotensi menghasilkan total emisi hingga 26,48 ton setara karbon dioksida (CO2) per tahun. Perhitungan Trend Asia menyimpulkan estimasi kebutuhan lahan HTE itu paling sedikit 2,33 juta ha atau 35 kali luas daratan DKI Jakarta.
Emisi itu muncul mulai dari deforestasi, pengelolaan HTE hingga produksi pelet kayu. Alih-alih berkurang, pencampuran biomassa-batu bara ini akan menambah emisi dari PLTU yang dalam RUPTL 2021-2030 diproyeksikan terus naik menjadi 298,9 juta ton CO2e pada 2030.
“Dalam konteks co-firing pada akhirnya untuk tidak dipensiunkan, karena menyumbang bauran energi baru terbarukan, yang mereka lakukan justru adalah memperpanjang usia PLTU yang harusnya pensiun, seperti PLTU Paiton, PLTU Ombilin, dan PLTU Suralaya,” kata Amel.
“Itu memperparah krisis iklim yang terjadi,” imbuhnya.
Amel menyebutkan, program co-firing hanyalah solusi palsu yang akan memunculkan masalah-masalah baru, karena kebutuhan biomassa itu didapat dari penanaman HTE di lahan-lahan Perhutani dengan reclaiming lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat. Kata Amel, hal itu akan berimbas pada land grabbing.
“Ya, itu akan terjadi di Paiton ketika mengembangkan tanaman energi. Pasti akan ada land grabbing, penyingkiran masyarakat, menjadikan masyarakat buruh, itu akan terjadi. That’s why kami bilang memperparah. Kehadiran solusi palsu ini akan memperbesar ketimpangan dan memperparah krisis iklim,” tegas Amel
Di Jawa Timur, kata Amel, ada enam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada di bawah Perhutani disetting untuk menyuplai pembangkit listrik yang menerapkan sistem co-firing yang ada di Jawa Timur. Tak hanya PLTU Paiton, tetapi juga PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban.
“Dampaknya luas, banyak. Itu jalurnya lebih panjang, ranah kerusakannya lebih besar. That’s why kenapa kita harus melawan solusi palsu dalam transisi energi supaya nggak lebih parah krisis iklimnya,” kata Amel.
Klaim bahwa co-firing merupakan salah satu bentuk transisi energi dan menurunkan emisi juga dibantah oleh Wahyu. Ia menyebutkan, co-firing bukan transisi energi, melainkan hanya akal-akalan untuk menunda pemensiunan dini. Meskipun klaim bisa menurunkan emisi sampai 400 ribuan ton karbon.
“Tidak seindah itu,” katanya.
Membangun HTE yang ekstensif, kata Wahyu, berpotensi menimbulkan deforestasi. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) selama ini menunjukkan kecenderungan itu. Ia merujuk data MapBiomas Indonesia, 38 persen lahan dari total tutupan HTI tahun 2019 berasal dari pembukaan hutan alam. Tentunya co-firing dengan biomassa, Wahyu menerangkan, tidak mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan batu bara PLTU.
Data Statistik PLN (2021) menunjukkan penggunaan biomassa sebanyak 282.628 ton, naik signifikan dari 9.731 ton pada 2020. Pada saat yang sama, penggunaan batu bara juga naik menjadi 68,47 juta ton, dari 66,68 juta ton pada 2020.
“Justru praktik ini seolah-olah mengurangi porsi penggunaan batu bara di PLTU, kesannya co-firing ini lebih bersih, rendah emisi. Padahal, porsi biomassa yang dicampur hanya berjumlah kecil, 1 sampai 10 persen, sementara 90-an persennya tetap bersumber dari batu bara. Atau 6-20 %, tetap saja sisanya batu bara,” kata Wahyu.
“Jadi hanya pembakaran dicampur, sehingga secara logis tidak mengubah apapun. Emisi berkurang tapi tak lebih dari 5%, secara umum sekitar 1-3 % saja.”
Baik Amel maupun Wahyu belum melihat komitmen nyata dari pemerintah terkait transisi energi. Wahyu melihat komitmen tersebut juga nihil dari kebijakan yang di Jawa Timur. Dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Timur menjelaskan beberapa rancangan serta strategi dari tahun 2019 hingga 2050. Terdapat 4 prioritas pengembangan energi terbarukan yang ada di jawa timur yaitu energi surya, air, panas bumi dan sampah.
“Belum dapat dikatakan serius dilakukan. Di sisi lain, energi terbarukan di Jawa Timur yang saat ini diupayakan masih berkutat pada PLTP dan PLTA, dalam realitasnya jenis pembangkit listrik ini juga menimbulkan problem atau resiko yang cukup tinggi. Apalagi kebijakan energi sebagaimana tercantum dalam RUED Provinsi Jawa Timur fokus utamanya masih pada dekarbonisasi sistem energi sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim, namun mengabaikan resiko yang timbul terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya,” jelas Wahyu.
Ia juga mengkritisi arah kebijakan energi yang masih bertumpu pada sektor ekonomi. Jika dilihat dari data yang tersedia bahwa pemenuhan pasokan energi terbesar justru pada sektor industri sebanyak 42 persen di tahun 2016. Wahyu menilai, pengembangan pembangkit listrik justru bukan untuk kebutuhan masyarakat sekitar tetapi ke sektor ekonomi skala besar.
“Tentu ini menjauhkan dari tujuan akses yang adil dan merata. Niat EBT tidak untuk mendorong transisi yang sesungguhnya seperti mendorong masyarakat untuk menggunakan listrik dari sumber tersebut, tetapi lebih kepada untuk memenuhi kepentingan industri dan pemenuhan listrik untuk kawasan ekonomi khusus,” katanya.
“Padahal dalam RUED Provinsi Jawa Timur konsep transisi energi berkeadilan telah disinggung untuk menjadi prioritas dalam rancangan kebijakan. Namun jika dilihat dalam implementasinya masih banyak menimbulkan permasalahan baru.”
Itu sebabnya, Wahyu menegaskan bahwa transisi energi berkeadilan itu menjadi salah satu cara untuk memastikan transisi energi yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pasar. Konsep desentralisasi energi, kata Wahyu, menarik, di mana setiap kampung bisa berdaulat atas energi serta memanfaatkan sumber daya di sekitarnya.
Di wilayah Jawa Timur terdapat berbagai wilayah yang memiliki potensi energi yang cukup beragam. Ia mencontohkan di wilayah Madura dan Kepulauan kecil di sekitarnya memiliki potensi energi surya yang melimpah dan dapat dibangun pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil dengan menyesuaikan kebutuhan energi.
“Secara pengelolaan mereka mengerti kebutuhan dan biaya perawatan, serta mereka tahu konsumsi mereka sendiri, sehingga listrik yang dihasilkan akan sesuai kebutuhan. Serta dengan energi lokal di setiap kampung, juga akan mendorong semua orang terlibat, serta mengembalikan lagi hubungan mereka dengan alam yang telah retak,” kata Wahyu.
Amel juga menyitir konsep transisi energi versi pemerintah dengan merubah dari energi kotor ke energi bersih yang less emisi. Di titik itu, ia sepakat. Hanya saja, kata Amel, yang dibutuhkan bukan hanya phasing out coal, tetapi juga transisi dari hal-hal yang industrial ke yang community based.
“Kita mulai mengangkat apa-apa, inisiatif-inisiatif komunitas. Kan mulai banyak tuh inisiatif komunitas terkait renewable energi. Itu yang harusnya itu yang didorong pemerintah. Jadi transisi dari yang industrial ke komunitas. Itu harus dilakukan,” katanya.
Di samping itu, Amel menyebutkan transisi perekonomian mau tidak mau juga mesti dilakukan, dari yang akumulasi kapital ke yang berbasis komunitas. Sebab, emisi yang dihasilkan dari industri yang akumulasi kapital turut menyumbang krisis iklim.
“Jadi transisi energi itu adalah cara untuk kita melawan krisis iklim, cara untuk mereduksi emisi. Kalau misalnya itu mau dilakukan ya itu tadi harus dibarengi dengan transisi yang lain juga enggak cuma energinya aja gitu. Aspek justnya (keadilan) juga harus ada di situ gitu untuk kita merecognize terkait ketimpangan, terkait dampak yang selama ini dialami masyarakat. Bukan hanya sekadar bahan bakunya, tapi juga sistemnya,” terang Amel.
* * *
“Kalau aku ya, aku sendiri, seandainya ada mau gusuran lagi, kalau saya yang penting cocok uangnya saya lepas.”
Pernyataan yang keluar dari mulut Martini itu menunjukkan kepasrahan tatkala hidup berdampingan dengan PLTU Paiton. Perubahan yang terjadi pada hidup Martini justru bergerak ke arah yang menyedihkan. Dengan tegas dan lantang, Martini menuturkan bahwa hidup di Bhinor tak lagi mengenakkan.
“Ya udah, istilahnya gimana ya, dibilang enak, enggak. Dibilang enggak ya enak di sini. Kan orang semua mau cari enak,” kata Martini.
Tak hanya itu, akses air bersih yang terbatas menjadi salah satu alasan Martini tak betah. Kebutuhan air untuk mandi dan mencuci Martini mesti membayar Rp60.000-100.000 per bulan. Itu belum air khusus konsumsi dan menanak nasi, seharga Rp10.000 per jeriken.
“Air PAM (Perusahaan Air Minum) itu kuning kalau buat masak nasi,” ujar Martini.
“Yang tadinya, di sana (Sumber Gelatik) air nggak beli, kayu nggak beli. Aku kayu masak enggak beli, aku pindah ke sini baru beli. Kayu, air, sayuran, istilahnya ada “tunjangan” dari alam. Gratis,” kata Martini.
Saat pindah ke Dusun Krajan, “Entek, bayam aja nggak ada.”
Ada banyak hal yang hilang dari kehidupan Martini sejak PLTU Paiton berdiri. Tak hanya air, dan tanaman. Hewan peliharaan Martini pun tak ada. Sejak pindah dari Sumber Gelatik, 64 ekor kambing dan dua sapi miliknya harus dijual. Sebab, keterbatasan lahan di tempat barunya di Dusun Krajan. Dan kenangan-kenangan indah Martini di bherghete hanya menjadi cerita.
Kondisi itu kian parah karena paparan debu batubara. Saat berbincang di kursi warung makan Martini, ia mengusap telapak tangannya ke meja. “Kalau itu, inilah. Sampeyan kalau nggak percaya, ini sudah dilapi, sek tetap. Apalagi sekarang ditambah debu dari proyek tol,” kata Martini.
PLTU Paiton, kata Martini, memang ada manfaatnya bagi sebagian orang. Namun bagi keluarga Martini, tampaknya tak terlalu ada manfaatnya. Hal tersebut terbukti dari kondisi suami Martini.
“Suamiku rog rog asem, kata orang jawa. Mau makan rog rog asem. Kadang kan ada yang lebat, masih ada yang tua ada yang mudah digerog kan, kadang enggak semua jatuh kan. Itu namanya rog rog asem. Kadang ada, kadang enggak,” jelas Martini.
Martini memang sempat dikontrak PLTU, tetapi tak lama. Kata Martini, bila boleh memilih, ia mending memasak 20 kilo beras–seperti di Sumber Gelatik–tetapi berkepanjangan, ketimbang masak dua kuintal beras tetapi tak berlanjut.
“Sama dengan orang kerja tol gaji murah tapi dua tahun (dikontrak) enggak pergi-pergi. Kalau overhaul memang ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kan tiga minggu, tiga bulan paling poll,” kata Martini.
Kondisi itu membuat Martini tampak putus asa hidup di Bhinor. Bahkan seandainya kondisi itu tak berubah dalam dua tahun ke depan, ia memilih untuk menjual rumahnya dan pindah ke rumah suaminya.
“Aku dua tahun lagi kalau cuman gini terus aku mau pulang ke rumah suami,” imbuhnya putus asa.
“Makanya aku selalu berdoa, mudah-mudahan ada yang gusur gitu. Yang gusur sekarang kan tergantung kita, kalau kita mau dan cocok, kita pergi. Kalau seandainya ada, aku iya (jual) lebih baik pergi. Karena sudah dibilang sehat, enggak. Dibilang enak, enggak. Itu kalau aku pribadi.”
*Martini, Suaidi, Zarkasi, dan Sutarji adalah nama samaran demi keamanan dan keselamatan narasumber.
Catatan: Pada 7 Desember 2023 kami mengirimkan permintaan konfirmasi kepada PT PLN Nusantara Power melalui WhatsApp ke Wiji Dwi Purbaya, Asisten Manajer Umum, Sipil, dan CSR Nusantara Power. Pada 11 Desember 2023, ia membalas, “Masih menunggu arahan dari pusat.” Kami juga mengirim surel ke alamat email yang tertera di situs plnnusantarapower.co.id, [email protected]. Keduanya belum ada respons sampai artikel ini dirilis.