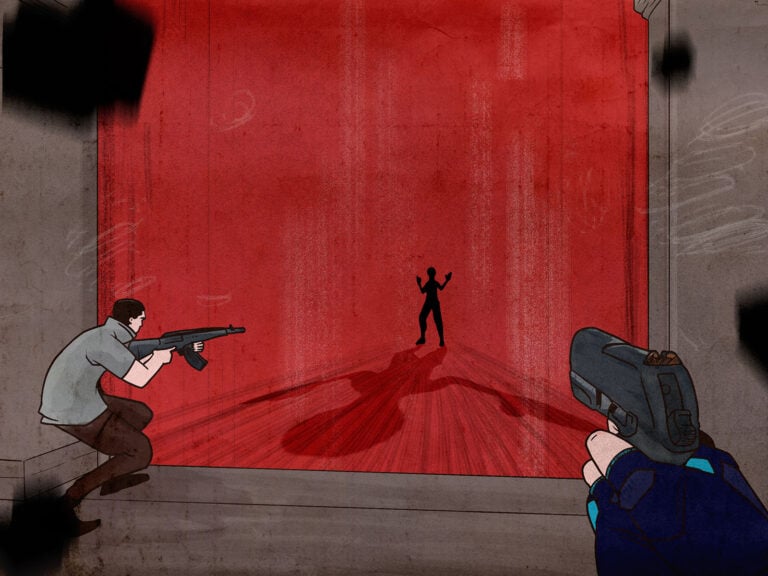Perempuan, termasuk anak perempuan, korban kekerasan seksual memiliki hak yang diatur undang-undang untuk menggugurkan kandungannya. Kendati demikian, kenyataan di lapangan menemukan sebaliknya.
Peringatan: Kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, stigmatisasi aborsi
PEMBUNUHAN. Begitu kata seorang dokter kandungan utusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan 14 minggu.
Dalam sebuah forum diskusi, dokter yang pernah menjabat sebagai kepala sebuah klinik bayi tabung itu mengatakan, “Ini berlawanan sekali. Yang satu susah punya anak, yang satu membuang-buang anak.”
Pernyataan itu ia lontarkan salah satunya untuk merespons pengalaman Melati, anak usia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan pada 2021.
Melati, melalui penuturan pendampingnya, berupaya mengakses layanan aborsi yang sah menurut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
Tetapi, birokrasi di lapangan yang rumit, lamban, dan tidak berperspektif korban membuat Melati gagal mengakses layanan tersebut dan mesti menanggung kehamilan tidak diinginkan (KTD) di usia dini.
Tidak sampai di situ, dokter kandungan tersebut meminta para peserta diskusi yang termasuk di antaranya para aktivis perempuan untuk menonton sebuah film propaganda anti-aborsi yang merekam proses aborsi melalui ultrasonografi (USG).
Film yang ia maksud adalah The Silent Scream yang rilis pada 1984. Film propaganda itu menuai kritik dari komunitas kedokteran di New York karena “menyesatkan”, “tidak adil”, dan menggunakan special effects untuk membuat seolah-olah janin tampak meronta.
Dokter kandungan perwakilan POGI dan IDI itu bernama Ilyas Angsar. Ia memberikan pernyataan serupa dalam ajang penampungan pendapat oleh Kementerian Kesehatan terkait penyesuaian pasal aborsi dalam RUU Kesehatan pada 30 Maret.
“…Bagaimana janin di dalam rahim itu disodok-sodok, divakum, dia tidak bisa mengelak, dan harus meninggal dengan pasrah.”
“Teman-teman yang pro-choice mungkin perlu melihat video itu,” katanya. “Problemnya adalah apakah ada dokter spesialis obgyn yang mau melakukan aborsi 14 minggu?”
Dalam kesempatan yang sama, dokter kandungan lain, Rajuddin dari Universitas Syiah Kuala di Aceh, menyampaikan, “Kalau hal ini diberi usia kehamilan sampai 14 minggu, atas dasar apa ini? Itu bukan pemerkosaan lagi. Itu sudah menikmati hubungan seksual.”
Organisasi profesi IDI dan POGI menolak keras pengecualian larangan aborsi untuk korban kekerasan seksual dengan batas kandungan maksimal 14 minggu.
Mereka mendesak pemerintah mengembalikan batas usia menjadi 6 minggu, sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 terdahulu.
Hanya saja batasan 6 minggu dalam UU tersebut tidak mengacu pada indikasi medis, tetapi merujuk Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 yang membolehkan aborsi untuk korban perkosaan ketika janin berusia di bawah 40 hari atau, dalam kepercayaan Islam, sebelum ruh ditiupkan.
“Kami yang Muslim pasti mengikuti Fatwa MUI. Kita kalau tidak mengikuti ulama-ulama kita akan masuk–akan jadi apa?” kata Ilyas.
Pada Mei 2023, IDI mengadakan forum bertajuk “Kontroversi Aborsi dalam RUU Omnibus Law Kesehatan.” Di forum itu, perwakilan POGI yaitu Wakil Ketua Umum Budi Wiweko dan Ketua Keluarga Berencana & Reproduksi Nurhadi Rahman menyampaikan mereka berpegang pada Lafal Sumpah Dokter yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960.
Sumpah ini diadopsi dari Deklarasi Jenewa pada 1948 atas penyempurnaan Sumpah Hipokrates. Secara global, sumpah dokter telah mengalami amendemen secara berkala sejak 1948. Amendemen itu tidak ikut terjadi di Indonesia.
SUMPAH DOKTER INDONESIA
DEMI ALLAH saya bersumpah:
…
Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
…
***
Pada 2021, Melati yang duduk di bangku SD baru tiga kali menstruasi ketika diperkosa seorang laki-laki paruh baya.
Keluarga mengadukan kasusnya ke Women’s Crisis Center (WCC) di Jombang, Jawa Timur. Usia kandungan Melati sudah memasuki minggu keempat. Sebelumnya, mereka telah melapor ke polsek setempat tetapi tidak ditanggapi dengan serius.
Kata kepolisian, “Jangan sampai menggugurkan kandungan. Nanti berdosa.”
WCC Jombang mendampingi Melati untuk dapat mengakses layanan kesehatan. Tetapi, di tempat Melati tinggal, fasilitas kesehatan tidak ramah korban kekerasan seksual.
Demi akses aborsi, pendamping dan keluarga korban pergi dari satu puskesmas ke puskesmas lainnya untuk mendapatkan rujukan layanan ke tingkat fasilitas kesehatan lebih tinggi. Namun, puskesmas tidak berani memberikan rujukan.
“Di daerah itu susah sekali. Yang mau memberikan rujukan agar korban bisa ke fasilitas kesehatan yang lebih maju, itu sangat susah,” cerita Direktur WCC Jombang yang juga pendamping Melati, Ana Abdillah.
WCC Jombang berinisiatif mengadakan bedah kasus antar-instansi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) Kabupaten Jombang. Di dalamnya terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Polres Jombang, RSUD, dan tim advokat. Akan tetapi, instansi-instansi pemerintahan itu menutup akses untuk Melati.
Kata pihak Dinas Sosial, “Anak sejak usia nol mesti dilindungi.” Pihaknya juga mempertanyakan apakah Melati dapat disebut sebagai “korban perkosaan” seperti yang tertera UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sebab UU Perlindungan Anak tidak mengenal istilah perkosaan.
Pihak RSUD Jombang mendorong Melati untuk melanjutkan kehamilannya dengan meyakinkan bahwa, “Bayinya akan tumbuh menjadi anak yang sehat.”
Seorang kepala dinas mendukung WCC Jombang mendampingi Melati mengakses layanan aborsi. Tetapi, katanya, “Jangan bawa-bawa nama dinas, ya. Secara institusi kami nggak bisa.”
Setiap instansi saling lempar tanggung jawab dan enggan mengambil keputusan. Mereka mempertanyakan kebenaran kasus perkosaan dan mencurigai hubungan dengan anak di bawah umur itu terjadi secara sukarela.
Mereka khawatir kasus itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jombang itu kota santri. Kalau memberikan akses aborsi, nanti banyak korban yang minta aborsi juga.”
Kesimpulan dari bedah kasus, layanan aborsi hanya dapat dilakukan dengan adanya rekomendasi dari kepolisian. Tetapi, Polres Jombang saat itu beralasan mereka tidak berpengalaman sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi.
Kasat Reskrim Polres Jombang juga memperingatkan pendamping Melati mereka dapat dikriminalisasi atas upaya membantu melakukan aborsi.
Ketika akhirnya Melati mendapatkan rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya, satu-satunya rumah sakit umum daerah di Jawa Timur dengan fasilitas yang mumpuni itu menolak memberikan layanan.
Kata mereka, “Janinnya sehat, kok. Tubuh korban bongsor.”
Kehamilan Melati semakin membesar dan lewat dari batas usia 6 minggu.
Pasien-pasien Korban Kekerasan Seksual
Di klinik pribadinya di DKI Jakarta, Belas, bukan nama sebenarnya, kerap menemui pasien-pasien dengan kehamilan tidak diinginkan karena menjadi korban kekerasan seksual. Belas telah bekerja sebagai bidan selama 19 tahun.
Saking seringnya mendapatkan pasien korban kekerasan seksual, Belas berinisiatif untuk membuka layanan rumah singgah (shelter) bagi mereka yang membutuhkan.
Belas tidak pernah mendapatkan pasien korban kekerasan seksual dengan usia kehamilan kurang dari 6 minggu. Rata-rata kehamilan pasiennya yang mengalami KTD telah berusia 4-5 bulan. Paling rendah berusia 12 minggu.
Beberapa meminta melakukan aborsi. Tetapi, terhalang oleh peraturan hukum Indonesia, Belas tidak dapat melayani mereka. Ada ancaman kriminalisasi bagi tenaga medis dan kesehatan yang berpartisipasi memberikan layanan aborsi di luar hukum yang sah.
Pengalaman-pengalaman itu jadi pergulatan batin di diri Belas. Ia paham bahwa para perempuan yang tidak menginginkan kehamilan itu akan tetap mencari akses aborsi di tempat manapun. Dan mereka berisiko untuk mengakses layanan aborsi yang tidak aman.
“Ada yang bilang ke saya, ‘Kalau Ibu nggak kasih, saya akan cari.’”
“Bahkan ada teman saya sendiri, ‘Gue akan cari. Kalau nanti ada apa-apa sama gue, jangan nyesel ya.’”
Menolak akses ke yang membutuhkan layanan, bagi Belas, adalah hal menyakitkan. “Karena artinya saya menolak. Saya sudah melakukan sesuatu yang unethical dari sumpah jabatan.”
Belas bertemu dengan pasien perempuan yang hamil karena tidak dibolehkan memakai kontrasepsi oleh pasangannya. Perempuan yang diam-diam memakai kontrasepsi tanpa sepengetahuan suaminya. Perempuan pekerja rumah tangga (PRT) yang diperkosa oleh majikan laki-lakinya lalu diusir oleh majikan perempuan (istrinya).
Perempuan yang menyerahkan bayinya ke anggota keluarga lain setelah melahirkan. Perempuan yang menginginkan kehamilan pertamanya, tetapi kehamilan-kehamilan selanjutnya bukan lagi pilihannya.
Sebelum pandemi, Belas mendapatkan pasien seorang anak perempuan yang duduk di bangku SMP. Ia diperkosa oleh pacarnya di kampung halaman. Anak tersebut datang ke Jakarta menemui ibunya yang sedang bekerja, meminta bantuan Belas, dan tinggal sementara di rumah singgahnya. Dengan usia kandungan sudah sekitar 7 bulan, anak itu tak mendapatkan pilihan lain selain melanjutkan kehamilannya.
Si anak dan ibunya hampir meninggalkan bayi yang telah dilahirkan di klinik Belas karena kehamilan tidak diinginkan. Tetapi, mereka mengurungkan niat itu dan membawa serta bayi ke kampung halaman.
“Tapi itu bukan happy ending,” kata Belas. “Karena si perempuan (korban) mengalami banyak hal. Si anak juga mengalami banyak hal. Dibilang anak haram.”
Seorang pasien meninggalkan bayinya setelah melahirkan di klinik Belas. “Bayinya ditinggal dalam keadaan rapi di atas tempat tidur,” cerita Belas. Belas meminta pertolongan dinas sosial setempat untuk menampung bayi yang ditinggalkan. Tapi dinas sosial menolak.
“Mereka nggak mau menerima. Nggak ada anggaran, katanya.”
***
Aborsi sebagai tindak pidana pertama kali diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang lalu diadopsi dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 beserta dengan pengecualiannya.
Pada 2009, ketika UU Kesehatan disahkan, Belas menyaksikan alih-alih UU membuka akses layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan, peraturan itu justru menguatkan stigma di kalangan tenaga kesehatan dan medis.
Pada 2014, aturan turunan UU Kesehatan berbentuk Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi keluar.
Ketua Umum PB IDI saat itu, Zaenal Abidin, kembali menentang layanan kesehatan ini. Pihaknya menilai aborsi untuk korban perkosaan bertentangan dengan Sumpah Dokter dan kode etik kedokteran.
“Jangan ajak kami. Jangan timbulkan pertentangan batin pada seorang dokter,” kata Zaenal Abidin saat itu.
Dalam PP, penyelenggaran aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh “penyelenggara pelatihan yang terakreditasi”.
Kementerian Kesehatan pada 2016 menetapkan Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang “Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.”
Peraturan itu mewajibkan pelayanan aborsi diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri. Organisasi profesi juga harus ikut serta menyusun kurikulum dan menyelenggarakan pelatihan.
Namun hingga kini, Kementerian Kesehatan belum menunjuk secara terang fasilitas kesehatan yang dapat memberikan akses layanan aborsi aman untuk korban kekerasan seksual.
Marcia Soumokil, dokter umum dan Direktur Yayasan IPAS Indonesia, menyorot sederet persyaratan ini justru mempersulit penyediaan layanan di lapangan.
“Dari seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak ada satu pun pelayanan kesehatan yang harus ditunjuk oleh kementerian. Karena kita sudah punya otonomi daerah. Tapi, khusus layanan aborsi aman, harus ditunjuk oleh kementerian,” sebut Marcia.
Belas pernah bekerja di rumah sakit. Ia menyaksikan ketidakjelasan aturan turunan, implementasi dari UU, beserta dengan ancaman kriminalisasi membuat fasilitas-fasilitas kesehatan merancang mekanisme atau SOP mereka masing-masing.
Bukan untuk melayani pasien, melainkan untuk melindungi diri dari kriminalisasi.
Kecurigaan terhadap perempuan yang mengaku diperkosa juga semakin kuat.
“Ada stigma di sana,” kata Belas. Mereka mempertanyakan, “Apa benar diperkosa?”
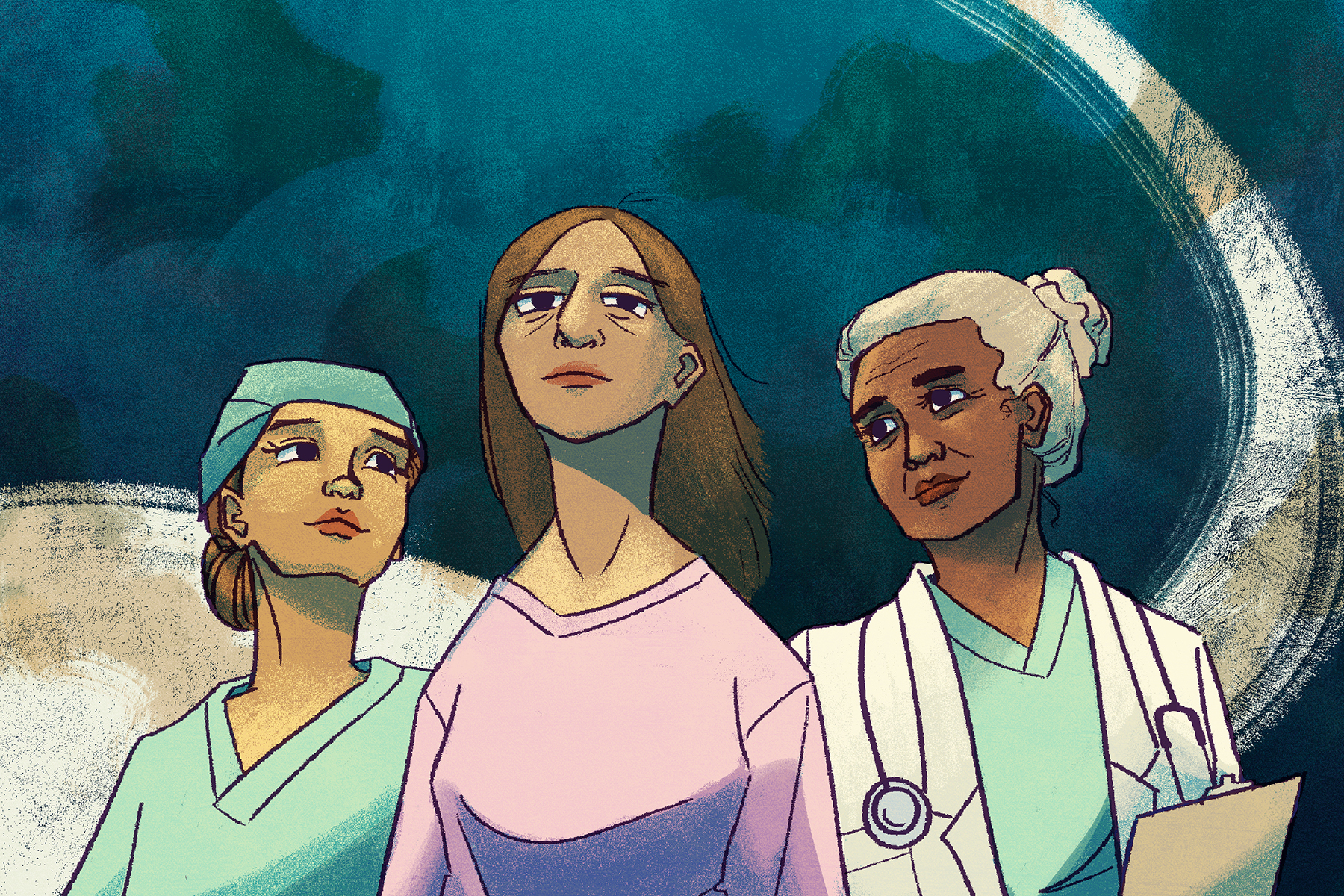
Akses Layanan Aborsi yang Aman
Di Indonesia, dari 2,8 juta kehamilan tidak direncanakan/diinginkan sepanjang 2015-2019, lebih dari setengah di antaranya berakhir diaborsi.
Ketentuan pelonggaran batas usia kehamilan aborsi untuk korban kekerasan seksual pada omnibus law UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, selaras dengan revisi KUHP yang telah disahkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Januari 2023.
Kedua regulasi itu memperluas pengecualian, tidak lagi “korban perkosaan,” tetapi menjadi “korban kekerasan seksual yang dapat menyebabkan KTD.” Ini merujuk pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual secara luas.
Batas usia kehamilan 14 minggu sesuai dengan pedoman terkini World Health Organization (WHO) yang telah memasukkan layanan aborsi sebagai bagian dari layanan kesehatan esensial.
Khusus untuk usia kehamilan hingga 14 minggu, layanan aborsi dapat dilakukan dengan aman menggunakan obat-obatan atau alat bedah sederhana, kata WHO.
Kendati demikian, IDI menawarkan berbagai macam alasan menolak batas usia kehamilan 14 minggu. Salah satunya faktor keamanan.
Dokter kandungan Ari Kusuma Januarto, anggota advokasi IDI dan Ketua Dewan Pembina POGI mengatakan, “Namanya aborsi itu, itu punya risiko. Risiko pada ibunya jelas. Bisa terjadi pendarahan. Infeksi. Pembiusan.”
Ia juga menambahkan bahwa perubahan dari 6 ke 14 minggu justru memberikan peluang bagi lebih banyak perempuan untuk melakukan aborsi.
Samsara, organisasi yang fokus pada pemenuhan akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi, menyimpulkan bahwa pembatasan layanan aborsi sejatinya muncul dari tenaga kesehatan. Pola itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara lain.
Ika Ayu, Direktur Samsara, mengatakan stigmatisasi layanan ini dimulai dengan mengatakan bahwa tindakan hanya akan membawa dampak negatif kepada situasi kesehatan fisik maupun mental seseorang, terlepas dari adanya rekomendasi metode aborsi yang aman.
“Banyak sekali pengalaman korban, perempuan, individu yang dihilangkan,” kata Ika.
Membatasi akses untuk aborsi berisiko membuat perempuan mengakses layanan aborsi yang tidak aman, tetapi tidak mengurangi jumlah perempuan yang mengakses aborsi.
Aborsi tidak aman adalah satu dari lima penyebab utama kematian ibu secara global.
WHO “Abortion Care Guideline” yang terbit pada 2022, merekomendasikan aborsi untuk usia kehamilan kurang dari 14 minggu menggunakan metode bedah vakum aspirasi. Metode ini, terutama aspirasi vakum manual (AVM), direkomendasikan karena lebih aman, cepat, sederhana, dan murah dibandingkan kuretase tajam.
Metode ini dapat digunakan di fasilitas-fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas, karena tidak memerlukan daya listrik, anestesi, dan tidak hanya dapat dilakukan oleh dokter.
Sementara itu, usia kehamilan kurang dari 12 minggu bisa dilakukan dengan obat-obatan seperti mifepristone dan misoprostol yang telah masuk dalam daftar obat-obatan esensial untuk aborsi sejak 2005.
Marcia Soumokil, dokter umum dan Direktur Yayasan IPAS Indonesia, menekankan, “Aborsi dapat dilakukan menggunakan alat bedah sederhana di sistem layanan kesehatan yang sangat standar, bahkan bisa dilakukan di puskesmas di Puncak Jaya (Papua). Syaratnya, alat itu hanya bisa dipakai untuk kehamilan sampai 14 minggu.”
Di Indonesia, metode AVM direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk tindakan asuhan pasca-keguguran, yaitu ketika seseorang mengalami abortus inkomplit atau missed abortion. Tetapi, AVM juga masih terstigmatisasi sebagai metode yang disalahgunakan untuk melakukan aborsi dan belum menjadi standar metode di kebanyakan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Jika mengikuti prosedur yang aman dan legal, layanan aborsi memiliki risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan melahirkan. Riset pada 2012 menunjukkan bahwa risiko terjadinya komplikasi atau kematian akibat melahirkan 14 kali lebih tinggi dibandingkan aborsi aman.
Untuk Tidak Menghalangi Akses
Sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional, RS dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta kerap menerima pasien korban kekerasan seksual yang mengalami KTD dan ingin menggugurkan kandungannya.
Pasien-pasien ini adalah rujukan dari berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Kebanyakan dari fasilitas kesehatan tersebut gamang mengambil keputusan, lalu menyerahkannya ke RSCM.
Tindakan aborsi, secara teknik, bukan hal yang sulit. Perkaranya, kata dokter kandungan Seno Adjie, adalah decision.
“Kadang-kadang saya pikir, kenapa cuma masalah abortus harus dirujuk? Cuma memang mereka agak gamang memutuskan. Tidak mau menjadi masalah di rumah sakitnya dari sisi hukum maupun etik. Sehingga rujuk ke RSCM,” terang Seno.
Kini, Seno menjabat sebagai Ketua Koordinator Pelayanan Obgyn di RSCM.
Untuk pasien yang diduga adalah korban kekerasan seksual, RSCM memiliki tim kelayakan atau komite etik yang akan memutuskan apakah pasien layak mengakses aborsi atau tidak.
Pasien korban kekerasan seksual yang ingin mendapatkan layanan aborsi tidak dapat langsung mendapatkan tindakan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang jadi dasar keputusan tim kelayakan. Mereka akan meminta surat aduan korban ke kepolisian dan hasil visum. Mereka juga akan memeriksa kondisi kesehatan pasien untuk memastikan aborsi dapat secara aman dilakukan.
Jika telah memenuhi persyaratan, tim kelayakan RSCM akan segera melakukan tindakan.
“Biasanya nggak sampai satu minggu. Ketika dilaporkan, langsung dibahas. Karena korban perkosaan ada batas waktu,” ujar Seno.
Tim RSCM tidak mendata jumlah pasien korban kekerasan seksual yang mengakses layanan aborsi setiap tahunnya. Tetapi, Seno mengatakan bahwa setiap tahun selalu ada kasus. “Pasti ada. Dan lebih dari satu kali,” katanya.
Pasien-pasien datang dari berbagai daerah, dari Depok hingga Padang. Ada pula kasus korban perkosaan dengan disabilitas mental. “Oleh tim etik, kami anggap perkosaan. Karena tidak ada consent. Secara hukum sah untuk dikerjakan.”
Dalam perjalanannya, tim kelayakan aborsi juga mempertimbangkan indikasi kedaruratan medis ketika mendapatkan korban kekerasan seksual yang mengalami KTD.
Misalnya, tim kelayakan RSCM menemui pasien anak berusia 10 tahun yang diperkosa oleh tetangga. Kepolisian telah mengeluarkan surat yang menyebutkan ia korban perkosaan. Anak itu mengalami KTD usia 8 minggu.
Tim kelayakan memanggil psikolog anak. Mereka menemukan dampak psikis yang berat jika kehamilan tetap dilanjutkan. “Sehingga, diputuskan ini salah satu indikasi medis. Karena ini medis, lebih dari 6 minggu tidak apa.”
Ada juga perempuan korban perkosaan yang datang ke rumah sakit dengan usia kandungan 27 minggu. Tidak menginginkan kehamilannya, ia berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. “Kami nyatakan ada indikasi medis karena mau bunuh diri. Dikeluarkan.”
Doctors Without Borders dalam situsnya menyebutkan bahwa di banyak negara, hukum aborsi tidaklah hitam putih, legal atau ilegal. Sebagaimana di Indonesia, aborsi dapat sah secara hukum jika bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang yang hamil.
Seno tidak dapat memastikan apakah Kementerian Kesehatan telah secara resmi menunjuk RSCM sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Selama ini, tindakan yang dilakukan RSCM sepenuhnya merujuk pada aturan yang ada.
“Kalau memang hal itu menjadi suatu permintaan utama dari korban dan memenuhi syarat secara hukum, sebagai rumah sakit yang memang mematuhi hukum dan melayani masyarakat, kami bisa melakukan tindakan itu,” kata Seno.
Ia tidak memungkiri perdebatan keamanan batas usia kehamilan 14 minggu di kalangan organisasi profesi. “Beberapa mengatakan makin tidak aman,” kata Seno.
Namun, ia meyakini bahwa aborsi tetap aman selama dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. “Kalau di RSCM, aman-aman saja. Insya Allah mudah-mudahan aman.”
Seno tidak bilang setuju atau tidak setuju dengan aborsi. Ia hanya meyakini aborsi mesti diregulasi untuk menekan angka aborsi tidak aman. “Secara pribadi, saya juga meminta ada perbaikan dari peraturan aborsi kita. Kalau kita ingin mengadakan aborsi yang aman, harus ada perluasan regulasi. Kalau tidak, akan banyak aborsi yang tidak aman.”
Stigmatisasi Berujung Penghalangan Akses
Mengetahui bahwa layanan kesehatan di Indonesia tidak bisa sembarang memberikan akses aborsi, kebanyakan pasien tidak pernah langsung pergi ke fasilitas kesehatan. Mereka memilih mencari cara untuk menggugurkan kandungannya sendiri terlebih dahulu.
Selama delapan tahun berpraktik sebagai dokter umum, Sandra Suryadana mengaku tidak pernah mendapatkan pasien yang terang-terangan meminta akses layanan aborsi.
Permintaan atas layanan aborsi justru kerap Sandra dapatkan ketika ia memberikan layanan via telekonsultasi. Permintaan yang juga ia tidak bisa penuhi. “Mungkin karena mereka tidak berani (datang langsung),” kata Sandra.
Riset Guttmacher Institute dan Universitas Indonesia pada 2018 memperkirakan 43 dari 1.000 perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia melakukan aborsi. Dari jumlah perempuan aborsi, hampir sepertiganya melakukannya sendiri dan sedikit lainnya pergi ke penyedia layanan tradisional atau apoteker. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi jamu atau pijat tradisional.
Awal 2019, Sandra menggagas platform media sosial Dokter Tanpa Stigma (Instagram: @doktertanpastigma). Melalui platform itu, Sandra dan rekan-rekannya kerap mendengar pengalaman buruk seputar layanan kesehatan dari para audiensnya.
Dalam hal kesehatan dan reproduksi, para audiens Dokter Tanpa Stigma mengeluhkan pengalaman pemeriksaan mereka ke dokter obgyn yang tidak ramah perempuan, menceramahi ranah personal pasien, dan mempermalukan pasien.
Ketika masih bekerja di rumah sakit, Belas menemui rekan-rekan kerjanya yang ogah memberikan akses kontrasepsi kepada pasien. Mengetahui pasiennya adalah seorang janda, mereka mempertanyakan permintaan kontrasepsi oleh pasien. “Ngapain KB? Buat apa?” Belas mengulang kata-kata rekannya.
Mereka juga meragukan pengalaman pasien korban kekerasan seksual. “Ikutan goyang atau nggak?”
Belas pernah menghimpun persepsi tenaga-tenaga kesehatan – bidan, dokter, dokter spesialis – terhadap korban perkosaan dan akses layanan aborsi dalam penelitiannya. “Ada yang memandang itu adalah reinkarnasi dosa masa lalunya. Itu takdirnya. Apapun itu kehamilan harus dilanjutkan.”
Seno selaku dokter kandungan di RSCM juga kerap menemukan sejawat dokter yang menolak memberikan kontrasepsi darurat kepada pasien.
Kontrasepsi darurat adalah obat pencegah kehamilan yang dapat seseorang konsumsi 3-5 hari setelah seseorang melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Tenaga kesehatan yang menolak memberikan kontrasepsi darurat menyamakan obat ini dengan tindakan aborsi.
Implikasinya, otonomi pasien atas tubuhnya diabaikan. Perempuan tidak dibiarkan untuk memilih dan menanggung konsekuensi yang ia sanggupi.
“Pendapat pribadi saya, semua perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan reproduksi,” kata Seno. “Kalau seorang obgyn bertanya ke saya, kalau sesuai prinsip atau agama tidak mau kasih, tidak apa. Tapi dia harus tahu bahwa pasien itu berhak. Nggak boleh nggak kasih jalan. Kasih jalan (merujuk) ke dokter lain.”
Praktik yang mencampuradukkan moral dengan etika itu kerap ditemukan di kalangan tenaga kesehatan.
Rasa frustrasi Belas atas kenyataan itu kadang membuatnya melontarkan humor gelap,
“Perempuan harus hampir mati dulu baru dapat layanan.” Ia tertawa kecut.
Deklarasi Jenewa World Medical Association (WMA) telah mengalami perubahan per Oktober 2017. Tetapi, Sumpah Dokter Indonesia yang pertama kali berlaku pada 1960, yang juga didasarkan pada Deklarasi Jenewa 1948, belum mengikuti perubahan Deklarasi Jenewa terkini.
SUMPAH DOKTER
(versi World Medical Association)
SEBAGAI ANGGOTA PROFESI MEDIS:
…
SAYA AKAN MENGHORMATI otonomi dan martabat pasien saya*;
SAYA AKAN MENJAGA rasa hormat yang setinggi-tingginya terhadap kehidupan manusia**
…
*Tidak ada dalam Sumpah Dokter Indonesia.
**Tidak lagi memasukkan “…mulai saat pembuahan.”
Pendidikan Kesehatan yang Berorientasi pada Pasien (People-centered)
Sandra berproses menjadi lebih peka setelah ia mengakses berbagai literatur di luar pendidikan kedokteran. Ia juga belajar dari pengalaman di lapangan, bahwa banyak pasien perempuannya adalah korban kekerasan berbasis gender.
Baik di puskesmas, klinik perusahaan, RSUD, rumah sakit swasta, hingga di klinik kecantikan, Sandra bertemu dengan perempuan korban kekerasan.
“Di klinik kecantikan, aku tetap mendengar cerita hal yang sama. Dan itu baru aku. Teman-temanku yang kerja di tempat lain pasti ketemu juga dong? Kok aku nggak pernah dengar ada yang membicarakan ini? Masa sih yang bisa kita lakukan cuma jahit lukanya dia?”
Pemahaman atas layanan yang berorientasi pada pasien (people-centered) dan berperspektif gender tidak Sandra dapatkan ketika ia mengikuti pendidikan kedokteran. Fasilitas-fasilitas kesehatan di tempat Sandra bekerja dulu juga tidak memiliki SOP penanganan yang berperspektif gender.
Menurut Sandra, permasalahan muncul ketika biaya pendidikan kedokteran yang terlampau mahal sehingga hanya kelompok ekonomi atas yang dapat menjangkaunya.
“Tidak banyak ada representasi keberagaman di situ. Itu aja sudah cukup susah membuat mereka dapat relate dengan masalah pasien yang beragam,” terang Sandra.
Begitu juga dengan Belas yang mendapatkan perspektif pelayanan yang humanis ketika ia belajar di luar pendidikan formal kebidanan. Sementara, di pendidikan formal, senioritas justru marak terjadi.
“Lebih ke bagaimana digembleng, harus kompeten, tapi luput bahwa penyedia layanan kesehatan perlu menjadi humanis,” cerita Belas.
Sebagai seorang bidan, Belas lebih nyaman bekerja di kliniknya dibandingkan di rumah sakit. Di klinik yang semula milik ibunya yang sudah pensiun itu, Belas merasa memiliki otoritas. Kewenangan yang tidak ia dapatkan ketika bekerja di rumah sakit dulu.
Ia menyaksikan perlakuan dokter yang sewenang-wenang kepada tenaga kesehatan lain termasuk dirinya. Hardikan dari dokter jadi konsumsi sehari-hari. Ia juga pernah kena pukul di tangan karena ia salah memberikan alat.
Dalam kebidanan, posisi yang hierarkis itu memengaruhi kompetensi dan kewenangan bidan yang menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pada akhirnya berpengaruh pada akses layanan untuk masyarakat.
Untuk tindakan aborsi aman di bawah usia 14 minggu dengan metode bedah, WHO merekomendasikan tidak hanya dokter umum maupun dokter spesialis yang berwenang melakukannya, tetapi juga bidan, perawat, hingga tenaga kesehatan tradisional/komplementer.
WHO menyatakan bahwa tugas ini termasuk dalam kompetensi utama bidan. Juga, pasien perempuan umumnya merasa mendapatkan layanan yang lebih suportif di tangan bidan. Di daerah-daerah dengan akses, infrastruktur, dan sumber daya dokter yang terbatas, peran bidan maupun perawat menjadi krusial dalam memperluas akses layanan aborsi.
Tetapi, di Indonesia, kewenangan melakukan tindakan aborsi dominan ada pada dokter spesialis obgyn.
“Sekarang, kita bisa lihat relasi kuasanya: kalau sudah urusan perempuan; maternal health, aborsi, itu approval-nya ke spesialis obgyn. Kalau mereka semua menolak, lalu mau gimana?” kata Belas.
“Bagaimana dehumanisasi itu terjadi di sistem layanan kesehatan yang seharusnya memanusiakan manusia.”
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang RUU Kesehatan pada Januari 2023, Budi Gunadi menyampaikan kekhawatirannya atas relasi kuasa antara dokter dengan tenaga kesehatan lain di Indonesia.
Ia mendapatkan keluhan dari para bidan dan perawat. “Kalau di luar negeri, perawat dan dokter itu setara. Satu tim. Di sini, kastanya begini.” Budi Gunadi memperlebar jarak kedua tangannya yang tadinya bersandingan. “Di luar negeri, dokternya sangat menghargai perawat. Di sini nggak. Perawat itu pesuruh.”

Pada 2014, gabungan sejumlah organisasi profesi, termasuk IDI, melakukan judicial review menolak tenaga medis berada dalam satu golongan dengan tenaga kesehatan.
Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga medis yaitu dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis masuk dalam rumpun “tenaga kesehatan”, bersama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti psikolog, perawat, bidan, dan lainnya.
Agustus lalu, Kementerian Kesehatan menegur tiga rumah sakit terkait praktik perundungan terhadap dokter-dokter yang sedang mengikuti program pendidikan.
Sikap itu disayangkan oleh perwakilan IDI yang menilai Kemenkes “berlebihan.” Mereka beralasan itu adalah bagian dari pendidikan kedisiplinan, dan bahwa “kelakuan oknum tidak bisa digeneralisir.”
Ketika diwawancarai langsung, perwakilan IDI Ari Kusuma Januarto juga memberikan pernyataan serupa. “Kami sangat khawatir dengan framing dokter saling bully. Kalau ditanya oknum, semua oknum ada.”
Seorang dokter menyebutkan bahwa potensi ancaman memberikan layanan aborsi kepada korban kekerasan seksual bukan hanya dari sisi hukum. Tetapi juga dari organisasi profesi.
Sebelum omnibus law UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 disahkan, seluruh izin praktek dokter dipegang oleh IDI. Pemerintah daerah berwenang untuk mengeluarkan izin praktek, tetapi atas rekomendasi dari IDI. Untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, setiap dokter mesti mendaftarkan diri sebagai anggota IDI.
“Masalahnya, kalau kami melakukan itu, kami bukan cuma berhadapan dengan tekanan masyarakat. Tapi juga tekanan organisasi profesi,” kata dokter itu. “Kalau kami melawan sikap organisasi profesi, praktek dan karier kami bisa jadi dipersulit.”
Pada 2022, PPH Unika Atma Jaya dan Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia merilis laporan “Analisis Situasi Aborsi di Indonesia.” Laporan itu menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang memberikan informasi dan layanan aborsi dibayang-bayangi ancaman kehancuran karier.
Seorang narasumber penelitian memberikan kesaksian,
“Dia (dokter yang memberikan konseling) langsung menceritakan bahwa kemarin dokter di (nama rumah sakit) sudah ada yang dipecat karena melakukan ini (aborsi).”
Terlepas pengesahan omnibus law UU Kesehatan yang menuai pro dan kontra, pengalaman sejumlah tenaga kesehatan dan pendamping korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan yang telah berlaku sedang tidak baik-baik saja.
“Yang sekarang sudah jelas tidak baik. Untuk apa kita bertahan dengan sistem yang sudah tidak baik?” kata seorang dokter.
Layanan yang Menjangkau Korban
Akses layanan aborsi untuk korban kekerasan seksual berkaitan erat dengan penanganan korban kekerasan seksual yang sigap dan terpadu. Dengan batas usia kehamilan yang terbatas, korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya mesti segera mendapatkan penanganan.
Secara ideal, korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik dan mental, pengobatan luka, pencegahan/penanganan penyakit menular seksual, pencegahan/penanganan kehamilan, terapi psikiatri dan psikoterapi, dan rehabilitasi psikososial.
Hal ini tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS.
Hanya saja, di lapangan, prinsip penanganan ini belum terlaksana dengan baik.
Sejak pemerintah mengambil alih kewenangan layanan pendamping korban kekerasan seksual, akses pendampingan menjadi lebih terbatas.
Ana dari WCC Jombang merasakan perubahan itu. Sejak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berubah menjadi Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) di bawah pemerintah daerah, birokrasi pelayanan pendampingan korban menjadi lebih tidak fleksibel.
WCC Jombang mendampingi kasus seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. “Rambutnya diguntingin sama suami, digebukin sampai berdarah-darah,” cerita Ana.
Saat itu tanggal merah. Ketika meminta bantuan UPTD, mereka beralasan tidak bisa melayani karena sedang di luar jam operasional.
Begitu pula akses terhadap rumah aman. “Korban yang butuh akses masih disuruh tunggu. Hari Senin, masuk kerja jam 9, pulang jam 3 sore.”
“Artinya, kita berhadapan dengan sistem yang perspektif, empati, dan responsivitas layanannya tidak dibentuk,” tambah Ana.
Prinsip layanan yang berperspektif korban, menurut Margaretha Hanita, bukan semata layanan yang dapat korban jangkau. Tetapi, “Layanan yang menjangkau korban.”

Margaretha Hanita adalah seorang dosen, praktisi, dan aktivis di bidang resiliensi perempuan yang pernah bekerja di P2TP2A selama 15 tahun. Ia kini mendampingi Polda Metro Jaya dan sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta membangun layanan yang berperspektif korban.
Korban-korban kekerasan seksual, dalam praktiknya, masih menghadapi birokrasi lembaga yang rumit. Misalnya, layanan yang tidak tersedia 24 jam, akses ke rumah aman yang terbatas, persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menyulitkan korban yang tidak memiliki/kehilangan kartu identitas, hingga skema pembiayaan yang belum jelas.
Korban kekerasan seksual tidak mendapatkan jaminan pembiayaan dari BPJS yang layanannya merujuk pada penyakit tertentu. “Tapi visum bukan penyakit. Luka akibat kekerasan seksual bukan penyakit. Luka, patah tulang hidung, disiram air keras, itu bukan penyakit,” kata Hanita.
Ketika masih bekerja di P2TP2A dulu, Hanita kerap menemukan anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan pelayanan karena ia tidak memiliki NIK. Seorang anak korban perkosaan berkelompok (gang rape) ditemukan di kolong jembatan.
Pemerintah daerah lalu mensyaratkan korban didaftarkan terlebih dahulu ke dukcapil sebelum dapat menerima bantuan dana. “Harus dijadikan warga DKI Jakarta dulu. Harus pakai biometrik dulu,” cerita Hanita.
Ada pula kasus korban tindak pidana perdagangan orang yang kartu identitasnya diambil.
Layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual melibatkan koordinasi lintas-sektor.
Di RSUD Kabupaten Bekasi, institusi terkait perlu mengajak setidaknya pihak kepolisian, DPPPA, dan dinas sosial untuk mewujudkan layanan terpadu pasien korban kekerasan seksual.
“Butuh komitmen tinggi untuk membikin PPT. Kami harus melibatkan banyak pihak lintas sektor,” terang Ida Hariyanti selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Diagnostik di RSUD Kabupaten Bekasi.
Tahun depan, RSUD Kabupaten Bekasi berencana meresmikan layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Di rumah sakit, pasien dapat sekaligus mengakses pendampingan dari DPPPA. Laporan hasil pemeriksaan dari rumah sakit juga dapat langsung diserahkan ke kepolisian.
Umumnya, pasien korban kekerasan seksual datang ke rumah sakit dengan surat permintaan visum et repertum dari kepolisian kepada dokter forensik.
Tetapi, RSUD Kabupaten Bekasi juga tidak menutup kemungkinan bagi pasien yang belum melapor ke kepolisian untuk datang terlebih dahulu ke rumah sakit. “Kami tangani dulu kegawatdaruratannya, pemeriksaan lengkap, kalau memang perlu kami hubungi kepolisian,” jelas Suryo selaku dokter forensik di RSUD Kabupaten Bekasi.
Dengan koordinasi lintas-sektor, mereka bisa menerapkan pelayanan dalam satu waktu, satu tempat.
RSUD Kabupaten Bekasi jadi satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang telah menyiapkan alur khusus menangani korban kekerasan seksual. Tidak banyak pula instansi pemerintahan terkait lainnya yang telah menerapkan prinsip tersebut.
Untuk dapat mewujudkan itu, kata Hanita, “Kita harus punya empati terhadap korban. Bisa dibayangkan korban mau melapor saja sudah syukur.”
Dalam hal akses layanan aborsi untuk korban kekerasan seksual, pelayanan yang belum satu atap, sigap, dan tidak berperspektif korban pada akhirnya ikut menghambat akses tersebut.
“Jangankan korban yang membutuhkan akses aborsi aman, korban yang butuh akses rumah aman aja, masih disuruh tunggu. Entar-entar saja, sampai kehamilannya besar dan melebihi batas yang ditentukan undang-undang,” kata Ana.
Penutup
Melati, anak korban perkosaan di Jombang, tidak pernah mendapatkan haknya atas akses layanan aborsi. Setelah Melati melahirkan, anaknya langsung diadopsi orang lain.
Selama proses kehamilan, keluarga Melati tidak mendapatkan dukungan layanan kesehatan dari pemerintah. “Sebatas kebutuhan sembako,” ujar Ana dari WCC Jombang. Sementara biaya pemeriksaan kehamilan memakai uang pribadi keluarga Melati dan hasil penggalangan donasi.
Melati dan orangtuanya trauma berat. WCC Jombang sempat mengajak orangtua Melati mencarikan baju untuk bayi yang Melati lahirkan. Mereka tidak mau memegang-megang baju di dalam toko. “Jangankan pegang baju bayi. Masuk ke dalam toko saja mereka enggan,” cerita Ana.
Sepanjang WCC Jombang mendampingi korban kekerasan seksual, tidak ada satupun yang pernah dapat mengakses layanan aborsi.
Pada 2021, WCC Jombang mendampingi lima kasus KTD dari total 41 kasus kekerasan seksual terhadap remaja perempuan (8-18 tahun). Pada 2022, ada 7 kasus KTD dari 46 kasus aduan kekerasan seksual.
Seorang korban perkosaan yang mengalami KTD adalah orang dengan disabilitas mental. Seorang korban lain diancam pasal perzinahan ketika hendak melaporkan kasusnya.
Riset PPHK Unika Atma Jaya dan Knowledge Hub Kesehatan Reproduksi Indonesia menemukan terdapat total 160 putusan pidana terkait kasus aborsi sepanjang 2017-2021. Sebanyak 45 perempuan yang membutuhkan akses layanan aborsi menjadi korban kriminalisasi.
Sejumlah kasus dikenakan UU Perlindungan Anak dengan pasal berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan […].”
Sepanjang pengalaman mendampingi korban, akses layanan kesehatan oleh pemerintah untuk korban masih sebatas pada menanggung biaya visum. Ketika korban mengalami kehamilan, biaya rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, hingga melahirkan mesti korban tanggung secara mandiri.
Riset menunjukkan sepanjang periode 2015-2019, terdapat total kehamilan mencapai 7,9 juta setiap tahunnya di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2,8 juta kehamilan tidak direncanakan dengan hampir separuhnya berakhir dengan aborsi.
Kata Ana, persoalannya bersifat sistemik menyangkut minimnya kepekaan layanan kesehatan terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual. “Ada banyak celah dalam struktur hukum yang tidak punya perspektif terhadap korban. Ke depannya, UU Kesehatan kita harus lebih manusiawi.”
Secara prinsip, peraturan akses layanan aborsi di KUHP dan omnibus law UU Kesehatan membuka peluang bagi perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan hak mereka.
Tetapi, undang-undang masih membutuhkan aturan turunan yang akan memastikan kesediaan layanan. Dalam hal UU Kesehatan baru, aturan-aturan itu masih dalam proses penggodokan.
Project Multatuli telah mengirimkan surat permohonan wawancara ke Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan sejak 8 Agustus 2023. Lalu juga mengirimkannya ke Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Hingga kini, permohonan wawancara tidak mendapatkan respons.
Sepanjang 2015-2016, sebanyak 36% kehamilan di Indonesia tidak direncanakan/diinginkan.
“Ketika undang-undang mengatakan korban kekerasan seksual yang mengalami KTD bisa mengakses layanan itu, harusnya dia bisa mengakses layanan itu.” Marcia menekankan, “Mari memberikan hak kepada mereka yang sudah diatur undang-undang.”
Kamu butuh layanan?
Konseling psikologi:
- Yayasan Pulih: https://yayasanpulih.org/konsultasi-online/
Konseling kesehatan seksual dan reproduksi termasuk kehamilan tidak diinginkan:
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia: https://pkbi.or.id/kontak/klinik-kami/
- Samsara: https://samsaranews.com/our-works/
Akses layanan kehamilan tidak diinginkan:
- Women on Web: https://www.womenonweb.org/en/
Membutuhkan layanan lain? Cari Layanan: https://carilayanan.com/.
Project Multatuli berkolaborasi dengan Konde.co dan Koran Tempo untuk liputan “akses layanan aborsi aman untuk korban kekerasan seksual.” Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan IPAS Indonesia.