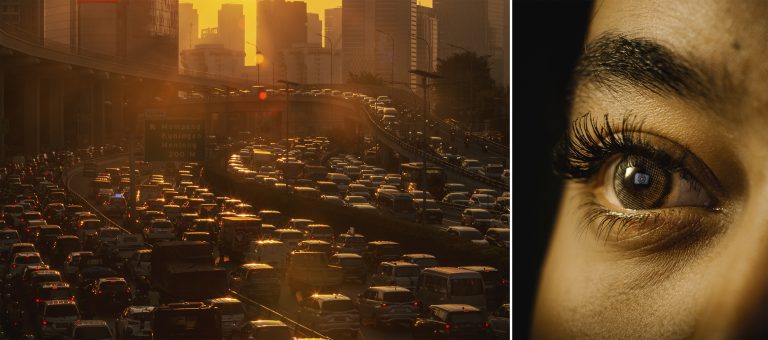Penemuan gas di Arun, Aceh Utara pada 1971 menandai awal dari transformasi besar-besaran di Lhokseumawe. Kilang LNG milik PT Arun NGL mulai dibangun pada 1974 dan resmi beroperasi pada 1978, mendorong lonjakan ekonomi yang menjadikan kota ini dikenal sebagai “kota petrodolar.”
Selama lebih dari tiga dekade, Lhokseumawe tumbuh sebagai kawasan industri dengan ekspor LNG, kondensat, dan LPG bernilai miliaran dolar, disertai kehadiran pabrik pupuk, kertas, dan industri turunan lain yang menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, ada yang dikorbankan dari pembangunan megastruktur ini. Empat desa, yakni Blang Lancang Timur, Blang Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong Barat, dihapus dari peta demi proyek yang melibatkan kerja sama Pertamina, Mobil Oil (Exxon), dan konsorsium Jepang.
Ketika cadangan gas menipis pada awal 2000-an, dampak sosial dan ekonomi tak terhindarkan. Ribuan orang kehilangan pekerjaan, dan kota yang bergantung pada sektor migas tanpa diversifikasi ekonomi terjerembab dalam stagnasi.
Reportase ini adalah catatan reflektif untuk pemerintah dan pelaku usaha: di balik narasi besar transisi energi, ada kebutuhan mendesak merancang masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja dan komunitas yang ikut menopang industri.
M NASIR USMAN mengenang pelepasan kapal terakhir pengangkut Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair dari kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) pada Oktober, sebelas tahun silam.
Seremonial digelar meriah di kawasan kilang, Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Tradisi peusijuek alias tabur tepung tawar yang biasa mewarnai upacara penting di Aceh juga dilakukan.
Tenda didirikan dekat kapal. Arun NGL mengundang banyak tamu. Puncak acara berupa pemotongan tali tambat kapal tanda pelepasan. “Bukan duka dan sedih,” kata Nasir (57), mantan pekerja di kilang itu pada pertengahan April 2025.
Seremoni semeriah itu hanya berlangsung sesaat. Hari-hari berikutnya, perusahaan mulai memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Nasir sebenarnya juga masuk dalam daftar pemecatan tetapi ia diminta perusahaan untuk tetap bekerja sampai kilang benar-benar ditutup dan beralih kepemilikan ke PT Perta Arun Gas (PAG), anak usaha Pertamina.
Nasir bekerja di Arun NGL sejak 1988. Awalnya, ia ditempatkan di divisi keamanan, lalu bergeser ke operasi pada 1996. Belasan tahun jadi operator, pada 2010, ia kembali ke keamanan. Dua tahun kemudian, ia pindah lagi ke operasi sampai Arun NGL tutup.
Nasir angkatan terakhir di Arun. Ia adalah saksi mata saat perusahaan itu tumbang dan akhirnya berhenti beroperasi. Ia menyebut tidak ada masalah dalam proses pembayaran pesangon karyawan. Beberapa fasilitas yang diberikan perusahaan, seperti rumah atau kendaraan, juga tidak ditarik.
“Miliaran-lah mainnya. Buka usaha cukup. Tidak ada yang ratusan juta,” kata Nasir, merujuk besaran uang pesangon dari Arun.
Bahkan sebelum benar-benar tutup, para karyawan juga diikutsertakan dalam program pelatihan pra-pensiun di beberapa kota di Pulau Jawa selama sepekan dengan materi seputar pertanian hingga wirausaha.
“Kami dibawa ke contoh-contoh bisnis yang berhasil. Seperti peternakan di Pulau Jawa. Lokasinya beda-beda, ada yang dibawa ke Bandung dan Jogja. Saya ke Jogja,” katanya.
Pulang dari Jawa, karyawan bekerja seperti biasa, dan menunggu giliran di-PHK.
Seingat Nasir, transisi PAG sudah dimulai sebelum Arun NGL berhenti pada 2015. Pada masa itu, Nasir langsung ditugaskan bekerja di kilang PAG untuk proses regasifikasi, begitu juga dengan pekerja bagian operasi lainnya.
Arun NGL tidak pernah berjanji karyawan akan dipindahtugaskan ke PAG. Akan tetapi, di sela-sela masa transisi, para pekerja di bagian operasi kilang ditawarkan untuk mengikuti seleksi pekerja dengan PAG.
Seleksi berupa wawancara mengenai nominal gaji, selebihnya tidak ditanyakan.
“Wawancara diatur waktu per gelombang. Pulang kerja ditunggu di main office,” kata Nasir.
“Kalau pekerja tidak mau lanjut [ke PAG], saat wawancara tidak sepakat, besoknya tidak masuk lagi.”
Namun, tawaran gaji dari PAG rupanya tidak setara dengan Arun.
“Dulu di Arun NGL gajinya Rp20 juta per bulan. Kemudian beralih ke PAG, Rp8 juta,” kata Nasir.
Dari semua karyawan Arun NGL di bagian operasi yang berjumlah sekitar 80-an orang, kata Nasir, empat di antaranya menolak dan tidak dipanggil untuk seleksi wawancara PAG.
“Yang menolak saya lihat ada yang ke luar negeri,” ujarnya.
Menurut Nasir, karyawan Arun NGL yang beralih ke PAG kebanyakan dari bagian operasi kilang. Sementara bidang lain hanya diambil sesuai kebutuhan.

Teuku Khaidir, Presiden Direktur PAG periode 2013-2017, dalam buku Mengembalikan Kemasyhuran Arun NGL(2021), mengatakan mereka kesulitan ketika mengalihkan pekerja eks Arun NGL ke PAG. Beberapa pekerja, seperti di bagian Sulfur Recovery Unit (SRU), menolak bergabung karena gaji tidak sesuai standar Arun.
Dalam rapat dengan Pertamina, disinggung bahwa standar gaji Arun NGL mengikuti ExxonMobil. Karena perusahaan baru, PAG sulit memenuhi standar gaji tersebut. PAG mengikuti standar gaji Pertamina.
Khaidir lantas menghubungi koleganya di PT Badak NGL, Pertamina, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Kepada Khaidir, mereka mengaku bisa membantu apabila tenaga kerja tak bisa diserap dari Arun NGL.
Bermodal itu, Khaidir memberi pengumuman kepada eks pekerja Arun NGL.
“Apabila tawaran PAG tidak diterima, maka peluang untuk bekerja di PAG tidak tersedia lagi karena sudah ada tenaga kerja yang siap untuk didatangkan dari Jawa, Bontang, dan Aceh sendiri. Mereka akhirnya mengerti dan mau bergabung bersama PAG,” kata Khaidir.
Khusus pekerja operasi kilang, sebanyak 125 pekerja Arun NGL masuk dalam gelombang pertama perekrutan PAG. Selanjutnya, direkrut lagi berkisar 80 orang. Mereka juga dapat pelatihan terkait teknologi baru regasifikasi. Mereka diberangkatkan lagi ke Jawa, termasuk Nasir.
“Training untuk menyesuaikan dengan teknologi baru. Pelatihan operator. Bagian regasifikasi saja,” kata Nasir.
Nasir memilih tetap mengambil tawaran PAG walaupun gajinya jauh berkurang karena ia masih tetap harus membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya.
Di PAG, Nasir dan pekerja eks-Arun NGL lainnya berstatus pekerja waktu tertentu (PWT) yang dikontrak per tahun. Pada tahun kedua, PAG membuka kesempatan eks-Arun NGL mengikuti seleksi menjadi karyawan tetap.
Seleksi digelar lebih ketat, mulai dari psikotes hingga kesehatan lengkap. “Kebetulan kami lulus, tapi ada yang tidak lulus. Eks-Arun NGL yang tidak lulus tes tetap di situ, tapi jadi PWT saja,” kata Nasir.
***
Arun NGL tercatat memproduksi LNG, kondensat, LPG, dan sulfur yang diekspor ke Korea Selatan dan Jepang. Lebih dari tiga dekade berjalan, Arun NGL mengapalkan 4.269 kargo LNG dengan nilai tiap pengapalan US$10 juta. Karenanya, Lhokseumawe dikenal kota petrodolar.
Kehadiran Arun NGL menghidupkan industri lain di kawasan itu, seperti pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Humpuss Aromatik.
Namun, tanda-tanda kemunduran itu dimulai pada awal tahun 2000. Produksi LNG dan kondensat terus menurun akibat menipisnya cadangan gas. Pada tahun 2007, hanya tiga dari enam train LNG yang beroperasi, dan menjelang 2014, hanya satu unit tersisa dengan kapasitas terbatas.
Penurunan produksi ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi awal dari berakhirnya era kejayaan industri gas di Lhokseumawe.
Krisis pasokan gas tidak hanya melumpuhkan Arun, tetapi juga meruntuhkan ekosistem industri penunjangnya.
Pabrik pupuk PT AAF tutup sejak 2003, PT PIM 1 sempat mati suri pada 2012, dan PT KKA berhenti beroperasi pada 2007. Sementara itu, PT Humpuss Aromatik lebih dulu berhenti pada 2000 karena kekurangan kondensat.
Runtuhnya sektor-sektor ini mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja, merosotnya pendapatan daerah, dan memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada industri migas.

Saat Arun NGL resmi berhenti beroperasi pada Oktober 2014 dan seluruh fasilitasnya diserahkan ke PAG setahun kemudian, Lhokseumawe kehilangan pusat pertumbuhan ekonominya.
Produksi LNG turun 91 persen dan kondensat anjlok lebih dari 80 persen dalam satu dekade terakhir operasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama periode 2005 hingga pengapalan terakhir pada 2014, produksi LNG dan kondensat di Arun NGL mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Setidaknya, dalam kurun waktu 10 tahun menuju penutupan, terjadi penurunan produksi LNG sekitar 91 persen, dan produksi kondensat turun lebih dari 80 persen.
Tak Ada yang Tidak Kena Imbas
Kekhawatiran atas pemutusan hubungan kerja sudah dirasakan para karyawan Arun NGL sejak kabar cadangan gas semakin menipis.
“Bagaimana ini pekerja-pekerja, dibayar tidak hak-hak karyawannya?” tutur A. Hamid Matsyah (64), salah satu eks-pekerja yang menceritakan suasana saat itu.
Desas-desus PHK direspons para karyawan dengan meminta pertemuan bersama pihak perusahaan. Pertemuan berlangsung, dihadiri perwakilan pekerja dengan manajemen perusahaan dan perwakilan pemerintah daerah.
Kesepakatan muncul pada 2014. Perusahaan menyepakati adanya Statutory Redundancy Payment (SRP) atau pesangon yang jumlahnya tergantung posisi dan lama bekerja.
“Yang enggak pensiun, semua sekaligus dipensiunkan dengan cara dibayar semua hak-haknya. Dalam hal ini, pembayaran kepada semua karyawan di bulan Oktober tahun 2015,” kata Hamid.
Jelang transisi ke PAG, Arun NGL juga membentuk Satuan Tugas. Sedikitnya 33 karyawan dari berbagai bidang tergabung dalam tim itu, termasuk Hamid yang mewakili divisi aset. Pesangon anggota satgas hanya dibayar 90 persen. Sisanya diberikan ketika tugas mereka tuntas pada 2017, berikut dengan tambahan gaji dan bonus.
“[Satgas] Itu untuk menentukan mana barang belum clear dan belum tepat, serta membuat urusan dengan PAG,” kata Hamid.
Namun Hamid tidak dapat bertugas hingga selesai. Desember 2015, ia sakit dan berobat ke Malaysia. Ia diberhentikan. Sisa pesangon dan gaji tiga bulan bekerja sebagai tim transisi dibayar Arun.
Menurut Hamid, ada sekitar 100 mantan karyawan Arun NGL yang dipanggil untuk bergabung ke PAG. Yang Hamid tahu, salah satu kriterianya umur pensiun minimal sisa lima tahun lagi.
“Saya pun waktu itu tinggal 8 bulan lagi [pensiun]. Tidak bisa lagi, ada dipanggil,” kata eks-pekerja yang bergabung ke Arun NGL pada 1984 ini.

Sepanjang beroperasi, Arun NGL sudah tiga kali mengurangi karyawan. Pertama sekitar 1997, kemudian periode 2004-2005, dan terakhir saat akhirnya tutup pada 2015. Hamid mengatakan selama tiga peristiwa pengurangan ini, perusahaan tidak pernah mendapat komplain terkait pesangon.
Kecuali pada tahun 2000. Arun NGL pernah didemo pekerja berstatus kontrak. Sulaiman Hasan salah satu saksinya. Ia bekerja untuk perusahaan sub-kontrak Arun NGL untuk divisi telekomunikasi sejak tahun 1981.
Selama bekerja, Sulaiman terikat kontrak dengan perusahaan berbeda-beda. Namun pekerja di lapangan adalah orang-orang yang sama. “Kontraktornya banyak, tapi pekerjanya tetap [sama],” ujarnya.
Soal pembayaran, Sulaiman menerimanya dari perusahaan yang mengontraknya. Yang berbeda, karyawan Arun NGL mendapat bonus tahunan dan bonus enam bulan sekali. Tuntutan dipenuhi, karyawan kontrak sempat diberikan bonus selama dua tahun berjalan.
Ketika transisi dari Arun NGL ke PAG, perusahaan kontraktor juga ikut bertransisi. Sulaiman sudah mulai bekerja untuk PAG sejak 2013. “Karena sebelum ada kontrak baru, ada rapat yang menjelaskan bahwa kami akan bekerja untuk PAG,” katanya.
Akan tetapi, PAG tidak membutuhkan pekerja sebanyak Arun NGL. Alhasil, perusahaan-perusahaan kontraktor juga mengurangi pekerjanya. Misalnya di bagian telekomunikasi, dari tujuh pekerja di sana yang dibutuhkan hanya lima orang.
Mereka yang dipecat, menurut Sulaiman diberi pesangon. Hitungannya, setahun bekerja dibayar sebesar tiga kali gaji pokok. Seleksi pekerja yang akan diputuskan dipilih berdasarkan asal daerah. Sebab, perusahaan mengutamakan warga sekitar.
Sulaiman termasuk pekerja yang lolos seleksi bekerja di PAG. Ia putra asli Blang Pulo, kampung penyangga kilang LNG Arun. Ia baru berhenti saat masuk usia pensiun pada 2018.

Pada masa jayanya, Arun NGL disebut memiliki karyawan hingga 2.000 orang. Namun, data lain menyebutkan karyawan penghuni perumahan karyawan Arun NGL adalah 1.305 orang.
Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah karyawan tetap pada tahun 2006 mencapai 580 orang. Jumlah terus merosot hingga tersisa 270 pekerja tetap pada 2014.
Selain karyawan tetap, Arun NGL juga mempekerjakan pekerja asing sedikitnya dua orang per tahun serta karyawan kontraktor, baik yang berada di bawah pengawasan langsung maupun kontraktor umum.
Kejayaan yang Eksklusif
Jalan Nasional Banda Aceh-Medan membelah Gampong Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Kedai-kedai berderet di sisi kiri dan kanan. Di antara kepadatan itu, ruas jalan utama menuju kilang LNG Arun terbentang sekitar satu kilometer.
Blang Pulo termasuk desa terdekat dan persis di pinggir area kilang LNG Arun. Namun, Arun NGL tidak berperan banyak dalam menghidupi desa itu. Saat Arun NGL beroperasi, warga tetap menjalani harinya dengan aktivitas masing-masing, ke sawah dan kebun.
“Waktu itu memang Arun sedang luar biasa, tapi masyarakat seperti biasa juga,” kata Teungku Ahmad Adami, Penjabat Keuchik Blang Pulo, 15 April 2025.
Selama beroperasi, Teungku Adami mengaku bahwa sistem penerangan umum di desanya terus menyala. “Sekarang tidak lagi,” katanya sambil menunjuk tiang lampu yang dipasang Arun NGL di median Jalan Nasional Banda Aceh-Medan.

Perusahaan sempat memiliki program kesejahteraan warga, melalui dukungan kegiatan agama. Namun, hal itu tidak berlangsung lama.
Begitu juga dengan peluang perekrutan warga sekitar. Warga Blang Pulo yang berstatus karyawan Arun NGL tercatat hanya sedikit. Menurut Teungku Adami, kebanyakan warga direkrut menjadi sekuriti atau tugas lainnya di bawah perusahaan kontraktor di Arun.
Pada 2012 masyarakat Blang Pulo pernah berdemonstrasi di Arun NGL meminta pekerjaan. Saat itu kilang sedang shutdown atau berhenti untuk perawatan. “Skill itu kadang-kadang ada di masyarakat di sini,” kata Teungku Adami.
Kendati demikian, dampak ekonomi semakin terasa saat Arun NGL berhenti operasi. Rumah-rumah warga yang disewa pekerja kembali kosong, kendati enam tahun kemudian, beberapa di antaranya hidup kembali karena kehadiran Universitas Malikussaleh.
Teungku Adami menuturkan saat ini tidak ada peninggalan Arun NGL yang dapat dimanfaatkan warga desanya.
“Di sini tidak ada bangunan yang dihibahkan [ke desa]. Tidak ada dampak bagi ekonomi masyarakat [yang berkelanjutan] setelah perginya Arun,” katanya.
“Seandainya ada anak baru lahir beberapa tahun ini, kita ceritakan Arun mungkin mereka tidak akan percaya. Karena memang tidak terlihat bekas dari kejayaan Arun.”
Data BPS menempatkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Aceh secara berturut-turut sejak 2018 hingga 2024.
Semasa Arun NGL, kondisi kemiskinan di Lhokseumawe sebenarnya tidak jauh berbeda. Misalnya, pada 2007 dan 2008, kota ini berada di puncak daftar wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Aceh.
Senada, tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe juga berada pada angka yang tinggi saat Arun NGL beroperasi. Pada tahun 2003, persentase penduduk miskin mencapai 16,39 persen, salah satu yang tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Bahkan menjelang penghentian operasional Arun NGL, kondisi tersebut tidak banyak berubah. Pada tahun 2007, angka kemiskinan mencapai 12,75 persen, dan meningkat tajam menjadi 15,87 persen pada 2008. Angka ini justru turun saat Arun NGL sudah sepuluh tahun pergi. Misalnya, pada 2024 menjadi 10,44 persen.
***
Di tengah gagalnya Arun NGL membangun kesejahteraan di Lhokseumawe, pemerintah pusat berambisi kembali membangun kejayaan dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Kawasan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diresmikan Presiden Jokowi pada 2017, dan diklaim akan menyerap hingga 40 ribu tenaga kerja.
KEK ini menempati sebagian wilayah eks kilang LNG Arun dan area industri lainnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara, dengan luas sekitar 2.622 hektare. Kawasan dikembangkan konsorsium Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dengan pengelolaan oleh PT Patriot Nusantara Aceh.
Pemerintah menjanjikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, serta fasilitas ekspor-impor. Pengelola KEK mengandalkan infrastruktur yang sudah ada, termasuk fasilitas regasifikasi yang dioperasikan PAG, untuk menarik masuk industri hilir energi dan manufaktur.
Namun sejak diresmikan, perkembangan KEK Arun berjalan lambat. Beberapa perusahaan memang mulai beroperasi, seperti Pupuk Iskandar Muda dan anak usaha Pertamina, tapi aktivitas industri belum signifikan. Banyak lahan di KEK masih kosong atau belum dikelola optimal.
Hal ini juga terjadi pada PAG yang beroperasi di lahan eks kilang Arun NGL. PAG, yang diresmikan Jokowi pada 2015, juga ditargetkan bisa mendorong pertumbuhan industri dan mengatasi pengangguran serta kemiskinan di Aceh dan Sumatra Utara.

Sejak Oktober 2015, seluruh operasional kilang LNG Arun dialihkan ke PAG. Sedikitnya 8.549 item aset eks Arun NGL diinventarisasi secara bertahap dan selanjutnya dikelola LMAN. Aset-aset itu termasuk kilang produksi di Blang Lancang, cluster III eks PT Exxonmobil Oil di Matangkuli, Aceh Utara, eks kompleks perumahan Arun NGL, hingga fasilitas water intake di Peusangan, Bireuen.
Perkara aset ini, pada tahun 2020, LSM Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) menggugat Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan ke Komisi Informasi Publik di Jakarta. Mereka meminta DJKN membuka ke publik aset ExxonMobil dan Arun NGL yang dikuasai negara melalui LMAN. Gugatan dikabulkan.
Namun, DJKN menggugat balik keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam putusan 2021, majelis hakim mengabulkan gugatan DJKN dan membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik.
Temuan di lapangan memperlihatkan sejumlah bangunan di bekas kompleks perumahan Arun NGL terbengkalai. Salah satunya adalah rumah nomor 118. Halaman rumah itu dipenuhi semak belukar, menandakan lama tidak terurus. Semua pintu rumah telah hilang, membuat siapa pun dapat keluar masuk dengan leluasa.
Bagian dalam rumah tampak kosong tanpa perabotan. Pada saklar lampu, tidak terlihat lagi kabel-kabel listrik, menunjukkan bahwa instalasinya telah dicabut atau rusak. Di kaca jendela bagian depan, terpasang stiker yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan aset milik LMAN.

Pulang ke Tanah Leluhur
Rumah-rumah berdinding papan kayu dan anyaman bambu terlihat di sepanjang Jalan Rancong, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dengan beratap seng dan daun rumbia, kawasan permukiman ini berada tepat di sebelah pagar kompleks eks kilang Arun NGL.
Rumah milik Syamsuddin M Jafar misalnya, hanya berjarak sekitar 20 meter dari gerbang sisi barat kompleks kilang. Dekat pintu pagar yang tertutup rapat itu terpacak plang bertulisan “Objek Vital Nasional”.
Syamsuddin tinggal di rumah sederhana itu bersama keluarganya.
“Rumah kami berkonstruksi kayu. Ditiup angin bisa roboh. Kami bangun semampu kami,” kata Syamsuddin (53), ditemui di rumahnya pada pertengahan April. “Karena kondisi ekonomi kami tidak bisa bangun rumah beton.”
Syamsuddin membangun rumah itu pada 2015. Ia bersama beberapa keluarga lainnya memutuskan pulang ke tanah leluhur di area yang dulu menjadi kilang LNG Arun NGL.
“Sekarang kami pulang ke tanah leluhur. Di sini juga ada makam leluhur kami, dan itu identitas, bukti kami pernah menetap di sini puluhan tahun lalu,” kata Syamsuddin yang juga Ketua Ikatan Keluarga Blang Lancang-Rancong (IKBAL).

Sebelum ladang gas ditemukan, kawasan seluas 271 hektare itu dulunya permukiman. Secara administratif terbagi empat desa: Blang Lancang Timur, Blang Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong Barat.
Sedikitnya 542 kepala keluarga tinggal di sana. Menurut Syamsuddin, kehidupan ekonomi masyarakat saat itu makmur. Sebab, kampung-kampung didukung letak geografis dekat laut. Pekerjaan warga umumnya nelayan. Kawasan itu juga dikelilingi tambak, persawahan, dan kebun.
“Secara ekonomi sudah mandiri. Tanpa kehadiran proyek Pertamina pun, [dalam hal ini] Arun, ekonomi masyarakat sudah makmur,” tutur Syamsuddin.
Kehidupan warga yang tenang lantas terusik pada 1974. Temuan gas di Arun membuat penduduk mesti hengkang dari tanah lahirnya. Empat kampung itu menjadi lokasi pembangunan kilang LNG Arun.
“Mau tidak mau dengan berat hati kami harus pindah. Kampung ini lalu diambil oleh perusahaan Pertamina yang bekerja sama dengan pemerintah saat itu,” katanya.
Saat proses pengambilalihan lahan, Syamsuddin baru berusia 2 tahun. Ia mendengar cerita dari orangtuanya, bahwa warga sebenarnya didesak untuk melepas tanah dengan janji warga bakal mendapat ganti rugi lahan dan resetlemen alias pemukiman kembali.
“Ketika akhirnya kampung kami diratakan, kami tidak punya pilihan lain. Masa Soeharto, kalau bertahan tidak mungkin,” katanya.
Syamsuddin mengakui masalah ganti rugi lahan sudah tuntas dibayar. Persoalannya, resetlemen belum diberikan. Bahkan setelah kilang LNG Arun selama puluhan tahun ikut memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.
“Mulai dari 1974 sampai 2025 belum ada titik temu,” kata Syamsuddin.
Seusai ganti rugi lahan, kakek dan ayah Syamsuddin yang saat itu tinggal di Rancong Timur pindah ke Pasi Krueng Geukueh. Warga lain juga pindah ke daerah seperti Panton Labu, Takengon, hingga Banda Aceh. Mereka membeli tempat tinggal baru dengan uang pembebasan lahan.
Menurut Syamsuddin, pemerintah saat itu mengaku masih mencari lahan resetlemen. Pertama di Alue Paya Cicem, Seunuddon, Aceh Utara. Warga menolak tinggal di sana karena sulit mencari kerja. Lokasi kedua di kawasan pegunungan Mbang, Aceh Utara.
“Kami yang melaut dipindahkan ke gunung, kan tidak cocok,” kata Syamsuddin.
Pencarian lahan resetlemen berlarut-larut, sementara warga akhirnya terpaksa beradaptasi dengan tempat barunya masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, situasi kawasan itu makin memanas karena konflik senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Meredam pemberontakan, pemerintah mengirim ribuan tentara ke Aceh yang berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) pada rentang 1989-1998.
Selama nyaris satu dekade itu, di sekitar kilang LNG Arun yang megah, terdapat Pos Satuan Taktis dan Strategis (Sattis) Rancong yang ditempati Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat. Tempat-tempat itu diduga menjadi lokasi orang-orang yang dituduh GAM disiksa dan dibunuh tanpa proses peradilan.
Syamsuddin dan warga lain mencoba memahami kondisi itu. “Tidak mungkin lah kita mendesak sementara konflik masih terjadi,” katanya.
Setelah reformasi, mantan penduduk empat kampung itu menuntut kembali resetlemen. Sejak tahun 1999, mereka masih melakukan berbagai upaya menuntut haknya ke PT Arun NGL, Pertamina, sampai pemerintahan. Dari berkirim surat hingga demonstrasi.
Puncaknya pada 2015, ketika warga memutuskan menempati kembali tanah leluhur. Saat itu, 600 kepala keluarga mendirikan tenda dan tinggal persis di samping pagar kilang LNG Arun. Mereka menamakannya posko pengungsian.
Belakangan mereka mendirikan rumah. Tapi seiring perjalanan waktu, masalah ekonomi, dan perjuangan mereka yang belum sampai pada titik temu, sebagian warga pergi dari kawasan itu.
“Sekarang rumah yang masih ada di sini sekitar 200-an,” kata Syamsuddin.

Masalah dihadapi warga ini juga dimediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2013. Dalam pertemuan itu, mengemuka solusi agar BUMN melepaskan tanah PT Pertamina seluas 121,9 hektare di Ujong Pacu Lhokseumawe untuk resetlemen.
Dalam surat yang ditujukan ke Menteri BUMN pada 7 Januari 2014, Komnas HAM menyebut upaya Pemerintah Aceh dan Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah itu tidak direspons Menteri BUMN. Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 11 Maret 2014 juga menyurati Menteri BUMN meminta realisasi hibah tanah itu.
Komnas HAM menyatakan penolakan atau pengabaian atas upaya penyelesaian permasalahan yang dialami warga eks Blang Lancang dan Rancong digolongkan sebagai pelanggaran HAM.
Saat menjamu Menteri BUMN Dahlan Iskan di Meuligoe Aceh pada Jumat, 28 Maret 2014, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan map berisi surat permohonan hibah tanah milik PT Pertamina/PT Arun NGL di lokasi Ujong Pacu Lhokseumawe.
“Tanah tersebut kita minta dihibahkan karena saat ini tidak lagi dipakai seiring menurunnya pengelolaan gas,” kata Zaini, mantan Menteri Luar Negeri GAM itu.
Dahlan Iskan kala itu mengatakan bersedia membantu. Ia mengaku tidak keberatan apabila tanah milik PT Pertamina tersebut dihibahkan.
“Namun, aset milik negara kewenangan Menteri Keuangan, maka saya siap memfasilitasi Gubernur bertemu dengan Menteri Keuangan,” kata Dahlan.
Selain itu, warga mengadukan masalah ini ke Presiden Joko Widodo saat ia datang ke Blang Lancang untuk meresmikan terminal penerimaan dan regasifikasi LNG di Arun NGL pada 9 Maret 2015.
Sekretariat Kabinet lantas menindaklanjuti pertemuan warga eks Blang Lancang-Rancong dan Jokowi itu dengan menggelar rapat koordinasi di Jakarta. Persamuhan dihadiri berbagai pihak, termasuk kementerian dan pemerintah daerah.
Rapat itu tidak membuahkan hasil apapun. Hingga kini, janji pemukiman kembali tidak kunjung terpenuhi. Syamsuddin bersama warga lainnya juga masih tinggal di gubuk reyot.
“Kalau masalah ini sudah selesai, kami tidak mungkin juga tinggal di sini,” katanya. “Karena ini kawasan proyek vital, bahaya.”
“38 tahun diambil hasil migas di Arun di Blang Lancang, berapa kapal itu? Ratusan triliun asetnya. Masa masalah resetlemen ini? Kecil kali, itu.”
Kemegahan yang Semu
Teuku Kemal Fasya, Antropolog Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, menilai kejayaan Arun NGL semasa masih beroperasi bagaikan magnet yang menarik banyak orang. Tapi, kemegahan itu memudar ketika perusahaan berhenti beroperasi dan beralih ke PAG.
Menurutnya, kehadiran Arun NGL justru membawa ruang eksklusif di tengah-tengah warga dan budaya Aceh. Misalnya, kompleks perumahan ExxonMobil di Blang Pulo menerapkan standar keamanan ketat. Tidak sembarang orang bisa mengakses kawasan itu.
“Termasuk juga kehidupan seperti di Barat, misalnya ada kolam renang. Di foto lama itu kita lihat banyak bule pakai bikini, biasa itu berenang. Termasuk ada pub-nya juga, ada minuman alkohol. Jadi ruang yang secara eksklusif hadir di Aceh,” tuturnya.

Ruang eksklusif ini juga terbentuk di komplek perumahan Arun. Anak-anak yang dulu besar di perumahan Arun NGL juga menjadi anak-anak eksklusif yang enggan membaur.
Arun NGL tidak berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat ketika perusahaan angkat kaki, beberapa aset seperti kabel listrik, dan bagian-bagian rumah hilang diambil warga.
“Masyarakat jadi pengutil. Mereka anggap wajar saja mencuri. Dulu kan kita tidak bisa masuk. Jadi ketika sudah beralih politik, beralih sistem ekonomi, tidak lagi dikuasai oleh Arun, malah mereka menggerogoti,” kata Kemal.
Realitas itu menunjukkan bahwa kehadiran industri migas di Aceh tidak serta merta membangun. Teori ekonomi trickle down effect atau efek kesejahteraan yang menetes ke lapisan masyarakat bawah tidak terjadi pada kasus Arun NGL, lanjut Kemal.
Industri ekstraktif nyatanya tidak dapat menjadi penolong utama kehidupan masyarakat. Industri seperti Arun NGL hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.
Tahap awal pembangunan infrastruktur memang menyerap banyak pekerja, tapi hanya berlangsung singkat. Setelah proyek selesai, pekerja pun menyusut. Pekerja di sektor industri migas terbatas pada mereka yang punya keahlian tertentu.
“Orang-orang yang menikmati hasilnya hanya mereka yang dekat dengan struktur perusahaan dan kekuasaan. Selebihnya tidak merasakan kesejahteraan,” kata Kemal.
Menurut Kemal, Lhokseumawe sudah harus bergeser ke sumber ekonomi di luar migas. “Kita tidak bisa lagi menggunakan pola pikir lama, ada migas kita sejahtera. Itu bullshit,” kata Kemal.

***
Fernan, Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, menilai apa yang hari ini terjadi di Aceh Utara dan Lhokseumawe setelah Arun LNG berhenti beroperasi menjadi pembelajaran agar pemerintah bisa menyiapkan sejak awal mekanisme transisi energi menjelang berakhirnya eksploitasi migas.
Penyiapan ini termasuk menjamin transisi tenaga kerja dan menyediakan instrumen ekonomi mandiri di luar sektor migas. Pemerintah juga harus memastikan alih fungsi lahan bekas wilayah kerja pertambangan migas agar tidak terjadi konflik berkelanjutan seperti yang dialami warga Blang Lancang-Rancong.
“Ini menjadi pelajaran penting karena hari ini ada delapan operator migas yang berstatus eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh. Jangan sampai kutukan sumber daya alam atau resource curse di Arun terulang,” kata Fernan.
Nurdin (50), adalah warga lain yang ikut bertahan tinggal di sekitar eks kilang LNG Arun. Rumahnya berkonstruksi anyaman bambu. Ia tinggal bersama istri dan empat anaknya. Rumah itu ia bangun dengan memotong pohon dan bambu yang tumbuh di sekitar kawasan kilang.
“Tidak ada uang bangun rumah. Bahan bakunya seperti kayu kami ambil di sekitar kilang. Potong bambu,” ujar Nurdin.
Rumah Nurdin saat ini tidak berdiri persis di tanah asal. Keluarganya dulu tinggal di Rancong Barat. Saat pembebasan lahan, mereka pindah ke Kuala Meuraksa Punteut, Lhokseumawe. Pada 2015, ia membawa serta keluarganya kembali ke tanah leluhur.
Sejak tinggal di kawasan eks kilang Arun, ekonomi Nurdin makin sulit. Pekerjaan tidak menentu. Ia biasanya melaut. Di waktu lain, ia memetik buah sawit yang tumbuh di sekitar.
“Cukup beli beras untuk anak-anak,” katanya. Tapi pada saat yang lain, Nurdin berat menutupi kebutuhan harian. “Kami harus berhutang.”
Nurdin nyaris menyerah menuntut haknya. “Sampai saat ini belum ada kepastian. Kami sudah merasa lelah,” katanya.

Pada sore mendung setelah hujan sempat mengguyur sebentar, Syamsuddin bersama Nurdin mendekat ke gerbang itu dan menatap plang berkelir putih bertulisan “area tertutup”.
Sampai kapan akan tinggal di sana dan menuntut resetlemen?
“Kami tetap menuntut hak kami berdasarkan perjanjian. Kami tetap akan bertahan sampai ini selesai,” jawab Syamsuddin.
“Masa perusahaan raksasa tidak bisa menyelesaikan persoalan. Apakah PT Arun pabrik tempe dan tahu?”