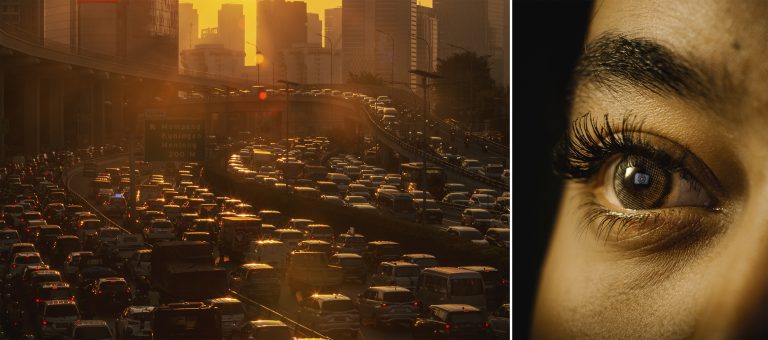Penolakan proyek geothermal di Flores bukan sekadar soal lingkungan, tetapi pilihan moral Keuskupan Agung Ende untuk berpihak pada rakyat.
“Para imam diancam untuk dibunuh! Kami, tim, diancam untuk dibunuh! Kades (kepala desa) diancam untuk dibunuh!” ucap RD Reginald Piperno atau Romo Perno dengan lantang.
Imam Keuskupan Agung Ende yang kini bertugas sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran itu menyadari ancaman pasti akan datang ketika ia, bersama para rohaniwan dan pegiat lingkungan, menolak keberadaan proyek geothermal di Pulau Flores.
Sejak awal, pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Flores, termasuk Keuskupan Agung Ende.
Dalam momen Natal Bersama di Ndona, awal tahun ini, Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD, secara terbuka meminta para imam di Keuskupan Agung Ende untuk memberikan perhatian dan informasi kepada umat dan masyarakat atas dampak pembangunan.
Dukungan Keuskupan Agung Ende kepada warga muncul setelah beberapa waktu melihat dan mendengar langsung kesaksian warga yang terdampak proyek geothermal di wilayah seperti Mataloko dan Sokoria.
“Saya menentukan sikap, menolak geothermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kevikepan kita,” kata Uskup Budi, dikutip dari akun Youtube Komsos Keuskupan Agung Ende (KAE).
Upaya gereja menolak pembangunan geothermal juga ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Advokasi Geothermal Keuskupan Agung Ende yang melakukan aktivitas di antaranya konsolidasi dengan paroki-paroki di titik-titik geothermal, serta penilaian lapangan.
***
Kerusakan Lahan Menahun
Sudah hampir dua dekade warga di Kampung Turetogo, Desa Wogo, hidup was-was karena rumah dan lahan pertaniannya bisa sewaktu-waktu lebur karena uap panas.
“Kalau tidur malam, runtuh, ya, sudah, kami runtuh saja,” kata Maria Baka (64), salah satu ibu rumah tangga di kampung yang berada di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Sejak 2006, lubang-lubang kecil yang mengeluarkan uap panas dan bau tidak sedap seperti telur busuk bermunculan, berjarak sekitar 300 meter rumahnya yang juga berada di area pertanian warga. Dari satu-dua lubang, hingga hari ini, jumlahnya mencapai sekitar 20-an lubang.

Kehadiran lubang-lubang itu berasal dari pengeboran sumur untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal di Mataloko. Proyek ini adalah kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan NEDO (New Energy Development Organization) Jepang pada periode 1998-2000.
Namun, pengeboran sumur ini gagal karena kemunculan semburan uap liar, sehingga ditutup. Pengeboran kedua dilakukan pada tahun 2000, diawali dengan ritual adat bunuh kerbau yang diikuti oleh mantan Bupati Ngada Yohanes Samping Aoh. Pengeboran pada titik kedua ini juga tidak berhasil.
Dampak dari kegagalan upaya eksplorasi ini terus dirasakan warga sekitar hingga hari ini.
Bukan hanya lubang-lubang uap panas kecil, sejak keberadaan proyek tersebut, kebun-kebun warga tidak produktif karena tanaman mati.
“Kami takut ini kalau mereka bor lagi di sana kita ini habis,” kata Felix Pere (79), salah satu warga yang menjadi saksi hidup kegagalan pengeboran pertama itu.
Sekitar 300 meter dari belakang rumah Felix, terdapat lubang-lubang menyerupai kawah lumpur berwarna abu-abu pekat dan menyemburkan uap panas. Selain itu, atap rumahnya yang terbuat dari seng tidak bisa bertahan lama lebih dari enam bulan.

Felix telah berkali-kali mengganti atap seng rumahnya, namun Maria bersikeras tidak akan menggantinya.
“Mau runtuh atau bagaimana caranya, ini tanah leluhur kami, mau lari ke mana, mati hidup kami di sini!” kata Maria.
Sejak kemunculan lubang-lubang berasap itu, satu per satu warga meninggalkan lahan pertanian milik mereka. Lubang yang semula kecil juga akhirnya membesar, menyerupai kali yang membuat lumpur panas juga mengalir ke sungai di sebelah lahan. Air pun mulai tercemar.
Hasil kajian Tim Advokasi Geothermal Keuskupan Agung Ende mencatat, sejak 2006 hingga April 2025, jumlah lubang semburan lumpur panas di sekitar desa berkisar 20 titik. Tanda-tanda kemunculan lubang semburan panas awalnya seperti puntung rokok yang terbuang di lahan kering. Asap lalu membesar dan membentuk lubang. Setelah membesar, lubang sempat mengering tetapi muncul lubang baru di titik lainnya.

“Ada rumah di Desa Wogo yang semburannya muncul di dapur, sekarang tinggal pondasi, mereka sudah pindah jauh dari Mataloko karena trauma,” kata Romo Perno.
Ia meragukan klaim PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menyebut semburan terjadi pada tempat-tempat yang telah memiliki plang sebagai penanda. Masalahnya, semburan juga terjadi di luar plang yang telah terpasang.
“Ada 15 meter di luar plang yang mereka pasang, tanah ini milik warga,” ujar Romo Perno melanjutkan.
***
Oktober 2024, sejumlah warga terdampak bergabung dan membentuk Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Paroki Santo Yosep Laja di Kecamatan Golewa Selatan.
April 2025, belasan warga yang tergabung dalam forum itu menuntut semua pihak yang bertanggung jawab dalam proyek geothermal untuk tidak lagi menyedot air dari aliran Sungai Tiwubala, mulai dari mata air Wae Nuka sampai Pua-Maumbawa.
Nikolaus Ago, sang ketua forum, mengatakan pihak berwenang tidak pernah transparan dengan aktivitas proyek. Beredar informasi bahwa proyek pembangunan geothermal akan dilanjutkan dan menargetkan mata air di wilayah Laja sebagai sumber ekstraksi. Dugaan itu semakin kuat dengan adanya pemasangan pipa-pipa berwarna oranye ke arah Laja yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu.
Pembangkit listrik geothermal membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mengekstraksi cairan panas dari perut bumi. Biasanya pengeboran untuk mencari sumber panas hingga 3.000 meter. Beberapa laporan Project Multatuli menemukan penyedotan air untuk proyek geothermal berakibat pada kekeringan, lapisan tanah yang rentan longsor, hingga pencemaran air oleh mineral berbahaya.

Bagi warga setempat, air bukan hanya dipakai untuk minum atau kebutuhan sanitasi. Air menjadi salah satu unsur penting dalam ritus budaya dan sumber penghidupan warga. Oleh karena itu, pencemaran air akan mengganggu ritus-ritus adat yang selama ini telah diwariskan turun temurun.
Mikael Keo (55), salah satu anggota forum menambahkan, air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga di desa tersebut diambil dari mata air Wae Mosa dan Wae Kusi. Dahulu, air terlihat jernih dan bisa langsung diminum tanpa perlu melalui proses memasak menggunakan api. Kini, air tidak bisa langsung diminum begitu saja. Air terlihat keruh, sesekali tercium aroma belerang.
“Tidak berani minum langsung, harus masak,” kata Mikael.
Tak jauh dari rumah Mikael, Esi Daku (70), seorang perempuan renta menunjukkan air dalam bak mandi yang penuh dengan endapan lumpur. Air yang telah dimasak pun masih memiliki endapan berwarna coklat yang pipih dan mudah hancur saat dipegang.
“Dulu jernih, sekarang kalau tampung air selalu ada lumpur tanah di bawah,” ucap Esi.
Kajian Tim Advokasi menemukan sumber-sumber mata air panas, seperti di Manna dan Molumegeze, kita tidak bisa lagi dijadikan tempat pemandian bagi warga, terutama yang memiliki penyakit kulit. Selain itu, sungai irigasi yang mengairi sawah untuk sebagian lahan pertanian di Mataloko juga telah tercampur dengan material semburan lumpur panas. Akibatnya masyarakat merasakan penurunan produksi pertanian.
“Wilayah ini hutan lebat kini menjadi wilayah tandus,” ungkap Romo Perno.

Romo Perno menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dengan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal). Dalam dokumen itu, air yang digunakan untuk kepentingan pengeboran diambil dari mata air Mataia di Mataloko.
“Tapi dalam pelaksanaannya diambil dari mata air Waeluja (Laja) kurang lebih 5 km dari Mataloko,” katanya.
***
“Flores ini ada salah apa sampai kamu kasih lubang kami punya tanah semua? Flores ini Pulau Bunga, bukan Pulau Geothermal,” ucap Dominikus Losa, warga Desa Radabata di Kecamatan Golewa, saat kami temui di rumahnya.
Meski cahaya lampu ruang tamu hari itu terlihat suram, sorot matanya yang tajam tak bisa menutupi kemarahannya. Ia mati-matian tidak mau menjual tanah untuk dijadikan lokasi pengeboran proyek geothermal.
Sebelum malam menjemput, Domi ditemani anak perempuannya mampir ke kebun yang ia pertahankan untuk tidak dijual. Pada bagian tengah lahan seluas 50 x 70 meter itu, terdapat susunan batu yang dipagari seadanya. Ia membersihkan sekeliling batu, sambil mulutnya komat-kamit berdoa. “Saya harus izin dulu,” ucapnya datar.
Tempat yang disebut sebagai mata uma itu adalah altar sesajian bagi leluhur. Mata uma merupakan simbol ruang hidup, keberadaan leluhur, tempat segala ritus kebudayaan dimulai. Dari tempat itu, masyarakat adat memanjatkan doa pada leluhur. Mereka meyakini mori watu mori tana atau leluhur sebagai pemilik tanah.

Sudah empat tahun, Domi berkeras mempertahankan tanah leluhurnya. Ia menolak sejumlah tawaran dari berbagai pihak baik secara lisan maupun tulisan. Ia berpegang pada pesan Paus Fransiskus untuk selalu menjaga Bumi.
Domi juga menganggap kebutuhan listrik di daerah itu sudah terlampau cukup, sehingga tidak dibutuhkan listrik dengan jumlah besar, apalagi sampai harus melukai Bumi.
“Sudah gagal total bagaimana bisa ada pengembangan? ‘Kan, tidak masuk akal, itu maksudnya bagaimana?” ucapnya.
Lahan milik Domi merupakan kebun ulayat untuk dua keluarga besar. Lahan itu berbatasan langsung dengan pagar lokasi pengembangan baru proyek geothermal yang sedang dalam proses pemasangan pipa.
Gereja dan Gerakan Melawan Kesewenangan
Secara garis besar, terdapat 12 titik yang telah ditandai sebagai titik geothermal di wilayah Keuskupan Agung Ende dengan perincian lima berada di Kabupaten Ende, tiga di Kabupaten Nagekeo, dan empat di Kabupaten Ngada.
Di Ende, lima titik itu berada di Sokoria, Kecamatan Ndona Timur; Detusoko, Kecamatan Detusoko; Jopu, Kecamatan Wolowaru; Kombandaru, Kecamatan Ende; dan Lesugolo, Kecamatan Kota Baru.
Di Nagekeo, tiga titik ada di Pajoreja, Kecamatan Mauponggo; Maropokot, Kecamatan Aesesa; dan Rendoteno, Kecamatan Aesesa Selatan.
Sementara di Ngada, titik yang telah ditandai berada di Mataloko, Kecamatan Golewa; Nage, Kecamatan Jerebuu; Gou Inelika, Kecamatan Bajawa Utara; dan Mangeruda, Kecamatan So’a.
Hasil penelusuran Tim Advokasi menyimpulkan bahwa proyek geothermal tidak cocok dilakukan di Pulau Flores, termasuk di Mataloko. Ada beberapa alasan yang mendasari sikap penolakan tersebut.
Wilayah Flores umumnya, terutama tiga kabupaten yang berada dalam wilayah Keuskupan Agung Ende yakni Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende memiliki topografi berbukit-bukit yang menyisakan sedikit lahan untuk pertanian dan tempat tinggal warga yang sebagian besarnya adalah petani.

Romo Perno bersama timnya menyadari, proyek yang membutuhkan lahan luas dan air dalam jumlah besar ini akan berdampak pada daerah pertanian yang sejak lama dikenal dengan kesuburan tanahnya.
Bagi masyarakat Flores, pertanian menjadi bagian penting dalam pembentukan kebudayaan setempat. Banyak ritus adat/budaya di tiga wilayah tersebut yang berhubungan dengan pertanian.
Hasil kajian juga mencatat potensi kerusakan struktur adat dan budaya akibat keberadaan proyek. Romo Perno menyebut lokasi proyek geothermal berada di tempat pemukiman penduduk dan kurang lebih 500 meter dari perkampungan adat Wogo.
“Ketika kita mengambil lahan sedemikian besar, pertama terjadi perampasan ruang hidup masyarakat, lalu pemusnahan budaya, secara perlahan membunuh masyarakat petani, karena sebagian besar masyarakat itu petani,” kata Romo Perno.
***
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya pernah mengevaluasi kegagalan proyek geothermal pada tahun 2004. Dalam dokumen hasil kajian disebutkan sumur-sumur pengeboran tidak memenuhi syarat sebagai pemasok uap untuk PLTP Mataloko yang menargetkan produksi hingga 40 ton fluida per jam untuk kapasitas listrik 2,5 MegaWatt. Sumur-sumur itu juga telah ditutup pasca-semburan liar uap panas dan gas.
Kendati demikian, pada 2005, pengeboran sumur ke-5 dan 6 kembali dilakukan. Pada tahap ini, pengembangan geothermal berada di bawah koordinasi PLN dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Setahun berselang, PLTP Mataloko dengan kapasitas 5 MW itu selesai dan diresmikan. Empat tahun beroperasi, pembangkit mengalami kerusakan pada 2010. Kerusakan sempat diperbaiki. PLTP beroperasi kembali pada 2013 hingga 2015. Tapi, tidak lama, kembali tidak berkapasitas pada akhir tahun 2015.
Meski mengalami kegagalan berulang, PLN tetap memaksakan melanjutkan proyek geothermal pada tahun 2019 dengan pengeboran di lokasi berbeda. Proyek dengan anggaran mencapai Rp108 miliar tersebut kembali dihentikan karena memunculkan gas belerang.
Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menyebut proyek geothermal Mataloko sebagai bentuk pengkhianatan, karena telah mengalami kegagalan berulang, namun tidak dihentikan. Pemerintah dinilai tidak bertanggung jawab karena mengaktifkan kembali proyek tersebut bahkan memperluas proyek itu ke wilayah lain di Ngada maupun Pulau Flores atau Lembata secara umum.
Selain dampak lingkungan, proyek geothermal di Mataloko juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi kulit, sesak napas, hingga gangguan mata. Namun, pantauan Jatam menemukan fasilitas kesehatan di wilayah dengan tambang tidak memiliki perbaikan dalam hal fasilitas dan kompensasi.
“Mataloko telah menjadi bukti telanjang dari kegagalan proyek energi yang mengatasnamakan kemajuan namun meninggalkan jejak penderitaan, kerusakan, dan kematian yang mengintai,” ucapnya
Melki menyoroti adanya pengabaian pada kondisi nyata Flores yang merupakan wilayah rawan bencana di jalur cincin api atau ring of fire; zona patahan aktif dengan potensi gempa bumi, dan letusan gunung api.
Maka dari itu, proyek ini bukanlah solusi hijau, melainkan pemicu bencana yang lebih besar, lanjutnya.
“Untuk siapa semua ini dilakukan? Siapa yang menikmati listrik dan keuntungan dari proyek ini? Apakah warga kampung atau justru industri hilir semacam pariwisata super premium?” kata Melky.
Tim “Independen” Usulan Gubernur
Jumat, 4 April 2025, Gubernur NTT Melki Laka Lena menggelar pertemuan tertutup dengan Uskup Budi di Istana Keuskupan Agung Ende. Dalam pertemuan itu, Melki mendukung usulan agar pembangunan geothermal sebaiknya ditunda.
Setelah pertemuan itu, Pemerintah Provinsi NTT mengirim surat ke Keuskupan Agung Ende meminta agar keuskupan mengirimkan empat orang untuk menjadi bagian Tim Penyelesaian Masalah Pengembangan Panas Bumi (Geothermal) di Flores.
Keuskupan Agung Ende menolak permintaan itu. Dalam surat balasannya, Sekretaris Keuskupan Agung Ende RD Damianus Dionisius Nuwa mengatakan tujuan pembentukan tim tidak sesuai dengan hasil pembicaraan Uskup Budi dan Gubernur Melki beberapa waktu lalu.
Menurut Romo Damianus, dalam pertemuan, Gubernur Melki menyatakan akan mengusulkan adanya perbaikan atas dampak dari proyek geothermal yang dialami warga. Sebelum melakukan perbaikan, dibutuhkan kajian investigasi dari data-data di lapangan. Maka dari itu, kajian harus dilaksanakan oleh tim independen. Namun, pihak Keuskupan Agung Ende menemukan bahwa PLN dan perusahaan juga terlibat di dalam tim tersebut.
“Karena itu tidak seharusnya kita melibatkan pihak yang sedang melaksanakan ataupun yang menolak proyek tersebut,” kata Romo Damianus dalam surat jawaban tersebut.
Menurutnya, tim seharusnya terdiri dari akademisi juga didampingi para ahli terkait lainnya.
“Kami tetap berkomitmen untuk berpihak pada masyarakat yang menjadi korban dari proyek geothermal ini,” katanya.
Melky Nahar dari JATAM meminta agar Gubernur NTT Melki Laka Lena tidak perlu mengelabui publik dengan tim uji petik karena semua fakta lapangan telah cukup untuk membuktikan kerusakan fatal dari proyek geothermal di Pulau Flores.
Yang dibutuhkan kini, bukanlah tim studi, melainkan keberanian menegakkan keadilan seperti penghentian total operasi geothermal di Flores, melakukan audit forensik independen terhadap dampak lingkungan dan sosial, penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran dan kelalaian, serta pemulihan ekosistem dan kompensasi penuh untuk warga terdampak.
Dari Surat ke Jejaring Gereja
Pernyataan penolakan proyek geothermal yang disampaikan Uskup Budi pada acara Natal Bersama awal tahun ini, bukan menjadi akhir dari sikap gereja.
Upaya membangun resistansi umat kembali dipertegas melalui Surat Gembala Prapaskah Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende 2025. Surat itu ditandatangani oleh enam uskup: Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden SVD, Uskup Denpasar Mgr Silvester San, Uskup Larantuka Mgr Fransiskus Kopong Kung, Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, Uskup Maumere Mgr Edwaldus Martinus Sedu, dan Uskup Labuan Bajo Mgr Maksimus Regus.
Pada poin pertama, Provinsi Gerejawi Ende menyoroti eksploitasi energi yang terjadi di wilayah keuskupan. Berangkat dari penekanan Paus Fransiskus dalam Laudato Si yang menekankan bahwa ada keterkaitan antara krisis sosial dan lingkungan, Gereja Katolik mendorong penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab dengan visi berkelanjutan.
Gereja sepakat melihat bahwa geothermal bukan pilihan yang tepat untuk konteks Flores dan Lembata dengan berbagai hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya. Geothermal adalah pilihan eksploitatif yang bertabrakan dengan arah utama pembangunan yang menjadikan wilayah itu sebagai daerah pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan unggulan, dan kelautan.
“Eksploitasi yang tidak bijaksana berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan kebudayaan,” bunyi surat yang ditandatangani pada 13 Maret 2025.
Sikap serupa kembali diserukan oleh Keuskupan Agung Ende pada 15 Maret 2025, setelah mendapat kunjungan dari Kementerian ESDM Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (ESDM-EBTKE), PLN, PT Daya Mas Nage Geothermal, PT Sokoria Geothermal Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngada, dan Pemerintah Kabupaten Ende.
Selain pernyataan tulis yang telah dikeluarkan pada beberapa kesempatan, sikap keberpihakan Keuskupan dengan warga terdampak juga pernah ditunjukkan melalui aksi damai tolak proyek geothermal Mataloko di Bajawa, pada Maret 2025. Aksi serupa juga dilakukan pada Juni, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Romo Perno menegaskan, aksi damai dan penyampaian surat resmi penolakan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Menurutnya, aksi tersebut justru bentuk ajakan terhadap para wakil rakyat untuk terlibat bersama dalam gerakan mendukung warga.
“Kami mengajak mereka untuk terlibat untuk menyuarakan suara kami, meneruskan suara karena kita semua korban,” kata Romo Perno.
Ia juga menegaskan tentang Laudato Si yang menjadi bentuk kepedulian gereja untuk berhati-hati menjaga lingkungan. Untuk itu, para imam harus “tegak lurus” pada perjuangan yang telah dimulai melalui pernyataan Uskup Budi.
Tak hanya para imam di Keuskupan Agung Ende, sesama umat juga harus ikut berempati terhadap para korban dan ikut dalam jalan perjuangan yang sama.
“Gereja selalu berpihak pada korban, tetap berpihak pada masyarakat dan para korban, dan gereja akan berjuang dengan berbagai cara,” Romo Perno menegaskan.
Baginya, ancaman pembunuhan yang diterima oleh para pegiat lingkungan termasuk para imam dan tim advokasi dari Keuskupan Agung Ende menjadi bukti bahwa telah terjadi konflik horizontal yang cukup tinggi dalam lingkungan sosial masyarakat.
Namun, penyadaran publik terus berjalan hari demi hari untuk membangun resistansi di masyarakat bahwa para pihak yang melakukan pengancaman juga menjadi korban penipuan dari proyek itu. Sosialisasi yang tidak transparan itu menjadi bukti manipulasi pada masyarakat.
“Semua masyarakat lokal itu sebenarnya jadi korban, baik yang setuju maupun tidak setuju, itu semua jadi korban penipuan,” tukasnya.
***