Peringatan: Artikel memuat penuturan kekerasan seksual dan percobaan bunuh diri yang dapat mengganggu kenyamanan Anda
Mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berpihak pada korban tidak berjalan maksimal di organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Pelaku tak jera, sementara korban menanggung sendiri traumanya.
JINGGA butuh waktu meyakinkan diri ia adalah korban kekerasan seksual sebelum memutuskan untuk melapor ke bagian sumber daya manusia (SDM) di tempatnya bekerja, sebuah organisasi yang giat berkampanye tentang pemberdayaan perempuan muda.
“Ini tuh apa, ya?”
“Kejadian kayak gini tuh wajar nggak, sih?”
Ia sempat mengisahkan kejadian itu ke rekan kerjanya. Tapi, rekan kerjanya menyarankan Jingga membatalkan niat untuk melapor.
“Oh, dia tuh emang suka sama elo tau. Suka sama suka. Sudah, nggak usah diaduin,” kata Jingga, menuturkan respons rekan kerjanya itu.
Di sisi lain, pelaku berlagak menyesal dengan mengatakan, “Gue minta maaf. Gue harusnya nggak boleh kayak gini. Harusnya gue jagain elo.”
Terduga pelaku adalah atasannya sendiri, Selatan. Jingga bekerja di organisasi nirlaba (NGO), Yayasan Plan International Indonesia.
Permintaan maaf atasannya itu malah membuat Jingga menyalahkan diri sendiri. Padahal kejadiannya bukan baru sekali.
Kejadian-kejadian itu terus merasuki pikirannya, mengganggu kesehariannya, dan menyerang kesehatan mentalnya. Pada satu titik, Jingga sempat melakukan percobaan bunuh diri.
Jingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Kendati begitu, keputusannya untuk mundur justru memunculkan keberanian untuk mengadukan kasusnya.
Ia melaporkan kasusnya langsung kepada salah satu petinggi Plan International Indonesia. Laporan langsung diteruskan ke departemen SDM dan ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi internal.
“Jadi aku cukup berekspektasi mereka akan cukup baik menanganinya,” kata Jingga.
Ketika itu ia tidak memahami apakah organisasi memiliki pedoman penanganan kasus kekerasan seksual. Ia hanya menggantungkan harapan pada nilai-nilai yang diusung organisasi.
Harapan yang ada dalam benak Jingga adalah kasus akan ditangani tanpa menyudutkan posisinya sebagai penyintas.
Ia juga berharap mendapatkan informasi dan akses terhadap pendampingan psikologis, transparansi atas setiap tahap proses investigasi, jaminan keamanan dan kerahasiaan dari kasus yang sedang ditangani, termasuk identitasnya sebagai pelapor.
“Power Abuse, Bukan Kekerasan Seksual”
Apa hubungan antara kamu dan pelaku di luar pekerjaan?
Pertanyaan itu menjadi pembuka yang dilontarkan tim investigasi kepada Jingga dalam pertemuan dengar (hearing) kesaksian awal sesudah pembentukan tim “investigasi”.
“Aku jawab, nggak ada hubungan apa-apa. Kita hanya karyawan biasa, dan hubungan di divisi itu memang dekat seperti teman-teman kampus. Jadi nggak ada hubungan apa-apa,” kata Jingga.
Pada sesi itu tim investigasi menyatakan kasus akan diselidiki dengan mengumpulkan semua fakta, termasuk dari pelaku. “Kita akan coba menyelidiki, tapi kita di sini harus netral, pakai praduga tak bersalah. Nanti, si terduga pelaku ini akan kita wawancara,” cerita Jingga.
Kendati demikian, selama proses penyelidikan, tim investigasi tidak pernah menawarkan Jingga untuk menghadirkan saksi dari pihaknya. Alih-alih, tim menghadirkan saksi-saksi dari pihak terduga pelaku.
Para ‘saksi’, menurut penuturan Jingga, menyampaikan kesaksian yang hanya menguatkan argumen tentang ada “hubungan romantis” antara Selatan dan Jingga.
Tim investigasi juga seperti tidak serius ketika menawarkan pendampingan psikologis untuk Jingga selama proses tersebut. Dari penuturan salah satu bekas rekan kerjanya, Plan International Indonesia memiliki akses ke psikolog apabila dibutuhkan, tetapi tidak pernah ada informasi yang jelas terkait akses ke layanan tersebut.
“Jika memang disuruh ke psikolog, [aku seharusnya] dibuatkan link mungkin, atau benar-benar dijembatani ke psikolognya. Kan nggak mungkin aku tiba-tiba chat, ‘Aku dapet kekerasan, nih,’” kata Jingga.
Pertemuan kedua Jingga dan tim terjadi berkisar kurang dari satu bulan. Namun, pada pertemuan ini, tim mengaku selama ini tidak melakukan investigasi tetapi hanya mendengarkan keterangan dari beberapa pihak: Jingga, Selatan, dan sejumlah saksi. Alasannya: investigasi bukan bidang yang mereka kuasai.
Kendati demikian, menurut Jingga, tim menyimpulkan tiga poin dari hasil pertemuan-pertemuan itu.
Pertama, pelaku mengakui ada hubungan seksual tetapi membantah itu dilakukan dengan paksaan, melainkan “mau sama mau”.
Kedua, tim memutuskan tak ada kekerasan seksual yang terjadi karena tak ada bukti dan saksi pendukung. Namun, pelaku dinyatakan telah melakukan penyelewengan kekuasaan alias power abuse.
Jingga mempertanyakan pertimbangan keputusan itu dalam forum tersebut. Ia menolak klaim “mau sama mau”.
“Karena di bawah pengaruh alkohol jadi kami nggak tau sebenarnya kamu mau atau nggak. Jadi masih abu-abu posisinya, dan kita nggak bisa investigasi lebih jauh soal consent ini karena kita nggak ahli di bidang itu,” ujar Jingga, menyampaikan ulang jawaban tim.
Dalam penjelasan mengenai aktivitas seksual oleh UN Women, consent atau persetujuan aktivitas seksual tidak dapat diberikan oleh orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol. Tanpa persetujuan, maka perilaku tersebut masuk dalam kategori kekerasan seksual.
“Setelah itu, mereka memutuskan kasus ini sudah selesai. Pelaku sudah dihukum dengan diberhentikan … Klaimnya itu power abuse, tapi bukan kekerasan seksual,” katanya..
Poin terakhir yang tim sampaikan kepada Jingga adalah rekomendasi agar ia melaporkan kasus ini ke ranah hukum dengan syarat, “Kalau mau mengajukan ini ke ranah hukum, silakan lapor polisi, tapi perlu diingat, melapor ke polisi itu pasti melelahkan, capek, susah, dan sebagainya.”
“Yang mana aku juga sudah tahu,” kata Jingga.
Gosip Menyebar, Jingga Dikejar
Jingga menghadapi seluruh proses penanganan kasusnya seorang diri. Tanpa pendamping dan dukungan, khususnya dari Yayasan Plan International Indonesia yang pernah menjadi tempatnya mencari nafkah dan pengalaman hidup itu.
Sementara, selama menjalani proses itu, “Aku merasa kalut, aku takut.”
Keadaan diperburuk dengan tersebarnya informasi terkait pelaporan Jingga ke organisasi. Informasi tersebar dari mulut ke mulut yang pada akhirnya sampai kembali ke telinga Jingga.
“Tentu saja aku merasa nggak aman. Aku merasa [kasus] ini nggak benar-benar tertutup sampai kasus ini banyak yang tahu, banyak orang yang akhirnya tahu, padahal harusnya ditutup, jangan sampai ada yang tahu,” katanya.
“Dan orang-orang …. ketika aku mengadu, aku takut aku disalahkan, yang akhirnya itu beneran terjadi.”
Salah satu mantan rekan kerjanya, yang juga dekat dengan Selatan, menghubunginya secara intens dengan tujuan mengajak Jingga bertemu.
Kekecewaan terhadap penanganan kasus yang dialaminya memuncak. Bukan hanya tidak ada jaminan keamanan dan kerahasiaan, tetapi juga kesimpulan tim investigasi menyanggah ada kekerasan seksual.
“Aku berharap mereka mengakui ada kekerasan seksual di kantor mereka. Dan mereka bisa menjadikan itu pembelajaran baru dari hal tersebut, (bagaimana agar) mereka menangani lebih baik,” ungkap Jingga.
Utara, Kuning, dan Korban Lainnya
Di organisasi Plan International Indonesia, Selatan bukan satu-satunya yang ketahuan diduga melakukan kekerasan seksual.
Sebelum kasus Selatan dan Jingga, ada pelaporan lain yang melibatkan terduga pelaku lain, sebut saja Utara.
Utara dilaporkan oleh korban, sebut saja Kuning. Tapi, Utara tidak sampai dipecat karena lebih dulu mengundurkan diri sebelum kasus itu diproses.
Utara pindah ke organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka, Yayasan Tifa, pada Agustus 2018. Ia mendapat surat rekomendasi dari atasannya sebagai salah satu syarat melamar ke Tifa.
“Kesalahan dari pihak Tifa, pihak kami sebagai recruiter, adalah kami tidak spesifik menanyakan tentang track record kekerasan seksual,” ungkap Darmawan Triwibowo, Direktur Eksekutif di Yayasan Tifa pada Februari 2016 hingga 1 Mei 2019.
Dalam rekomendasi yang diberikan atasan Utara sebetulnya memuat pernyataan, “He also needs to conduct interpersonal relations carefully especially with female colleagues. However, I believe that he has capabilities to perform better”.
(Ia perlu lebih hati-hati dalam menjalin hubungan interpersonal, terutama dengan rekan kerja perempuan. Namun, saya percaya ia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkelakuan lebih baik.)
Namun, Tifa tak terlalu mempertanyakan kalimat dalam surat rekomendasi tersebut.
Permasalahan mulai terungkap saat Darmawan menerima surat elektronik dari Kuning pada Oktober 2018.
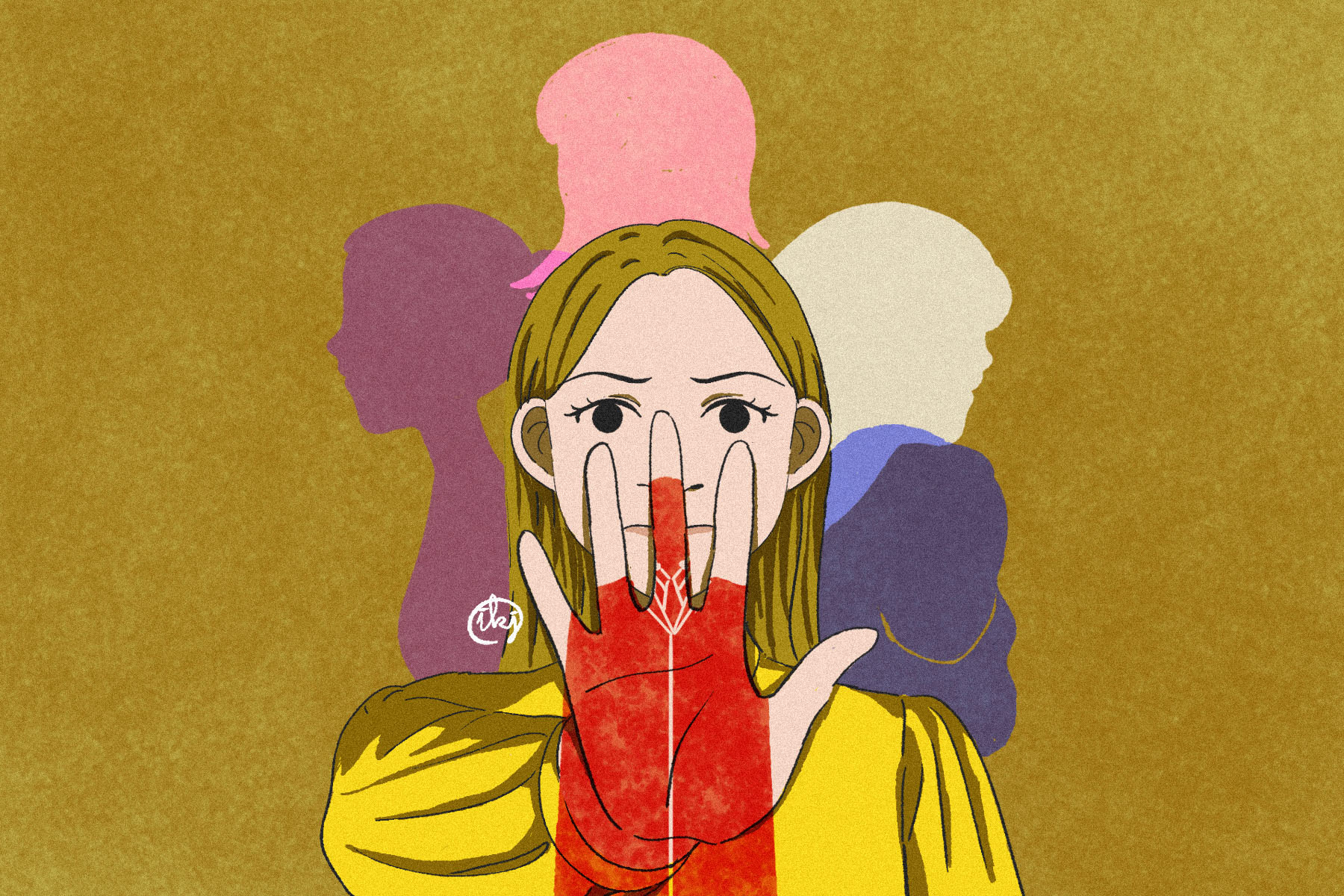
“Saya menerima surel dari Kuning. Kuning menyampaikan informasi bahwa Utara adalah pelaku pelecehan seksual berulang, repeated sexual offenders, di tempat bekerja sebelumnya, Plan International. Kuning menyatakan dirinya salah satu korban Utara dan meminta Yayasan Tifa mengambil tindakan terhadap Utara,” kata Darmawan.
Darmawan menindaklanjuti surel tersebut dengan menghubungi Direktur Plan International Indonesia, Dini Widiastuti.
Menurut Darmawan, Plan mengetahui tentang dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Utara. Namun, Utara mengundurkan diri sebelum kasus tersebut diproses. Kedua, surat rekomendasi tidak dikeluarkan secara resmi oleh organisasi, melainkan secara pribadi dari atasan Utara.
Masalah lain yang dihadapi oleh Tifa adalah tidak ada aturan internal yang mengatur tentang kekerasan seksual. Kasusnya tak banyak bergerak hingga Februari 2019, hingga datang laporan pelecehan seksual lain yang dilakukan oleh Utara kepada korban lain.
“Setelah mendapatkan informasi tersebut, saya memutuskan untuk membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut peristiwa yang terjadi,” kata Darmawan dalam wawancara pada awal Maret 2022.
Tifa akhirnya mengacu pada aturan-aturan organisasi lain yang bisa menjadi celah. Salah satunya prosedur umum penanganan konflik antar-staf dan acuan dasar penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja dari sumber lain.
“Jadi prosesnya memang kami tidak membuka pengaduan, tapi kemudian tim investigasi yang melakukan proses snowballing ke korban,” ungkap Darmawan.
Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya karena Tifa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memproses kasus ini dengan komprehensif. Hal lain, prosedur ini memiliki kelemahan, yakni kemungkinan ada penyintas yang tidak teridentifikasikan.
Investigasi berjalan sekitar enam pekan, dengan temuan Utara melakukan kekerasan seksual terhadap individu yang berbeda-beda, bahkan setelah ia menjadi pekerja di Tifa. Dua korban di antaranya adalah pekerja di Tifa.
Hasil investigasi juga menghasilkan dua putusan. Pertama, Yayasan Tifa memberhentikan Utara karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, di antaranya mengancam rasa aman dan keselamatan rekan kerja.
Kedua, Yayasan Tifa memberikan waktu dua minggu bagi Utara untuk menyelesaikan sisa beban kerjanya, serta mempersiapkan proses hand over. Dan, selama periode tersebut, Utara dilarang berada di lingkungan kerja maupun melakukan aktivitas yang mewakili Yayasan Tifa.
Kosongnya Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual
Meski tim investigasi Tifa menemukan bukti kekerasan seksual tetapi tidak ada sanksi selain pemecatan yang dijatuhkan kepada Utara.
“Karena kelemahan peraturan internal di Tifa, kesalahan ini harus di-frame dengan klausul lain yang memungkinkan organisasi memberikan sanksi. Nah, kami melihat bahwa pelecehan seksual yang dilakukan Utara itu menyebabkan pekerja lain merasa terancam atau tidak aman di tempat kerja,” jelas Darmawan.
Kasus itu menjadi refleksi bagi Darmawan terkait dampak dari kekosongan aturan mengenai kekerasan seksual dalam sebuah organisasi.
“Kalau melihat kronologinya, memang masih jauh dari ideal. Banyak sekali loophole ketika kami melakukan hal itu, tapi kami berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan acuan [aturan] yang ada dengan tambahan dari informasi lain,” katanya.
Darmawan menggarisbawahi keselamatan dan keamanan pekerja, termasuk dari kekerasan seksual, merupakan tanggung jawab organisasi.
Mekanisme keselamatan dan keamanan harus mencakup pencegahan yang dilakukan sejak tahap rekrutmen, penanganan saat terjadi laporan dugaan kasus, hingga memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.
“Yang kedua, proses investigasi ini tidak mungkin berjalan kalau tidak ada keberanian dari korban untuk bersaksi, menyampaikan keluhan, meskipun secara tertulis. Untuk mereka bisa bersaksi, mereka butuh trust dan rasa aman bahwa organisasi akan mendengar mereka,” katanya.
Chelvi Yuliastuti dari Departemen SDM Yayasan Tifa mengonfirmasi ada sejumlah perubahan yang menyangkut peraturan kekerasan seksual sesudah menangani kasus terduga pelaku Utara.
Kepada Project Multatuli dan KBR, Chelvi mengatakan saat ini Tifa memberlakukan prosedur lebih ketat atas pengecekan latar belakang calon pekerja. Mereka membuka Unit Penanganan Aduan sejak Oktober 2021.
“Jenis aduannya ada tiga. Pertama, terkait proses kerja sama; kedua, terkait perilaku yang tidak pantas; ketiga, terkait pelecehan seksual atau sexual harassment,” ujar Chelvi pada medio 2022.
Bila ada dugaan kasus, Tifa akan menggandeng jasa atau konsultasi dengan pihak ketiga, atau lembaga lain, yang memang secara khusus berfokus pada penanganan masalah kekerasan, baik proses pendampingan hukum maupun psikologis.
“Karena … mungkin di proses rekrutmen, kami bisa melihat dia orang baik, tapi saya enggak tahu selama berjalannya waktu, misal ternyata memang ada staf yang ternyata melakukan hal seperti itu,” kata Chelvi.
Antara “Willingness” atau “Kekeluargaan”
Project Multatuli dan KBR telah berbicara dengan pihak Plan International Indonesia, termasuk Dini Widiastuti, untuk mengonfirmasi kasus-kasus di atas. Kendati demikian, organisasi tidak bersedia untuk mempublikasikan informasi yang diberikan kepada tim reportase.
Poppy Diharjo, salah satu penggerak No Recruit List (NRL) yang mendampingi masalah kekerasan di ruang kerja, menyampaikan berbagai sektor pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bahkan lingkup aktivisme belum sepenuhnya memiliki mekanisme yang mampu menciptakan ruang aman kepada pekerjanya dari kekerasan seksual.
“Gue bilang, mau NGO, mau apa kek, rata,” ungkap Poppy.
Kadang-kadang emang bikin patah hati. Lo ngomong-ngomong saja bisa, ngomong begini, tapi ternyata di perusahaan lo begitu.Click To TweetHal senada disampaikan Nisrina Nadhifah, biasa disapa Ninis, yang berkecimpung di lingkungan NGO selama 13 tahun.
Ninis menjelaskan isu gender, termasuk kekerasan seksual, mulai masuk ke arus utama di lingkungan aktivisme pasca-Reformasi. Namun, percakapan soal pembenahan masalah kekerasan seksual di internal lingkup NGO baru muncul beberapa tahun terakhir, khususnya sejak banyak diramaikan di sosial media seperti Twitter.
“Beberapa di antaranya berhasil menanganinya dengan baik. Ada yang memang sudah punya SOP, ada yang belum punya SOP,” ujar Ninis.
“Tapi sebagian dari mereka, tidak. Bisa jadi karena tidak punya SOP, bisa jadi kombinasi antara memang tidak punya SOP dan memang tidak punya willingness. Itu menjadi kombo yang berbahaya. Karena setidaknya, kalau punya willingness (tapi) tidak punya SOP, bisa dibantu pembuatan SOP.”
Salah satu akar permasalahan yang membuat sejumlah lembaga masih membiarkan atau menormalisasi masalah kekerasan seksual adalah argumen nilai “kekeluargaan”.
“Di sini kita sudah seperti keluarga, memiliki cita-cita yang sama, punya visi-misi yang sama.”
“Selalu dalihnya sama-sama keluarga, satu sirkel,” kata Ninis.
Artikel ini berangkat dari Jingga yang hingga kini masih pontang-panting mencari keadilan. Jingga menemui dan membagi kisahnya ke tim kolaborasi Project Multatuli dan KBR terkait kasusnya tak tuntas hingga traumanya masih membekas.
Sampai hari ini Jingga masih merasa tak aman karena desas-desus mengenai kasusnya terus berpindah dari satu mulut ke mulut, dengan versi dirinya sebagai antagonis dalam permasalahan ini.
Jingga belum mengakses layanan psikolog untuk memulihkan dirinya.
“Sekarang aku masih gini-gini saja. Mungkin nanti akan coba ke psikolog, karena sekarang aku masih agak takut,” ujar Jingga.
Laporan ini adalah bagian pertama dari serial reportase #KekerasanSeksualDiTempatKerja, kolaborasi Project Multatuli dan KBR. Semua nama penyintas dan pelaku dalam artikel ini disamarkan atas alasan yang kami tuangkan dalam artikel pengantar. Serial reportase ini didukung oleh Kawan M.
Tim Kolaborasi membuat survei kekerasan seksual di ruang kerja, pembaca bisa berpartisipasi melalui tautan ini: https://bit.ly/KS-ruangkerja
Dengarkan siniar liputan KBR:
Pada 19 Mei 2022, Plan Indonesia melayangkan hak jawab atas artikel ini. Kami memuatnya pada 20 Mei: Hak Jawab Plan Indonesia untuk Artikel ‘Mendobrak Sirkel Sendiri: Saat Penyintas Melaporkan Kekerasan Seksual di NGO’
Pembaca bisa mengakses layanan konsultasi psikologi dan aduan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual berikut ini:
- Bantuan bagi korban kekerasan: carilayanan.com
- Hotline Kesehatan Mental dan Pencegahan Bunuh Diri: +62 811 3855 472 (L.I.S.A)
- ##NoRecruit List, melalui surat elektronik: [email protected]
- Link aduan kekerasan Komnas Perempuan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkS3HC1aSbk44u6joenNT-F-b1Of5aUKnuDUfrj6KLeuxlpg/viewform
- Link aduan KBGO (penyebaran konten intim via digital): https://id.safenet.or.id/laporkasus









