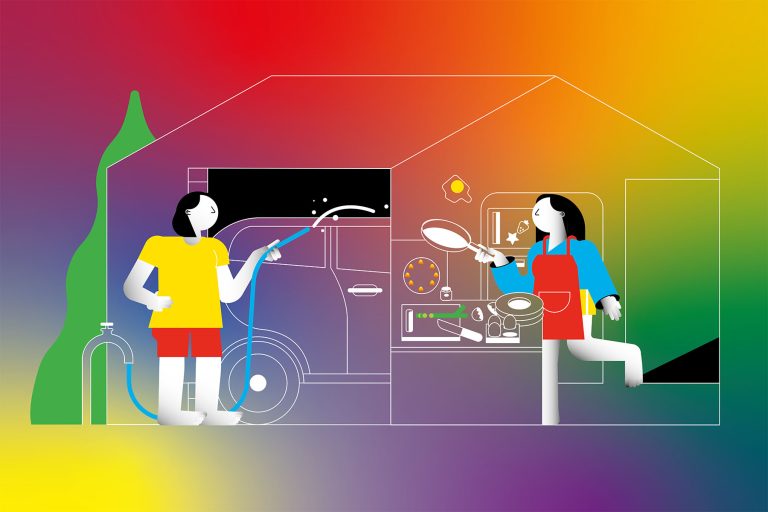Bayi laki-laki itu menangis di gendongan bapaknya. Tangisnya seketika berhenti ketika saya memberanikan diri mengajaknya bicara. Mata bayi 8 bulan itu menelisik sosok asing di depannya.
“Lagi sakit dia. Demam,” kata si bapak, Muhamad Agung, menjelaskan kenapa anaknya rewel.
“Sudah dibawa ke dokter tadi,” timpal Siti Halimah, ibu si bayi.
Muhamad Agung dan Siti Halimah, pasangan suami istri (pasutri) Gen Z. Kami bertemu di Kutawaringin Kabupaten Bandung, akhir April 2022. Usia Agung 22 tahun dan Siti dua tahun lebih muda. Mereka menikah di usia lebih muda lagi, saat Agung berumur 19 tahun dan Siti 17 tahun, usia yang masih tergolong anak-anak. Kemiskinan mempertemukan mereka.
Selepas SMP, Agung yang berumur 16 tahun, memutuskan berhenti sekolah dan memilih bekerja. Alasannya klasik, membantu orang tua, khususnya ibu. Ayah Agung meninggalkan ibu dan dua anaknya ketika Agung duduk di kelas 4 SD. Sejak itu, si ibu menjadi orang tua tunggal. Dia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil demi membiayai kehidupan mereka bertiga.
Agung kecil disuguhi kerja keras ibunya. Tetapi, kemiskinan terus mengiringi mereka. Kondisi itu membuat Agung ingin segera bekerja. Ia tak sabar memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, pun tak tahan bila terus membebani ibunya. Sekolah tidak lagi membuatnya betah, sementara cita-citanya sudah lama dilupakan.
Saat kelulusan tiba, Agung langsung mengiyakan ketika seorang tetangganya mengajak bekerja di sebuah pabrik garmen. Tak perlu ijazah sekolah tinggi-tinggi, ia hanya perlu pandai menjahit. Agung belajar menjahit dalam waktu seminggu. Ia diajari menjahit menggunakan mesin, bagaimana menjahit lurus, lingkaran, dan segitiga. Setelah mahir, si sulung dari dua bersaudara itu mulai bekerja di sebuah pabrik garmen yang memproduksi celana merek lokal terkemuka.
Di pabrik itu, Agung dipekerjakan sebagai buruh lepas yang bekerja secara borongan. Upahnya dihitung berdasarkan jumlah celana yang dijahit. Dalam waktu 9 jam kerja, Agung harus menyelesaikan target 800 helai celana per hari. Jika target tidak tercapai, jam kerja Agung ditambah, tanpa uang lembur.
Agung bukan satu-satunya, pekerja usia anak di pabrik itu. Agung tidak bisa menyebut angkanya dengan pasti. Ia hanya mengatakan, “banyak anak seumuran saya” yang diperlakukan sama dengan buruh dewasa lainnya. Di pabrik itulah, Agung dan Siti bertemu.
Siti masih berusia 14 tahun ketika melamar kerja ke pabrik tersebut. Perempuan berlesung pipit itu tidak menuntaskan pendidikan menengah pertama.
“Saya gak selesai SMP. Mau kerja saja, mau cari uang sendiri, bantu orang tua,” ungkap Siti, alasan yang senada dengan Agung.
Orang tua Siti tak bisa menolak keinginan anak bungsunya tersebut. Pendapatan keluarga saat itu hanya dari keuntungan menjual buah-buahan yang menjadi usaha bapaknya. Siti merasa keputusannya tepat, ketika kurang lebih setahun kemudian, ayahnya meninggal.
“Jadi setelah bapak meninggal, otomatis gak ada penghasilan,” beber Siti.
Siti kerja di bagian jahit, sama dengan Agung, dengan kondisi kerja yang juga serupa. Dia tetap bertahan bekerja di pabrik itu, meski tanpa kejelasan status, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja. Sebab, pikirnya, tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya.
Siti tidak menyangkal, jika dalam hatinya masih terbersit keinginan bersekolah dan bermain seperti teman-teman sebayanya. Namun, melihat kondisi ibunya, keinginan itu dipendam kembali, termasuk cita-cita menjadi dokter.
“Dari kecil sih pengen kerja, semenjak lihat mama, kasihan. Gaji langsung dikasih ke mama semua. Paling kalau mau jajan, baru minta ke mama,” ujar Siti.
Siti bekerja di pabrik tersebut hingga bertahun-tahun kemudian, bahkan saat kondisi hamil. Ia baru berhenti kerja setelah melahirkan anak, buah perkawinan dengan Agung.
Siti menikah karena disuruh ibunya, mengingat dia sudah setahun berpacaran dengan Agung. Ketika Agung melamar, sang ibu langsung menyetujui, meski saat itu usia Siti masih 17 tahun. Siti juga tidak menolak lamaran Agung. Bagi Siti, pernikahan menjadi jalan untuk menggantungkan hidupnya pada seorang lelaki yang dianggap sebagai jodohnya.
Di satu sisi, Agung menganggap sudah waktunya ia menikah. Ibunya pun mendukung dengan alasan “daripada diomongin tetangga” lantaran dianggap sudah lama pacaran dengan Siti.

Akan tetapi, kehidupan pernikahan tidak seromantis yang Agung dan Siti bayangkan. Terlebih lagi, bagi Siti yang berusia belia, di mana teman-temannya masih sekolah dan bermain dengan leluasa. Sedangkan Siti, berkutat dengan tugasnya sebagai istri dan ibu satu orang anak.
“Kadang suka iri lihat teman-teman yang lain. Iri pengen main, jalan-jalan sama teman. Tapi kan sekarang gak bisa, susah sama anak,” cetus Siti.
Pernikahan ternyata juga tidak melepaskan Siti dari kesulitan ekonomi. Apalagi, sumber penghasilan keluarga hanya dari Agung, sejak Siti berhenti kerja. Susahnya lagi, upah yang diterima Agung tidak tetap karena dihitung berdasarkan target dan orderan setiap bulannya. Dengan bertambahnya anggota keluarga baru, biaya kebutuhan sehari-hari menjadi membengkak.
Agung memang tidak lagi bekerja di pabrik garmen yang dulu. Dia sudah pindah ke pabrik garmen lain dengan harapan mendapat penghasilan yang lebih baik. Tapi apa hendak dikata, kondisinya ternyata tidak jauh berbeda.
Agung tetap berstatus buruh kontrak, padahal sudah dua tahun lamanya bekerja di pabrik tersebut. Upahnya tidak kunjung naik, tetap dibayar sesuai target dan orderan atau yang dikenal dengan sebutan upah kontribusi. Jam kerjanya kadang normal atau delapan jam, tapi seringkali molor hingga 12 jam dan tanpa uang lembur.
Dalam sebulan, besaran upah yang diterima Agung tidak menentu. Pernah mencapai Rp3,5 juta, tapi tak jarang juga hanya menerima Rp 1,9 juta. Angka itu diterima Agung setelah manajemen memotong sebagian upahnya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, juga iuran serikat pekerja.
Agung membeberkan skema upah yang diterimanya. Setiap pakaian dengan jenama tertentu memiliki upah yang berbeda, dari Rp100 hingga Rp280 per helai. Upah juga ditentukan tingkat kesulitan pengerjaan. Misalnya, jenama X dengan level A atau tingkat kesulitan tinggi akan dibayar lebih besar dibanding jenama Y yang tingkat kesulitan rendah atau level C. Agung mencontohkan upah menjahit untuk sebuah merek dengan level C, dia hanya dibayar Rp100 per helai pakaian. Agar mendapatkan upah sebesar Rp3,5 juta dalam satu bulan, Agung harus menjahit sebanyak 1500 helai pakaian per hari atau 500 helai pakaian per hari untuk merek tertentu dengan level B yang dibayar Rp280 per helai pakaiannya.
Saya tersentak lantaran kedua jenama yang disebut Agung berskala internasional dan cukup popular. Harga satu kemeja atau kaosnya, yang saya lihat di sebuah toko online, bisa mencapai Rp500 ribu.
Saya jadi ingat unggahan seorang Gen Z lulusan Universitas Indonesia (UI) yang sempat viral di pertengahan 2019. Si Fresh Graduate menolak sebuah pekerjaan karena digaji Rp8 juta. Saya bisa melihat begitu jauhnya kesenjangan yang terjadi antara Agung dan lulusan UI tersebut.
Agung juga menyadari betapa murah harga pekerjaannya, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya memiliki ijazah SMP dan keterampilan menjahit, sulit baginya beralih profesi.
“Kalau dibilang capek, ya capek, tapi gimana lagi. Kerjain saja, jalanin saja, apalagi sudah punya anak dan isteri. Saya cari yang (upah yang) besar gak ada, jadi yang kecil saja. Alhamdulillah dicukup-cukupi, agak dikurangi pengeluarannya,” ungkap Agung yang memangkas 50 persen jatah rokoknya sejak punya anak.
Agung sempat kelimpungan ketika diwajibkan mengunduh aplikasi Pedulilindungi untuk mengakses tempat kerja. Ia harus mengganti telepon genggamnya dengan kapasitas yang lebih besar agar bisa mengunduh aplikasi tersebut. Membeli handphone baru dengan harga Rp2 juta, tentu bukan jumlah yang kecil bagi Agung, tapi mau gak mau harus dilakukan. Akhirnya, Agung membeli secara kredit. Situasi yang sepertinya tidak terpikirkan oleh si pengambil kebijakan.
Jika Agung kelimpungan, Siti seringkali kebingungan mengelola keuangan setiap bulannya. Dalam sebulan, ia mengungkapkan, biaya kebutuhan harian mencapai Rp 3 juta. Jika kurang dari itu, Siti dengan berat langkah mencari pinjaman ke sana-sini.
“Suka pusing [mengelola uangnya]. Kalau sedikit, susah ngaturnya gimana, tapi dicukup-cukupkan. Kadang nombok, cari pinjaman sama orang lain. Nombok untuk beli pampers. Sudah punya anak mah untuk berobat, untuk keperluan lainnya. Susah sih kalau sudah punya anak dihemat-hemat juga,” keluh Siti.
Agung dan Siti telah membuang jauh keinginan bergaul dengan teman-temannya. Siti disibukkan dengan mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan Agung lebih memilih mencari uang dibandingkan menghambur-hamburkannya. Fokus Agung hanya bekerja, meski kondisinya tidak ideal.
Sikap Agung ini berbeda jauh dengan label yang sematkan pada Gen Z “pada umumnya”. Berdasarkan survey Randstad Workmonitor 2022, 41 persen pekerja Gen Z lebih memilih jadi pengangguran ketimbang merasa tidak bahagia di tempat kerja. Bagi Agung, menganggur bukan sebuah pilihan. Ada anak isterinya yang bergantung padanya, yang hidupnya harus diperjuangkan.

Tak Bisa Kuliah, Menggantung Cita-Cita
Sinta Nugraha tersenyum lebar, memamerkan behel yang memagari giginya. Rambut panjangnya dicat sewarna rambut jagung. Penampilannya modern ala muda-mudi Gen Z.
Kami bertemu di kawasan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat di penghujung April 2022. Dibonceng Sinta dengan sepeda motornya, saya dibawa ke tempat tinggal gadis belia itu. Setelah melalui sebuah gang kecil sepanjang 100 meter dari jalan lingkungan, kami tiba di sebuah rumah dengan sejumlah kamar kos, tempat di mana Sinta tinggal sebulan terakhir ini dan terpisah puluhan kilometer dari rumah orang tuanya.
Kamar kos Sinta berada di lantai dua. Ukuran kamarnya cukup luas dan juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai: dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan ruangan untuk menerima tamu, seperti saya. Di ruangan itu, ada satu unit televisi datar berukuran 19 inch.
“Itu saya beli dari gaji saya, termasuk motor, dan bayar kos ini,” tutur Sinta sambil tersenyum.
Usia Sinta masih terbilang muda, 21 tahun. Di usia tersebut, idealnya Sinta sedang giat kuliah meraih gelar sarjana. Namun alasan “tidak ada biaya” membuat Sinta mengubur cita-citanya menjadi dokter. Biaya masuk universitas terlalu mahal bagi anak dari seorang buruh. Sinta lantas menggantung cita-citanya, lalu banting setir menjadi buruh pabrik.
Begitu lulus SMA, hal pertama yang terpikir Sinta adalah mencari kerja, bukan memilih kampus. Kemiskinan mendorong gadis yang waktu itu belum genap berusia 18 tahun mencari jalan menghidupi dirinya, juga ayah dan ibunya. Ayahnya seorang buruh serabutan yang sudah memasuki usia lansia, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga berusia setengah abad lebih. Sinta merasa sudah waktunya ia membantu meringankan beban orang tuanya.
“Maaf bapak gak bisa ngebiayain sekolah lagi, gak bisa kayak orang tua lain yang bisa nguliahin anak sampai sarjana,” ujar Sinta menirukan perkataan bapaknya saat dia minta izin bekerja.
Sinta anak bungsu dari lima bersaudara. Keempat kakaknya sudah lebih dulu bekerja di pabrik. Sinta pun mengikuti jejak kakak-kakaknya bekerja di pabrik. Pekerjaan pertamanya adalah buruh di sebuah pabrik roti. Sinta ditempatkan di bagian pengemasan. Sayangnya, ia hanya dipekerjakan sebagai tenaga kontrak dengan upah kecil dan tanpa libur kerja yang jelas. Bertahan hampir satu tahun, Sinta lalu mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain.
Beberapa kali melamar kerja, Sinta akhirnya diterima di PT Chuan Cheng Hat (CCH) Indonesia, sebuah pabrik garmen spesialis topi yang berbasis di Taiwan. Di pabrik itu, usia Sinta paling muda. Rata-rata teman kerjanya berusia di atas 25 tahun.
Kondisi kerja di pabrik CCH bisa dibilang lebih baik bagi Sinta. Dia langsung diangkat sebagai pegawai tetap setelah tiga bulan masa percobaan dan menerima gaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan pemerintah. Hak buruh lainnya, seperti BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja juga dipenuhi. Sinta pun bebas menjadi anggota serikat pekerja.
“Saya beberapa kali ikut demo buruh. Waktu demo Omnibus Law, saya ikut. Terakhir, demo penetapan UMK (upah minimum kabupaten/kota), saya juga ikut,” sebut Sinta.
Sinta konvoi mengendarai sepeda motor bersama ratusan buruh lainnya menuju Gedung Sate, saat aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Oktober 2020 silam. Di Gedung Sate, para buruh bergabung dengan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi serupa. Sinta dan mahasiswa berada dalam rentang usia yang sama. Bedanya, Sinta mengenakan kemeja putih biru bertuliskan Serikat Pekerja Nasional (SPN), sementara mahasiswa mengenakan jas almamater dengan logo masing-masing kampusnya.

“Aku ikut demo. Aku harus tahu memperjuangkan hak buruh itu kayak gimana. Jadi aku tertarik untuk ikut memperjuangkan nasib buruh. Aku kayak ngelakuin ini buat semua buruh. Orang tua juga tahu (aku ikut demo). (Mereka) cuma bilang hati-hati,” imbuh Sinta dengan nada bangga.
Aktivitas Sinta ini berbeda dengan sebagian Gen Z dan Milenial pekerja kerah putih di ibu kota, yang justru cenderung apatis terhadap aksi demonstrasi, enggan berserikat, bahkan sebagian menolak disebut sebagai buruh. Alih-alih memiliki kesadaran sebagai pekerja, beberapa justru mengolok-olok para buruh pabrik yang demonstrasi dengan mengendarai sepeda motor yang bagus namun menuntut upah naik. Mereka adalah buruh Gen Z dan Milenial idaman korporasi yang tak banyak protes, enggan demo dan berserikat, meski kerja lembur tanpa bayaran.
Sebagai buruh pabrik, keseharian Sinta dihabiskan untuk bekerja, dari Senin sampai Jumat, selama 8 jam setiap harinya. Sinta bisa saja memanfaatkan hari liburnya untuk nongkrong bersama teman-teman sebaya di kafe, ngobrol berbagai topik sambil mereguk kopi bermerek, layaknya pergaulan Gen Z seperti label yang direkatkan pada generasinya. Tapi itu tidak ia lakukan dengan banyak pertimbangan, terutama soal keuangan.
Nongkrong, ngafe, atau jalan-jalan di mal, menurut Sinta, adalah aktivitas yang menghabiskan waktu dan uang. Bagaimanapun, Sinta masih berjuang membiayai hidup dan membantu orang tua.
Dari penghasilannya setiap bulan, ia menyisihkan sebagian untuk ditabung sedikit demi sedikit dengan harapan cukup membiayai kuliahnya kelak. Sinta tak tahu kapan biaya itu bisa terkumpul. Kendati demikian, asa itu masih ia genggam. Cita-cita menjadi dokter masih digantung, bukan dikuburnya. Apalagi, keinginan kuliah terasa semakin kuat, jika bertemu teman yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
“Ada merasa kayak sedih, aku gak bisa kuliah. Pernah juga menyesali hidup kok gak kayak yang lain bisa kuliah. Tapi gak apa-apa karena keadaan juga, gak bisa maksain. Gak apa-apa kerja dulu. Semoga nanti, kalau ada rezeki, pakai uang sendiri bisa kuliah. Keinginan kuliah sebenarnya besar. Insya Allah masih ada harapan,” tutur Sinta.
Seperti kebanyakan orang, Sinta memiliki akun media sosial (medsos), seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram. Akan tetapi, Sinta bukan pengguna aktif. Ia jarang mengunggah status atau foto. Satu-satunya alasan membuat akun medsos ialah mencari informasi lowongan kerja. Pekerjaannya di pabrik roti, dia dapatkan dari informasi yang beredar di grup Info Loker.
Lantaran kurang aktif di medsos atau dunia maya, Sinta tak terpapar demam K-pop. Sinta lebih menyukai lagu-lagu Judika, Rossa, dan D’ Paspor, sebuah band indie asal Karawang yang muncul pada 2008. Tontonannya bukan drama korea atau serial di Netflix, tapi sinetron Ikatan Cinta di televisi.
Kehidupan Sinta memang berbeda dengan gambaran Gen Z yang digembar-gemborkan. Walaupun, di era serba digital ini, Sinta sering juga berbelanja di toko online, tapi dengan alasan lebih murah, bukan karena konsumtif.
Bila Gen Z sering traveling dengan alasan healing, Sinta sama sekali tidak pernah memikirkannya atau paling tidak mengesampingkan keinginan itu. Dia masih harus bekerja keras sebagai buruh pabrik demi bertahan hidup, membantu orang tua, dan menyelamatkan cita-citanya.

Problematika yang diwariskan
Kisah Sinta, Agung, dan Siti potret realitas yang masih jadi momok bagi Gen Z: putus sekolah, eksploitasi pekerja anak, dan perkawinan anak. Tiga isu yang sebetulnya telah terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Namun yang bikin miris, masalah itu masih saja terjadi di era Gen Z, generasi yang diklaim memiliki akses pendidikan yang lebih lapang, kesempatan bekerja yang lebih beragam, dan aturan yang melarang perkawinan anak dengan terbitnya Undang-undang Perkawinan yang telah direvisi.
Lantas, mengapa ketiga problem sosial yang telah terjadi sejak Gen Baby Boomers itu terus diwariskan hingga Gen Z?
Kehidupan Sinta, mungkin saja lebih baik dari Agung dan Siti. Namun, ketiganya memiliki isu yang sama, yakni kesulitan mengakses pendidikan akibat kemiskinan.
Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa saja membebaskan biaya sekolah. Namun, ada faktor lain yang nampaknya luput dari perhatian pemerintah. Dari cerita Sinta, Agung, dan Siti, bukan biaya sekolah yang menjadi kendala utama, tapi jeratan kemiskinan yang menjauhkan mereka dan bangku sekolah. Bagaimana ketiga Gen Z itu bisa tenang belajar di sekolah atau perguruan tinggi, bila setiap hari menyaksikan orang tua mereka berjibaku mencari nafkah?
Merujuk data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terdapat 6.030 pelajar sekolah dasar baik negeri dan swasta yang putus sekolah di tahun ajaran 2019/2020 dan 190 pelajar di tahun ajaran 2020/2021. Di jenjang SMP, sebanyak 3.684 pelajar putus sekolah di tahun ajaran 2019/2020 dan 111 pelajar di tahun ajaran 2020/2021. Sementara di jenjang SMA, ada 1.581 pelajar putus sekolah di tahun ajaran 2019/2020 dan 25 pelajar di tahun ajaran 2020/2021.
Di lingkup nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan, dari dasar hingga menengah atas, pada 2021.
Eksploitasi Pekerja Anak
Sebanyak 3,8 juta Gen Z di Indonesia adalah pengangguran, sebuah fakta yang memprihatinkan, tapi ironisnya, di sisi lain, angka pekerja anak yang masuk kategori Gen Z juga tinggi.
Usia Agung dan Siti tidak lagi tergolong anak-anak, tapi mereka sempat menjadi pekerja anak, enam tahun lalu. Mereka menjadi bukti dari terjadinya praktik-praktik eksploitasi anak yang telah berlangsung bertahun-tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 mengungkapkan, jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5–17 tahun jumlahnya mencapai 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak–anak yang bekerja. Dari total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk–bentuk pekerjaan terburuk.
“Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif,” mengutip Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada 2020 atau selang 11 tahun kemudian, jumlah pekerja anak masih saja tinggi. Mengacu pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2020, ditemukan 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun atau 3,36 juta anak yang bekerja. Anak yang bekerja berarti, anak yang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu pendek, tidak mengganggu waktu sekolah, dan tanpa unsur eksploitasi. Sementara itu, dari 3,36 juta anak yang bekerja, sebanyak 1,17 juta merupakan pekerja anak. Pekerja anak merupakan anak yang bekerja secara intens sehingga dapat mengganggu serta membahayakan kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembangnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, pertengahan tahun lalu sempat mengatakan, angka pekerja anak di Indonesia semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan terutama setelah datangnya pandemi Covid-19. Situasi tersebut dapat terbaca dari data Sakernas 2020 dan 2019, yang menunjukkan peningkatan persentase pekerja anak di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Peningkatan pekerja anak terjadi pada kelompok umur Gen Z, yakni 10-12 tahun dan 13-14 tahun.
Ancaman Perkawinan Anak
Perkawinan anak atau perkawinan yang terjadi di bawah usia 19 tahun menjadi potret suram Gen Z. Lagi-lagi, Agung dan Siti jadi contoh nyata dari maraknya perkawinan anak pada generasi tersebut.
Siti mengungkapkan, tidak hanya dia yang menikah di usia yang terbilang anak-anak. Teman-teman sekolahnya banyak yang menikah di usia 15 hingga 17 tahun.
Dengan terbitnya, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah mengalami perubahan. Di UU No. 1 tahun 1974, batas usia yang diperbolehkan menikah, perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Di undang-undang perkawinan yang baru, batas usia menjadi 19 tahun, baik perempuan maupun laki-laki.
“Jika ada yang menikah di bawah usia 19 tahun, termasuk kategori anak yang berumur di bawah 18 tahun, itu harus ada dispensasi dari pengadilan tinggi agama,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, saat dihubungi melalui sambungan telepon, akhir April 2022 lalu.
Dari jumlah dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan agama itulah, DP3AKB Jawa Barat bisa mengetahui jumlah perkawinan anak yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Di 2020, jumlah perkawinan anak tercatat sebanyak 9.821 orang dan 6.794 orang di 2021. Kemudian, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun di Jawa Barat pada 2019 mencapai 12,3 persen di atas rata-rata nasional yaitu 10,82 persen. Pada 2020 jumlahnya menurun menjadi 11,96 persen.
Dari 26 kabupaten kota di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya mencatat kasus perkawinan anak tertinggi di 2021, yakni sebanyak 910 orang. Sementara, Kabupaten Bandung Barat, di mana Siti tinggal, mencatat angka 249 perkawinan anak. Angka yang cukup menguatkan omongan Siti.
Masih tingginya angka perkawinan anak di wilayah Jawa Barat menjadi perhatian DP3AKB Jabar. Kepala dinas yang biasa disapa Kim tersebut menyatakan, terdapat sejumlah faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak. Salah satunya, kesulitan ekonomi.
“Anak-anak ini seolah menjadi beban orang tua ketika ada yang melamar ataupun merasa sudah cocok dan lebih mapan, sudahlah nikahkan anaknya untuk mengurangi beban orangtua,” ujar Kim.
Penyebab lain, minimnya pengetahuan orang tua dan anak tentang kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan apabila seseorang menikah di usia dini. Dampaknya bisa dari sisi emosional dan kesehatan reproduksi.
“Jadi alat reproduksinya belum siap dan matang. Ini akan berdampak negatif bagi si perempuannya. Misalkan, nanti akan berisiko pendarahan pada saat melahirkan, kemudian kanker servik, dan juga akan berpotensi melahirkan anak stunting, kurang gizi, sehingga ke depan ini berpengaruh kepada kualitas dari generasi penerus kita,” papar Kim.
Kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang masih melekat di masyarakat menjadi penyebab berikutnya. Kepercayaan “lebih baik dinikahkan daripada berbuat zina” dan anggapan “anak perempuan yang tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tidak laku dan menjadi perawan tua” masih diyakini banyak orang.
Gen Z yang dikatakan sebagai generasi tech savvy, ternyata menurut Kim, turut mendorong tinggi angka perkawinan anak. Kemajuan teknologi informasi ini bagaikan pisau bermata dua. Dampak positifnya, wawasan pengetahuan menjadi lebih luas, berbagai peluang pekerjaan ataupun pendidikan lebih terbuka, dan juga mendukung kreativitas. Namun, dampak negatifnya juga tak kalah banyak. Khusus yang berdampak pada perkawinan anak, kata Kim, munculnya influencer atau selebgram yang secara tidak langsung mempromosikan perkawinan dini. Di samping, kemudahan mengakses konten pornografi dan pornoaksi yang memicu married by accident, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan akibat kehamilan di luar nikah.
“Adanya film-film dan influencer yang menikah muda yang disiarkan di media sosial begitu kelihatannya sangat sempurna, sangat happy, yang hanya menampilkan bagian yang manis-manisnya dari sebuah pernikahan, tanpa melihat persoalan tanggung jawab, toleransi dan lain-lainnya, itu juga menjadi satu pendorong bagi remaja-remaja tertarik menikah muda,” pungkas Kim.
Perjalanan hidup Sinta, Agung, dan Siti terbingkai menjadi sehelai potret suram Gen Z. Realitas itu seakan mengkonter klaim sejumlah pihak yang menggambarkan manisnya kehidupan Gen Z. Tidak dipungkiri memang, ada perwakilan Gen Z yang memiliki privilese kehidupan yang nyaman, mudah, dan legit. Namun kondisi itu tidak lantas mengaburkan kenyataan getir yang justru dialami oleh sebagian besar Gen Z.
Laporan ini adalah bagian dari serial reportase #UnderprivilegedGenZ. Serial ini didukung oleh Kawan M.