Tulisan ini mengandung kata-kata eksplisit yang kami pertahankan demi menghargai proses batin narasumber. Artikel ini kami kecualikan dari lisensi Creative Commons (tidak bisa direpublikasi) atas permintaan narasumber.
Masih jelas dalam ingatan Rafa, saat-saat ia selalu bergegas melipat mukena tiap kali ia menuntaskan tahiyat akhir saat salat. Ia tak nyaman berlama-lama mengenakan mukena. Pikirnya, ia tak mau berdoa sebagai orang lain. Maka, sebelum memanjatkan doa, tiap usai salat jamaah, Rafa melepas atribut tersebut.
Meski begitu, kepalanya masih saja bergemuruh, dipenuhi pertanyaan yang jawabannya baru ia sadari akhir-akhir ini. “Ya Tuhan, aku salat di saf yang salah, apakah aku diterima?”
Jelang remaja, Rafa mulai memberanikan diri untuk beribadah sebagai diri sendiri, tanpa mukena. Namun bukan kedamaian seperti yang ia bayangkan akan ia rasakan. Sebaliknya, ia justru makin cemas, sebab takut bila ibadah yang ia lakukan diketahui oleh keluarganya.
“Salatnya ngebut, kayak lagi maling. Karena takut ketahuan, takut dimarahin, takut dipukul. Sudah nggak pakai mukena, salatnya buru-buru, jadi tambah nggak ngerti lagi deh diterima apa nggak,” kata Rafa, lalu kami tergelak bebarengan membayangkan kelakuan Rafa.
Tanpa sekat Rafa menceritakan sepenggal memorinya kala masih berstatus pelajar, 11 tahun lalu. Sebelum kembali melanjutkan cerita, Rafa pamit sesaat ke meja belakang bar. Ada dua pembeli yang mesti ia layani terlebih dahulu.
Ini pertemuan kesekian saya dengan Rafa. Saya lebih dulu mengenal sosoknya sebagai Koordinator Umum Women’s March Yogyakarta pada 2020 lalu. Kini ia tengah aktif bersama komunitas yang ia inisiasi, Transmen Talk Indonesia. Meski telah beberapa kali bertukar kisah, ini adalah kali pertama saya mewawancarainya. Tak berselang lama, pukul 15.00 WIB Rafa menghampiri saya. Rupanya jadwal kerja hari ini telah tuntas ia lakoni.
“Hari ini kebagian 2 shift, sudah masuk dari jam 7 pagi tadi,” terang Rafa.
Rafa mengaku beruntung bisa mendapatkan pekerjaan di coworking space. Karena kebanyakan temannya sesama transpria justru mengalami diskriminasi sistematis untuk memperoleh pekerjaan. Ia sudah setahun bekerja di sana sebagai barista. Kartu kependudukan yang memuat identitas lahirnya, juga hanya diketahui oleh tim manajemen perusahaan. Gelar sarjana yang Rafa peroleh seusai kuliah kedokteran gigi di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, tak bisa ia manfaatkan. Sebab serupa dokumen kenegaraan Rafa yang lain, ijazahnya belum mencantumkan nama yang ia hayati sendiri. Rafa merasa nama di ijazah itu bukan dirinya.

“Yah meskipun bukan pekerjaan formal yang kantoran, atau yang sesuai dengan bidang keahliannya aku, aku tetap merasa punya privilese lebih. Karena nggak semua teman-temanku (yang transpria) punya koneksi dan kesempatan yang setara untuk bisa dapet lapangan pekerjaan tanpa didiskriminasi latar identitas gendernya,” jelas Rafa.
Kerap kali, coworking space tempatnya bekerja juga menjadi ruang aman bagi Rafa ketika ia membutuhkan tempat untuk berkegiatan secara daring. Pertimbangan tempat merupakan salah satu faktor yang Rafa utamakan, sebab pembahasan yang kerap ia bicarakan adalah seputar SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics) dan queer.

“Tiap ada kesempatan untuk jadi narasumber dan berbicara soal, entah transpria, laki-laki menstruasi, atau SOGIESC secara keseluruhan, biasanya aku juga di sini. Karena ada ruang privat yang bisa aku pakai, suasananya aman, dan aksesnya lebih mudah karena aku karyawan di sini,” terang Rafa.
Namun kesempatan memiliki pekerjaan, tak lantas membuat Rafa memiliki tiket terusan untuk terhindar dari kekerasan. Sebagai seorang barista, ia justru memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi untuk di-misgender, atau praktik memanggil sapaan yang tidak sesuai dengan identitas gender orang tersebut.
“Customer terbiasa justifikasi hanya dari penampilan luar. Itu pun berdasar asumsi dan standar normatif mereka saja. Ekspresi mana yang menurut mereka adalah ekspresi gender perempuan, maka mereka akan memanggil orang tersebut dengan sebutan ‘mbak’, dan begitu sebaliknya,” jelas Rafa.
Sudah tak terhitung berapa kali ia mengalami misgendering di tempat kerja. Rasanya sangat menyakitkan karena itu berarti ia tidak diakui, dirinya tak penuh sebagai seorang laki-laki. Bayang-bayang memori traumatik leluasa hadir tiap kali pembeli di hadapannya menyebutnya dengan sapaan yang merujuk pada gender yang tak pernah ia hayati seumur hidupnya.
“Ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena lagi kerja. Tapi kalau pun lagi luang, aku lebih sering diam. Karena butuh energi yang besar ‘sekadar’ buat menegur atau menjelaskan. Dan seringnya aku sudah lebih dulu kehabisan tenaga,” ungkap Rafa.
Rafa sempat berinisiatif untuk menyematkan semacam “kartu identitas” yang ia buat sendiri dengan tulisan “Mas Rafa” terukir di atasnya. “Karena sudah capek banget. Jadi biar mereka bisa baca namaku, dan tahu cara menyapaku, yaitu dengan sebutan “Mas” dan bukan sebutan lain yang asosiasinya ke gender yang bukan genderku,” tutur Rafa.
Perkara sapaan barangkali menjadi sesuatu yang sangat sepele bagi kelompok cisgender. Tentu saja hal tersebut karena mereka, termasuk saya, dilingkupi hak istimewa hidup dalam tataran normativitas biner gender.
Namun sesuatu yang sederhana tersebut tak dapat Rafa dan kawan-kawan transgender rasakan. Sebagai seorang transpria, Rafa dihadapkan untuk harus selalu tawar menawar dengan keadaan. Visibilitas dan representasi yang minim, membuat ruang-ruang inklusif semakin sukar diperoleh. Transpria atau transgender pria merupakan salah satu dari ragam identitas gender yang mengalami peliyanan di Indonesia. Pada latar perjalanannya, identitas ini memiliki padanan dengan trans maskulin, trans laki-laki, atau trans man. Tak ada sebutan yang paling benar, sebab yang paling berhak dan valid dalam menyematkan label-label tersebut adalah individu itu sendiri, seseorang yang menghayati langsung identitas gender tersebut.
Bertahan Hidup Sebagai Transpria
Hari makin sore. Gugusan awan yang sedari tadi menebal, perlahan jatuh ke tanah. Pertengahan Juni kali ini, agaknya langit justru riuh-riuhnya memanen rintik. Sebelum kembali asyik pada perbincangan kami, saya menyeruput cafe mocha yang Rafa buat. Di tengah segala situasi yang tambah tak pasti, saya beruntung memperoleh kesempatan mendengar kisah-kisah ini.
Rafa melanjutkan cerita mengenai pengalaman-pengalaman traumatiknya, yang bagi banyak orang kejadian ini dianggap remeh dan bahkan tak disadari. Selain misgendering, transpria juga langganan mengalami kekerasan outing dan deadnaming.
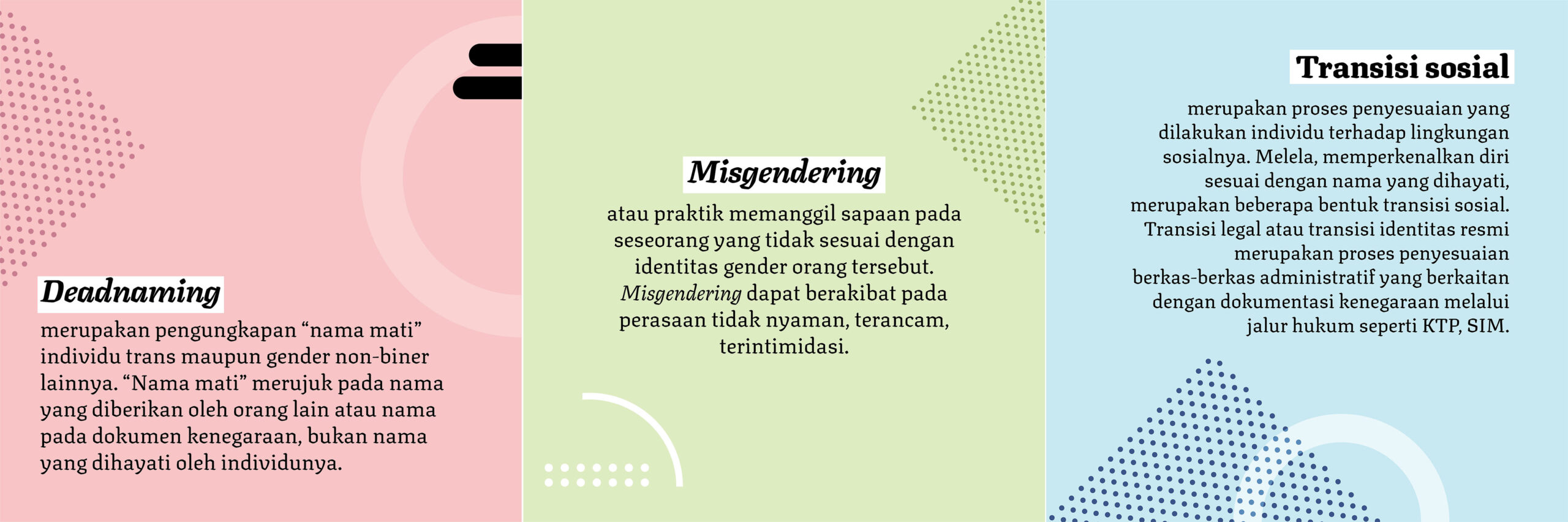
Pada saya, Rafa menuturkan bahwa pelaku outing dan deadnaming sering didominasi oleh orang-orang terdekat, seperti kawan dan kerabat. “Mereka terbiasa memanggil dan mengetahui nama mati seorang transgender, karena mereka keluarga biologisnya. Meski sudah diberi tahu, mereka menolak memanggil dengan nama yang kami rasa lebih nyaman, serta memilih untuk menyakiti dan menjadi tuhan-tuhan kecil bagi keluarganya sendiri.”
Trans Journalists Association menyatakan bahwa deadnaming merupakan kejahatan yang tidak manusiawi. Praktik tersebut berbahaya karena merusak otonomi dan melemahkan identitas gender seseorang. Salah satu momen paling menguras energi bagi Rafa adalah ketika ia harus mengalami deadnaming selama seharian penuh, yakni ketika hari besar keagamaan tiba.
Kekalahan Saban Lebaran
Pada tiap perayaan Idul Fitri, Rafa tak pernah benar-benar merasakan kemenangan. Bahkan sebulan sejak awal Ramadan tiba, kepalanya justru dipenuhi pikiran tentang bagaimana ia mesti berhadapan dengan keluarga besarnya ketika Lebaran. Hijabnya kok nggak dipakai? Kenapa pakai baju koko? Padahal cantik kalau pakai rok lho, mbak! Suara-suara represif tersebut terus bergema dan menganak pinak. Sering kali lontaran-lontaran itu dibarengi dengan memanggil nama mati, dengan pronomina yang salah, ataupun dibubuhi dengan kata-kata sifat yang lekat diasosiasikan dengan gender perempuan. Maka dari itulah, sulit bagi Rafa untuk utuh mengilhami momen Lebaran, sebab tak pernah ia miliki kesempatan menjadi diri sendiri di hari yang katanya suci.
Tak ada yang memilih terlahir sebagai minoritas yang melulu distigma sebagai biang bencana atau petanda kiamat, begitu pula Rafa. Baginya apa yang ia hayati datangnya dari hati. Salah bila ada yang menuding dirinya bagian dari queer karena pilihan, terlebih gaya hidup. Tidak ada kata “berubah”, tidak ada kata “menjadi”. Sejauh yang Rafa bisa ingat, ia adalah seorang laki-laki, sejak pertama kali.
Rafa sama sekali tak menaruh perhatian ketika teman-teman sebayanya antusias dengan miniset motif princess yang akhirnya bisa mereka pakai. Rafa santai saja sebab pikirnya, dadanya tak akan membesar. Patokannya adalah om dan pakdenya yang biasa bertelanjang dada ketika di rumah. Namun berbulan-bulan setelahnya, Rafa merasa tubuhnya mengkhianatinya.
“Masa pubertas mulai datang, dan badanku tidak bisa menjadi badan yang aku inginkan. Kenapa kok kalian (payudara) tumbuh. Kalian nggak seharusnya berada di sini. Apa yang salah. Kemana penisku?” berulang kali Rafa remaja mempertanyakan itu semua. Perkembangan tubuh yang terjadi selama transisi dari masa kanak membuat perasaan tak nyaman terus menerus menderanya. Tiga tahun ke belakang, baru ia tahu bahwa ketaknyamanan yang selama ini ia rasakan merupakan disforia gender.
Siksaan Ruang Ganti Baju
Rafa muak tiap ada yang seenak jidat melontarkan lelucon seksis bahwa selama ini dirinya “menang banyak” karena memiliki banyak teman perempuan dan sering melakukan kegiatan bersama, termasuk ketika berganti pakaian.
“Bagaimana bisa? Aku justru tersiksa. Rasanya pusing.”
Rafa menuturkan bahwa tiap pelajaran olahraga dan teman-teman perempuannya berganti pakaian di kelas, Rafa memilih hengkang. “Aku pasti keluar, entah ke kamar mandi atau main ke mana. Karena aku merasa aku laki-laki. Aku nggak boleh melihat mereka, aurat.”
Terkadang bila harus berganti pakaian di tempat yang sama, Rafa memilih berganti di ruangan paling sudut dan menghadap dinding. “Satu, karena aku nggak mau melihat mereka ganti baju. Dua, karena aku juga nggak mau mereka melihat tubuhku.”

Sangkaan berbau seksis dan diskriminatif kerap ditujukan kepada Rafa. Padahal ia tak pernah sekali pun merasakan sesuatu seperti yang dituduhkan tersebut. Tumbuh sebagai seorang anak yang dikonstruksikan “berbeda”, membuat Rafa tak memiliki banyak kawan. Kawan-kawan perempuan menjauhinya sebab ia “dianggap cowok”, namun ia juga tak bisa berbaur dengan sesama kawan laki-laki sebab “dianggap kurang cowok”. Pada dua kelompok tersebut, label aneh, tomboy, dan lesbian erat disematkan pada diri Rafa.
“Aku sempat percaya bahwa apa yang kualami ini adalah hukuman dari Tuhan.”
Setiap kali Rafa mendapat perlakuan body shaming atau mendengar komentar-komentar atas tubuh yang menaunginya, nyeri seketika menyeruak di barisan pertama. Ujaran seperti “montok”, “besar”, dan “seksi” tak hanya membuatnya merasa malu, melainkan juga pening di kepala. Sebab Rafa sadar bahwa kata-kata tersebut asosiasinya mengarah pada sosok perempuan, sementara dirinya sama sekali tak pernah menghayati gender tersebut.
Perasaan sakit yang berulang, tanpa ia belum tahu apa yang terjadi, membuat Rafa giat merutuki diri sendiri. Keyakinannya sebagai laki-laki, ia amini sebagai dosa besar. Begitulah hukuman Tuhan yang harus ia pikul sepanjang hayat. Menyalahkan diri menjadi pembenaran yang paling masuk akal bagi Rafa, setidaknya sampai 2018, tahun ke-25 ia hidup sebagai orang lain.
Menyiasati Aturan Ibadah
Hidup sebagai seorang transpria, membuat Rafa juga harus bernegosiasi dengan aturan peribadatan yang ia jalani. Ketika ia telah memiliki kesempatan untuk menjadi diri sendiri saat melakukan salat, pelbagai perasaan dilema tetap tak henti menghantui.
“Kali pertama aku salat sebagai Rafa, aku pikir akan ada kedamaian yang aku rasakan, seperti wah this is the first time! Tapi ternyata enggak. Kepala justru berisik dengan pertanyaan nanti kalau aku salat, terus sentuhan sama bapak-bapak di sebelah, batal nggak ya?”
Rafa menuturkan kekhawatiran yang menerus ia rasakan ketika memutuskan salat sebagai laki-laki di ruang publik. Rafa tak peduli bila wudunya “dihitung” batal, namun bila orang lain “dihitung” batal juga, Rafa merasa sangat berdosa karena membuat orang tersebut tak diterima salatnya. “Kalau dia batal tapi nggak tahu, kan kasihan. Mungkin di salat hari ini ada doa-doa dan pengharapan lebih, tapi wudunya jadi batal waktu sentuhan sama aku ketika salat,” cemas Rafa.
Inisiasi yang kemudian bisa Rafa lakukan ketika salat jamaah adalah memilih saf di bagian paling ujung, serta tidak berada tepat di belakang imam. Upaya ini Rafa lakukan agar ketika tiba-tiba imam berhalangan di tengah salat, ia tidak harus maju dan menggantikan imam. Namun kekhawatiran itu tetap saja bersemayam. Rafa tak pernah tahu apakah jamaah di sebelah kanan dan kirinya adalah pengikut mazhab, yang menganjurkan jari kelingking kaki saling bersentuhan sebagai syarat rapatnya saf.
“Kalau ada jarak meski sedikit, nanti dimasukin setan, begitu kata orang-orang. Tapi aku mikir, Allah apa sekaku itu sih? Dengan segala cerita kebaikan yang Dia punya, apakah iya Allah se-sensitif itu? Atau sebenarnya, aturan manusianya aja yang kaku?”
Ungkapan retoris Rafa membuat saya bertanya-tanya, apakah dengan konsep yang sama, ketakutan atas “sentuhan dan batal” juga bisa diredam. “Belum. Nggak bisa, sampai hari ini. Bahkan dengan konsep ketuhanan yang aku punya, selalu masih ada pertentangan.”
Rafa menjelaskan bahwa konsep kelingking yang harus bersentuhan ketika salat dapat ia patahkan, sebab ia jarang mendengar doktrin tersebut. Rafa hanya sering mendengar ayo safnya dirapatkan, tanpa dibubuhi anjuran-anjuran lain yang lebih detail. Namun hal tersebut tak berlaku tentang aturan bahwa jamaah dengan jenis kelamin yang berbeda akan batal wudunya ketika bersentuhan. Rafa teringat bahwa sejak kecil ketika salat jamaah, selalu ada candaan ketika anak laki-laki menggoda anak perempuan yang sudah wudu dengan menyentuhnya. Alhasil, anak perempuan tersebut harus kembali ke kamar mandi dan mengulang wudu.
‘Takut Dipukulin’
Konsep lain yang menimbulkan dilema yang serupa adalah ketika Rafa masih berada dalam rakaat salat, dan tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya. Konsep tersebut berarti orang tersebut meminta Rafa menjadi imam dan mengajaknya berjamaah.
“Konsep itu juga belum kelar di aku. Aku nggak masalah jadi imam. Tapi selalu ada bising suara yang berkata apakah aku boleh jadi imam? Salat mereka yang aku imami akan sah nggak ya?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kian menguat tiap Rafa pergi salat di ruang publik bersama sang ibu. Ibunya “membolehkan” ia untuk salat di saf laki-laki, namun selalu dengan catatan: harus berada di ujung saf, karena bila di tengah ada kemungkinan untuk diajak menjadi imam.
“Ya cukup sakit sih sebenarnya.”
Sikap sang ibu secara tidak langsung menyangkal gender yang Rafa hayati. Sebab konsep yang berlaku menganjurkan bahwa imam salat adalah laki-laki.
Pernah sekali waktu, dalam suatu perjalanan mereka berhenti untuk salat di musala SPBU. Namun sang ibu tak memintanya untuk menjadi imam. “Ibu nggak mau aku imamin. Aku tahu, karena ibu tipikal orang yang kalau ada cis-male salat di depan beliau, beliau pasti langsung bilang mas, ikut ya. Tapi hal itu nggak ia lakukan sama anak laki-lakinya sendiri.”
Kenyataan menyakitkan tersebut hanya bisa Rafa pendam. Meski tampak sederhana, sejatinya tersusun kompleksitas perasaan yang mesti Rafa lalui ketika ia hendak beribadah. Proses intimasinya terhadap Tuhan, mau tak mau tetap menimbulkan pertentangan di dalam batinnya. Begitu pula dengan penerimaan diri maupun keluarga atas identitas gender serta karakteristik biologis yang masih terkait dengan aturan-aturan peribadatan.
Kebimbangan senada Rafa alami pula pada anjuran salat jamaah yang lain seperti salat Jumat. Bagi umat muslim laki-laki, hukum dari salat Jumat ialah fardhu ain atau wajib. Namun Rafa tak pernah mengerjakannya, meski kini ia telah lebih leluasa salat sebagai diri sendiri. Saya tak memahami keputusannya. Saya pikir Rafa kini punya otonomi lebih dibanding ketika ia di dalam kloset atau belum melela (coming out). Namun saya keliru.
“Kenapa aku nggak pernah salat Jumat? Karena takut bikin salat orang lain batal. Karena takut ‘ketahuan’ bukan cowok (cisgender laki-laki). Karena takut ketahuan LGBT. Karena takut dipukulin.Click To TweetSontak saya tertampar. Bahkan untuk bisa berdialog dengan Tuhannya sendiri, individu transpria dihadapkan dengan sekian perjuangan. Ketimpangan nyata terasa, setidaknya bagi saya, seorang cisgender perempuan yang memiliki privilese untuk beribadah tanpa rasa was-was. Namun tidak halnya dengan Rafa. Kekhawatirannya bertambah karena ia tahu bahwa tubuh yang menaunginya bukanlah gambaran ideal yang dikonstruksikan oleh maskulinitas hegemonik.
“Badanku dari belakang mungkin terlihat kecil. Pinggang, pinggul, juga pantatku kelihatan besar nggak ya kalau dari belakang? Ketika ngantre wudu dan rame, mas-mas atau bapak-bapak di sana akan ngomentari aku nggak ya?” pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik Rafa.
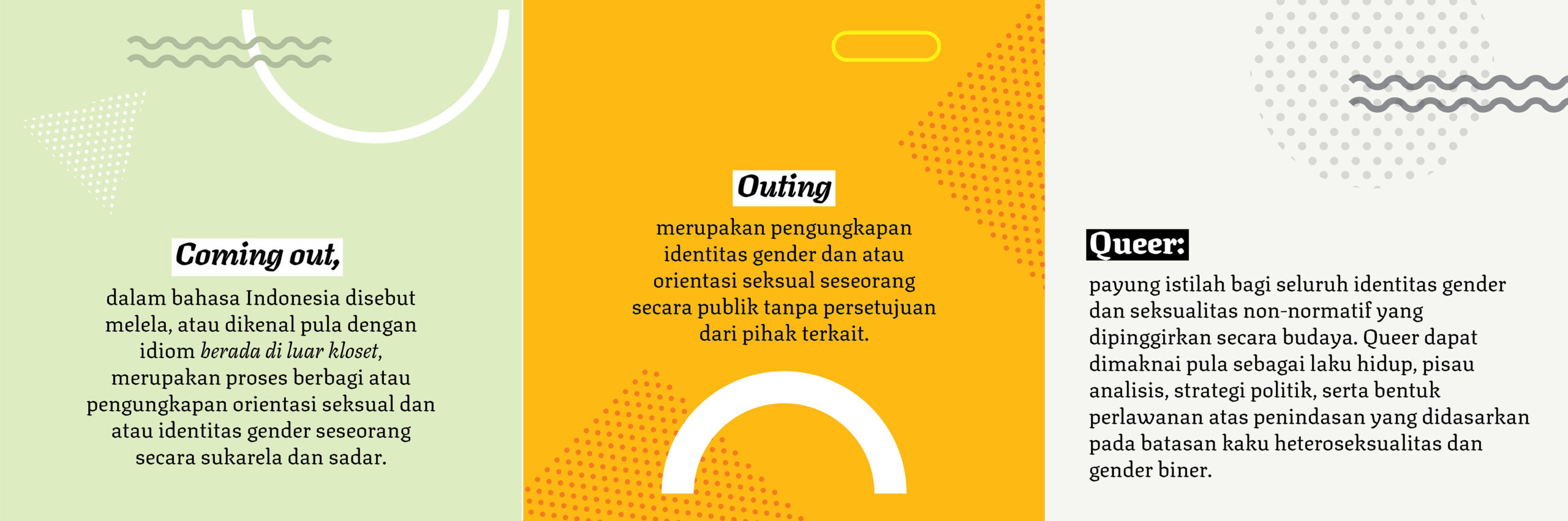
Rafa menjelaskan bahwa tak masalah bila komentar tersebut tak terlontar. Namun ia tak bisa mengantisipasi bila ada yang tiba-tiba melakukan konfrontasi. “Kalau dari mereka ada yang berasumsi bahwa aku perempuan, apakah mereka bakal melakukan tindakan lebih?” dengan detail Rafa menjelaskan pada saya tentang ketakutannya. Terlebih bila ia memilih salat Jumat di salah satu masjid besar di dekat rumahnya.
“Kalau masjidnya besar, saf perempuan itu kan adanya di lantai atas, sementara di bawah diisi oleh cisgender laki-laki semua. Dan ada banyak blind spot di masjid. Pahit-pahitnya kalau ada yang curiga aku siapa, aku bisa ditarik ke sana. Aku diapa-apain nggak ada yang tahu.”
Transpria dan Pengalaman Menstruasi
Kelangkaan ruang aman bagi transpria untuk menjalankan ibadah, berimplikasi pada pengalaman disforia gender yang mesti dilalui. Bagi para transpria yang belum atau memilih tidak menjalani transisi fisik, yang berupa transisi medis, misalnya HRT (Hormone Replacement Therapy), maka peristiwa biologis seperti menstruasi tetap akan mereka alami saban bulannya. Kondisi ini memunculkan pertentangan batin, bahwa penghayatan diri mereka sebagai laki-laki terbentur dengan aturan yang mengharuskan mereka yang sedang menstruasi, untuk tidak diperkenankan menjalankan ibadah, seperti salat, puasa, serta menginjak rumah peribadatan.
“It’s hard actually. Rasanya sangat menyakitkan, apalagi konstruksi yang terus berulang adalah menstruasi milik perempuan,” kata.
Rafa menuturkan bahwa ada dua hal yang banyak tidak diketahui orang tentang siklus alami tersebut, yakni tidak semua perempuan mengalami menstruasi, serta tidak semua yang mengalami menstruasi adalah perempuan.
Rafa menyusun definisi yang lebih inklusif tentang menstruasi. Baginya menstruasi merupakan peristiwa biologis yang terjadi atau dialami oleh individu yang terlahir dengan rahim, sementara tidak semua yang terlahir dengan rahim adalah perempuan. Rafa menjelaskan bahwa menstruasi bukan milik satu gender saja, sebab jelas ada laki-laki yang pengalaman hidupnya mencatat bahwa ia pernah, sedang atau masih menstruasi. Siklus bulanan ini juga tak jadi penentu identitas gender seseorang. Celakanya, konstruksi normatif masih terus menggemakan peristiwa ini sebagai “kodrat” yang dialami oleh perempuan.
Kontradiksi antara konstruksi normatif dan pengalaman valid yang dialami Rafa sebagai transpria, membuat dirinya mengalami perselisihan hebat. Hingga kini Rafa masih meyakini bahwa ia juga tak boleh menyentuh Al-Qur’an ketika siklus bulanan tersebut menghampiri.
“Dulu aku pengikut mazhab yang melarang mereka yang sedang menstruasi untuk menyentuh Al-Qur’an. Tapi keyakinanku pun mengalami perubahan, dari mulai boleh menyentuh tapi harus dilapisi alas, sampai boleh menyentuh tapi Al-Qur’an yang ada terjemahannya dalam bahasa selain Arab.”
Berulang kali Rafa meredefinisi keyakinannya sendiri mengenai konsep tersebut. Sempat Rafa berpikir apakah benar sehina dan sekotor itu orang yang sedang menstruasi sampai bila kitab suci dipegang oleh mereka, maka nilai sucinya akan berkurang. Doktrin-doktrin tersebut secara tak langsung mempengaruhi pola pikir Rafa dalam melakukan proses penerimaan diri (coming in).
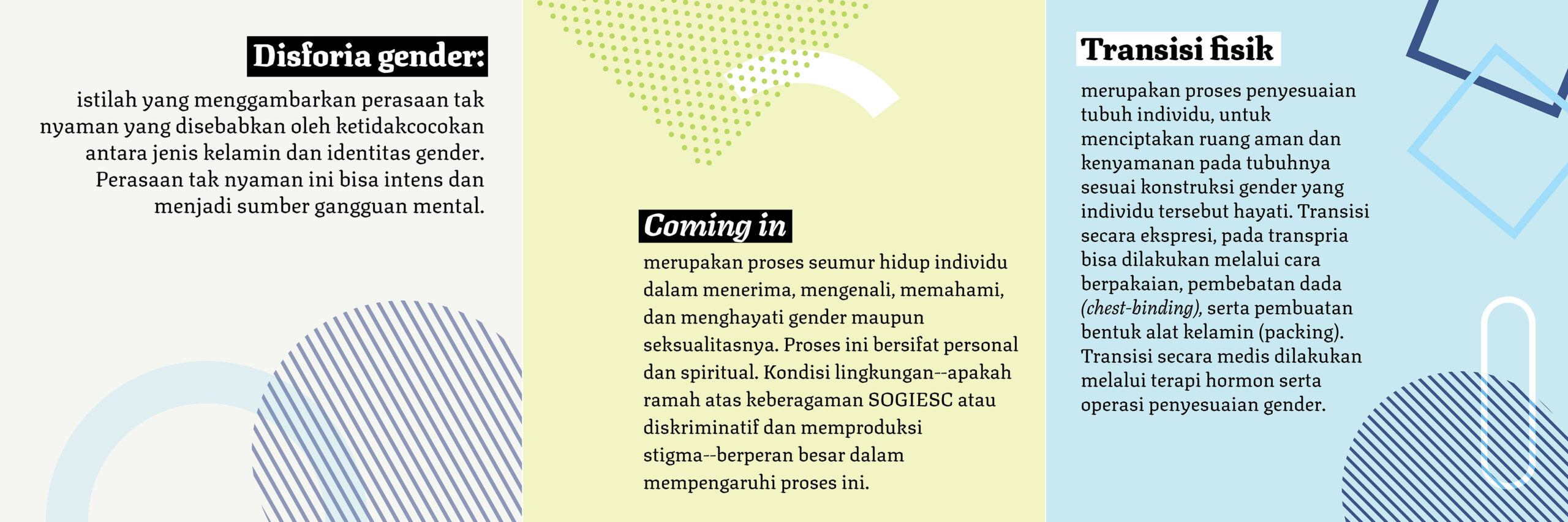
“We never ask to bleed. They give us a body that naturally bleeds. We cannot control anything.”
Sering Rafa bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan ketika segala aturan peribadatan mengenai menstruasi kerap kali berbenturan dengan identitas gender yang ia hayati serta kondisi karakteristik seks yang ia miliki. Namun jawaban tak kunjung ia temui.
Pernah pada masa awal setelah Rafa melela kepada ibunya, ia mengalami kebimbangan. “Ketika aku sudah bisa keluar rumah tanpa pakai jilbab, aku merasa ada keharusan untuk salat bareng ibu tiap kali waktu salat tiba.” Suara-suara di kepala Rafa menerkam dengan berujar ibunya pakai jilbab dan anaknya laki-laki, tapi kok nggak salat? Padahal ketika itu dirinya sedang mengalami menstruasi.
Rafa tak bisa lepas dari ajaran bahwa orang yang sedang menstruasi tidak diperkenankan salat. Namun ketika berada di ruang publik, disforia gender yang ia rasakan bertubi menghampiri. Orang-orang akan melihatku sebagai siapa, adalah yang berputar di pikiran Rafa kala itu.
“Kalau aku dikira bukan orang Islam malah nggak apa-apa, oh mungkin anaknya beda agama sama ibunya, aku berharap orang-orang berpikir begitu. Tapi yang sering muncul adalah pikiran apakah aku akan disangka perempuan? Apalagi ketika rambutku gondrong, penampilanku masih akan dikaitkan dengan ekspresi gender perempuan. Suara-suara itu makin kenceng, aku akan dilihat sebagai laki-laki yang beragama beda atau perempuan yang lagi menstruasi ya?”
Rafa mengingat pengalamannya ketika menstruasi pada hari raya. Pergolakan batin Rafa rasakan sebab ia tak bisa melaksanakan salat Id. Pada satu sisi, Rafa senang karena dirinya tak harus merayakan Idul Fitri dengan mukena, namun ia tetap tak bisa berada di saf laki-laki untuk beribadah. Rafa tetap harus memakai jilbab dan busana muslimah, serta duduk di saf perempuan.
“Kalau aku flashback sekarang, aku pikir jatuhnya kerasa lebih sakit. Karena ketika aku ikut salat, pandanganku ke bawah, ke sajadah. Fokusku satu ke sana, meskipun kepalaku berisik kanan-kiriku kok pakai mukena semua, ya? Kapan aku bisa merayakan hari raya dengan baju koko, peci dan kanan-kiriku laki-laki juga. Tapi ketika aku menstruasi dan “dipaksa” duduk, maka sakitku nggak hanya di kepala. Sebab aku bisa melihat saf laki-laki di depan sana. Fokusku berjalan ke sana, membayangkan dengan lebih jelas aku ada di antara mereka, dan yang pasti aku tidak akan duduk. Kepalaku sibuk berkata harusnya aku ada di sana.”
Pernah pada satu masa ketika Rafa remaja, ia menangis selesai menunaikan salat Id. Rafa mengidentifikasi bahwa kesakitan yang ia rasakan bukan ketika ibadah salat, melainkan ketika selesai, dan ia masih bisa berjabat tangan dengan ibu, saudari, dan tantenya.
“Kok aku masih bisa salim ya sama ibu, harusnya kan nggak sebelahan salimnya. Harusnya salimnya nanti kalau salat Id nya sudah selesai, terus aku jalan ke saf belakang, jemput ibu, baru aku salim. Tapi ini enggak, aku masih bisa salim di sebelah ibu langsung selesai salat, dan bisa nangis bareng di satu saf yang sama.”
Ibadah yang Melelahkan
Sejak memperoleh kesempatan umrah tahun 2010 dan haji pada 2014, Rafa merasakan puncak pergolakan antara penghayatannya terhadap identitas diri dan keimanannya pada ritus-ritus keagamaan.
Rafa kelas 2 SMA kala ia menunaikan ibadah umrah. Perasaan bahagia tentu singgah sebab pikir Rafa, kapan lagi ia “diizinkan” berkunjung ke rumah Allah. Namun Rafa muram ketika harus mencetak paspor untuk pertama kalinya, karena ia dipaksa untuk mengenakan jilbab. Selama di sana, Rafa menerus menenangkan diri bahwa yang sedang pergi umrah adalah dirinya sendiri, meski dengan “bungkus” yang berbeda.
“Aku berusaha menjadi Rafa, diriku sendiri, meskipun casingnya adalah orang lain. Walau aku memakai baju yang tertutup semua dari atas sampai bawah, aku memakai sarung tangan, jilbab, kaus kaki. Tapi aku membayangkan diriku mengenakan kain ihram yang nggak berjahit.”Click To TweetPerasaan berkecamuk muncul ketika Rafa melihat bahwa saf salat di sana lebih cair. Jumlah jamaah yang sangat banyak membuat saf susah untuk diatur sehingga tidak ada garis batas yang kaku antara saf khusus laki-laki dan perempuan. Namun keadaan tersebut tetap tak berhasil membuat perasaannya membaik.
“Karena aku tahu apa yang sedang aku pakai, dan aku nggak bisa mengenakan pakaian yang ingin aku kenakan di tanah suci sana.”
Rafa kemudian mengisahkan perjuangannya menjalani rangkaian ritual dalam rukun umrah dan haji. Konflik batin Rafa rasakan, sebab terdapat pula beberapa tata cara peribadatan yang dibedakan antara gender perempuan dan laki-laki.
“Aku sebisanya berusaha, curi-curi gitu, melakukan ibadah dengan tata cara laki-laki, meski kadang dimarahin ibu hihi…”
Rafa menuturkan bahwa ketika rukun sai, jamaah laki-laki dianjurkan lari-lari kecil di Bathnul Wadi, sementara perempuan biasanya hanya dianjurkan jalan biasa. Selepas tawaf dan sai, para jamaah kemudian melakukan tahallul sebagai penutup rangkaian ibadah. Tahallul dilakukan dengan mencukur, setidaknya tiga helai rambut, sebagai pertanda bahwa manusia dituntut “mencukur” kesalahan masa lalunya serta memulai kehidupan baru dengan lebih baik.
Meski semata simbol, namun implikasi dari kegiatan tersebut kerap menegaskan garis batas yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Ritual mencukur rambut di Masjidil Haram tak bisa dengan leluasa Rafa terapkan, sebab rombongan jamaah yang bersama Rafa tidak melihat ia sebagai laki-laki.
“Aku merasa ibadah umrah dan hajiku tidak lengkap. Selain karena aku nggak bisa pakai ihram tanpa jahitan, nggak bisa bersentuhan dengan bapak-bapak karena harus terus menjaga wudu, aku juga nggak bisa bercukur gundul seperti mereka. Jadi kebanyakan bapak-bapak yang satu rombongan denganku, selesai tahallul langsung digundul. Aku merasa mestinya rambutku juga dicukur begitu, tapi tidak. Dan aku merasa ibadahku sangat kurang saat itu.”

Meski bermacam kesusahan menerpa, hal tersebut tak mengurangi harapan yang tekun ia langitkan di sana. Berbekal keyakinan bahwa segala doa akan makbul di tanah suci, Rafa kian rajin berdialog dengan Tuhan. Ajaran-ajaran yang menyebutkan bahwa doa yang diawali dengan shalawat di tiap sujud selama tiga kali akan didengar, Rafa praktikkan sungguh-sungguh. Ada satu rangkaian doa yang menerus Rafa ulang sepanjang perjalanan ibadahnya di Makkah.
Rafa tiba-tiba mengambil jeda. Saya terdiam dan memusatkan perhatian penuh kepadanya. Sembari menepuk pelan pundak Rafa, saya berkata bahwa tak apa rehat sejenak. Tak apa pula bila tak sanggup melanjutkan atau menceritakan keseluruhan kisah.
“Aku bahkan minta sampai spesifik…”
Ucapannya bergetar. Selama beberapa waktu Rafa tak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia teringat atas segala perasaan-perasaan yang memenuhinya kala itu. Meski hampir satu dekade sudah, namun luapan memori yang menghampiri, memunculkan kembali luka-luka yang belum kering benar.
“Aku bahkan dikasih keluarbiasaan sama Tuhan bahwa aku bisa mencium Hajar Aswad,” berangsur mereda, Rafa kembali membagikan kisahnya. Sebuah batu yang terletak di sudut tenggara Kakbah tersebut, diyakini oleh banyak orang memiliki keistimewaan. Maka merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang jamaah ketika ia berhasil memegang dan mencium batu Hajar Aswad.
Rafa menambahkan bahwa keistimewaan tersebut kian terasa sebab untuk menjangkau Hajar Aswad, ia harus melewati pusaran jamaah yang tak terhingga.
“Khusus arus yang menuju Hajar Aswad itu lapisan manusianya ramai banget, sementara di sisi yang lain lebih tipis. Dan untuk sampai ke sana, kami (Rafa dan ibunda Rafa) harus “melawan” banyak cisgender laki-laki, yang badannya itu jauh lebih besar dibanding kami.”
Rafa meyakini kisah-kisah yang mengatakan bahwa doa akan terkabul ketika dengan tulus diucapkan di hadapan batu suci tersebut. Harapan besar benar sungguh Rafa langitkan, ketika ia dapat menyentuh Hajar Aswad.
“Aku bahkan sampai pada titik di mana aku bisa mencium itu. Aku nangis… Aku taruh doanya di situ…”
Sebelum menyebutkan permohonan paling dalam dan paling personal yang pernah ia punyai, Rafa menghela napas panjang.
“Ya Allah, tolong ubah aku menjadi laki-laki muslim yang baik dan taat kepada-Mu. Ya Allah, tolong ubah payudaraku menjadi payudara laki-laki, tolong ubah kelaminku menjadi kelamin laki-laki, tolong ubah badanku menjadi badan laki-laki. Jadikan aku seorang laki-laki yang tidak lupa sama Engkau.”
Begitulah doa yang menerus Rafa rapal, pada tiap-tiap kesempatan di mana dongeng tentang keistimewaan suatu tempat tergelar.
“Aku ingat aku juga mengulang doa itu selama sujudku di rumah Tuhan yang utama itu. Terutama di makam Nabi. Katanya, di sana juga salah satu tempat yang mujarab. Doa-doa akan terkabul bila diucapkan di sana.”
Pergolakan kian terasa ketika hari-hari selepas haji, beranjak pergi. Rafa teringat rangkaian harapan yang ia langitkan, keimanan penuh yang ia pasrahkan, dan kekecewaan mendalam yang ia peroleh setelahnya.
“Aku tunggu bertahun-tahun kok enggak ada. Padahal aku sudah berdoa di tempat yang katanya orang-orang itu paling precious, but I don’t have any clue. They didn’t give me anything, in exact order. Apakah aku memang sedosa itu?”
Rafa kemudian mulai menggugat dongeng-dongeng yang sebelumnya penuh ia percayai. Ia juga mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan, juga kehadiran dirinya sendiri.
“Aku mulai menjauh dari agama, karena aku kecewa sama Tuhan,” Rafa menuturkan bahwa ia mulai lelah. Ritual-ritual yang ia jalankan, doktrin dan dongeng yang ia yakini selama ini, dirasa tak berpihak kepadanya. Kesulitan, penghakiman, dan kepedihan justru makin Rafa peroleh ketika telah dengan tekun ia tunaikan segala ritual itu.
Namun gugatan yang Rafa layangkan tak lain paling keras ia tujukan pada dirinya sendiri. Terlebih selepas ia melela kepada sang ibu pada 2016, tahun di mana gelombang kebencian dan persekusi terhadap komunitas queer kian masif terjadi.
Dua tahun selepas haji tapi tak Rafa rasakan perubahan apapun. Pikirannya kian bising mengamini tiap stigma yang ditujukan kepada transgender. Rafa merasa bahwa doanya tak dikabulkan, bahkan ketika ia sudah berdoa di tanah suci, karena dirinya memang menyalahi “kodrat”, karena dirinya adalah dosa. Internalisasi kebencian turut terbangun pada diri individu minoritas. Struktur sosial yang masih berkiblat pada normativitas gender biner, yakni cisgender laki-laki (cis-male) dan cisgender perempuan (cis-female), berperan besar dalam self-blaming tersebut.
“Ketika 2016 makin kencang narasi yang bilang transgender nggak boleh ibadah, perempuan yang menyerupai laki-laki salatnya nggak sah. Invalidasi dari masyarakat itu bikin aku makin berpikir, terus buat apalagi ngelakuin ritual agama, ngapain gue nyembah Elu lagi, gitu.”
Pertanyaan demi pertanyaan bertarung dalam diri Rafa tanpa pernah ada jawaban Keyakinan atas identitasnya selalu berbanding terbalik terhadap keyakinannya terhadap agama. Dua tahun tanpa kejelasan, Rafa kemudian mengamini bahwa identitasnya ialah pangkal dosa. Sebab tak ia temu jawaban, “perempuan dan laki-laki dalam kitab suci, standarnya yang bagaimana? Tuhan yang Mahakuasa itu, melihat aku sebagai apa?”
Penerimaan Diri, Proses Tanpa Henti
Saya mengikuti Rafa ke rumah. Ia tinggal berdua bersama ibunya di Yogyakarta. Rafa lanjut bercerita bahwa titik balik ia rasakan ketika mengenal figur publik yang merupakan seorang transpria muslim. Setelah segala kekecewaan mengendap, secara perlahan Rafa mulai meredefinisi konsep ketuhanan yang ia yakini. Pertemuannya bersama kawan yang memiliki kesamaan identitas dalam hal gender dan keimanan, membuat Rafa merasa tak sendiri dan berangsur bisa mengesahkan diri.
“Wah, berarti boleh kan ini? Nggak dosa, kan? Ibadahku diterima, kan?” Rafa mulai mengurai satu per satu kegelisahan yang dahulu kerap ia rasakan ketika beribadah. Rafa juga mulai membebaskan emosi perih atas kebencian-kebencian yang mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan transgender adalah sia belaka.
Lambat laun Rafa bernegosiasi dengan aturan dan tafsir-tafsir peribadatan yang kerap meliyankan transpria. “Aku percaya bahwa Tuhan seluarbiasa itu kuasa-Nya, dan Dia pasti punya kelonggaran-kelonggaran yang tak terhingga. Mungkin manusianya yang belum belajar. Mungkin kitanya yang belum tahu atau belum ketemu caranya. Mungkin akunya yang belum punya ilmu yang lebih progresif dan inklusif.”
Rafa senang bahwa tafsir progresif tentang keberagaman gender dan seksualitas manusia mulai diwacanakan. Namun penerimaan antara penghayatan atas diri dan penghayatan kepada Tuhan, memanglah proses belajar tanpa henti. “Aku akan memiliki penguatan ketika ada yang bilang bahwa transgender tidak dosa, aku bukanlah sebuah ujian atau cobaan. Sayangnya, selama ini hampir nggak ada anjuran atau aturan ibadah yang mention transpria secara langsung.”
Meski pertentangan antara identitas gender dan anjuran peribadatan menerus ada dalam diri Rafa, namun agensi-agensi sederhana menuntun ia pada penerimaan diri yang luar biasa. “Aku nggak bisa melawan apapun yang terjadi di dalam badanku. Sekarang yang kuyakini adalah Tuhan memberi aku tubuh ini, dan ya, Dia pasti memberi juga keringan-keringanan yang aku nggak tahu.”
Satu momentum hingga Rafa kini memiliki keselarasan yang lebih utuh antara identitas gender dan konsep ketuhanannya, adalah ketika kali pertama Rafa mengenal terminologi transman atau transpria. Rafa membaca satu artikel pada sebuah laman yang menyajikan cerita-cerita tentang coming out. Artikel yang berisi pengalaman dari seorang transpria itulah yang kemudian membuat Rafa terhenyak. Ia merasa tak sendiri, identitasnya memanglah eksis, dirinya bukanlah mitos dan stigma belaka. Untuk kali pertama Rafa merasa bahwa segala kebingungan dan kesakitannya selama ini divalidasi dan memiliki nama, yakni transpria.

Rafa mengatakan bahwa setelah ia tahu siapa dirinya, ia tak berhenti menangis dan tertidur. Kemudian sesuatu terjadi dalam mimpinya.
“Aku mimpi aku tidur, tapi bangun-bangun aku punya penis!.. I feel that! I touch my dick… It felt so real. So real… Kerasa nyata banget. Aku bisa pegang itu pakai tanganku sendiri. Penis yang pengen banget aku punya…”
Rafa menghentikan ceritanya. Ia menangis.
Saya terdiam. Bulir air mata saya tak kuasa turut mengalir. Yang ada di pikiran saya adalah betapa hebat perjuangan Rafa selama ini, dan betapa luar biasanya ia mau membagi kisah-kisah terdalamnya kepada saya, kepada kita.
Rafa masih sesenggukan ketika ia kembali melanjutkan kisahnya.
“Aku nggak percaya, aku terus ke kamar mandi, aku buka celanaku. Tapi penisnya hilang… penisku hilang, Himas… Aku ngeliat penisnya pelan pelan hilang… aku nangis di kamar mandi. Terus habis itu aku bangun, aku bangun dalam keadaan nangis, di atas tempat tidur yang sama. Sakit… sakit tapi seneng…,” Rafa menangis seraya tertawa. Dengan masih terbata-bata, ia menuturkan arti mimpi itu baginya.
“Meskipun sebentar, meskipun cuma di mimpi, aku ngerasa doaku dikabulin… Nggak hanya penisku yang tumbuh, tapi payudaraku juga nggak ada… payudaraku datar… Makanya aku ngerasa doaku dikabulin, meski sebentar.”
Mimpi yang Rafa alami kemudian menjadi pijakan baginya untuk meyakini bahwa dirinya sepenuhnya utuh. “Aku merasa bahwa itu cara Tuhan ngasih tahu ke aku, kalau this is my way, aku nggak aneh, aku memang dilahirin Tuhan dengan jalan cerita yang seperti ini.”
Menerima Diri, Menantang Cisheteronormativitas
Keinginan Rafa dalam memenuhi pelbagai macam atribut yang sistemik dikonstruksikan sebagai milik laki-laki, adalah valid. Rejim cis-heteronormativitas membuat masyarakat melulu mengamini bahwa identitas gender laki-laki tak terpisahkan dengan sifat dan ekspresi maskulin yang menyertai. Keberanian, kekuatan, superioritas hingga karakteristik seks seperti organ penis, kromosom XY, hormon testosteron mutlak menjadi definisi dari laki-laki “sejati”. Norma tersebut terus-menerus diulang hingga diyakini menjadi seolah kebenaran yang alami nan kodrati.
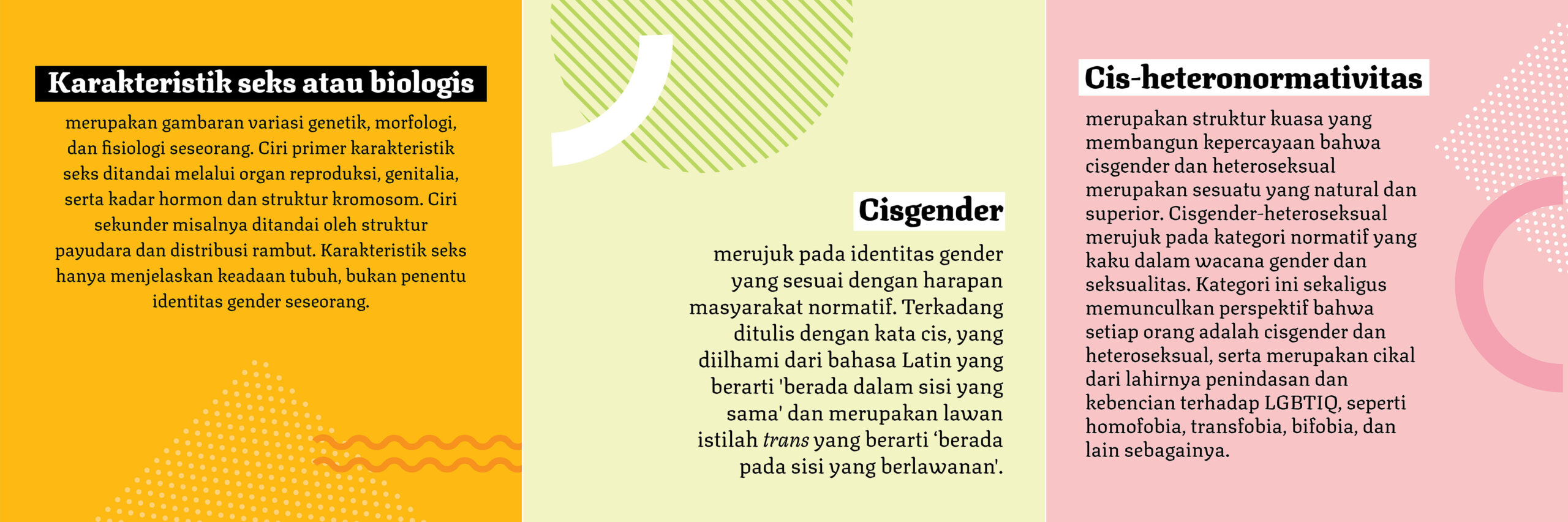
“Dulu aku pikir, tubuh laki-laki muslim adalah tubuh laki-laki cisgender. Yang berpenis, yang nggak punya payudara besar, yang berjambang, berkumis, suaranya berat. Dulu saat berdoa, kiblatku adalah tubuh cis-male.”
Rafa merefleksikan dirinya bahwa dahulu ia benar-benar kecewa terhadap Tuhan. Diskriminasi yang bertubi Rafa alami, dirasa tak menjawab segala ibadah yang tekun ia tunaikan.
“Saking kejamnya stereotip dan pembungkaman yang ada, sampai se-khusyuk, se-serius, sekaligus se-desperate itu doaku, haha. Saking pengennya “jadi” laki-laki yang diterima masyarakat normatif. Biar nggak dibully dan direpresi terus-terusan,” terang Rafa sambil tertawa, ia mengenang doa terdalamnya yang terus dilantunkan sepanjang ibadahnya di tanah suci.
Namun kini, Rafa mulai mengenal Tuhan dari sudut pandang yang lain. Bukan melalui dongeng atau doktrin semata, melainkan melalui dirinya sendiri. Lusinan pertanyaan yang memutari kepala Rafa sejak dini, satu per satu mulai memanen jawaban.
“Tuhan sudah menjawab doaku dengan membuatku menjadi pribadi yang lebih berani speak up tentang ketubuhan dan gender. Aku membawa pola pikir baru bahwa tubuh ini adalah tubuh laki-laki yang memiliki keragaman SOGIESC yang melekat di dirinya.”
Rafa mengatakan bahwa penerimaan diri tak lantas artinya tak melakukan transisi fisik. Proses coming in seorang transgender dan gender non-biner lainnya tetap valid, dengan atau tanpa tindakan transisi sekalipun, baik transisi sosial, fisik, maupun legal. Rafa juga menuturkan bahwa keinginan suntik HRT serta operasi rekonstruksi dada dan kelamin masih ada. Ihwal tersebut merupakan upaya yang ia lakukan untuk mengakomodasi kenyamanan diri. Namun ada sederetan pertimbangan yang harus Rafa prioritaskan, baik dari segi ruang aman, kesehatan fisik, mental serta finansial.
“Harapan untuk bisa hormonal dan operasi itu selalu ada, tapi sedikit banyak aku sudah nggak menganggap aku dosa, kutukan, atau hukuman. Sebab aku sudah paham dan yakin bahwa tubuh yang membersamaiku adalah tubuh laki-laki dengan keberagamannya. Dadaku adalah dada laki-laki, kelaminku adalah kelamin laki-laki.”
Berdasar pada pemahamannya yang tumbuh serta kecintaan dirinya yang kian utuh, Rafa menyadari bahwa Tuhan mendengarnya. “They answered my prayer by helping me become stronger, louder, and wiser than before. Doaku terkabul. Doaku makbul. Dalam bentuk yang beyond my imagination.”
Perjalanan Keimanan: Pulang Menemukan Diri dan Tuhan
Pasca 2018, Rafa merasakan perubahan besar ketika ia memutuskan hidup sebagai Rafa secara publik. Transisi sosial yang ia alami tentu tak berjalan mulus, bahkan terjal jalan justru lebih liku menghadang. Namun ketika Rafa mencoba memeluk identitasnya sendiri, maka ketika itu pula ia merasakan Tuhan hadir memenuhinya. Hadir begitu dekat pada tiap jenis keberagaman yang ia temui.
“Ketika sudah lebih berani untuk merangkul siapa aku, dan ketika semesta memintaku untuk lebih belajar banyak tentang kehidupan, aku merasa Tuhan lebih dekat. Aku merasakan bahwa hidup nggak cuma tentang agama dan ajarannya, tapi juga tentang manusia.”
Rafa menuturkan bahwa aktivisme yang ia lakukan menuntunnya pada perjumpaan dengan kawan-kawan dari latar gender dan seksualitasnya yang beragam. Tak hanya manusia, melainkan juga seisi makhluk semesta yang memiliki beragam karakter, jenis dan spesies. Rafa mengungkapkan bahwa kuasa Tuhan semegah itu hingga bisa menciptakan miliaran atau bahkan tak terhingga karakteristik hewan, tumbuhan, galaksi, dan lain sebagainya.
“Masa iya kuasa Tuhan dikerdilkan dengan menganggap bahwa Dia cuma menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan.”
Rafa kemudian mencontohkan bahwa seorang manusia memiliki miliaran sel dalam tubuhnya, ada bermacam lapisan spektrum yang mengaliri tubuh manusia. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, Rafa mengatakan bahkan dimungkinkan ilmuwan-ilmuwan tidak tahu label untuk satu atau dua hewan yang mereka pikir baru ditemukan.
“Mungkin mereka belum nemu sama sekali nama hewannya ini apa, tapi sebenarnya hewannya sudah hidup dari lama, kitanya saja yang belum ketemu sama mereka, ilmuwannya saja yang belum meneliti, belum tahu, makanya dikira nggak ada. Tapi ketika sudah diketahui, diteliti, diberi nama, jadi tahu mau manggilnya apa. Tapi sebelum nemu namanya apa, bukan berarti hewan tersebut nggak ada, kan.”
Analogi yang sama berlaku pada ragam gender dan seksualitas yang dimiliki manusia. Visibilitas dan informasi yang terbatas mengenai identitas transpria, tak lantas menihilkan bahwa transpria itu tidak ada.
“Aku menemukan Tuhan lewat keragaman manusia, tumbuhan, hewan, dan banyak hal lainnya di Bumi. Karena aku menemukan Tuhan di banyak tempat, maka aku percaya, kuasa Tuhan tidak akan bisa disekat-sekat.”
Serupa penghayatannya dalam mendobrak binerisme gender, begitulah Rafa kemudian memaknai agama, aturan peribadatan dan Tuhan. “Aku percaya Tuhan itu baik. Aku nggak mau lagi terjebak pada kotak-kotak. Aku memilih untuk mengagungkan, membawa nama Tuhan dan dekat dengan-Nya dengan caraku sendiri, yang aku percayai, yang aman dan nyaman untuk aku lakukan.”
“I never ask to be born as transgender or to be confused. Because I never ask, so I believe that They have something that I don’t understand right now. Aku percaya Dia pasti punya jawaban dari kegelisahanku selama ini.”
Malam telah larut. Sebelum pamit, kembali saya berterima kasih kepada Rafa. Telah sedia membagi kisahnya, memutar kembali memori masa silam, serta berkenan traumanya diulik ulang. Kerendahan hati kembali saya dapatkan, Rafa justru kembali berterima kasih. Ia mengatakan bahwa di tengah represifnya berita yang membingkai komunitas queer, masih ada yang memiliki keberanian dan empati, menawarkan ruang bagi kelompok minoritas untuk bersuara.
Rafa teringat bahwa awal dirinya merasa tak sendiri, awal bahwa segala kegelisahannya ternyata memiliki nama, adalah melalui artikel yang ia baca. Pengalaman satu orang transpria yang dipublikasikan, barangkali bisa sangat berharga bagi individu-individu transpria yang lain. Meski sebelumnya tak kenal, namun pengalaman identitas hingga ketertindasan yang sama membentuk koneksi yang saling memvalidasi dan menguatkan.
“Siapa tahu di luar sana, ada juga saudara-saudara (transpria)ku yang membaca ini. Begitulah proses berbagi. Ada luka dan trauma yang dijinakkan, agar ada pelajaran yang bisa dibagikan, setidaknya buat aku pribadi.”
Penulis merupakan satu dari tujuh penerima fellowship menulis tema kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dipilih dari 75 peserta kelas menulis yang diadakan oleh Yayasan Pantau pada April-Agustus 2021. Laporan ini adalah bagian dari serial #HakMinoritas.










