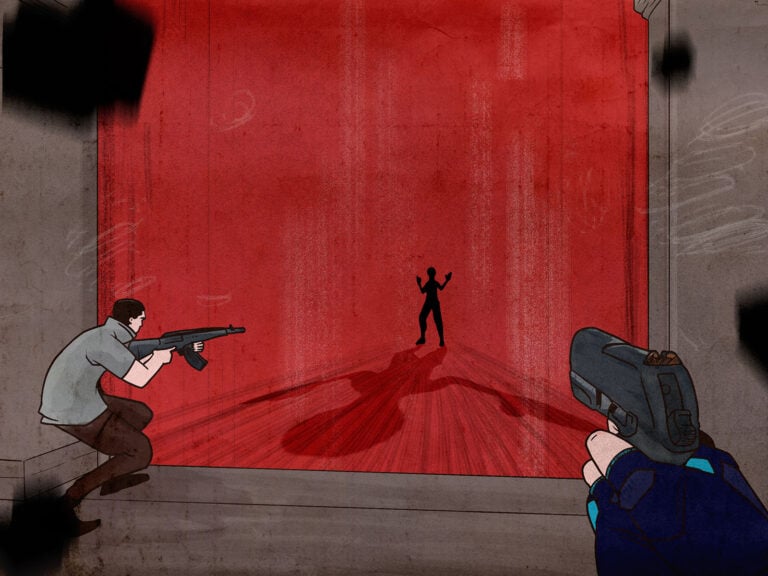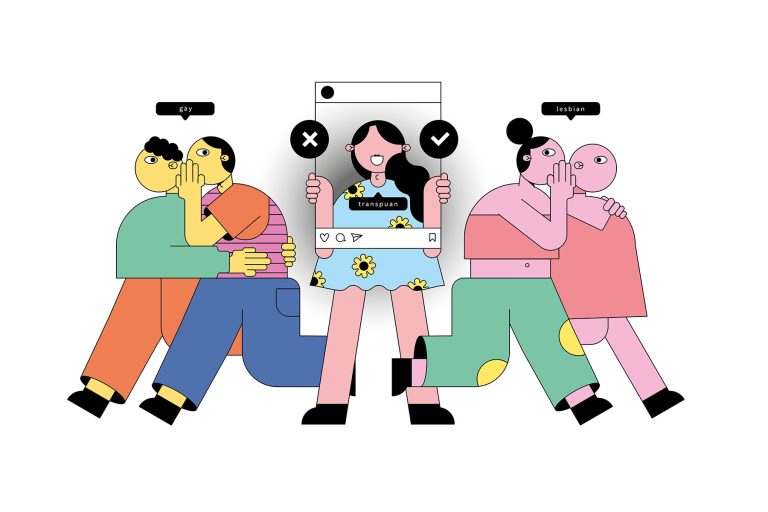Ruangan sunyi. Bunga (she/they) mengabarkan kawannya akan terlambat hadir. Kami kemudian mematikan kamera dan audio di ruang pertemuan Zoom.
Saya menatap layar gelap, sembari merutuki diri sendiri. Lima belas menit berlalu, kawan yang dinanti hadir. Hal pertama yang saya lakukan adalah meminta kawannya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Bunga; saya menyesal tidak memahami bahasa isyarat sedikit pun.
“Nggak papa, kita sama-sama belajar,” kata Bunga sambil tersenyum di layar.
Ini pertama kali kami bertatap muka. Saya mengenal aktivis Tuli asal Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ini lewat Instagram. Di platform berbagi foto dan video tersebut, Bunga secara terbuka menyatakan dirinya sebagai biseksual dengan berbagai identitas gender yang sering berganti-ganti seiring waktu alias genderfluid.
“Aku sudah merasa bahwa aku mempunyai perasaan suka terhadap perempuan dan laki-laki, tapi dulu aku belum tahu itu namanya apa,” kata Bunga.
Pernah satu ketika Bunga mencoba menyampaikan perasaan itu ke keluarganya tapi hanya meninggalkan kebingungan-kebingungan lainnya. Sampai akhirnya ia memutuskan selama tidak ditanya, ia tidak akan membahas identitasnya meski pihak keluarga sering menanyakan kapan dirinya akan menikah. “Sekarang aku nggak berani juga untuk ngomong (tentang identitas queer). Nanti dicoret dari KK (Kartu Keluarga),” katanya, sambil tertawa.
Informasi seputar penyandang disabilitas saja belum banyak yang inklusif, apalagi ditambah difabel yang queer. Di tengah keterbatasan itu, pada September 2019, Bunga bertemu dengan komunitas Tuli dan teman Dengar yang juga biseksual. Teman Dengar adalah sebutan bagi orang non-disabilitas dan yang ditemui Bunga ketika itu kebetulan bisa berbahasa isyarat. Pertemuan itu membuka jalan baginya untuk menggali informasi, berdiskusi, hingga menumbuhkan kepercayaan diri untuk coming out (membuka orientasi diri).
Tapi, perjalanan setelah membuka diri tidak semakin mudah.
“Ada yang tanya, kok nggak pernah pacaran sama cowok, itu aku ngerasa tertekan sih. Aku terus coming out kalau aku biseksual. Malah nanya biseksual itu apa, dan dibilang harus tetap salatlah, perkuat imannya,” ungkap Bunga.
Berada di fasilitas publik adalah cobaan ganda bagi Bunga yang menghayati diri sebagai genderfluid dengan ekspresi maskulin.
“Soal toilet aja aku bingung, cowok (cisgender) atau cewek (cisgender) aku masuknya. Saat aku udah memilih masuk, banyak sekali yang ngeliatin aku. Aku nggak nyaman di situasi seperti itu. Orang-orang kok pada ngeliatin aku,” tutur Bunga.
Pekerjaan juga sulit diraih. Dua tahun sejak lulus dari sekolah menengah kejuruan pada 2017, Bunga tak kunjung mendapat panggilan kerja. Lamarannya selalu ditolak, bahkan seringnya tidak direspons sama sekali.
Di ruang publik, pelecehan seksual tak jarang dialami.
“Pengalaman aku di Jakarta, banyak sekali cowok yang catcalling aku. Aku nggak nyaman. Aku mau ngomong kasar, tapi juga nggak bisa,” ungkap Bunga yang kini berprofesi sebagai pengajar Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo).
“Aku Bisa Bangkit Lagi”
Oktober 2021, Bunga sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun.
Tekanan hidupnya memuncak. Sebagian besar persoalan datang dari kaum mayoritas yang menolak untuk belajar menerima kehadirannya, apalagi sistem yang ikut memperburuk situasi.
“Untungnya aku bisa selamat. Ada temanku yang membantuku di hotel waktu aku coba untuk bunuh diri,” kata Bunga.
Tapi dari titik itu, Bunga berhasil bangkit dan menjadikannya sebagai sebuah pencapaian, “Aku bisa beraktivitas lagi, menjadi narasumber, mengisi webinar. Aku bisa bangkit lagi, bagiku itu adalah prestasi.”
Menemukan definisi yang sesuai, maupun istilah-istilah queer dalam bahasa Indonesia masih amat sulit. Kamus Besar Bahasa Indonesia belum mengakomodasi makna kosakata queer, cisgender, apalagi genderfluid. Bisa jadi juga, kata-kata itu tak lolos verifikasi oleh kuasa penyusun kamus.
Transfer informasi yang kerap luput mempertimbangkan hak-hak minoritas ini yang membuat Bunga bersama komunitas Queer-Tuli maupun Kawan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bekerja estra. Bunga bilang, belajar bahasa isyarat adalah harus bagi orang-orang Dengar.
“Karena itu juga termasuk aksesibilitas kami,” katanya, dengan juga mengingatkan bahwa Tuli juga beragam dan tidak semuanya membutuhkan bantuan JBI. Ada yang lebih nyaman menggunakan medium tulis atau ketik.
Hal lainnya, sulit juga menemukan Kawan JBI yang paham dengan wacana queer, padahal kontribusi mereka cukup besar dalam proses inklusivitas informasi ini. “LGBTQ itu apa, cara menjelaskannya bagaimana. Nah teman Dengar yang memahami ini, itulah yang akan membantu kita untuk mengetahui konsep tersebut,” kata Bunga.
Sontak saya terdiam. Menyadari apa yang saya pahami perihal wacana queer, luput saya diskusikan dengan teman Tuli. Beruntung saya ditegur. Meski berat, saya mengakui kesalahan-kesalahan yang bahkan tak pernah terlintas di benak saya bahwa itu adalah kesalahan. Rupanya ada banyak hal mapan yang leluasa saya kukuhkan.
Percakapan dengan Bunga usai. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada Kawan JBI. Jujur, saya merasa bersalah karena menyisipkan istilah yang ‘aneh-aneh.’ Beruntung kawan JBI yang ramah queer itu, inklusif menerjemahkannya melalui Bisindo.
Ruangan kembali sunyi. Layar Zoom kini hanya menampilkan wajah saya. Sebelum mengakhiri pertemuan, saya terusik dengan tombol unmute yang berada di kiri bawah layar Zoom. Tombol yang harus terus saya nyalakan. Sungguh, betapa bersalahnya saya menjadi orang Dengar yang juga tuna isyarat.
DISABILITAS PSIKOSOSIAL
Ardhanarishvara (he/him) didiagnosis Bipolar and Borderline Personality Disorder (Bipo-BPD) atau gangguan kepribadian ambang sejak 2014. Tapi baru belakangan ini, Ardhan paham apa yang dialaminya adalah ragam disabilitas psikososial.
“Iya, disabilitas psikososial ini masih sedikit yang tahu, kebanyakan mikir disabilitas pasti ke arah fisik,” kata Ardhan.
Penampilan fisik yang tampak baik-baik saja membuat penyakitnya kerap dianggap tidak nyata. Ardhan kerap dituduh berpura-pura atau bersikap lebay manakala gejala gangguan, seperti di antaranya perubahan suasana hati, keputusan impulsif, ledakan kemarahan, dan emosi, sedang muncul.
“Padahal emang illness ini pusatnya di otak. Siapa juga kan yang mau, cuma bisa tiduran aja di kamar, ngurung diri, lemes, nggak ada energi, wah crippling banget deh,” tutur Ardhan.
Tapi Ardhan menolak klaim pihak-pihak, bahkan tenaga profesional, yang mengaitkan gangguan psikososial yang dialaminya dengan identitasnya sebagai seorang trans-maskulin non-biner dan gay. Ardhan terlahir dengan anatomi seksual yang tipikal disematkan pada perempuan. Tapi pada perjalanannya, ia lebih nyaman berekspresi maskulin, meski ia bukan transpria.
“Jangan lantas karena tahu aku Bipo-BPD (Bipolar dan Borderline Personality Disorder), dianggapnya queerness-ku itu karena mental illness-ku, karena nggak stabil identitas dirinya atau apalah. Karena psikiater dan psikologku dulu pernah menganggap aku nggak trans, cuma BPD aja, jadi labil identitas dirinya,” kata Ardhan.
Asumsi teledor dari tenaga profesional, tentu rentan berdampak buruk bagi pasien queer. Eksistensi pengalaman dalam diri seseorang, tak lantas bisa menihilkan identitas yang lain. Kesemuanya bisa berkesinambungan, namun bisa pula berjalan sendiri-sendiri dan bukan bagian dari sebab-akibat.
“Sebenarnya genderku lebih ke two souls atau two spirits, dan aku tertarik sama laki-laki saja, aku juga masih mempelajari sih, tapi so far kesimpulannya ini, hehe,” katanya.
Ardhan sehari-hari bekerja di bidang desain dan ilustrasi. Beberapa poster dan karya ilustrasinya terpajang di Instagram yang menjadi platform berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang transpria, Transmen Talk Indonesia. Ia juga terlibat aktif dalam Yayasan Bali Bersama Bisa, Yayasan Teman Baik Nusantara, serta membantu di LISA Helpline, layanan dukungan psikologi gratis dan hotline pencegahan bunuh diri.
Bersama kawannya, Ardhan juga mendirikan Pride Care Indonesia, sebuah komunitas yang mendukung transpria serta mengupayakan penggalangan dana untuk top surgery (mastectomy) dan hysterectomy maupun hal-hal yang berhubungan dengan transisi medis, serta membagikan chest binder (bebat dada) secara gratis.
Semampu yang Ardhan bisa, ia mulai menghindari orang-orang beracun yang dulu diperlakukan seolah merekalah pusat alam semesta. “Aku cuma pengen pulih, nggak kambuh-kambuh lagi, hehe,” ungkap Ardhan.
Kehadiran queer dengan pengalaman disabilitas di ruang publik menurut Ardhan masih sangat sulit ditemui. Ini menjadi wajar, sebab ada sekian pertimbangan keamanan dan kenyamanan bila seorang queer-disabel menyatakan dirinya secara out-proud-loud di Indonesia.
Ardhan terpikir untuk membuat komunitas atau sistem dukungan yang bisa menjadi ruang bagi para queer-disabel untuk berkumpul. Ketika bertemu dengan saudara-saudara yang memiliki kondisi dan penghayatan serupa, ia merasa tidak sendirian.
“Sayangnya energiku lagi low banget, kalau lagi hipomania pasti langsung aku bikin, hahaha,” ujar Ardhan.
“Muka Sudah Tumbuh Bulu, Masih Dipanggil Bu”
Bicara soal depresi, Ardhan lalu menceritakan pengalaman paling menyebalkan menjadi seorang queer sekaligus penyandang disabilitas di fasilitas kesehatan. Satu paket kekerasan, yakni misgendering dan deadnaming dari tenaga kesehatan, bisa dipastikan akan ia alami saban minggunya.
Ardhan harus rutin ke fasilitas kesehatan tiap delapan hari sekali untuk bertemu dengan psikiater. Ardhan terbelenggu dengan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang hanya membolehkan pasien kembali berobat dengan rentang waktu delapan hari dari jadwal kontrol sebelumnya.
“Aku itu harus mengambil obat bipolar seminggu sekali di Faskes II, dan tiap itulah aku dipanggil “Bu”, itu rasanya nggak enak banget, capek banget,” katanya.
Ia merasa sangat tidak nyaman dipanggil dengan sapaan yang merujuk pada gender yang tidak ia hayati. Ardhan lebih nyaman dipanggil dengan pronominal persona “Kak”, “Mas”, “Pak”, “Bang” atau kalau dalam bahasa Inggris dengan sebutan “He”, “Him”, dan “His.”
“Malunya itu lho, kaki udah buluan, muka udah tumbuh bulu, masih aja dipanggil Bu!” kesal Ardhan, merujuk pada Hormone Replacement Therapy (HRT) demi menunjang keamanan dan kenyamanannya.
Ardhan mengatakan masih banyak fasilitas kesehatan yang tidak inklusif terhadap queer. Beruntung, Ardhan kini ditangani oleh dokter dan psikiater yang lebih memahami identitasnya. “Dokterku sekarang baik banget, aku dipanggil Ardhan terus,” tuturnya.
INVALIDASI
Pengalaman traumatis dari para tenaga profesional kesehatan juga dirasakan Remi (he/it). Memiliki pengalaman disabilitas psikososial dengan jenis neurodivergen, serta menghayati diri sebagai genderqueer boy/non-biner, membuat misgendering dan invalidasi bertubi-tubi Remi hadapi.
Invalidasi, seperti yang juga dialami Ardhan, adalah situasi saat seseorang membuat penyangkalan atas perasaan orang lain.
“Aku berkali-kali pindah dokter dan tetap tidak menemukan yang ‘klop’. It’s really hard to find a doctor who will like, help you. Well I guess, kebanyakan masih tidak mengenal konsep queer,” ujar Remi.
Situasi ini membuat Remi frustasi. Ia takut. Sebab kemana lagi ia harus mencari pertolongan, bila tenaga profesional pun tak layak menjadi ruang aman.
“Aku pernah di-gaslighting sama psikolog, dia bilang kamu emang beneran transgender?, kalau kamu transboy kamu hanya boleh suka sama perempuan!”
“Bahkan seorang terapis, ketika aku cerita tentang disforia gender yang aku alami, dan aku menjelaskan betapa sakitnya itu, dia malah make it fun, bikin jokes, bilang itu gender apa? aneh banget!” Pengalaman ini sering menjadi alasan mengapa komunitas queer-disabel urung mencari pertolongan ke tenaga kesehatan profesional.
Remi mengkritik banyak dari dokter yang tak bisa melihat korelasi, bahwa kondisi mental seorang queer bisa diperparah karena keadaan lingkungan yang tidak menerima mereka. Dokter dan tenaga kesehatan ini, kemudian tidak memberi solusi, karena tidak mengerti sama sekali keadaan individu queer di Indonesia.
“Beneran deh, nggak sehat banget hidup di +62. Bikin makin hopeless. Sangat sulit, super sulit mencari bantuan atau bahkan untuk didengar suaranya. Mau datang (periksa) kemana? Nggak tahu lagi mau kemana…” ungkap Remi.
Karena di satu sisi, mereka membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk mendiagnosis apa yang terjadi. Dengan harapan, diagnosis itu menjadi penunjuk arah ketika diri kembali siap melaju, setidaknya begitulah yang Remi percayai.
Serupa penghayatannya atas gender dan seksualitas, diagnosis neurodivergen menjadi label baru yang kini juga ia hayati. Namun menyandang label di luar tataran normatif yang ableist, tidak akan pernah mudah.
“Habis didiagnosis itu rasanya kayak menemukan sesuatu. Istilah neurodivergen sangat membantu untuk mendeskripsikan rasa yang aneh ini. Ini sulit dideskripsikan, dan ketika menemukan label itu, waw! there is literally me! Diagnosis ini membantuku, tapi juga bikin aku terpukul, dan it’s not going to be the same, ever,” terang Remi.
Remi menerangkan neurodivergen adalah istilah untuk menjelaskan bahwa otak manusia juga memiliki keragaman. Pada orang-orang dengan neurodivergen, mereka belajar, berperilaku, serta memproses sesuatu secara ‘berbeda’ dari apa yang dianggap sebagai tipikal atau ‘normal.’
Namun tak banyak yang memahami keragaman itu. Acapkali Remi mencoba menjelaskan cara kerja otaknya tak akan selalu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat semisal dalam melakukan pekerjaan maupun bersosialisasi, tapi ia tak didengar. Ia kehilangan ruang untuk bersuara.
“Setiap kali aku berbicara, opiniku jadi nggak valid lagi. Sama sekali nggak dipertimbangkan, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Mereka malah ngatain aku kebanyakan baca.”
Hingga Remi sampai pada titik kesadaran bahwa hidupnya memang berbeda dengan orang-orang neurotipikal. “Mereka nggak akan bisa lihat dari kacamataku.”
Baginya semuanya terhubung, antara identitas gender, orientasi seksual, maupun cara kerja otaknya. Ia lantas meyakini bahwa dirinya tak bisa masuk ke dalam kotak-kotak biner gender. Ia meletakkan ‘non-biner’ sebagai state of mind, untuk memaknai pengalaman gender di dalam jiwanya.
“Aku merasa nggak resonate dengan maskulin dan feminin. Nggak bisa masuk gitu ke otakku, kenapa harus jadi dua dan dikategorikan. I understand that it could be useful to categorize things sometimes, but it ain’t me.”
Selain non-biner, Remi juga merasa nyaman mengidentifikasi gendernya dengan label genderqueer boy. Gender, baginya, adalah apa yang beresonansi dengan penghayatan seseorang sehingga sangat mungkin bila seseorang merasa nyaman dan utuh pada satu atau lebih identitas.
“Aku resonate dengan gender konvensional yang sudah tersedia dalam masyarakat, seperti “boy” atau “man”, tapi nggak lantas nyaman dengan maskulinitas tradisional yang ada, I could be a flamboyant-macho-femboy with beard and muscle and lipstick with high heels dancing!”
Melalui identifikasi dirinya, Remi hendak menggugat bangunan kaku antara identitas dan ekspresi gender seseorang. Remi tak sepakat bila pakaian yang ia kenakan, barang yang ia sukai, hobi yang ia tekuni, seolah menjadi penanda atas gender yang dihayati. Kesemuanya tak lain adalah spektrum yang bisa dipertukarkan dengan sangat cair dan seharusnya, bisa sangat menyenangkan.
“Aku juga menghayati label ‘neurodivergen’, rasanya label ini kayak ‘non-biner’ kalau buat gender, tapi kalau ‘neurodivergen’ adalah label tentang how we process the world,” jelas Remi.
Orang-orang tanpa disabilitas (non-disabled person) kerap luput pada apa yang tak tampak, sehingga sulit menemukan adanya kepentingan bagi diri mereka. Maka tak jarang, kelompok mayoritas menjustifikasi pengalaman disabilitas seseorang hanya sebatas pada norma yang mereka yakini saja.
Tentu saja, anggapan mereka salah. Disabilitas psikososial berhubungan erat dengan kondisi fisik atau apa yang ada pada otak. Remi menjelaskan bahwa apa yang ia alami juga berwujud, tetapi mungkin tak terlihat–atau tak dilihat. “Karena adanya di otak, jadi nggak kelihatan.”
Ia menuturkan bahwa reaksi yang terjadi di otak pada orang dengan pengalaman neurodivergen, sama dengan orang yang fisiknya sedang terluka. “Rasanya kayak disiksa. We experience mental anguish and torment on a daily basis. Sangat debilitating. Sangat sangat melumpuhkan.”
Menguatkan diri untuk menjelaskan kondisinya, tentu dibutuhkan keberanian dan ketahanan ekstra. Namun ketika Remi berhasil speak up, tak ada balas dekap yang ia harap.
“Itu ada yang lebih menderita dari kamu,” kalimat ini yang justru Remi dapatkan.
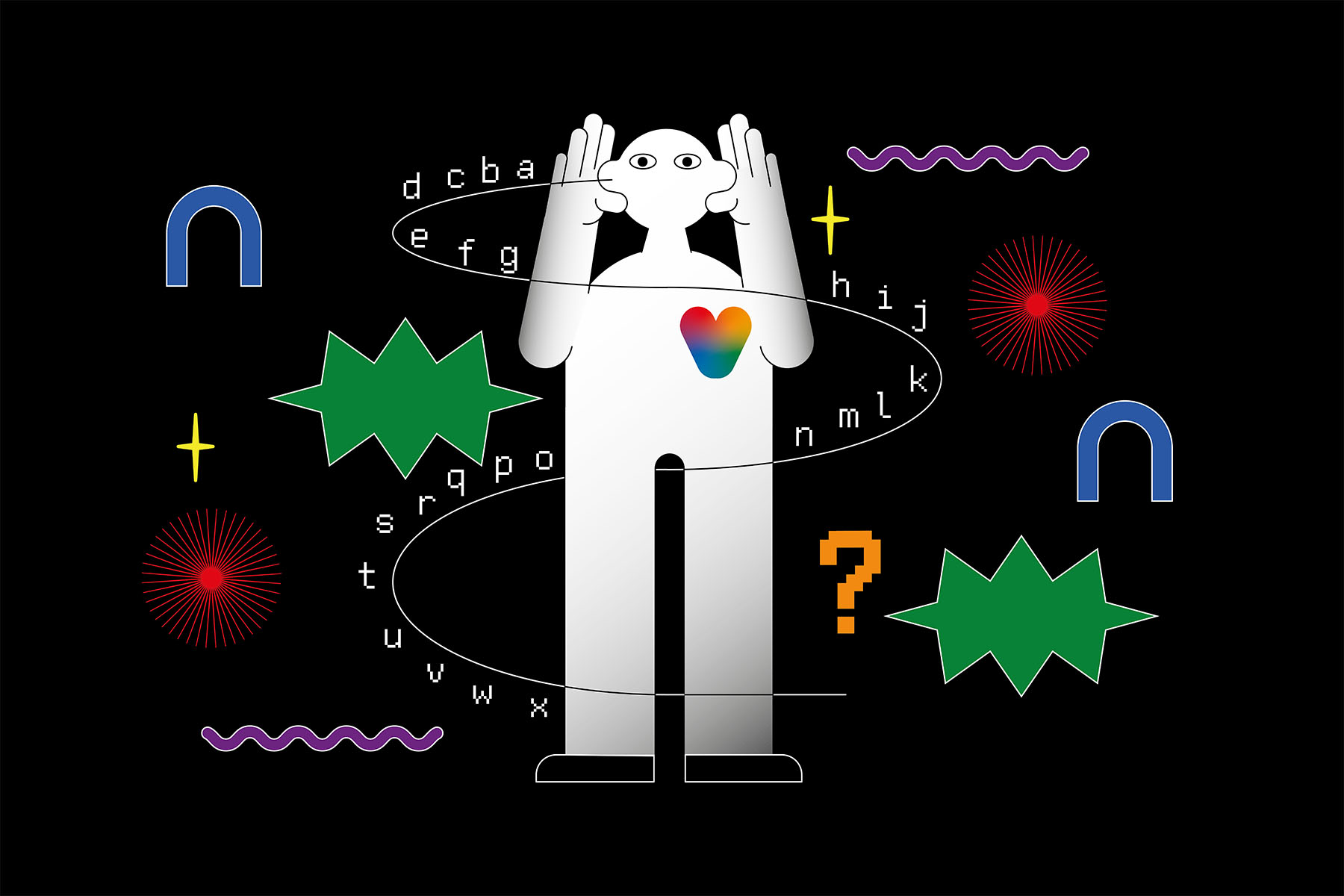
“Keluarga More Like KELUAR GA!”
Memiliki kombo identitas membuat Remi menjadi semakin terasing. Sedari kecil, Remi sudah berbeda dan kerap dicap aneh.
Ia tak pernah bisa menjalin relasi yang baik dengan teman-temannya. Perilakunya dicap ‘berbeda’ oleh orang-orang di sekitarnya. Remi tahu, orang lain terganggu dengan apa yang ia lakukan, meski ia tak bermaksud demikian.
“Aku nggak mengerti kenapa, padahal maksudku bukan begitu.”
Namun tiap kali Remi menjelaskan, tiap kali pula mereka tak mendengarkan. Orang-orang di sekitarnya lebih memilih tak peduli dan mengambil jalan pintas bahwa Remi ‘aneh’. Titik.
Tapi, yang paling mencengangkan baginya adalah ketika keluarganya menganggap pengakuan identitasnya mengada-ada dan bahkan dituduh tidak bersyukur.
“I don’t know what family is… I never feel at home. Keluarga more like KELUAR GA!”
“…aku merasa terkutuk…seolah kami tidak valid, tidak nyata.”
Struktur sosial yang berkiblat pada tatanan ableist dan cisheteronormatif, membuat Remi susah menemukan ruang aman, bahkan pada lingkar terdekat kehidupannya. Sedikit bergetar, Remi kemudian mengungkapkan apa yang baru saja ia alami beberapa hari lalu.
“For the past few days, I have been trying to kill myself.”
Namun dengan cepat Remi meminta maaf, dan menjelaskan sesuatu dengan terburu-buru.
“Oh, I’m so sorry… it’s too much information, but I’m just trying to tell you that it’s not fun, and it’s hard. I’m not really recovered. I’m trying… I’m trying… I’m not recovered yet.”
Cisheteronormatif menjadi keyakinan bahwa cisgender adalah orientasi seksual yang paling normal dan sepatutnya dimiliki manusia, sementara ableist adalah fenomena sosial yang mendiskriminasi penyandang disabilitas.
Saya tak bisa banyak berkata. Saya hanya bisa berujar, “Remi. jangan minta maaf.” Dunia terlampau jahat dan manusia-manusia di dalamnya tak dapat berbagi peluk kepada yang Liyan.
Saya hanya bisa meminta maaf, selama ini tak ubahnya kaum mayoritas yang tak menaruh perhatian pada kondisi ini. Saya hanya bisa berterima kasih, terima kasih sudah percaya dan berbagi kisah. Terima kasih telah berani menjadi diri sendiri. Terima kasih telah tak henti bertahan, satu hari lagi.
LANTAI DASAR
Brian (he/they) ingat betul setiap memori kelam yang dia alami selama tiga tahun duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bunyi bel penanda pergantian kelas menjadi suara yang paling indah baginya. Brian menjalani tiga tahun dengan hardikan, dicap berbeda dengan ratusan siswa lainnya karena memiliki kelainan pada kakinya.
Saya berbincang dengan Brian melalui pesan teks. Ia tidak merasa aman dan nyaman bila membicarakan topik queer disabilitas via layar Zoom, sebab ia berada di rumah. Kendati begitu, ia bersedia membagikan memori kelamnya semasa SMP dulu.
“Waktu itu aku belum diperbolehkan jalan dan disarankan untuk membatasi pergerakan, sedangkan di sekolah itu sistemnya tiap mapel (mata pelajaran) punya ruangan tersendiri, Jadi saat pergantian mapel, murid-murid pindah kelas. Sayangnya ada beberapa mapel yang kelasnya di lantai dua,” papar Brian.
Brian telah meminta petugas sekolah untuk memindahkan kelas-kelasnya ke lantai dasar, mereka mengatakan bisa, tapi tak pernah terwujud. Brian merasa dikhianati. Kelas tetap berlangsung di lantai dua dan ia tak pernah bisa hadir. Ia menanti di lantai dasar, tapi tak ada satu guru pun yang menghampiri.
“Mungkin beliau nganggapnya aku udah paham kali ya, tapi kalau emang begitu ya tetep aja dihampiri kek, jangan ditinggal gitu aja,” ungkap Brian seraya mengirim emotikon tangis. Brian menambahkan bahwa ia bisa tetap mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas karena bertanya kepada teman-temannya.
Diskriminasi tersebut terus berulang, termasuk ketika ada kegiatan maupun tugas praktik. “Nggak usah ikut nggak papa,” begitu kata para guru terhadap diri Brian.
Alih-alih toleransi, sikap sekolah justru menunjukkan bahwa merekalah yang tidak mampu mengakomodasi kemampuan siswanya. “Pemakluman” sekolah atas kondisi siswa yang memiliki pengalaman disabilitas, tak lain buah dari penyakit abilisme. Kebijakan tak bisa dilakukan dengan “mengizinkan” siswa disabel tidak mengikuti pelajaran, sebab itu sama saja meliyankan dan menghambat siswa untuk mendapat materi pelajaran secara setara.
“Kayak misal saat mapel penjas (pendidikan jasmani) aku bisa aja tetap hadir di jam pelajaran. Nggak usah ikut olahraga karena emang aku nggak bisa. Tapi kan aku tetap bisa menyimak, ngeliatin teman-teman aku main, merhatiin teknik mereka, atau ikut jawab kuis dari gurunya,” jelas Brian.
Namun alternatif tersebut nihil dijalankan. Lagi-lagi, orang-orang tanpa disabilitas lebih nyaman mengambil jalan pintas.
“Sedih banget, masa aku nggak ikut belajar di kelas. Untung aku punya teman-teman yang mau nemenin aku waktu jam istirahat dan mau membantu menjelaskan mapel-mapel yang aku nggak bisa ikut,” Brian mengingat perjuangannya sewaktu sekolah dengan kesal sekaligus sedih.
Pengalaman diskriminatif tersebut ia alami selama rentang sekolah menengah pertama, “aku selama SD (sekolah dasar) masih sehat, masih bisa jalan.” Brian mengisahkan bahwa mulai memasuki jenjang SMP, ia baru mulai menjalani prosedur untuk menangani kakinya. Sejak saat itu pula, ia mulai menggunakan alat bantu kursi roda.
Ketika SMA, ia memilih belajar di rumah demi kesehatan dan keamanan. Begitu lulus, Brian kemudian pindah dari Pekanbaru ke Semarang untuk melanjutkan kuliah.
“Selama kuliah ini aku sudah mulai pulih dan diperbolehkan menggunakan kruk.”
“Aku Belum Come Out, dan Nggak Berencana Juga”
“Aku terlahir emang dengan kondisi tubuh yang tidak memungkinkan jalan dengan normal…Kurasa karena udah terbiasa ‘beda’ dari kecil, saat dewasa aku nggak merasa terlalu terkucilkan dengan identitasku sebagai queer.”
Brian menghayati dirinya sebagai seorang non-biner dan panseksual alias ketertarikan tanpa memandang identitas gender. Baginya, dukungan teman-teman dan keluarga yang membuat ia terus bertahan. “Tentu saja, aku belum come out ke mereka (keluarga), dan nggak berencana juga untuk come out,” ujar Brian.
Segalanya akan lebih rumit bila ia membongkar identitasnya. Brian lebih memilih menunggu sampai mapan dan mampu hidup mandiri. Saat ini, Brian lebih memilih berinteraksi dengan teman-teman queer melalui jejaring media sosial agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga. Tapi, pilihan itu berkonsekuensi. Brian belum pernah bertemu langsung dengan sesama queer-disabel, padahal ini penting untuk menumbuhkan semangat solidaritas.
Pada banyak sisi, visibilitas menumbuhkan semangat solidaritas. Sebab ruang-ruang bagi kelompok minoritas terbatas, maka ketika muncul saudara-saudara yang memiliki perjuangan dan penghayatan yang sama, muncul pula harapan dan kekuatan bagi sesamanya.
“Melihat representasi queer online bagiku juga membantu. Belakangan ini aku banyak menemukannya di TikTok, dan itu bikin aku hopeful,” ungkap Brian.
Di sisi lain, baginya, identitas sebagai seorang queer dan disabel, bagi Brian adalah suatu kekuatan. Ia tak menampik bahwa sangat sulit untuk merima lapis-lapis marginalisasi yang ia alami karena orientasinya ini. “Tapi kalau mengingat orang-orang yang aku temui, dan hal-hal yang aku lalui, walaupun nggak semuanya baik, aku tetap bersyukur karena dari situ aku belajar. Mungkin semua itu nggak bakal terjadi, kalau aku cishet dan abled.”
SINDROM KELELAHAN KRONIS
Sejak 2018, Jo Pradigda (they/them) mulai merasa mudah lelah. Ia juga mengeluh mulai tak kuat naik tangga atau pun berjalan jauh. Diagnosis awal, ia menderita chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Ia hanya dibekali obat pereda nyeri, dan tak ada tindak lanjut yang berarti.
Puncaknya terjadi setahun kemudian, ketika Jo tengah melakukan penelitian etnografi bersama petani adat di Sumatera Utara. Ia tengah berkegiatan di sawah ketika tiba-tiba badannya tak bisa dibungkukkan dan panggul belakangnya sulit digerakkan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia kemudian dilarikan ke dukun setempat.
Kesempatan beasiswa pascasarjana yang diraihnya ke Amerika Serikat dimanfaatkannya untuk menemui dokter dan memeriksa kondisi tubuhnya. Dokter bilang Jo memiliki kadar autoimun yang sangat rendah di bawah batas normal.
Awal 2020, Jo menemukan jawaban. Ia didiagnosis mengalami artritis reumatoid (rheumatoid arthritis). Pada saat itulah, Jo sekaligus mengalami masa-masa sulit untuk menerima diri bahwa tubuhnya memiliki limitasi, bahwa dirinya bagian dari orang-orang penyandang disabilitas.
“Rheumatoid arthritis ini menyebabkan rasa sakit atau pembengkakan di sendi,” kata Jo.
“Aku kalau lagi kena serangan itu jari-jariku bengkak, pergelangan tanganku bengkak, aku juga kena carpal tunnel, dan itu aku jadi nggak bisa ngetik. Terus aku juga kena di lutut, lower back pain itu udah pasti, udah nggak bisa ngapa-ngapain,” lanjutnya.
Beberapa terapi dan kegiatan juga mesti rutin ia lakukan, salah satunya adalah olahraga kardio. Hal tersebut berguna untuk meminimalisasi dampak buruk kelainan yang dapat menyerang sendi organ dalam, seperti paru-paru. Namun ihwal ini juga memiliki tantangan tersendiri.
“Orang kalau habis nge-gym, sendi sakit itu kan biasa yah. Tapi kalau aku, aku itu bisa seminggu penuh kerasa sakit semua. Butuh waktu yang lebih lama bagiku untuk healing kembali, to recollaborate, to rejuvenate, dibandingkan orang-orang non-disabel,” terang Jo.
Saya tak banyak mengerti mengenai artritis reumatoid, sampai akhirnya Jo bercerita bahwa ia tak bisa membuka tutup kaleng. Di titik itu, saya kembali merutuki diri. Menyadari bahwa sebelum ini, saya tak pernah merasa perlu belajar mengenai ragam pengalaman disabilitas. Tentu saja, sebab saya terlalu nyaman dengan hak istimewa yang saya miliki cuma-cuma.
Ya, Jo tak bisa membuka kaleng atau tutup botol berbahan dasar kaca.
“Aku nggak bisa buka. Aku bener-bener nggak bisa buka. Sampai akhirnya aku diajarin temenku, dengan cara dipanasin lebih dulu. Jadi kan aku harus kerja ekstra ya, manasin dulu botolnya, rebus dulu botolnya, udah kayak orang ‘bego’ gitu lho, di atas kompor kayak cuma buat buka botol saus kacang hahaha…” Jo tertawa satire.
Hidup di negara maju tak lantas menjanjikan bahwa abilisme seketika sirna. Jo juga dituntut menuruti pandangan bahwa seluruh tubuh itu sama.
Fasilitas pendidikan kerap tak memerhatikan bangun tata ruang yang aksesibel terhadap semua orang. “Gedung departemenku itu nggak ramah disabilitas. Aku udah bilang berkali-kali, aku itu nggak kuat naik tangga lebih dari lima menit. Kakiku bakalan sakit dan tremor,” kata Jo.
Lagi-lagi, kebijakan tunduk seturut kuasa ableist yang berkehendak. Rencana untuk pindah gedung yang menyediakan elevator, sekadar rencana.
“Mereka itu nggak mau pindah, simply karena ‘ya.. ini desain rumahnya bagus banget.’ No! desain rumahnya itu nggak aksesibel buat orang-orang yang pakai kursi roda,” tukas Jo.
Hal-hal sederhana bagi orang tanpa disabilitas, bisa jadi berdampak signifikan bagi orang-orang disabel. Namun kerap kali, orang-orang non-disabel abai dan memilih tak mau tahu.
Jo kembali menunjukkan bahwa ada banyak hal mapan yang perlu dirombak ulang. “Aku emosi banget kalau ngomongin ini,” Jo memulai kritikannya.
“Kalau lagi musim liburan, mereka itu ngedekor pegangan tangga yang aku nggak bisa megang. Sementara kalau aku naik tangga, aku mesti pegangan tangga. Aku bete banget!” Jo juga menuturkan bahwa ketika tidak kuat berjalan, terkadang ia menggunakan tongkat sebagai penunjang.
“Please banget, jangan dekor pegangan tangga! Not only it’s tacky, aku itu ngebayangin orang-orang yang kayak aku gitu lho, yang harus pegangan kuat, eh tau-tau ada daunlah, inilah, hhh.. itu frustrating banget.”
“Why Don’t You Learn My Language Too?”
Jo Pradigda menghayati dirinya sebagai seorang genderfluid dan nyaman menggunakan pronomina persona ‘they’. Namun fasilitas kesehatan, lagi-lagi, kerap melakukan misgender dan masih menerapkan bahasa dengan sangat biner. Terlebih ketika artritis reumatoid yang Jo alami ini, memiliki demografi dengan pasien terbanyaknya perempuan. Maka dokter secara serampangan mengasumsikan bahwa Jo seorang cisgender perempuan.
“I had a lot of gender dysphoria setiap berkali-kali ke ruang dokter,” kata Jo.
Ia merefleksikan ulang bahwa dirinya tidak mendiskriminasi kelompok cisgender dan heteroseksual, serta selalu berusaha memakai bahasa yang inklusif, “tapi kenapa aku nggak dikasih hal yang sama, aku belajar dengan bahasa mereka, why don’t you learn my language too?”
Jo mengungkapkan hal lain yang luput diwacanakan ketika membicarakan disabilitas adalah mereka dianggap tidak punya nafsu seks. Asumsi inilah yang sayangnya, masih diadopsi oleh beberapa kultur dalam komunitas queer. Jo mengkritik bagaimana media populer mempromosikan imajinasi atas tubuh laki-laki gay idaman. Penggambaran yang berpusat pada bentuk tubuh yang sehat dan maskulin, dimanifestasikan dengan potret laki-laki (cisgender) di pusat kebugaran dengan badan yang kekar dan otot yang menonjol.
“Sayangnya, imajinasi disabilitas itu nggak compatible sama image sexually liberated people.”
Selebrasi seksualitas perlu memperhatikan seluruh orang di dalam lingkaran, agar ruang aman yang setara bisa terus tercipta. “Kita punya teman-teman aseksual. Di saat yang sama, ketika ada supporting sexual freedom, ada queer-disabel yang tidak dianggap di dalam ruang image yang sama, ya karena dianggap mereka itu nggak punya sexual desire,” kata Jo.
Jo menilai ada bermacam material fisik yang perlu dirombak ulang, salah satunya standar tubuh yang dianggap valid agar dapat turut serta dalam bermasyarakat.
“Ketika kamu ngedesain suatu barang dan kamu mendesain barang sesuai tubuh kamu. Coba kamu pertimbangkan, ada tubuh-tubuh lain di luar sana. Jangan maksain cara kerja tubuhmu ke orang lain. Jangan mengasumsikan semua orang bisa naik tangga dan ngebuka botol kaca. Jangan pernah asumsiin badan kamu ke badan orang lain,” kata Jo.
Semua orang memiliki peluang untuk menjadi disabilitas, kata Jo, tanpa bermaksud menakuti. Ia mengambil contoh pandemi COVID-19 yang membuat puluhan juta orang terkena ‘disabilitas kolektif’.
“Mereka lebih gampang burn out, sesak napas, dan segala macem. Jadi justru yang sangat-sangat gampang berubah itu ability, bukan orang difabel. Pandemi ini udah membuktikannya,” kata Jo.
Serangkaian beban mental juga mesti dipikul queer-disabel secara bersamaan. “Kamu harus managing orang homofobia, di saat yang sama, kamu juga harus managing ableism di kantor kamu,” terang Jo.
Ia menyampaikan bahwa pada banyak kasus, queer-disabel memiliki keterbatasan akses yang lebih dipersulit dibanding ketika kelompok tersebut adalah cisgender-heteroseksual-disabel.
INSPIRATIONAL PORN
Jo menekankan pentingnya diksi disabilitas. “Untuk ngasih tahu bahwa dunia ini sangat ableist,” tegasnya.
Jo sangat tidak nyaman dengan perlakuan orang-orang non-disabel yang memaksakan kacamata pandangnya dan menyangkal kondisi yang penyandang disabilitas alami. Kamu itu bukannya nggak bisa, kamu itu cuma bisa hal yang lain aja. Jo mengungkapkan kalimat-kalimat ‘penyemangat’ yang tak lain adalah bentuk toxic positivity.
“Gue emang nggak bisa naik tangga, Bro! titik. I objectively, nggak bisa!” tegas Jo tiap ada sikap penyangkalan datang dari kaum ableist.
Sikap tersebut berbahaya, sebab ada tendensi untuk menormalisasi keadaan, dan justru mengaburkan perkara yang lebih serius, yakni meredefinisi ulang bangun ruang sekaligus pemikiran superior nan abilisme
Jo mengungkapkan bahwa ada satu tema yang selalu persis sama tiap ke mana pun ia pergi atau berada. “Oh My God, kamu itu keren banget ya, kuat banget bla bla bla…” Jo menirukan ungkapan-ungkapan yang selalu mampir ke dirinya.
“Tetap jadi inspirational porn di mana pun aku berada. Aku frustasi sendiri gitu lho, kayak, apa sih yang inspirasional dari nggak bisa naik tangga? I’m a bedridden. Ini nggak inspirasional. Ini menyakitkan tahu!”
Serupa Jo, Brian langganan pula ditetapkan sebagai figur inspiratif. Namun ucapan-ucapan yang mengiringi setelahnya, tak ubahnya lecutan semangat. Lecutan untuk kawan disabel, dan semangat untuk si ableist.
Lihat dia, sudah bertahun-tahun kayak gitu (disabel), tubuhnya ‘cacat’, jalan aja susah. Tapi saya nggak pernah dengar dia sambat (mengeluh). Kalau dia aja bisa, masak kamu engga?
“Mengkotakkanku sebagai sosok inspiratif, tapi di saat yang bersamaan malah ngerendahin aku,” ungkap Brian.
Brian kerap menerima penyangkalan dari orang-orang non-disabel. Tak hanya sekali dua kali, ia menegur mereka untuk menggunakan istilah yang tepat dan lebih nyaman bagi Brian. Namun ia justru dibantah dan bahkan mempertanyakan balik teguran Brian.
Aku deket sama penyandang disabilitas kok. Anakku disabel juga loh.
“Padahal anaknya masih kecil dan atau belum terlalu mengerti perihal inklusivitas disabilitas. Jadi si anak sejatinya masih belum bisa berpendapat istilah atau label apa saja yang dia merasa nyaman,” terang Brian.
Seseorang yang menghayati dan mengalami langsung peristiwa adalah yang paling berhak untuk menyematkan label yang ia rasa nyaman kepada dirinya sendiri. Istilah atau label merupakan sesuatu yang sangat sakral, hal tersebut tak lain sebagai petanda perjalanan, perjuangan, serta bagian dari identitas diri.
Brian merasa nyaman dengan identitas dirinya sebagai tunadaksa, sebaliknya, istilah seperti ‘lumpuh’ tak ia sukai, sebab memiliki nilai rasa menghina dan mengasumsikan bahwa tunadaksa tak memiliki kemampuan atau tak layak untuk melakukan sesuatu.
Merasa dekat dengan seorang penyandang disabilitas juga tak lantas menjadikan seseorang otomatis menjadi inklusif. Ego primitif dengan sikap berlagak paling tahu, justru akan membenamkan orang-orang non-disabel pada lubang dalam, tempat segala pongah dan antikritik bersemayam.
“Okay, Anda dekat atau memegang peran caretaker bagi seorang disabel. Caretaker ini bisa orang tua, perawat atau profesi lain yang berhubungan dengan tugas menjaga atau mengasuh. Tapi bukan berarti Anda otomatis menjadi lebih ngerti, lebih tahu tentang struggle kami. Anda hanya menyaksikan. Tidak merasakan,” ungkap Brian, sebuah jawaban yang ingin sekali ia sampaikan terhadap orang-orang jahat tersebut.
“Kalau dibilangin jangan ngeyel atau ngebantah! Dengerin! Pahami!”
Satu lagi yang kerap luput diperhatikan oleh orang-orang non-disabel. Bahwa sikap heroik tak lantas menjadi berarti bila tak diawali dengan meminta consent atau persetujuan.
“Ini paling sering aku alami, orang menghampiri aku dan langsung dorong kursi rodaku tanpa izin,” Brian kembali meluapkan keheranannya kepada orang-orang non-disabel.
Tentu, ia mengapresiasi niat baik. Namun meminta izin adalah yang paling utama. Ini berlaku dalam segala ihwal, termasuk dalam hal menawarkan bantuan kepada orang lain.
“Yaudah deh mau digimanain lagi, hehe.”
Laporan ini bagian dari serial #HakMinoritas
Artikel mengalami pembaruan pada Sabtu, 11 Desember 2021, untuk memperdalam pengalaman disabilitas psikososial yang dialami narasumber.