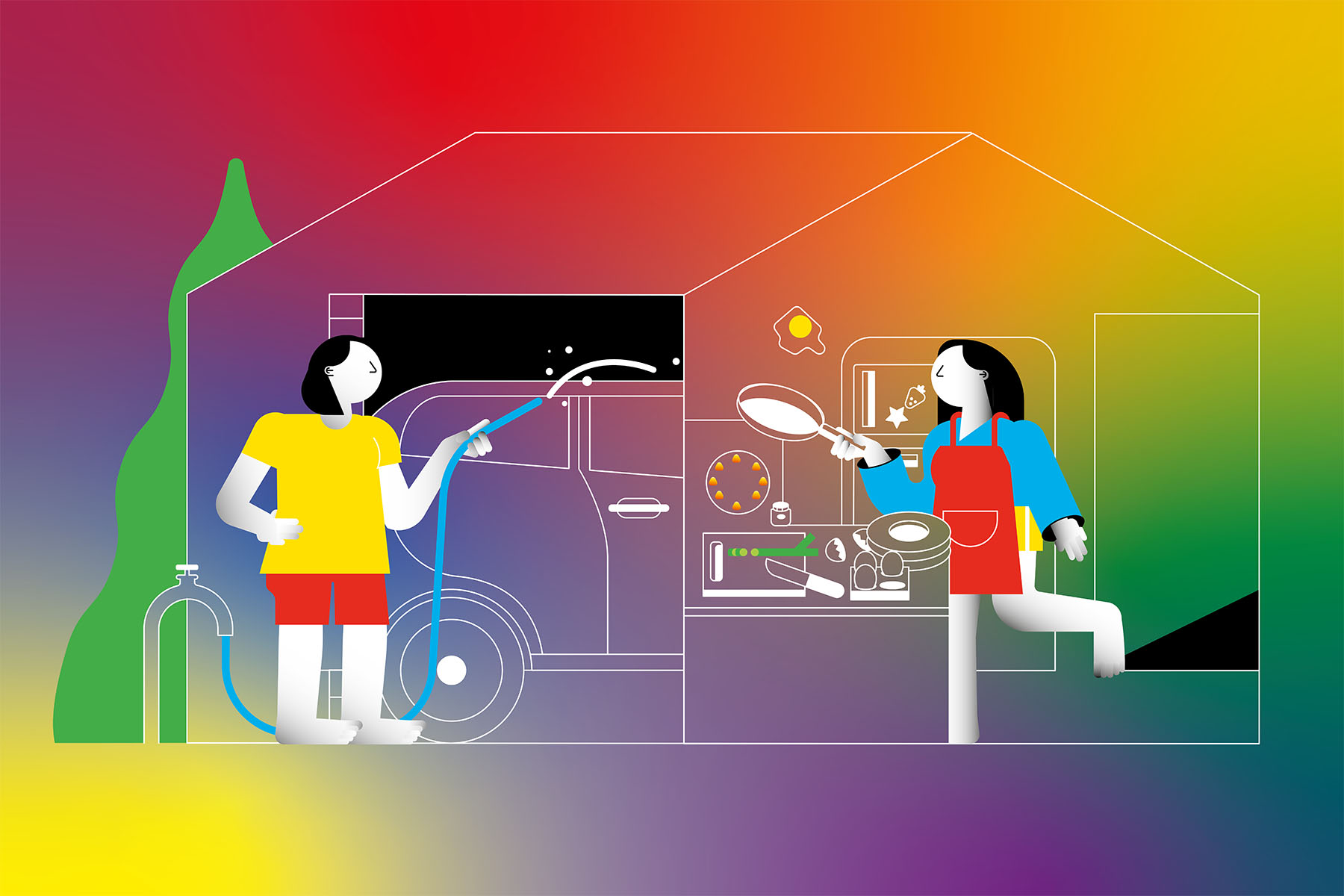Peringatan: artikel memuat penuturan tentang depresi dan niat bunuh diri yang dapat mengganggu kenyamanan Anda
“Aku pengen ngerasain bebas jadi diriku sendiri. Padahal itu di rumahku, kenapa kok aku nggak bisa bebas?”
Perasaan tidak bebas ketika berada di rumah adalah salah satu alasan kuat ketika Ang (26) memutuskan pindah ke Kudus. Ibunya yang protektif membuatnya makin tak betah tinggal di rumahnya di Semarang.
Dulu, ketika ia lulus SMK, ia berpikir, pola asuh orangtuanya bakal berbeda. Ia mungkin bisa lebih bebas setelah statusnya bukan lagi pelajar, tapi itu tidak terjadi.
Ketika ia bekerja sebagai karyawan pemasaran di sebuah kantor kecil di Semarang, ibunya tetap tak memberikan keleluasaan: sulit keluar rumah kecuali kerja, diuber desakan untuk menikah, dan bahkan dilarang mengenakan celana pendek saat bepergian.
Itu semua bikin Ang jengah. Pada 2015, ia akhirnya memberanikan diri menyusun rencana keluar dari rumah. Ia mendatangi ibunya dan mengatakan ia diterima kerja di salah satu perusahan di Kudus. Diterima kerja di Kudus hanyalah modus untuk mengelabui ibunya agar diizinkan keluar dari rumah.
Keberaniannya mengucap keinginan yang jelas bakal ditentang ibunya muncul kuat sesudah ia berdiskusi dengan Ken, partnernya.
“Ngomong aja kerja di Kudus,” ujar Ken.
Modus itu sukses. Ibunya memperbolehkan dengan catatan si ibu akan sering mendatangi Ang.
Sebenarnya, saat itu Ang masih terikat kontrak di Semarang. Ang menyewa dua kamar kost kecil, satu dekat kantornya dan kedua di Kudus. Ia merencanakan dengan matang kepindahannya jauh-jauh hari, sembari mempersiapkan tempat yang akan dikunjungi sang ibu.
Suatu kali, orangtuanya datang ke Kudus tanpa mengabari Ang. Biasanya, mereka mengirim pesan singkat berbunyi, “Aku meh neng Kudus (Aku mau ke Kudus). Beresi kosmu sik (Bereskan kosmu).”
Namun pesan singkat justru datang dari kakak keduanya, menjelaskan dengan ambigu, “Kok kayaknya bapak sama ibu mau ke Kudus ya, soalnya aku disuruh berangkat naik vespa.”
Ang tergopoh-gopoh meminta izin pulang cepat kepada kantornya meski sudah mendekati jam bubar karyawan, lantas memacu motor menuju Kudus. Saking paniknya, dalam perjalanan, Ang ditabrak mobil dari belakang. Alasan dari pemilik mobil, Ang melewati marka pembatas jalan. Alhasil, Ang harus membayar kerusakan mobil.
Tragedi ini membatalkan niatnya ke Kudus. Terpaksa, Ang berkelit kepada orangtuanya bahwa ia harus mengantarkan teman kerjanya pulang ke Demak lalu mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa ditemui di kos. Orangtuanya tetap marah, mengomeli Ang karena dianggap tidak menghargai kedatangan mereka.
Usai kontrak kerjanya di Semarang kelar, Ang benar-benar pindah ke Kudus. Ang ikut bekerja dengan salah satu kerabat Ken di toko roti. Ang bertanggung jawab sebagai asisten baker di pagi hari dan pramuniaga toko saat malam. Kala itu, ia tidak mendapat upah tapi Ken menyediakan tempat tinggal dan makanan sehari-hari.
Kepada keluarga dan kerabat Ken, Ang dikenalkan sebagai teman.
Pasangan homoseksual masih sulit diterima bagi sebagian besar keluarga di Indonesia, termasuk bagi keluarga Ken dan Ang. Karena itu, tidak mungkin mereka mengumbar status hubungan mereka kepada keluarga, kecuali jika berniat cari perkara. Dalam beberapa kasus di Indonesia, individu yang mengaku homoseksual ke keluarganya justru diusir dari rumah atau disembuhkan dengan rukiah. Keduanya sama-sama menyakitkan.
Kenyataan itu membuat Ken dan Ang ketar-ketir tiap waktu.

Sulit Mendapat Kerja, Bikin Usaha Diusik Ibu Kontrakan
Tinggal di Kudus dengan KTP Semarang memperkecil peluang Ang mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Perusahaan lebih memprioritaskan pencari kerja yang beridentitas asli Kudus. Jika memang tidak tercatat sebagai penduduk Kudus, setidaknya punya ‘orang dalam’ yang bisa mendukung dalam proses rekrutmen. Namun, Ang tidak mempunyai keduanya. Ia pun mengurungkan niat.
Selama beberapa bulan Ang dan Ken bekerja di toko roti. Mereka hidup hemat dan memperbanyak tabungan untuk modal usaha. Sejak awal, mereka memang bersepakat, bekerja di toko roti merupakan batu loncatan. Bukan sekadar mengumpulkan uang, tapi mereka mengamati proses mengelola bisnis rumahan.
Pada pertengahan 2016, mereka berdua keluar dari toko roti lalu coba peruntungan berbisnis makanan. Mereka menyewa ruko dua lantai seharga Rp14 juta per dua tahun. Harga awal 7,5 juta per tahun, tapi Ang membujuk induk semangnya agar memberikan diskon. Menegosiasikan harga sewa beriringan dengan keterbukaan Ang mengenai rencana bisnis makanannya.
“Boleh buka jualan di sini, tapi jangan kayak punyaku ya, Nok. Nek aku udah jualan jus, ya kamu yang lain,” pesan ibu pemilik kontrakan.
Ang dan Ken melihat potensi lingkungan sekitar yang dekat dengan SMP, sehingga muncul ide membuka jualan pancake dan minuman squash. Mula-mula laku keras. Tampilan minuman yang berwarna dan bersoda menarik minat beli dari anak-anak sekolah, bukan hanya untuk diminum tapi difoto dan diunggah di media sosial.
Namun, di tengah proses menikmati keuntungan, ibu pemilik kontrakan menggugat, “Jangan jualan minuman lagi. Anak-anak lebih suka beli di tempatmu daripada di tempatku.”
Ang memberontak dalam hati, merasa pembeli berhak memilih. Namun, demi menjaga ketentraman bersama, ia bungkam dan mengiyakan permintaan ibu pemilik kontrakan untuk berkolaborasi.
Tawarannya, Ang tetap berjualan pancake sementara ibu pemilik kontrakan menjajakan minuman. Alih-alih berjalan mulus, pembeli justru semakin berkurang setiap hari.
“Ya… mungkin kalau makan pancake minum jus bikin kekenyangan. Uang jajan anak-anak SMP juga seberapa sih? Mending milih beli minuman nanti makan di rumah. Emang kayaknya nggak hoki aja jualan makanan. Kami terus berhenti.”
Gagasan lain cepat bermunculan dalam benak Ang. Ia dan Ken memindahkan bisnis makanan ke tempat lain, lantas berjualan es cokelat. Tidak lama, mereka gulung tikar lagi.

Struggling Berbisnis Salon Kucing
Ang kemudian terbayang membuka usaha salon kucing. Saat itu, ia bergabung dengan komunitas pecinta kucing di Kudus.
Hasratnya untuk merawat kucing terealisasi setelah ia meninggalkan rumah Semarang. Banyak hal yang tidak kompak disepakati, termasuk saat Ang mengungkapkan keinginannya memiliki anabul kucing di rumah. Keluarganya hanya mengizinkan Ang memberi makan kepada kucing yang lewat di sekitar rumah, tapi melarang keras jika kucing sampai melangkah masuk.
“Aku waktu itu cuma punya Rp500 ribu. Aku beli kandang [kucing] dua, yang satunya rapuh. Kadang kalau kucingnya aktif, sela-sela antar besinya bisa meleyot. Alat pengeringnya juga second, karena lebih murah,” kisah Ang mengingat mula-mula memulai usaha salon kucing pada 2016.
Ruko tidak lagi berfungsi sebagai kafe, beralih menjadi rumah bagi kucing-kucing milik Ang maupun yang dititipkan. Ia menaruh beberapa kandang di luar saat siang hari, sehingga menarik perhatian pecinta kucing lain. Mereka saling menyapa dan berdiskusi. Ang menyisipkan promosi dalam pertemuan ini.
Ang dan Ken bersemangat mempromosikan usaha salon kucing dengan memasuki grup-grup di Facebook yang berbasis di Kudus, entah grup jualan ataupun grup komunitas.
Pelanggan pertama Ang seorang mahasiswa, yang hendak berangkat pelatihan kerja lapangan. Ia menitipkan tiga ekor kucing selama sebulan. Ang mematok harga relatif murah untuk jasa penitipan dan perawatan kucing, yakni Rp5 ribu dengan kandang dan Rp10 ribu tanpa kandang per hari.
Seiring meningkatnya permintaan dan kepercayaan terhadap salon kucingnya, Ang kini berani menaikkan tarif penitipan dan perawatan kucing menjadi Rp25 ribu. Di masa Lebaran, tarifnya menyesuaikan, bertambah menjadi Rp30 ribu. Sementara untuk jasa grooming atau memandikan kucing mulai dari Rp45 ribu untuk kucing dewasa dan Rp35 ribu untuk kitten di bawah usia 4 bulan.
Akan tetapi, mengandalkan penghidupan dari jasa grooming harus terhenti ketika pandemi COVID-19. Usai kasus penularan COVID-19 turun, beberapa pelanggan kembali menghubungi Ang tapi minta keringanan pembayaran bisa ditunda. Terkadang, Ang harus menunggu pembayaran jasa grooming seminggu kemudian atau bahkan awal bulan berikutnya.
“Ya nggak apa-apa… Pandemi, kan, efeknya buat siapa aja,” ujar Ang.
Ang melihat peluang lain selama pandemi. Ia mengamati peningkatan permintaan atas masker dan hand sanitizer. Ang dan Ken nekat menghabiskan tabungan terakhir, sekitar kurang dari Rp2 juta, untuk memborong perlengkapan protokol kesehatan.
Setelah kontrakan ruko habis, Ang hanya menerima panggilan jasa memandikan kucing sembari menerima pesanan masker dan merangkai manik-manik menjadi strap mask, gelang, atau kalung. Ken membantunya sesekali untuk mengantar pesanan.
Rata-rata pendapatannya berkisar antara Rp1,5 juta-Rp2 juta setiap bulan, masih di bawah upah minimum di Kudus. Jika ada pelanggan menitipkan kucing untuk dirawat, Ang bisa mendapat lebih dari Rp2 juta dalam sebulan.
Selain kebutuhan pribadi, Ang memilah penghasilan untuk menyokong uang kontrakan.
Pada tahun pertama mengontrak rumah, Ken membantu pembayaran secara penuh. Sementara mulai tahun ini, Ang sepakat menyisihkan Rp350 ribu setiap bulan untuk disetor kepada Ken.
“Ken membantuku untuk mandiri mengelola keuangan. Dulu nggak seterbuka ini. Sejak kami akhirnya bisa ngobrol dari hati ke hati, pas tahun 2019, akhirnya dalam hal keuangan juga ada perubahan.”

Beban Ganda karena Identitas Gender
Ang tinggal bersama Ken di sebuah rumah di pinggiran Kudus. Mereka mengontrak rumah satu kamar, dapur, dan kamar mandi seharga Rp8 juta per tahun. Ruang depan yang biasanya menerima tamu menjadi ruang tidur. Sementara kamar utama dihuni oleh 30 ekor kucing Ang.
Sebelum pindah ke Kudus, Ang pernah mengalami depresi karena keluarganya melarang dan membatasinya menyampaikan pilihan dan suara hati. Ia sempat dibawa ke psikiater tapi prosesnya justru semakin memberatkan. Hidup di dalam keluarga yang tidak menyediakan ruang aman bagi seorang lesbian, membuat Ang tak nyaman.
Sejak dalam keluarga, ia dididik menjadi perempuan nurut pada kodrat: Sekolah tak perlu tinggi, harus menikah, harus hidup mengurus suami dan anak.
Gambaran itu tidak ideal bagi Ang. Ia punya jalan yang ia inginkan sendiri. Sejak 2015, ia menjalin hubungan dengan Ken, salah satu harapannya terhadap Ken adalah mendapatkan ruang aman dari pasangan. Sayang, awalnya itu tidak bisa ia dapatkan.
“Setelah aku keluar dari rumah, aku cari ruang aman ternyata aku dapat pasangan yang depresi juga. Pada akhirnya, salah satu harus mengalah. Aku merasa bisa menekan, ya aku menekan [emosi] sekian tahun. Dulu, Ken itu tipe yang susah diajak ngomong. Nek (kalau) ada masalah seharusnya ngobrol, tapi ketika aku ngomong seolah-olah dia tutup telinga.”
Saat relasi mereka di ujung tanduk, Ang terpikir untuk berhenti. Ia merasa ia dan Ken tidak pernah saling mengenal dengan baik, justru melukai satu sama lain.
Sementara Ken, milenial berusia 30 tahun, punya masalah tak kalah rumit. Pilihannya untuk tampak single di mata keluarganya selalu buntu karena desakan menikah dengan laki-laki heteroseksual.
Dalam beberapa kasus, desakan menikah itu tidak terelakkan. Kisah Ben dan Bunga, misalnya. Kedua Gen Z di Jepara itu pernah menjalin tali kasih yang rumit. Bunga terpaksa menikah dengan laki-laki heteroseksual, tapi pada saat yang sama tidak ingin pisah dengan Ben. Keduanya sepakat melanjutkan hubungan meski Bunga sudah berstatus istri orang lain, meski akhirnya hubungan keduanya tetap kandas.
Ken tak ingin memilih jalan itu. Pilihannya untuk tetap bersama Ang pun berbuntut panjang.
Saat Ken meninggalkan rumah, keluarga membuntuti dan mengejar keberadaan Ken. Ang akhirnya jadi sasaran tembak ibu Ken karena dianggap memengaruhi Ken hingga nekat kabur.
Intimidasi yang berulang oleh keluarga Ken semakin menyesakkan keduanya. Ang mendorong Ken untuk menyelesaikan urusan dengan keluarganya. Ken menurut, ikut pulang bersama kakaknya. Alih-alih pulih, Ken justru mempunyai tendensi mengakhiri hidupnya. Lantas, Ang menuntutnya untuk keluar, tinggal bersamanya.
Keluar dari rumah karena keluarga tidak memberikan ruang aman, bukan berarti bisa lepas dari tuntutan bantuan finansial. Hal itu dialami Susi, seorang queer di Jepara. Susi anak bungsu dari empat bersaudara. Ketiga kakaknya sudah menikah; dua di antaranya tinggal di rumah peninggalan orangtua yang sudah tiada.
Status Susi sebagai pekerja justru menuntutnya ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga kakaknya. Beberapa alokasi untuk membayar listrik, membeli bahan makanan, atau memberi uang jajan kepada keponakannya masih terdengar masuk akal.
Namun, beban lain mulai dibagikan, seperti permintaan dari kakak pertamanya untuk membantu pembelian material pasir untuk bangun rumah. Menjelang Lebaran, keponakan-keponakannya tak sungkan memohon barang tertentu.

Berkomunitas: Menguatkan Tanpa Batas
Ketiadaan ruang, bahkan mulai dari unit terkecil yakni keluarga, untuk menyampaikan pilihan seperti yang dirasakan oleh Ang dan Ken tidak mengurungkan tekad merdeka.
Mereka memilih menciptakan ruang aman melalui kanal-kanal sederhana, mulai dari pertemanan, relasi personal, lingkungan tempat tinggal, sesama buruh, hingga berjejaring dengan komunitas.
Ang misalnya bergabung dengan sebuah komunitas LGBTQ+ di Jawa Tengah yang menyediakan ruang aman. Di sana mereka mengembangkan wawasan tentang SOGIESC (orientasi seksual, identitas & ekspresi gender, dan ketubuhan), kemampuan sosial, dan keterampilan hidup. Setiap kegiatan membuka kesempatan untuk teman-teman queer menjadi panitia pelaksana. Tanpa disadari, mereka belajar mengelola komunitas dan bertanggung jawab terhadap peran-peran yang dipilih.
Pendamping komunitas LGBTQ+ di Jawa Tengah giat menemui teman-teman queer di penjuru Jawa Tengah untuk nongkrong bersama. Kegiatan ini berkembang menjadi sesi curhat isu personal, yang pada gilirannya menciptakan keterhubungan antar individu queer. Misalnya, patah hati ditinggal menikah oleh pasangan, kasus penipuan uang hingga masalah keluarga.
“Aku pada akhirnya menemukan identitasku sebagai queer dari acara itu. Waktu itu kami belajar identitas gender, lalu mereka menyebutkan ada queer dan aku merasa cocok. Ya, itulah aku,” kata Ang.
Di komunitas itu, Ang menjumpai dinamika kehidupan Gen Z yang berbeda dengan label pemerintah sebagai Gen Z yang tech savvy, suka jalan-jalan, banyak nongkrong di warung kopi. Kehidupan mereka lebih tak terlihat.
Ia mungkin berjuang untuk mempertahankan pekerjaan demi membiayai kehidupan sehari-hari seperti Gen Z lain, tapi urusannya lainnya, mereka direpresi sampai akhirnya menyembunyikan identitas gender di tengah keluarga dan masyarakat yang konservatif.
“Aku belum tegas ngomong ke orangtuaku kalau aku nggak pengen nikah. Pengen banget sebenarnya ngomong, ‘Nanti kalau aku menikah, dinafkahi, hakku semakin dirampas.’”
Jika kehidupan bisa memberikan Ang banyak pilihan dan kesempatan, ia cuma ingin membeli tanah lalu membangun rumah sederhana impiannya, lalu hidup tenang dan damai bersama Ken dan 30 ekor kucingnya.

Ang, Susi, Ken, Ben, dan Bunga bukan nama sebenarnya.
Laporan ini adalah bagian dari serial reportase #UnderprivilegedGenZ. Serial ini didukung oleh Kawan M.
Pembaca bisa mengakses layanan konsultasi psikologi berikut:
– Hotline Kesehatan Mental dan Pencegahan Bunuh Diri: +62 811 3855 472 (L.I.S.A).
– Lihat daftar penyedia layanan konseling online di sini.
– Lihat daftar puskesmas dan rumah sakit di sini.