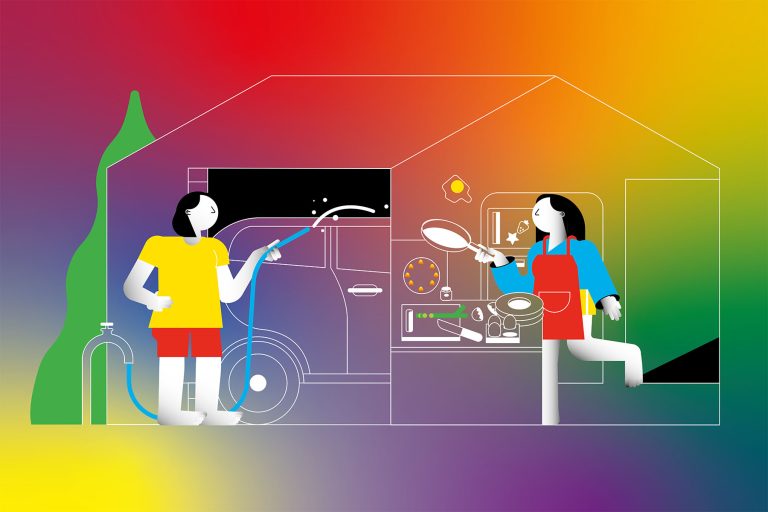“Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan,” begitu tulis penyair Joko Pinurbo dalam salah satu sajaknya dalam buku Epigram 60.
Potongan sajak ini dikutip ribuan kali dalam takarir konten media sosial, bahkan dicetak jadi baliho berukuran besar yang kondang jadi photobooth wajib di Malioboro, pusat daerah wisata Yogyakarta.
Publik menjadikannya jargon yang mewakili romantisme Yogyakarta, sebagai kota nyaman yang alih-alih tempat wisata, sudah terasa seperti rumah. Dan barangkali Yogyakarta memang menampakkan wajah seperti itu kepada publik, tapi tidak kepada Hayu (bukan nama sebenarnya).
”Sorry, ya, telat.” Hayu masuk tergopoh-gopoh ke kedai kopi tempat kami janjian, 30 menit sudah lewat dari jam seharusnya, “Tadi ketiduran pulang kerja. Mana motorku nggak ada, jadi harus nunggu dianter Pakdhe ke mana-mana.” Ia menekuk bibir.
“Lho kenapa? Lagi diservis motornya?”
“Ndak, sih. Biasa, lagi digadaikan ibu. Harusnya minggu depan wis mbalik, sih,” ia menjawab ragu.
Nada ragu itu beralasan. Pertama, ini bukan kali pertama motornya digadaikan oleh ibunya. Menurut sang ibu, menggadaikan motor adalah solusi paling cepat dan mudah jika situasi ekonomi mereka sedang sulit.
Sebagai anak tertua dan perempuan, Hayu tidak bisa menolak ide ibunya dan jika tak menawarkan solusi lain, ia tak punya. Kedua, beberapa tahun sebelumnya motornya pernah digadaikan dan berakhir dijual karena ibunya tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo.
“Aku masih trauma motorku nggak kembali, tapi ya udah mau gimana lagi?”
Penuh siasat dan mau kerja keras adalah rumus yang dipakai Hayu menjalani hidupnya yang baru berusia 20 tahun. Jika ditambah privilese dan kapital yang tepat, barangkali rumus tadi bisa membawanya ke kesuksesan usia muda, jadi kaya raya, dan punya gelar sarjana dari universitas ternama, sebagaimana gambaran ideal Gen Z yang diberikan oleh pemerintah. Riset Anissa Beta, dosen ilmu kebudayaan Universitas Melbourne, menyebut pemerintahan Jokowi sengaja menggaungkan citra ideal Gen Z ini lewat misalnya pilihan staf khususnya.
Sayangnya, nasib melempar Hayu jauh-jauh dari bayangan ideal tersebut.
Rumah Hayu hanya berjarak 500 meter dari Tugu Yogyakarta, tapi ia merasa tinggal di pusat kota tak serta merta membuat hidupnya lebih mudah. Nama kampungnya Jogoyudan, area kampung urban di pinggir Kali Code. Deretan bangunan hotel-hotel baru yang menjulang memagari kampung tempat Hayu tinggal, menyembunyikan area padat rumah-rumah yang hanya bisa dijangkau lewat gang-gang kecil.
Di rumah neneknya itu ia tinggal bersama ibu, dua adik laki-laki, dan sang nenek. “Kan jadi nggak usah mikir biaya sewa,” ujarnya.
Juni lalu Hayu menjalani operasi pengangkatan kista endometriosis pada rahimnya. “Sebenarnya udah ketahuan sejak lulus SMP empat tahun lalu. Kemarin ukurannya sudah 7 cm,” ia memegang perut bagian bawahnya. “Masak dokter kasih pilihan saya harus operasi atau menikah? Edan, pa! Ya aku langsung daftar operasi, untung pakai BPJS (Kesehatan),” tukasnya.
Seharusnya masa istirahat setelah operasi jadi waktu yang tenang, tapi Hayu justru merasa frustrasi. “Aku merasa bersalah banget bisa sampai sakit kayak gitu. Aku nggak suka nyusahin orang.”
Saat ini Hayu berbagi tanggung jawab dengan ibunya sebagai tulang punggung keluarga.
Mengenyam pendidikan di universitas setelah lulus dari SMK tak pernah jadi pilihan untuknya. Buang-buang duit. Maka saat kondisinya sakit dan ibunya kembali jadi satu-satunya sumber penghasilan, ia merasa tidak nyaman.
“Kemarin itu sebelum operasi ada cek lab bayar Rp800 ribu. Ya Allah. Bajingan tenan! Ngapa ta dadak lara ki?” Kenapa harus sakit, katanya.
Sejak Hayu kecil, ibunya bekerja di warung tenda pecel lele milik tetangga. Upah per hari ibunya Rp50 ribu, kadang tambah 1-2 ekor lele goreng yang jadi lauk favorit adik-adiknya. Dengan uang Rp50 ribu itu ibunya menghidupi lima orang di rumah. Dan menghidupi sesungguhnya tak cuma memberi makan, tapi juga semua kebutuhan lain yang kian hari kian tak murah.
Berutang atau menggadaikan barang berharga sudah jadi strategi bertahan hidup mereka sejak lama. Maka tak heran jika sebelum lulus SMK pun, Hayu telah belajar cari uang. Ia pernah jadi tukang cuci pakaian tetangganya.
“Lumayan dikasih Rp200 ribu tiap bulan. Aku anaknya mau-an kalau disuruh ini-itu sama tetangga, nggak malu karena ya ngapain pokoknya halal.” Ia tersenyum.
Hubungannya dengan sang ibu barangkali pas didefinisikan dengan istilah love-hate relationship. Ia sayang ibunya, tapi kadang lelah karena terus-terusan jadi samsak emosi ibunya yang tidak stabil. “Biasanya abis ditagih bank plecit (rentenir) terus uangnya habis, ibu marah-marahnya sama aku. ‘Kowe ora ngerti rasane dadi ibu’—(“Kamu enggak mengerti rasanya jadi ibu”),” kata Hayu. “Mana aku malu karena tetangga, kan, bisa dengar kalau Ibu teriak-teriak gitu.”
“Kadang kalau sudah judeg banget aku pingin jawab, ‘Aku mbiyen yo emoh nek lahir mung nyusahke kowe, Bu!’—(“Aku ya nggak mau lahir cuma menyusahkan kamu, Bu”), tapi nggak keluar dari mulut.”
Hayu bercerita seperti sedang bermonolog. Airmata menetes dari sudut sepasang matanya membentuk jalur mengilat di pipi. “Maaf ya aku nangis.” Ia buru-buru menyeka dengan tangan.
“Kalau di rumah aku nggak bisa nangis. Rumah nenekku itu nggak ada sekatnya, cuma satu ruangan gitu, lho. Jadi nggak ada privasi.”
“Sering nangis kenapa?”
”Takut, bingung, mikir hidupku gimana. Aku kalau lagi pingin nangis di kamar mandi, tapi favoritku nangis pas naik motor di jalan. Lega banget!”

Menolak jadi Bagian Lingkaran Setan Nikah Muda
Hidup di lingkungan padat penduduk, membuat Hayu tahu lebih banyak hal dari tetangga ketimbang orang rumah, bahkan soal asal-usul dirinya.
Dari tetangga yang senang berbagi gosip tanpa diminta, ia tahu dirinya anak hasil kehamilan di luar nikah. “Ternyata ibu masih SMP pas ketahuan hamil. Pas melahirkan aku, umurnya baru 16 tahun,” ceritanya.
Hayu menduga hal ini jadi salah satu faktor yang membuat emosi ibunya tak stabil. Dunia ibunya berhenti di masa remaja itu. “Kadang menurutku pola pikir ibuku nggak dewasa sama sekali, maunya dimengerti terus, paling benar terus. Aku yang baru 20 tahun aja bisa mikir lebih jauh. Dewasa itu emang bukan soal usia itu bener banget,” ujarnya.
Bapak dan ibu Hayu sudah pisah sejak enam tahun lalu, setelah adik kembarnya lahir. Bapaknya dulu mahasiswa rantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ngekos dekat rumah neneknya. Menanggung konsekuensi harus menikah muda, kerja tanpa keterampilan, dan hidup susah bersama, ibunya masih bisa. Tapi, saat bapak Hayu ketahuan selingkuh dengan tetangga sendiri, ibunya muntab.
“Pas aku kecil kalau bapak ibu mulai berantem aku selalu digendong tetanggaku, disuruh nonton TV sampai ketiduran di rumah.” Setelah dewasa, Hayu tahu bapaknya kerap memukul ibu. Tetangganya tak ingin Hayu kecil menyaksikan kekerasan itu.
“Dulu aku sering berdoa supaya bapak ibuku rujuk, biar aku punya keluarga utuh. Tapi sekarang aku sudah berhenti berdoa, walau jadinya aku yang kecewa tapi kayaknya emang udah bener pisah gini. Kalau bareng mereka cuma bikin sakit satu sama lain.”
Bapaknya kini mengontrak dekat rumah Hayu dan ibunya tinggal. Hanya tiga rumah jaraknya. Bapaknya ogah cari kerja, saat ini bekerja jadi kuli bangunan hanya jika mendapatkan panggilan. Hanya 1-2 kali Hayu diberi Rp100 ribu untuk jajan, selebihnya bapaknya sama sekali tak menafkahi keluarga mereka.
“Kayaknya bapak nggak mau cerai, karena takut hak asuh jatuh ke ibu dan dia malah nggak bisa ketemu aku dan adik-adik.”
Hayu kadang mengerti, punya suami yang tak berfungsi membuat tekanan hidup ibunya bertambah susah. Dua bulan terakhir ini, Hayu dilema antara sedih, marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa melihat pilihan pekerjaan baru ibunya. Tersebab warung pecel lele tempat kerja ibunya makin sepi, sang ibu mengiyakan tawaran kerja di sebuah salon spa.
“Aku nggak bisa membayangkan ibu ngapain, yang jelas ibu jadi sering pulang pagi.”
Hayu menilai keputusan ibunya itu seharusnya tidak perlu apalagi kini setelah Hayu ikut urun kebutuhan ekonomi keluarga. Tiap Hayu mengajak bicara soal ini, ibunya selalu menjawab tak punya pilihan lain untuk cari uang yang cukup untuk membahagiakan anak-anaknya.
“Padahal walau emang hidup serba kurang, bahagia itu nggak melulu soal uang. Aku kangen lho ditanya-tanya sama ibu, tapi kayaknya ibu sudah nggak bisa mikirin hal lain selain cari uang.” Ia tampak sedih.
Hayu mengamati bukan cuma ia yang punya masalah keluarga seperti itu. Faktor struktural seperti ekonomi atau kurangnya tingkat pendidikan, banyak pernikahan di usia muda, hadir di sekelilingnya.
“Ada tetanggaku yang dulu nikah muda, terus anaknya juga nikah muda, tapi keluarganya nggak ada yang beres. Aku takut banget jadi kayak orangtuaku. Makanya sampai sekarang aku nggak mau punya pacar. Iya kalau dapet yang bener, kalau nggak malah nambah beban. Masalah hidupku sudah banyak,” tukasnya.

Sama-sama Nge-mal, Kalian Belanja, Saya yang Jaga
“Masak beli celana dalam sama BH aja abis Rp2 juta? Itu sekali payment, lho! Belum kalau abis itu dia masuk ke toko lain,” Hayu berdecak-decak. “Aku nggak kebayang deh gimana orang bisa ngabisin duit sebanyak itu? Aku cari duit segitu sebulan, lho.”
Buatnya, menghabiskan uang setara upah minimum pekerja di Yogyakarta cuma buat belanja BH tidak masuk akal.
Sudah hampir setahun ini Hayu bekerja jadi sales assistant di salah satu toko retail fesyen populer di Plaza Ambarrukmo, salah satu mal terbesar di Yogyakarta. Saban hari ia berdiri selama delapan jam di sekitar rak-rak baju, berjaga jika ada pengunjung butuh bantuan.
Sebelum kerja di mal, Hayu pernah enam bulan bekerja sebagai housekeeping di Wisma MM UGM. Pekerjaan ini didapatkan setelah ia menyelesaikan program praktik kerja lapangan di tahun terakhirnya sekolah di SMK PI Ambarrukmo jurusan perhotelan. Menurut Hayu, keputusannya masuk SMK perhotelan lebih karena keadaan, saat itu cuma SMK ini yang masih ada kuota penerimaan siswa baru dengan KMS (Kartu Menuju Sejahtera).
“Aku sudah bilang ibu, ‘Kalau nggak ada uang, aku nggak sekolah nggak apa-apa.’ Tapi ternyata ada, ya udah sekolah lagi.”
“Aku nggak suka kerja housekeeping. Kerjanya ganti sprei, ngosek WC, pingin cari kerjaan lain aja,” ujarnya. Saat itu upahnya sebagai tenaga bantuan Rp70 ribu per hari.
Kini di tempat kerjanya sekarang, Hayu adalah karyawan termuda. Ia bekerja selama 6 hari dalam seminggu, dengan dua shift pilihan pagi dan malam. Alih-alih tempat hiburan, mal sudah jadi keseharian Hayu. “Mal itu ya tempat kerja aja, sih. Aku kalau cari hiburan ya nggak di mal lah.”
Ia kini sudah jadi karyawan tetap dan menerima gaji setara UMR Yogyakarta sejumlah Rp2.153.970. Setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ia menerima Rp2.050.000.
Gajinya tak cuma untuk dirinya: Rp1 juta dipakai bayar cicilan motor yang ironisnya sedang digadaikan sang ibu; Rp500 ribu diberikan ke ibu untuk keperluan rumah atau cicilan utang;
“Sisanya aku pakai bayar cicilan Shopee Paylater,” ia terkikik.
Dari layar ponselnya, Hayu menunjukkan pusat perbelanjaan dan hiburan yang biasa dan bisa ia akses. “Utang Paylater-ku masih 300-an ribu. Tapi nggak apa-apalah, kalau nggak gini aku nggak bisa nyandang (berdandan),” ujarnya sambil memamerkan sepatu Vans “premium” kesayangan yang dibelinya seharga Rp400 ribu. Kaos termahal yang dibeli dengan paylater adalah T-shirt merk VAST seharga Rp150 ribu, yang hanya dipakainya pada momen-momen spesial.
“Kadang aku pingin beli hoodie Uniqlo, tapi harganya nggak masuk akal, nggak bayangin pasti ibuku marah-marah,” ia nyengir.
“Dulu sebelum aku ambil cicilan motor, Rp1,5 juta dari gajiku selalu aku kasih ke ibu.”
Sejak punya gaji bulanan, ibunya menjadikan Hayu tumpuan finansial. Gaji Hayu selalu jadi jaminan tiap ada rentenir menagih utang atau jika ibunya sedang butuh uang.

Dengan sisa uang Rp200-300 ribu per bulan untuk dirinya sendiri, Hayu mesti bersiasat.
Ke tempat kerja, ia lebih sering bawa bekal ketimbang makan siang di warung soto atau kantin karyawan. “Temenku pernah komentar, enak banget tiap hari bawa bekal jadi uangnya utuh. Dia nggak tahu aja uangku bukan utuh, tapi nggak ada.”
Sejak kerja, Hayu tak banyak waktu bergaul. Ia juga tidak aktif di media sosial, apalagi jadi seorang tech-savvy seperti gambaran Gen Z lainnya. Ia hanya punya akun TikTok yang ia gunakan secara pasif.
Kadang-kadang saja ia nongkrong di salah satu coffee shop langganannya, tak jauh dari mal. “Kalau lagi darurat, sumpek banget aja.”
“Kadang aku minta sebat ke teman. Kalau sudah ngopi dan ngerokok, rasanya bisa lupa sama hidupku sebentar. Eh jangan bilang-bilang ibu, dia nggak tahu aku ngerokok.”
Terasing dari Imaji Kota
Selain kota wisata, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Menurut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ada 136 unit perguruan tinggi dari beberapa kategori seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ini membuat Yogyakarta jadi tujuan ribuan mahasiswa mewujudkan cita-cita setiap tahun.
Tapi, cita-cita adalah halusinasi bagi Hayu; hal yang muskil. “Dulu aku kepingin banget jadi Polwan. Sempat berdoa juga semoga dikasih jalan sama Allah, tapi makin ke sini kayaknya aku halu, ya?” Tawa di akhir ucapannya lebih bernuansa miris ketimbang lucu.
Barangkali secara tidak sadar, keinginannya jadi Polwan didorong oleh imajinya sendiri untuk jadi seorang perempuan yang punya kekuatan memberi rasa aman. Sebab rasa inilah yang absen dalam masa pertumbuhan Hayu. Ia hampir terkena pelecehan seksual oleh pihak yang seharusnya melindungi.
Kejadiannya saat ia baru lulus SMP. Saat itu ia membuka “jastip apa saja asal ada upahnya” demi uang jajan tambahan beli kuota internet. Suatu kali satpam SMP minta tolong dibelikan celana dalam, kondom, dan beberapa barang lain. Hayu yang tak curiga mengantarkan belanjaan ke sekolah yang sedang sepi.
“Dia menawarkan uang lebih kalau aku mau di-anu sama dia.” Saat itu ia datang bersama beberapa teman. “Kalau aku sendiri, kayaknya dia berani narik aku deh. Satpam bajingan emang.”
Meski tak bisa jadi Polwan, Hayu ingin bisa kuat untuk paling tidak melindungi diri sendiri dari kerentanan bertubi-tubi ini.

Meski tinggal di pusat kota, berkegiatan di hotel dan pusat perbelanjaan, Hayu nyatanya tak pernah benar-benar jadi bagian dari masyarakat yang menikmatinya. Ia mewakili gambaran dekat secara geografis tapi jauh secara akses.
Data Badan Pusat Statistik menunjukan kesenjangan ekonomi di Yogyakarta meningkat tajam sejak 2012. Sejak undang-undang keistimewaan Yogyakarta disahkan pada 2012, rasio ketimpangan tak pernah turun dari angka 0,4 dan selalu di atas angka nasional. Kecuali pada 2019, dalam periode 2015-2022, Yogyakarta hampir selalu menjadi provinsi dengan kesenjangan ekonomi tertinggi di Indonesia. Per Maret 2022, BPS mencatat Rasio Gini Yogyakarta mencapai 0,439.
Kesenjangan ini menjadi ironi mengingat status keistimewaan provinsi ini beserta triliunan rupiah dana keistimewaan yang mengucur setiap tahun. Ketika anggaran itu mengalir, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin justru semakin lebar. Orang seperti Hayu semakin jauh tertinggal di belakang.
Tahun 2019, ketika ramai gerakan “Jogja Ora Didol” yang memprotes pembangunan kawasan dan infrastruktur pariwisata oleh pemerintah daerah Yogyakarta, terutama pembangun hotel-hotel baru, hidup Hayu tetap tak tersentuh. Hari-harinya tetap berkutat di pekerjaan dan masalah keluarganya yang sudah amburadul. Area kampungnya tak ikut mengalami kekeringan seperti di kawasan lain.
“Aku nggak sempat mikirin isu begituan, maaf,” kata Hayu.
Satu-satunya hal yang ia nikmati dari pembangunan masif di sekitar rumahnya adalah Wifi gratis dari salah satu hotel yang dibangun dekat rumahnya.
“Jadi Pakdheku beli router, bisa nyambung ke Wifi hotel itu. Jadi aku bisa scrolling TikTok. Tapi, pas pandemi naik, Wifi selalu dimatikan. Hotelnya sepi kali, ya?”
Setiap kali pulang kerja, Hayu selalu langsung mengecek sambungan Wifi colongan tersebut. Di tengah penat kesehariannya, Wifi gratis dan konten TikTok bisa sedikit membuainya, membuatnya berhenti berpikir.
“Emang follow siapa di TikTok?”
“Nggak ada yang spesifik sih, siapa aja aku tonton. Hidupku itu kalau dipikir-pikir berat-e, makanya aku nggak suka mikir.”
Laporan ini adalah bagian dari serial reportase #UnderprivilegedGenZ. Serial ini didukung oleh Kawan M.