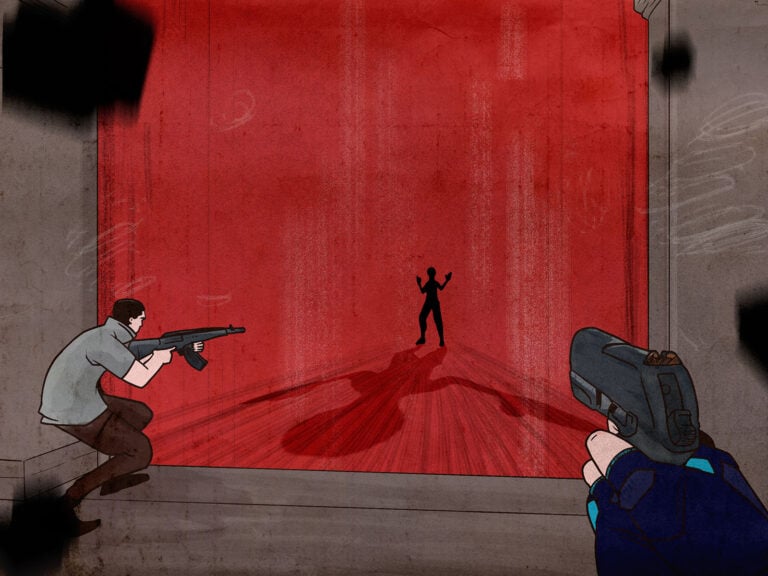Sinar matahari tidak begitu cerah tatkala saya menginjakkan kaki di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, 3 Mei 2021. Desa masih terlihat sepi, hanya ada beberapa toko kelontong yang buka, juga satu-dua mobil pengangkut sayur dan buah yang melintas melewati area dekat pintu masuk yang luasnya setara dengan lapangan sepakbola.
Di antara kesunyian itu, Zaenal berdiri dengan raut wajah yang cukup antusias. Tak lama usai saya mematikan sepeda motor, ia bergegas menghampiri dan menanyakan maksud kedatangan di Kanekes.
“Mau liburan, Bang?” tanyanya tanpa berbasa-basi. “Bisa saya antar masuk ke dalam. Kebetulan masih sepi, jadi lebih enak,” ia buru-buru melanjutkan.
Saya belum merespons sambutannya. Rasa letih masih menyelimuti sekujur tubuh. Perjalanan kurang lebih lima jam dari Jakarta dengan sepeda motor bikin badan kaku dan pegal. Terpaan debu jalan dan angin pegunungan juga bikin terkantuk-kantuk. Setelah sedikit melemaskan badan, barulah saya mengatakan tujuan pagi itu.
Zaenal mengangguk paham seraya memberi tahu bahwa sosok yang biasa bertugas melayani kepentingan jurnalis tengah mengikuti sesi pertemuan dengan warga dan tokoh desa. Saya pun diminta menunggu.
“Mari saya antar ke dalam dulu, biar nanti bisa istirahat sebentar sambil ngopi,” ajaknya ramah.
Zaenal bekerja sebagai pemandu wisata, usianya 30-an tahun. Ia lahir dan besar di Desa Kanekes, sekaligus menjadi bagian dari masyarakat adat Baduy Luar, yang menjadi tujuan kedatangan saya pagi itu. Langkah kakinya begitu lincah melewati satu demi satu tanjakan, menuju tempat peristirahatan, sementara saya cukup kerepotan mengatur napas.
Sekira 15 menit berjalan kaki, kami akhirnya tiba di tujuan. Pemandangan begitu asri. Angin berhembus tak terlalu kencang, membikin daun-daun pepohonan mengeluarkan bunyi yang meneduhkan. Tepat di depan saya, belasan warga tengah berkumpul di balai adat. Sebagian bercengkerama, sebagian lagi tak henti-hentinya menyeruput kopi dan mengisap batang rokok.

Pandemi yang memukul Indonesia selama setahun lebih membuat saya terbiasa menyaksikan rutinitas manusia menggunakan masker. Tapi, di balai adat itu, yang tersaji justru kebalikannya: masker tak hadir di tengah masyarakat. Saya cukup tertegun, dan sejurus kemudian melontarkan pertanyaan kepada Zaenal, yang juga tak mengenakan masker sepanjang kami bersua.
“Kenapa nggak pada pakai masker, Bang?” kata saya. “Wah, di sini, mah, enggak ada Covid-19. Masih nol sejak tahun kemarin. Makanya warga pada biasa aja,” ia menjawab.Click To TweetAntisipasi adalah Kunci
Sembari beristirahat, saya menunggu Jaro Saija, salah satu jaro di Kanekes, untuk berbincang-bincang. Jaro merupakan sebutan untuk ketua masyarakat dalam ranah formal bagi masyarakat Baduy.
Secara umum kelompok masyarakat adat Baduy terbagi menjadi dua, yakni Baduy Luar dan Baduy Dalam. Baduy Luar merupakan orang Sunda asli yang mendiami kawasan adat Kanekes, sebuah wilayah seluas lima ribu hektar di selatan Banten yang dikelilingi bukit dan lembah. Selain Baduy Luar, ada pula Baduy Dalam yang menempati daerah Kanekes.
Nama “Baduy” memiliki riwayat historis yang panjang. Judistira Garna dalam Masyarakat Baduy dan Kebudayaannya (1985) menulis bahwa sebutan “Baduy” diyakini terkait dengan nama Sungai Cibaduy atau Gunung Baduy. Dahulu, masyarakat setempat lebih memilih menyebut dirinya sebagai “urang” atau Orang Kanekes. Nama “Baduy” sendiri, mulanya, cenderung tidak disukai lantaran kerap dikaitkan oleh suku nomaden di Jazirah Arab: Bedouin—bisa juga Bedu atau Badawi.
Pemerintahan dan kehidupan adat Baduy dijalankan oleh Kapuunan sebagai lembaga adat tertinggi. Kapuunan terdiri dari tiga puun (pemimpin adat) yang masing-masing berkedudukan di tiga kampung Baduy Dalam—Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Masing-masing puun memiliki tugas yang khas. Puun Cikeusik bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan agama, pengadilan adat, dan upacara adat. Puun Cikertawana mengurus perihal kesejahteraan dan keamanan warga. Sementara Puun Cibeo mengurus perihal administrasi dan tamu (wisatawan) yang berkunjung ke Baduy.
Para puun menjalankan tugasnya dengan dibantu beberapa jaro yang merupakan ketua masyarakat dalam ranah formal. Para jaro umumnya berdiam di kampung-kampung Baduy Luar. Mereka bertindak sebagai wakil masyarakatnya dan penghubung dengan puun. Para jaro pun punya beberapa anak buah seperti carik (wakil pemerintah dan berasal dari luar Baduy), pangiwa, dan polisi desa.
Pada masa pandemi seperti sekarang ini, para jaro ini cukup sibuk. Saya pun baru berkesempatan ngobrol dengan Jaro Saija ketika jam sudah menunjukkan pukul satu siang. Raut wajahnya terlihat lelah setelah menghadiri pertemuan dengan warga, yang durasinya mencapai dua jam lebih. Hal yang dibicarakan seputar persiapan menyambut lockdown di masa libur Hari Raya Idul Fitri, pada minggu kedua Mei kemarin.
Agenda soal Covid-19 memang menjadi salah satu kesibukan yang mesti dijalani Jaro Saija. Tugasnya sebagai jaro bertambah kompleks, sebab ia harus memastikan keselamatan penduduk, utamanya mereka yang berada di kawasan Baduy Luar, dari ancaman pandemi. Ia bersyukur, sejauh ini tugasnya berjalan dengan baik.
“Alhamdulilah di Desa Kanekes 0 persen Covid-19,” katanya dengan cukup bangga.
Angka 0 kasus ini bukan klaim sepihak semata. Data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Banten, per 16 Mei 2020, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak terdapat 148 orang yang masih dirawat, 3.241 sembuh, serta 63 meninggal. Di antara data yang berhasil dikumpulkan, menurut Bachtiar, Kasi Imunisasi, Surveilans, dan Krisis Kesehatan Dinkes Lebak, tidak ada yang berasal dari Desa Kanekes, tempat Baduy tercatat secara administratif.
“Sebenarnya yang tahu soal itu adalah orang lapangan, mereka yang berada di Puskesmas Ciboleger atau Cisimeut. Yang tahu mereka. Tapi, berdasarkan data yang masuk ke kami, memang belum ada Covid-19,” ungkapnya, saat saya konfirmasi.
Pendapat serupa nyatanya keluar dari Iton Rustanti, Ketua Satgas Covid Puskesmas Cisimeut, yang berhubungan langsung dengan masyarakat Kanekes. Menurutnya, setelah melakukan beberapa kali tes, dengan bermacam jenis, dari rapid test hingga PCR, hasil yang didapat di kalangan masyarakat Baduy memang negatif.
“Pada bulan Oktober atau November, kami melakukan tes lagi, di jalur keluar-masuk sampai wilayah Baduy, dan negatif semua,” akunya.
Iton menjelaskan kunci pencapaian tersebut terletak pada pola komunikasi yang terbangun baik antara tenaga kesehatan dengan masyarakat Baduy, bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak. Begitu pandemi muncul, Iton menegaskan, masyarakat dan tenaga kesehatan di sekitar kawasan Baduy sudah siap menghadapinya.
“Kuncinya kita memaksimalkan penjelasan soal Covid. Meyakinkan mereka itu sulit ketimbang kita. Mereka lebih susah karena faktor pendidikan,” tuturnya.
“Susahnya adalah menjelaskan soal Covid karena belum banyak yang paham. Ini penyakit internasional. Makanya kami lari ke kepala desa, supaya bisa bantu kasih pemahaman, selain juga ke para guide,” tambah Iton.
Pola komunikasi ini didukung pula dengan inisiatif masyarakat Baduy Luar sendiri yang memang sejak awal tak ingin terlambat merespons kemunculan Covid.
Jaro Saija menyebut bahwa ketika Indonesia pertama kali kedatangan kasus positif, dirinya segera melakukan antisipasi dengan memberlakukan karantina wilayah, menjaga perbatasan, serta membikin aliran air di sekitar luar kawasan Baduy yang ditujukan untuk mencegah orang-orang masuk sembarangan.Click To TweetItu dari sisi teknis. Dalam konteks pendekatan kepada warga adat yang lain, Jaro Saija mengaku terus melakukan sosialisasi secara intensif, menekankan betapa pentingnya menjaga diri dari pagebluk. Tak sekali ia mengalami penolakan dari warga yang tak percaya Covid-19. Akan tetapi, ia tak memaksakan kehendak, asalkan yang bersangkutan tak bikin orang-orang di sekitarnya terganggu.
“Kalau nggak ada pelanggaran, harus bisa mengayomi. Kecuali ada pelanggaran adat dan negara, maka harus ditegaskan. [Kalau] dibiarkan saja jadinya kurang ajar,” jawabnya.
Sinergitas antara aturan adat dan negara jadi barang penting ketika membicarakan penanggulangan wabah di Baduy Luar. Jaro Saija menjelaskan bahwa selama ini keduanya mampu berjalan beriringan, tanpa mengangkangi satu sama lain. Aturan negara diimplementasikan melalui pemberlakuan pembatasan sosial, sementara aturan adat wajahnya bisa dilihat dengan pikukuh.
Dalam adat Baduy, pikukuh kurang lebih punya fungsi sebagai pedoman hidup. Salah satu yang populer yakni: Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, berarti bahwa “gunung jangan diratakan, lingkungan jangan dirusak.” Sedangkan dalam konteks pandemi, pikukuh yang dipegang adalah bahwa setiap penyakit (sasalan) pasti ada obatnya.
“Kuncinya adalah bisa atau tidak bisa, percaya yang dipegang sama hati sendiri. Semua sakit ada obatnya. Sakit kepala, sakit perut, ada mantra-mantranya. Itu bisa dibeli. Pakai apa? Puasa,” Jaro Saija menjelaskan.
Kesuksesan Baduy membendung Covid-19 masuk Kanekes ini berbanding terbalik dengan sejumlah masyarakat adat lainnya. Penelitian yang disusun Ahmed Goha dkk. berjudul “Indigenous People and the Covid-19 Pandemic: The Tip of an Iceberg of Social and Economic Inequities” menyebutkan bahwa infeksi Covid-19 telah menyerang komunitas adat di Brasil, Peru, AS, Kanada, sampai Australia.
Di New Mexico, ambil contoh, sebanyak 57 persen dari kasus Covid-19 dan 50 persen kematian muncul di masyarakat adat. Lalu di Brasil, penyebaran virus sampai pula di Manaus, ibu kota Amazonas, serta turut menyerang kelompok adat Yanomami.
Tingkat penularan virus di masyarakat adat empat kali lebih tinggi ketimbang populasi pada umumnya, masih mengutip penelitian Ahmed dkk. Ini tak terjadi dalam konteks Covid-19 belaka. Pada rentang 2009 hingga 2010, tatkala pandemi H1N1 menyerang, misalnya, masyarakat adat punya potensi tertular virus empat kali lebih tinggi dari penduduk biasa, selain juga risiko penyakit parah dan kematian yang sama tingginya—sekitar tiga hingga enam kali lipat.
Indonesia tak luput dari kemungkinan terburuk. Sekjen AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), organisasi swadaya yang fokus pada isu masyarakat adat di Indonesia, membawahi sekitar 2.000-an lebih komunitas dengan total anggota sebanyak 17 juta individu, Rukka Sombolinggi, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan langkah mitigasi sejak pandemi muncul pertama kali di Indonesia.
“Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown, AMAN sudah merespons lebih dulu dengan lockdown di wilayah adat. Pertama, [kami] sudah tahu waktu itu bukan situasi sembarangan. Kedua, masyarakat adat punya memori pandemi di masa lalu,” ujarnya kepada saya.
Bagi Rukka, memori masa lalu itu terjadi kala flu Spanyol tiba di Indonesia. Di Toraja, tempat kelahirannya, flu Spanyol membuat hampir sepertiga dari jumlah penduduk meninggal dunia. Mayat bergeletakan, sebagian besar dikubur tanpa prosesi adat sebagaimana mestinya. Kematian adalah kawan karib yang dijumpai sehari-hari.
“Bahkan, ada yang habis menguburkan jenazah, [kemudian] meninggal,” paparnya. “Cerita ini selalu diceritakan dari generasi ke generasi.”
Faktor Pendukung
Pencapaian nol kasus Covid-19 sepintas mustahil terwujud, lebih-lebih jika melihat bagaimana realitas di Indonesia saat ini, di mana mitigasi selalu terlambat, pencatatan data yang amburadul, hingga inkonsistensi kebijakan pemerintah.
Semua berkelindan, membentuk satu masalah besar yang menempatkan Indonesia pada posisi—serta situasi—serba rentan: mulai dari ancaman kolapsnya sistem kesehatan hingga gelombang kedua yang mengerikan, seperti halnya yang melanda India.
“Kita sekarang berada di level parah, yakni community transmission. Penyebaran virus ada di tingkat komunitas, sulit dilacak, dan itu bukan kasus impor. Dengan situasi seperti itu, sulit rasanya bilang bahwa satu daerah, apalagi dengan kemampuan tes yang sedikit, disebut atau masuk dalam zonasi hijau. Indikatornya belum banyak terpenuhi, mulai dari tes, pelacakan, semuanya segitu-gitu aja,” tutur Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, think tank kesehatan yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah.
Meski begitu, Olivia bilang, kemungkinan untuk mencapai nol kasus di suatu daerah, seperti Kanekes, masih terbuka lebar, asalkan “sejak awal tidak pernah terpapar pandemi.”
“Itu masih memungkinkan. Sudah ada studi yang menyebut bahwa infeksi rendah ada di masyarakat rural. Ini berhubungan dengan exposure hingga kepadatan penduduk,” imbuhnya.
Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, bilang terdapat faktor lain yang cukup krusial yang membuat Baduy bisa berhasil membendung Covid-19 masuk ke desa mereka.
“Mereka diuntungkan karena mereka tinggal di lokasi di mana aktivitas outdoor jauh lebih sering dilakukan. Satu fakta yang mendukung berisiko [terpapar virus] rendah. Aktivitas outdoor ini ditambah, namanya masyarakat adat, dari sisi jumlah penduduk tentu jauh lebih sedikit yang mobile,” ujar Dicky kepada saya.
“Sementara dari sisi kualitas ventilasi udara di kampung atau pedesaan jauh lebih bagus. Ini tentu sangat berdampak mengingat Covid itu airbone disease, penyakit yang ditularkan lewat udara,” Dicky menambahkan.
Selain itu, mobilitas masyarakat Baduy tak kelewat tinggi, tak seperti orang-orang yang tinggal di kawasan dengan setting perkotaan. Ditambah, yang kerap mereka jumpai pun juga orang-orang dengan mobilitas rendah.
“Sejauh-jauhnya mereka beraktivitas, ya, jalan kaki, apalagi Suku Baduy. Artinya, secara aktivitas atau mobilitas, mereka nggak seperti orang kota, yang bisa pergi ke Yogyakarta, Jakarta, atau Singapura,” terang Dicky.
“Beda lagi dengan orang di kota. Di bandara itu, misalnya, ada orang dengan mobilitas tinggi dari mana-mana. Potensi memaparkannya [virus] besar.”
Pencapaian di kawasan Baduy tentu memantik pertanyaan: dapatkan kondisi serupa, nol kasus, muncul di kawasan perkotaan? Hampir semua narasumber yang saya hubungi, yang selama ini fokus pada isu penanganan pandemi, memiliki argumen yang senada: nyaris tidak bisa.
“Dengan kepadatan di Jakarta, lockdown lokal sangat sulit. Jalan kaki sedikit, misalnya, sudah nyeberang ke RW sebelah. Sulit dilakukan, kecuali kalau memang lockdown semua sekaligus,” ungkap Olivia.
Sementara Dicky mengatakan bahwa kesulitan penerapan itu turut disumbang faktor perbedaan pola perilaku. Masyarakat di lingkungan perkotaan jauh lebih aktif, punya durasi interaksi lebih panjang, serta kebanyakan berada pada tempat-tempat indoor.
Meski Rentan Tetap Ada Solusi
Pandemi membikin semua aspek kehidupan menjadi rentan, tak terkecuali buat masyarakat Baduy. Bagi masyarakat Baduy Luar, pandemi meningkatkan kerentanan ekonomi mereka lantaran sektor pariwisata benar-benar menurun.
Arif, seorang pemandu wisata lokal di Kanekes, bilang sektor pariwisata benar-benar susah pada beberapa bulan awal pandemi. Nyaris tak ada yang berkunjung.
“Pokoknya selama wilayah dikarantina, pariwisata ikut turun,” ujarnya.
Ini pun berdampak pada penghasilan beberapa warga. Intan misalnya, pemudi Baduy yang bekerja sebagai penenun merasakan bagaimana kain tenunnya jadi mengalami penurunan penjualan. Ia termasuk beruntung karena punya beberapa langganan yang rutin membeli hasil tenunnya.
“Beberapa dijual ke langganan, walaupun nggak sebanyak dulu. Tapi, untungnya masih ada pemasukan,” katanya.
Intan sadar, memaksakan membuka pariwisata juga tidak baik. Ia dan warga lainnya takut bila orang tetap keluar masuk seperti biasa, wabah bakal mudah menular. “Apalagi banyak anak kecil dan orang tua di sini. Kalau nggak aman, jangan dulu,” kata Intan.Click To TweetMeski sektor pariwisata jadi turun, namun itu tidak banyak berpengaruh pada kehidupan masyarakat Baduy. Buat mereka sektor pariwisata hanya penunjang, bukan yang utama. Pekerjaan utama mereka adalah bertani.
Aji, warga Baduy Luar bilang dampak yang paling terasa dari pandemi ini adalah kampung menjadi lebih sepi. Sehari-hari ia pun tetap beraktivitas seperti biasa, pergi ke ladang setiap hari. Dari hasil ladang ini ia menggantungkan hidup.
“Mungkin sepi aja di sini, lainnya nggak pengaruh. Orang-orang di sini juga pada sehat,” katanya.
Urusan pangan di masa pandemi, masyarakat Baduy tidak terlalu khawatir. Mereka memproduksi pangan untuk komunitas mereka sendiri, tanpa bergantung pada pasar. Misalnya beras, mereka memiliki ladang padi sendiri yang hasilnya memang untuk kebutuhan sendiri dan tidak dijual. Hasil bumi selain padi biasanya mereka jual, tapi utamanya selalu buat kebutuhan mereka sendiri lebih dulu.
Masing-masing keluarga juga punya stok kebutuhan pangan yang mereka simpan khusus bila ada kondisi darurat, misalnya bencana alam atau pada masa paceklik. Mereka menyimpan gabah kering di tempat khusus yang bisa bertahan hingga beberapa tahun.
“Orang Baduy itu menggerakan kerja dengan bertani. Itu pendapatannya di situ. Utamakan bertani. Kalau kurang baru pemasukan dari kerajinan,” terang Jaro Saija.
Masalahnya, masyarakat adat tetap rentan sekalipun aspek ekonomi—mungkin—sudah mendapati solusinya. Dalam kasus Baduy Luar, kerentanan tersebut bisa dilihat melalui, yang pertama, akses ke fasilitas kesehatan.
“Sebetulnya dari sisi kerentanan kurang lebih sama dengan mereka yang tinggal dengan setting kawasan urban. Persoalan fasilitas kesehatan itu yang menambah kerentanan [masyarakat adat],” ucap Irma Hidayana dari LaporCovid-19, kanal laporan warga (citizen reporting platform) yang digunakan sebagai tempat berbagi informasi mengenai kejadian terkait Covid-19 namun luput dari jangkauan pemerintah.
“Kemudian, penting untuk dicek, apakah fasilitas kesehatannya terjangkau? Jadi, kalau ada keparahan, kasus terkonfirmasi, segera bisa ditolong. Kalau ada puskesmas, atau RS yang punya alat lebih lengkap dengan jarak agak dekat, nggak masalah. Kalau jauh, agak repot,” Irma menambahkan.
Yang menjadi problem ialah jarak antara Baduy Luar dengan rumah sakit terdekat, yang berstatus rujukan Covid-19, RS Kartini, menurut informasi dari Iton, mesti ditempuh sepanjang kurang lebih 30 km. Ini belum menghitung kondisi medan yang naik-turun di antara lembah dan perbukitan.
Berbicara soal akses fasilitas kesehatan tak bisa dimungkiri juga melibatkan persediaan obat-obatan. Kendati masyarakat Baduy meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya, namun hal tersebut tak cukup bikin mereka aman, demikian ujar Herry Yogaswara, peneliti ekologi-manusia dari Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) LIPI.
“Anggapan itu muncul karena mereka terbiasa mengobati berdasarkan sumber daya lokal, baik itu tanaman atau perilaku tertentu. Persoalannya, hal tersebut tidak berarti bikin mereka aman. Karena apa yang mereka katakan, mengenai itu, didasarkan pada pengalaman mereka dalam menghadapi situasi yang lalu. Hal-hal baru, seperti Covid-19, tentu belum ada obat yang ampuh. Covid beda, variannya beda,” ujar Herry.
Sedangkan kerentanan berikutnya, dapat ditinjau dari bagaimana penduduk adat Baduy tinggal. Dalam satu rumah, biasanya, dihuni lebih dari lima orang. Situasi berkerumun ini jelas membuka peluang untuk terciptanya klaster baru. Sekali virus tiba di kawasan Baduy, maka penyebarannya bisa lebih cepat.

“Mereka itu, kan, kolektifnya tinggi. Mereka melakukan banyak hal bersama-sama. Sejauh interaksi itu masih terjadi, maka masih punya peluang tertular. Covid-19 ini airbone disease. Kita sakit, ngobrol aja, maka keluarga bisa terjangkit. Apalagi kondisinya ada di dalam ruangan,” tutur Irma.
Penelitian Ahmed Goha dkk. menyebutkan bahwa walaupun posisi masyarakat adat rentan di masa pandemi, jalan untuk menghindarkan mereka dari bencana yang lebih besar bukannya tidak ada. Hasil riset Ahmed dkk. menerangkan pemerintah bisa meningkatkan mitigasi dan pengawasan. Selain itu, membatasi pergerakan manusia juga wajib dilakukan, di samping memastikan akses ke fasilitas kesehatan tak terganggu.
Rencana di atas memang terdengar menjanjikan, bila implementasinya juga tepat sasaran serta ditempuh secara efektif. Persoalannya, di Indonesia, kenyataan soal masyarakat adat jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Pandemi bukan satu-satunya masalah yang hadir di tengah-tengah mereka. Sebelum pandemi, masyarakat mesti berhadapan dengan konflik lahan, geliat pembangunan yang eksploitatif, hingga berbagai beleid hukum—UU Cipta Kerja dan UU Minerba—yang pro-pebisnis. Sengkarut itu lantas menempatkan masyarakat adat pada posisi yang rentan, dan pandemi hanya kian memperburuknya.
“Namanya daya lenting itu, kan, seperti karet: punya daya tahan maksimal. Yang terjadi sekarang ini [pandemi] ibarat menghadapi benda baru dari luar dan tidak dikenal. Cara menghadapinya, misalnya, ada empat bentuk. Masalahnya, empat bentuk itu tidak lagi terpenuhi oleh alam. Kayu ditebang, perusahaan sawit di mana-mana. Tidak mungkin efektif lagi. Prasyaratnya sudah tidak ada,” tegas Rukka.
Pencapaian nol kasus Covid-19 yang muncul di Baduy menegaskan bahwa masyarakat adat, sejauh ini, masih mampu bertahan. Yang belum—dan sepertinya sulit—untuk dijawab: bertahan sampai kapan?
Reporter Project Multatuli sudah melakukan swab antigen sehari sebelum ke Baduy dan sudah mendapat vaksinasi lengkap Covid-19.
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportasi #MasyarakatAdat dan Lingkungan Hidup.