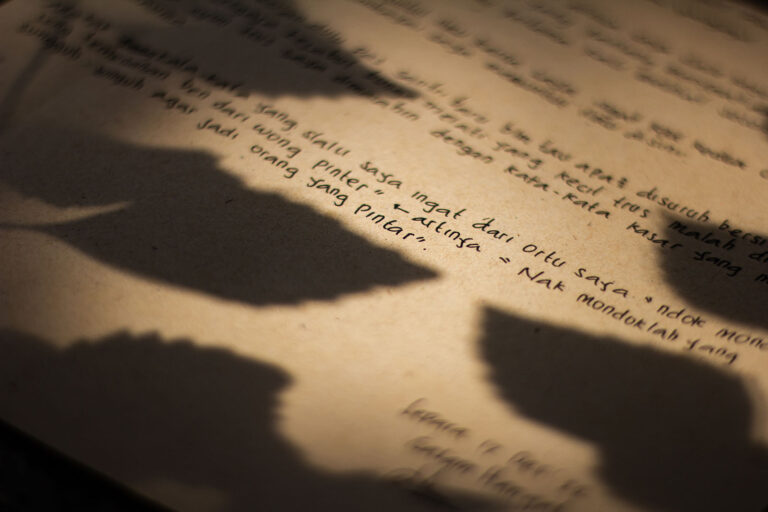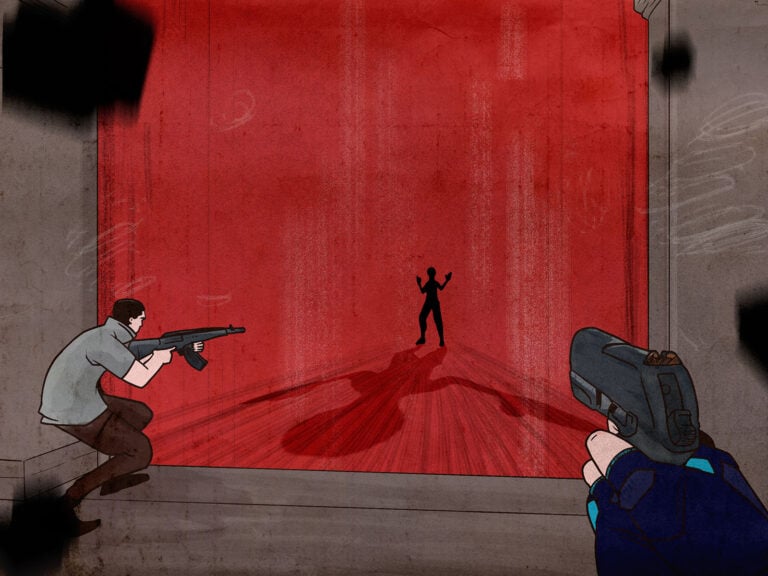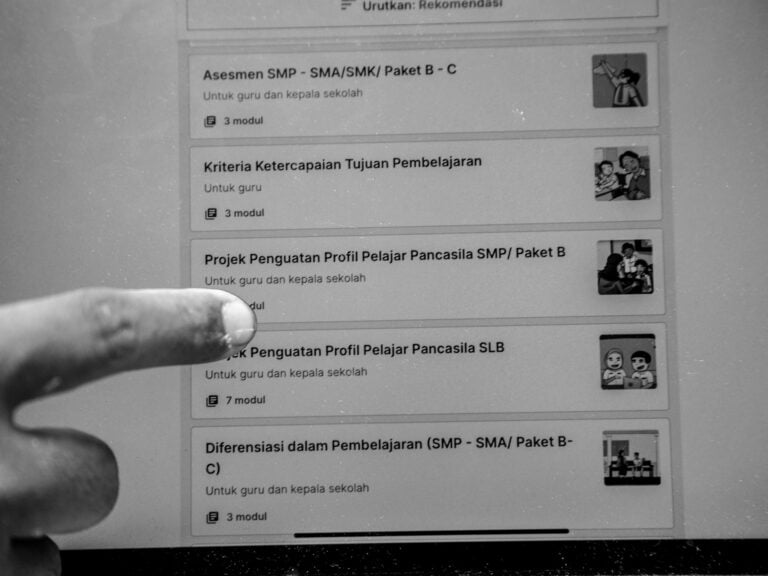Kebijakan berbasis bukti merupakan standar emas dalam tugas advokasi, apalagi bagi seorang peneliti. Kebijakan yang tidak didukung bukti kerap dianggap sebagai kebijakan yang gagal.
Kebijakan yang mengandalkan bukti tentu lebih baik dibandingkan kebijakan yang sekadar didorong kepentingan penguasa.
Namun kebijakan berbasis bukti tidak selamanya ideal.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan menyebabkan pembuatan kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok marginal.
Kekuasaan menentukan bukti yang dianggap valid
Klaim bahwa bukti layak dianggap valid atau tidak berkaitan erat dengan kekuasaan.
Bukti dari lembaga besar yang didominasi oleh peneliti level global kerap dianggap lebih mudah dipercaya dibanding bukti dari lembaga akar rumput yang sebenarnya lebih dekat dengan masyarakat.
Misalnya, negara-negara di dunia sering menggunakan indeks kemudahan berbisnis keluaran Bank Dunia sebagai landasan untuk mempermudah birokrasi.
Di Indonesia, salah satu pendorong pengembangan Undang-Undang (UU) omnibus Cipta Kerja adalah performa buruk Indonesia dalam indeks itu. UU Cipta Kerja kemudian tetap dibuat meski analisis lain menunjukkan bahwa kebijakan itu mengancam banyak kelompok, khususnya kelompok buruh.
Tahun ini, Bank Dunia menghentikan publikasi indeks itu karena isu manipulasi data. Analisis lembaga besar belum tentu bebas dari masalah.
Selain itu, kesamaan kepentingan lembaga dan kekuasaan juga membuat bukti-bukti dari lembaga yang dekat dengan kekuasaan cenderung bisa dianggap lebih benar dibandingkan bukti yang lain.
Ini rentan membuat lembaga riset dipolitisasi untuk menyediakan pembenaran atas praktik-praktik yang hanya menguntungkan kekuasaan.
Di samping lembaga riset, jenis riset juga kerap mempengaruhi bukti mana yang dianggap lebih valid.
Studi kuantitatif sering dianggap lebih saintifik dibandingkan studi kualitatif. Uji acak terkontrol (randomised controlled trial atau RCT) sering disebut sebagai standar emas dalam evaluasi dampak, termasuk dampak kebijakan. Pendekatan ini mengukur secara kuantitatif seberapa efektif suatu kebijakan atau intervensi dengan membandingkan performa kelompok intervensi dengan kelompok non-intervensi, yang keduanya dipilih secara acak.
Kebijakan dianggap efektif jika performa kelompok intervensi – secara kuantitatif – lebih baik dibandingkan kelompok kontrol.
Penganakemasan riset kuantitatif erat kaitannya dengan dinamika kuasa dan ketimpangan gender.
Riset kualitatif dengan sampel terbatas yang lebih banyak dilakukan perempuan kerap dianggap lebih feminim, kurang tepercaya, dan tidak solid dibandingkan studi kuantitatif yang didominasi oleh laki-laki.
Bukti sering kali bersifat kontekstual
Satu kebijakan atau program bisa terbukti efektif di daerah tertentu, namun ternyata gagal di konteks lain.
Di bidang psikologi, fenomena ini kerap dinamakan krisis replikasi. Misalnya, psikolog Carol Dweck asal Amerika Serikat (AS) membuktikan pentingnya pola pikir berkembang. Temuannya menunjukkan bahwa pelajar yang memandang bahwa intelegensi bisa dikembangkan cenderung akan berusaha lebih banyak sehingga bisa lebih sukses dibandingkan mereka yang memandang bahwa intelegensi bersifat permanen.
Sayangnya, intervensi pola pikir yang dilakukan di sekolah publik di Argentina tidak membuktikan hal yang sama. Pola pikir berkembang tidak berpengaruh pada sikap belajar dan performa akademis siswa di sana.
Di dunia pendidikan, hasil belajar kerap digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah kebijakan terbukti efektif atau tidak.
Meski memperbaiki kualitas pendidikan itu penting, kita perlu memahami bahwa tidak semua kebijakan pendidikan (harus) berorientasi pada hasil belajar.
Kebijakan zonasi yang membatasi seleksi nilai dalam penerimaan siswa baru belum tentu berhasil meningkatkan hasil belajar. Namun, temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil membuka akses anak-anak marginal ke sekolah negeri gratis.
Menghapus kebijakan zonasi hanya karena dianggap tidak efektif meningkatkan hasil belajar siswa akan berpotensi membatasi akses pendidikan anak-anak kelompok ekonomi menengah-bawah.
Sebaliknya, kebijakan yang berhasil meningkatkan hasil belajar siswa belum tentu tanpa problem.
Pelibatan orang tua dalam pendidikan sering dianggap dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meski tidak sedikit juga bukti yang membantahnya.
Kebijakan ini belum tentu layak diperluas karena adanya isu ketimpangan gender dalam tugas-tugas pendampingan belajar.
Pergeseran tanggung jawab sekolah ke orang tua juga berpotensi menstigmatisasi keluarga berpenghasilan rendah, yang meski peduli pada pendidikan anaknya tapi menghadapi banyak tantangan untuk membantu anak belajar.
Pengembangan kebijakan berbasis bukti cenderung eksklusif
Idealnya, kebijakan dibuat untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk sebagian elit.
Oleh karena itu, pengembangan kebijakan perlu mempertimbangkan aspirasi semua kelompok – termasuk kelompok marginal – terlepas mereka punya latar belakang sebagai peneliti atau tidak.
Semata menggunakan bukti sebagai landasan kebijakan bisa mengancam proses yang demokratis dalam pengembangan kebijakan.
Dalam demokrasi, setiap warga punya suara yang sama di mata hukum dan negara, termasuk dalam pembuatan kebijakan.
Sayangnya, bukti umumnya dimonopoli oleh peneliti, yang dominan berlatar kelas menengah.
Ketimpangan pendidikan serta terbatasnya mobilitas sosial di Indonesia membuat orang dari kelompok marginal sulit menjadi peneliti yang biasanya membutuhkan pendidikan tinggi.
Mendorong kebijakan berbasis bukti memberikan ruang penting pada peneliti menyampaikan suara, namun di sisi lain juga rentan mengabaikan suara kelompok marginal.
Sebuah studi menunjukkan bahwa elit kelas menengah cenderung lebih sering merepresentasikan kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan kelompok marginal.
Latar belakang peneliti yang umumnya adalah kelompok terdidik juga cenderung membuat mereka mudah menstigma kelompok lain yang pendidikannya lebih terbatas.
Dalam bukunya “The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good”, akademisi Harvard University Michael Sandel menjelaskan bahwa eksklusivitas dalam pengembangan kebijakan yang umumnya dilakukan sebagian kecil elit cenderung membuat kelompok non elit antipati pada negara. Ia menganggap hal ini juga berkontribusi pada populisme di AS, termasuk kemenangan Donald Trump.
Berbasis bukti saja tidak cukup, kebijakan harus berpihak
Penelitian memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah mendorong kebijakan yang lebih baik. Untuk kepentingan ini, kita yang berprofesi sebagai peneliti, penting untuk terus menggali bukti-bukti terkait efektivitas suatu kebijakan atau intervensi.
Pengetahuan ini harus disebarluaskan ke publik sebagai upaya untuk mendemokratisasi pengetahuan.
Dengan begini, pengetahuan tidak saja dimiliki oleh kelompok berpendidikan yang punya akses lebih memadai ke aktivitas riset, buku, hasil penelitian, termasuk ke lingkar kekuasaan.
Sebuah studi tentang produk pengetahuan Bank Dunia menunjukkan bahwa 31% di antaranya tidak pernah diunduh dan 87% tidak pernah dikutip. Ini tidak saja menggambarkan penggunaan sumber daya yang kurang efisien tapi juga betapa pengetahuan sulit diakses publik.
The Conversation Indonesia merupakan salah satu media tempat peneliti dapat membagikan hasil riset dan analisisnya kepada awam. Namun, perlu diingat bahwa media ini juga hanya menyediakan akses berbagi riset ke peneliti yang, seperti sudah saya sebut di atas, didominasi oleh kelas menengah.
Selanjutnya, peneliti perlu lebih banyak memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini kurang terdengar, terutama dari kelompok marginal, dalam penelitiannya.
Usaha yang dilakukan oleh Project Multatuli, sebuah platform yang mengusung keberpihakan pada kelompok rentan, dapat menjadi contoh. Di sana, peneliti dapat bekerja sama dengan media popular dan kelompok akar rumput untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan sistem dari bawah (bottom-up) yang lebih berpihak pada masyarakat umum.
Kebijakan berbasis bukti tentu lebih baik dibandingkan kebijakan tanpa bukti. Namun itu saja tidak cukup. Pengembangan kebijakan harus berbasis bukti dan mengikutsertakan suara kelompok rentan.![]()
Senza Arsendy, Research and Learning Specialist, Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.