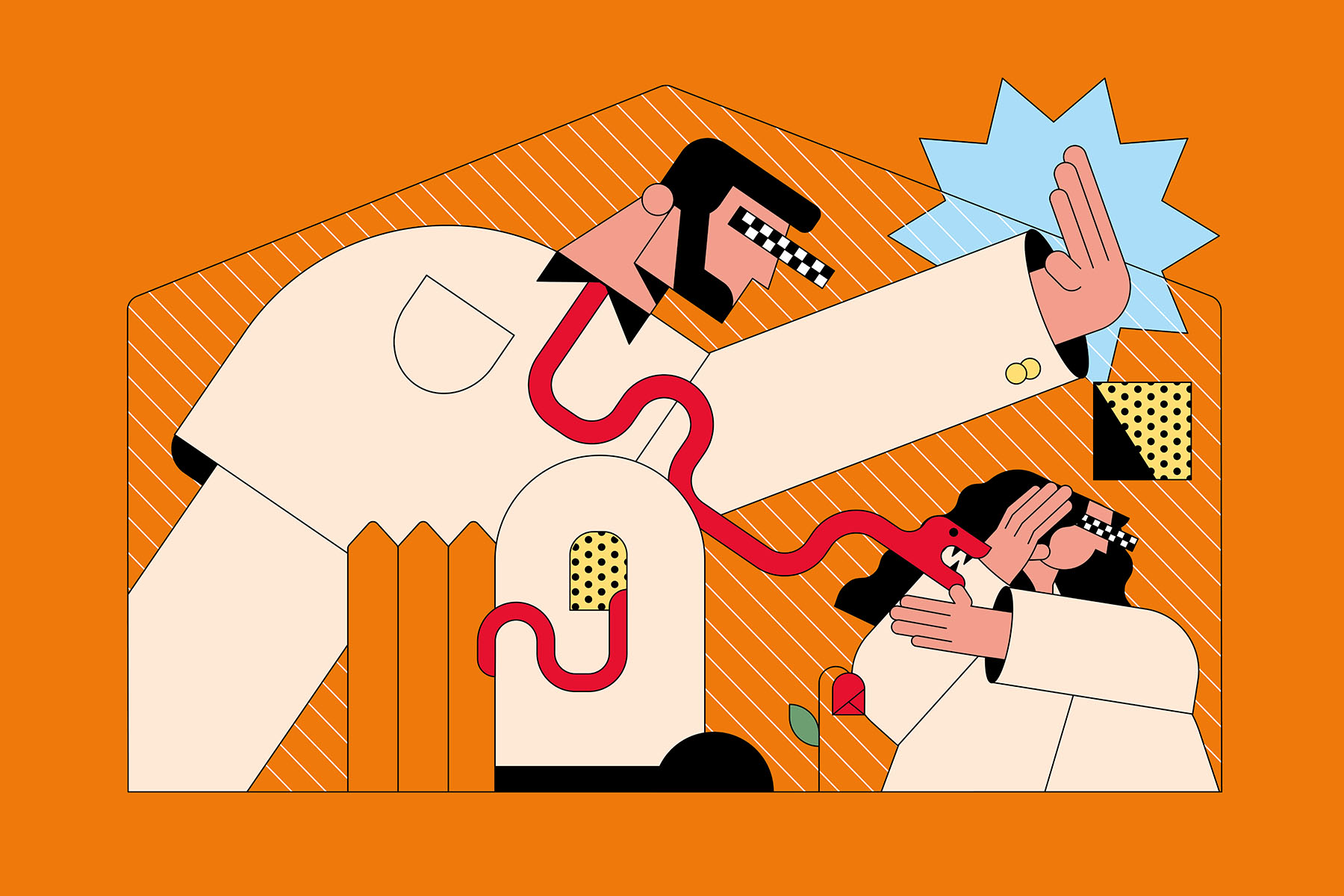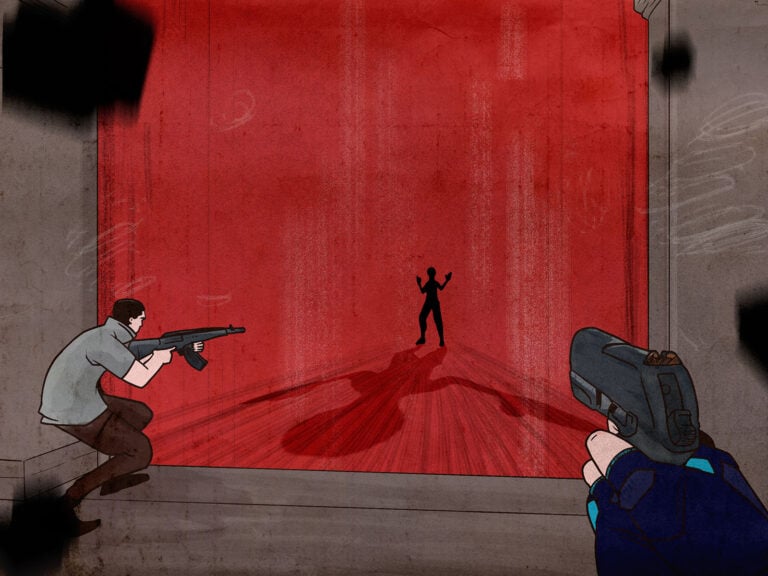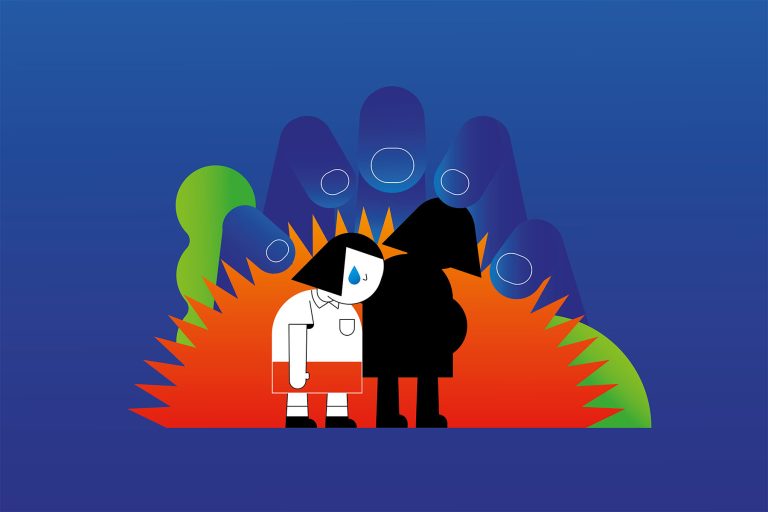Butuh waktu nyaris dua bulan bagi Sukma hingga ia berani keluar dari rumah. Butuh waktu hingga dua tahun, dan masih berjalan, bagi Sukma untuk bisa melihat laki-laki yang memegang sapu dengan biasa saja.
Ingatan Sukma atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya sepanjang pernikahan masih terasa nyata setiap kali ia menceritakannya kembali. Sementara, ia masih berpapasan dengan Randi, mantan suaminya sekaligus orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Sukma selama tiga tahun pernikahan mereka, karena jarak rumah mereka hanya 200-an meter.
Sejak awal, sebetulnya, Sukma tak pernah yakin atas pilihan menikah. Namun, keluarga Randi memaksa mereka menikah dengan alasan Sukma telah mengandung bayi Randi.
Sukma sempat ingin menggugurkan kandungannya, tapi keluarga Randi menolak dengan alasan “dosa”. Sementara orangtua Sukma tak mengetahui apa yang terjadi karena mereka saat itu pergi sebagai buruh migran di Afrika dan Taiwan. Akhirnya, di tengah kebingungan, Sukma menuruti keinginan keluarga Randi.
Pada usia 16 tahun, Sukma menikah dengan Randi yang berusia 19 tahun. Setelahnya hidup Sukma berjalan lebih cepat dan intens.
Ia, yang sebelumnya banyak bermain dengan teman-temannya, mendadak harus menjadi ibu rumah tangga. Pada usia 17 tahun, ia melahirkan anak pertama. Setahun berikutnya ia melahirkan bayi kembar.
Randi melarang Sukma bergaul dengan teman-temannya. Sukma juga dilarang menerima tamu jika tak ada suaminya di rumah. Seabrek pekerjaan domestik dijalankan oleh Sukma, dari membersihkan rumah, memasak, hingga mengurus tiga bayi.
Sementara Randi menjalankan hidup tanpa beban rumah tangga. Ia tak bekerja. Hampir setiap hari pergi pagi dan pulang malam, bermain dengan teman-temannya.
Memendam kegelisahannya beberapa tahun, Sukma mulai geram. Suatu malam, saat Randi pulang, Sukma berusaha bertanya, “Dari mana? Kok nggak pulang-pulang? Saya capek.”
“Nggak usah nanya-nanya,” bentak Randi. “Kamu mengurus tiga anak juga nggak akan mati.” Ia menampar wajah Sukma.
Sukma terdiam. Takut. Ia tahu Randi bakal melakukan banyak hal bila sudah marah, tak cuma memukul dengan tangan tapi juga dengan beragam benda di sekitarnya seperti sapu, pel, atau sabuk kulit.
“Pernah juga lempar pisau, saya ngeri,” ungkap perempuan asal Indramayu ini.
Sukma mengalami luka-luka. Tubuhnya lebam. Ia malu. Rendah diri. Jika ada tetangganya bertanya, ia biasanya menjawab luka-lukanya karena terjatuh saat mengasuh bayi.
Kewalahan mengerjakan segudang pekerjaan rumah, terenggut kebebasannya hingga kesulitan keuangan, satu hari Sukma akhirnya memilih pulang ke rumah orangtuanya. Saat itu ayah dan adiknya sedang di rumah. Ada orang yang bisa membantunya untuk mengasuh anak.
Melihat itu Randi marah luar biasa, tak suka saja melihat anak-anaknya dipegang oleh orang lain terlebih oleh adik Sukma.
“Akhirnya, kami bertengkar, terus saya dipukul,” kisah Sukma.
Sesudah kejadian itu, Randi pulang ke rumah orangtuanya, tak bisa dihubungi hingga satu minggu. Sementara Sukma sudah benar-benar tak sanggup menjalankan kehidupan dengan beban kekerasan setiap hari yang dilakukan Randi.
“Akhirnya, saya nggak pikir panjang lagi, langsung pergi ke kelurahan. Minta surat perceraian,” tegas Sukma.
Namun, proses pengajuan surat perceraian sempat tertahan di balai desa. Petugas menyampaikan perempuan dilarang meminta cerai.
“Saya sudah nangis-nangis, saya cerita saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Barulah saya dikasih [surat cerai]. Saya bahkan menyiapkan diri dicek kesehatan untuk visum sebagai bukti biar boleh cerai.”
Surat pengajuan cerai diberikan kepada Randi. Alih-alih menandatangani, Randi marah, kembali memukul Sukma. Randi merasa terhina karena “diceraikan oleh perempuan.”
Mendengar keributan itu, orangtua Randi memanggilnya. Samar-samar, Sukma mendengar apa yang disampaikan mereka, “Sudah, ditandatangani saja. Istri kamu segitu doang. Udah jelek, orang nggak punya. Nanti juga kamu bisa punya yang lebih dari dia.”
Randi mau menandatangani surat cerai dengan syarat Sukma membayar “rasa malu” karena telah “diceraikan oleh perempuan” sebesar Rp1 juta.
“Jadi saya pulang untuk pinjam Rp1 juta ke tetangga, terus saya kembali, memberi Rp1 juta dan dapat tanda tangan,” cerita Sukma.
“Saat mau pergi, saya bilang, ‘Ya Allah, harga diri laki-laki cuma satu juta doang!’ Setelah dia tanda tangan, saya langsung pergi.” Sukma mengisahkannya sembari tertawa.
Perceraian itu merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah diambil Sukma. Ia sangat lega, sekalipun masih meninggalkan banyak trauma. Pada usia 22 tahun ini, ia mulai kembali menata hidup, mempersiapkan diri mengikuti pekerjaan ibunya sebagai buruh migran.
“Trauma, nggak mau nikah lagi, takut,” katanya.
Menggugat Beda Umur Berbasis Gender dalam UU Perkawinan
Gina, juga perempuan asal Indramayu, Jawa Barat, kesal mengetahui masih banyak perkawinan anak di daerahnya, termasuk apa yang dialami Sukma.
Gina adalah penyintas yang pernah menjalani perkawinan anak pada usia 14 tahun. Ia dinikahkan dengan laki-laki berusia 35 tahun dengan alasan keluarganya bisa “mengurangi beban ekonomi.”
Saat itu suaminya memiliki satu anak berusia 7 tahun. Selepas menikah, Gina tinggal bersama suami dan anaknya. Ia dituntut mengurus anak, memasak, mengurus suaminya. Gina sering jadi sasaran amukan suaminya setiap kali melakukan apa yang dianggap suaminya “kesalahan” seperti membuatkan susu untuk anaknya terlalu panas, salah bumbu masakan, dan sebagainya.
“Padahal, kan, maklum, ora ngerti. Belum punya pengalaman ngurus anak. Saya aja masih anak,” ujar Gina.
Setiap kali suaminya marah, Gina hanya terdiam atau menangis.
“Setiap suami datang, saya takut, bingung, deg-degan, mau gimana menghadapinya? Saya harus bicara seperti apa, melayaninya gimana, saya nggak tahu sama sekali, ora ngerti,” ungkap Gina.
Pernikahan Gina hanya enam bulan. Gina mengajukan cerai selepas menceritakan apa yang dialaminya kepada orangtuanya. Sepanjang pernikahan, Gina tak pernah diberikan nafkah, sebagaimana yang diharapkan orangtuanya. Ia hanya mendapatkan rasa bingung, takut, serta kekerasan verbal dan fisik.
Trauma itu terus menetap sekalipun Gina kini berusia 39 tahun. Ia kerap takut dan gemetar setiap kali mengingatnya.
Pengalaman itu yang mengantar Gina menjadi satu dari tiga perempuan yang mengajukan judicial review Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait batas minimal perkawinan.
Awalnya, regulasi itu mengatur batas pernikahan untuk usia laki-laki adalah 19 tahun, sementara perempuan adalah 16 tahun. Gina menilai ada ketidakadilan di pasal tersebut, yang melanggar Konstitusi Indonesia.
Ia menggugat ketimpangan berbasis gender itu. Tak ingin ada banyak anak perempuan mengalami apa yang telah dialaminya.
“Karena di lingkungan saya masih banyak anak perempuan, adik-adik saya perempuan, saudara-saudara saya perempuan. Saya nggak mau mereka bernasib sama seperti saya. Saya masih punya dua adik perempuan kecil. Jangan sampai adik saya dinikahkan lagi seperti saya,” kata Gina.
Gina sempat merasa lega untuk sesaat karena gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2018.
Tak lama selepas itu, 15 Oktober 2019, Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan putusan itu untuk merevisinya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; usia minimal laki-laki dan perempuan kini sama-sama 19 tahun.
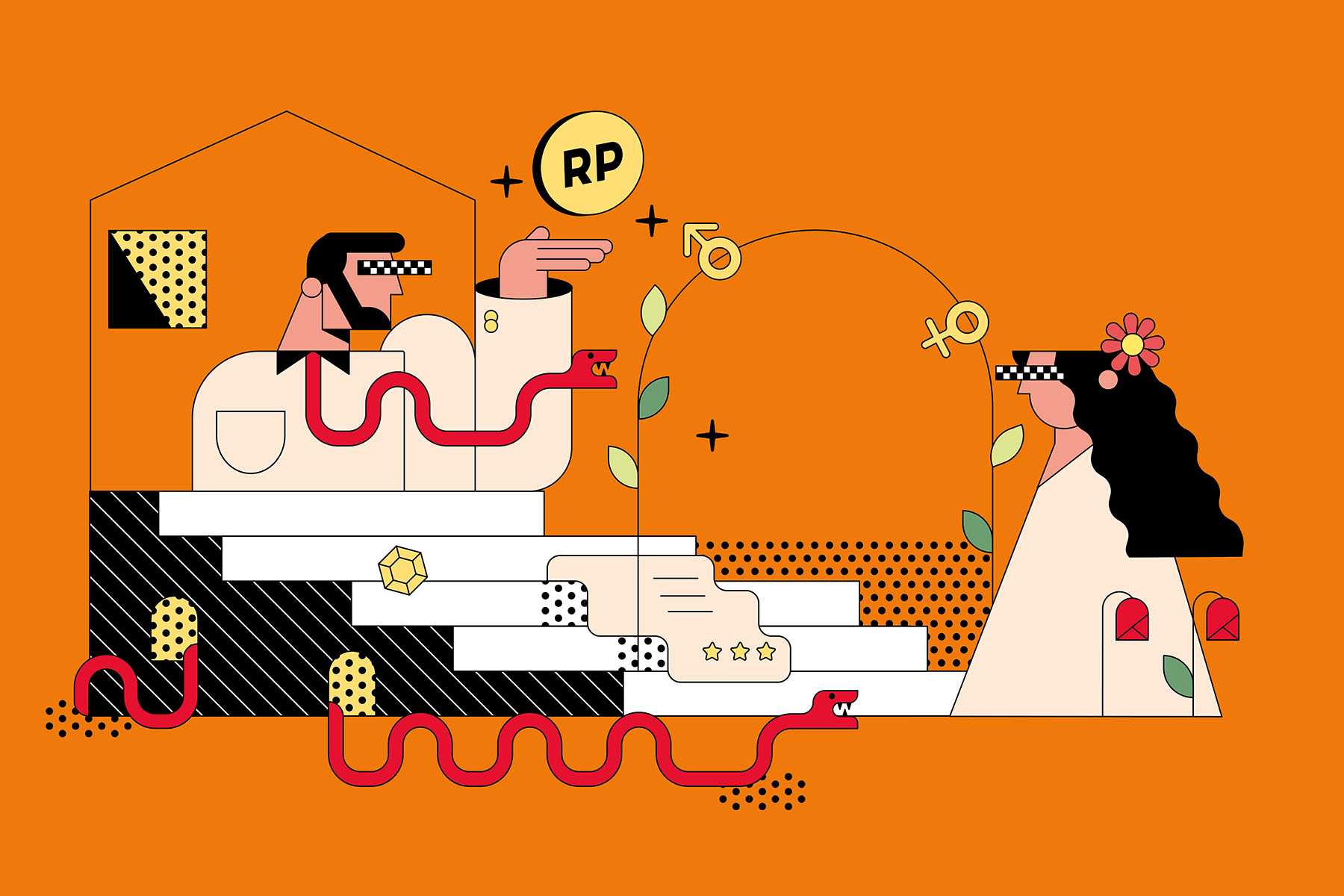
Revisi UU Perkawinan Belum Mampu Tekan Angka Perkawinan Anak
Berjalan dua tahun terakhir, Gina menilai belum ada perubahan signifikan di lingkungannya sendiri selepas revisi UU Perkawinan. Perkawinan usia anak masih marak.
“Saya miris kenapa enggak diterapkan di desa [saya]? Hanya diputuskan di MK saja. Masih ada [banyak] pernikahan anak,” ujar Gina.
Sekalipun batas usia menikah sudah ditetapkan 19 tahun, tetapi ada celah mengajukan dispensasi perkawinan anak melalui pengadilan agama. Proses untuk mendapatkan dispensasi kian mudah dan terus terjadi di berbagai daerah.
Tak hanya di lingkungan Gina, perkawinan anak masih masif di Indonesia.
Sepanjang 2020, setidaknya ada 64.196 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia; 95% di antaranya dikabulkan oleh hakim.
Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan setidaknya 1 dari 9 perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah menikah saat berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, data tahun 2015, terdapat sekitar 2 juta perempuan Indonesia yang sudah kawin dan putus sekolah saat usia di bawah 15 tahun.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka menekankan bahwa angka perkawinan anak yang tercatat belum merepresentasikan kenyataan sebenarnya. Mike menemukan masih banyak perkawinan anak tidak dilakukan secara resmi atau dikenal kawin siri.
Perkawinan anak lebih banyak terjadi di kawasan pedesaan (0,34 perempuan, 0,13 laki-laki) ketimbang perkotaan (0,23 perempuan, 0,035 laki-laki). Selain itu, anak perempuan dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah hampir lima kali lipat menikah pada usia anak ketimbang anak perempuan dari keluarga kelas menengah dan kaya.
Ada beberapa faktor tingginya angka perkawinan anak, jelas Mike. Pertama, faktor pandangan sosial atau budaya yang masih menempatkan posisi anak perempuan tidak setara dengan laki-laki.
Kedua, faktor kemiskinan sehingga anak perempuan, yang posisinya sudah tidak dipandang dengan setara, dinikahkan agar bisa mengurangi beban ekonomi keluarga.
“Faktanya, itu tidak menyelesaikan kemiskinan itu sendiri, apalagi ketika anak perempuan juga menikah dengan pasangan yang tidak siap dengan tanggung jawab keluarga,” kata Mike.
Ketiga, faktor tradisi yang kerap kali memperkuat alasan untuk menikahkan anak. “Berikutnya adalah dispensasi. Aturan dispensasi tidak menjadi mekanisme yang bisa menertibkan atau mencegah perkawinan anak.”
Faktor lain adalah kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan anak sehingga anak segera dikawinkan selepas melewati pubertas.
Terlebih, apabila anak memang telah mengalami kehamilan tak diinginkan, seolah-olah jalan keluar satu-satunya hanyalah dinikahkan. Sementara, permasalahan ini sebetulnya tak lepas dari masalah lain, yakni kekosongan edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas.
Segala faktor menumpuk ini, jelas Mike, kini semakin rumit dengan keadaan pandemi. Banyak anak yang pendidikannya terputus karena tidak semua sekolah sudah mampu melakukan pembelajaran secara daring, serta banyak keluarga yang terhantam perekonomiannya. Hal ini turut meningkatkan angka perkawinan anak.
Perkawinan Anak dan KDRT
Masalah perkawinan anak beririsan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dialami Sukma dan Gina.
Mayoritas korban dalam siklus kekerasan ini adalah anak perempuan karena terdapat ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.
Mike menjelaskan saat pernikahan terjadi antara sesama anak, seperti antara anak perempuan dan anak laki-laki, maka si anak rentan melakukan kekerasan karena belum siap secara mental, fisik, terlebih saat ada masalah ekonomi. Apalagi, dengan posisi yang umumnya laki-laki memiliki kuasa atau dominasi lebih dalam suatu pernikahan, maka perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan.
“Ketidaksiapan itu tentu akan membawa anak perempuan rentan mengalami KDRT,” kata Mike.
Apalagi anak perempuan menikah dengan pria dewasa, yang membuka ketimpangan relasi lebih besar.
“Di perkawinan orang dewasa saja, KDRT sudah menjadi pekerjaan rumah yang besar. Apalagi kalau perkawinan anak,” ungkap Mike.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susianah Affandy menjelaskan salah satu kekerasan yang sering ia hadapi adalah pemaksaan perkawinan terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan.
“Ketika anak hamil, masyarakat Indonesia tabu untuk tidak menikahkan. Bayangkan, kalau misalnya hamilnya itu diperkosa, bayangkan si pemerkosa itu bukannya dihukum tapi malah dikasih ‘hadiah’ dengan dinikahkan,” ungkap Susianah.
“Itu jahat, seharusnya dihukum. Di sini malah dikawinkan. Anaknya bisa trauma seumur hidup. Itu membuka kejahatan-kejahatan di depan mata.”
Terdapat sejumlah pihak yang bertanggungjawab dalam pembenahan masalah perkawinan anak di Indonesia, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dipimpin oleh Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
KPPPA bertanggungjawab mencegah perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam satu dari lima arahan presiden, yang diturunkan dalam Rencana Strategi KPPPA, salah satu untuk melakukan fungsi koordinasi.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KPPPA Rohika Kurniadi Sari menjelaskan, dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak, masih ada beberapa kendala.
“Sebetulnya perkawinan anak pelanggaran hak anak, tapi banyak yang belum ngerti,” kata Rohika.
“Kemudian, masih banyak penafsir agama yang membenarkan hal ini. Regulasi-regulasi juga belum diimplementasikan ke daerah-daerah.” tambahnya.
Salah satu langkah KPPPA adalah menguatkan koordinasi ke kementerian dan lembaga lain, seperti ke Kementerian Pendidikan untuk mengimplementasikan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual, serta melakukan intervensi saat mengetahui ada anak yang akan dikawinkan, ujar Rohika. Koordinasi ini juga mengajak Kementerian Desa agar ada aturan turunan yang bisa segera diimplementasikan di daerah-daerah.
“Harusnya, selain mendorong ada peraturan desa, dibangun juga mekanisme ketika kepala desa tahu ada yang mengajukan perkawinan. Desa harus mendapatkan pencatatan pertama. Ini yang kami usahakan. Profil desa harusnya mengerti kalau itu data perkawinan siri,” kata Rohika, mendesak desa-desa mulai mendata kawin siri usia anak.*
*Nama Sukma, Gina, dan Randi disamarkan atas permintaan narasumber
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #PendidikanSeksual tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan anak muda yang didukung oleh program fellowship jurnalistik dari Rutgers WPF Indonesia.