Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi, sudah saatnya mereka mendapat lebih dari gelar itu. Para guru, dengan segenap pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu mereka, nyatanya semakin butuh dihargai dengan kesejahteraan yang adil dan layak.
SUDAH ENAM BULAN proses renovasi rumah Bibi mandek. Ia dan suami punya rencana sederhana untuk rumah kecil berukuran 90 meter perseginya itu: mengubah muka depan rumah yang semula menghadap jalan, menjadi menghadap sawah.
Bibi adalah kepala sekolah tingkat pendidikan anak usia dini alias PAUD di Kalimantan Timur. Suaminya, buruh angkut sawit, baru mendapatkan upah setiap musim panen.
“Kapan jadinya, Bun?” anak kedua Bibi, Alesha, bertanya. Ia duduk di sebelah Bibi, memperhatikan Bibi yang duduk bersila sambil membuka laptopnya.
Mandeknya proses renovasi meninggalkan salah satu bagian dinding rumah panggung mereka terbuka. Sebagian atapnya juga bolong. Saban hujan deras, air bebas masuk ke dalam rumah tanpa hambatan. Semua kebasahan.
“Bunda belum tahu. Belum gajian-gajian begini, bagaimana mau dijadikan,” jawab Bibi apa adanya.
PAUD tempat Bibi bekerja bernaung di bawah yayasan. Pemasukan mereka bergantung pada anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah. Tetapi bupati yang sedang menjabat saat ini berstatus pelaksana tugas (Plt), sebab bupati resmi, sebut saja A, terjerat kasus korupsi dan lengser. Pemerintah daerah beralasan mereka belum memiliki wewenang untuk merancang anggaran dan menggaji pegawai-pegawainya.
Sebab itu, sudah tujuh bulan gaji Bibi belum cair. Kami menemui Bibi pada Juli. Pada pekan ketiga September, kami mengonfirmasi kembali kepada Bibi dan mendapat pengakuan bahwa gajinya masih belum dibayarkan.
Sore itu, Bibi mengeluhkan kepalanya pusing. Tadi pagi, ia menghadiri rapat dengan dinas pendidikan daerah. Mereka menjanjikan gajinya akan segera cair.
Sembari menunggu gajinya dibayarkan, Bibi diminta menyelesaikan tugas merancang ulang kurikulum menyesuaikan kebijakan terbaru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka.
Tenggat waktu yang dinas setempat berikan layaknya legenda Sangkuriang, “Sekarang juga, ya! Saya tunggu.”
“Apa ndak sakit kepala? Mereka kalau minta semaunya.” Ia menghela napas.
Ini bukan pertama kali gaji Bibi telat dibayar berbulan-bulan. Tahun lalu, ketika A menjabat, gajinya tak cair selama 11 bulan. “Semua dana terhambat kemarin, semenjak dia [A] menjabat. Ketahuannya setelah kami demo,” cerita Bibi, sambil menerangkan tunggakan gaji 11 bulan itu akhirnya dibayarkan pada tahun ini, dengan dicicil.
Bibi ingat dulu mantan bupati menjanjikan gaji mereka akan naik, setidaknya sesuai dengan besaran UMR, sekitar Rp3 juta. Sebelumnya, selama lebih dari 10 tahun menjabat sebagai guru sekaligus kepala PAUD, gajinya mandek di Rp1,1 juta.
Tetapi, janji itu hanya bertahan selama dua bulan. Setelah itu, Bibi kembali menerima gaji sebesar Rp1,1 juta. Pernah pula nominalnya turun menjadi Rp500 ribu. “Begitu dia ditangkap, ternyata rancangan peraturan itu tidak dikemana-manakan. Hanya ditaruh di atas mejanya,” cerita Bibi. “Jadi kami hanya dibohongi biar sabar, sabar, dan sabar.”
* * *
Nama lengkap Bibi adalah Badriah. Orang-orang biasa menyederhanakannya menjadi Bibi. Ia tak keberatan dipanggil Bibi karena seperti mewakili jiwa muda dirinya: selalu terlihat enerjik, senang mengobrol, dan nada bicaranya terdengar antusias.
Bibi anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia keturunan salah satu suku asli di sana. Bibi menjadi generasi pertama yang berhasil meraih gelar sarjana di keluarga besarnya. Generasi-generasi di atas Bibi rata-ratanya lulusan SD atau SMP. Berhasil lulus SMA/SMK atau S1 adalah sebuah anomali.
“Dulu suku kami terkenal dihina-hina. Ndak punya pendidikan,” cerita Bibi.
Telah menjabat sebagai kepala sekolah sejak 2009, Bibi kadang bertanya-tanya kenapa ia berakhir menjadi guru. Dulu ia membayangkan guru adalah profesi yang ideal: baju-baju seragamnya cantik. Gajinya pasti besar.
Maka, ketika ada tawaran untuk menjabat sebagai kepala PAUD, Bibi tak berpikir panjang. “Bergabunglah saya. Tapi tidak pernah menanyakan gaji pada saat itu,” kenang Bibi.
Bibi beranjak dari duduknya. Ia meregangkan tubuh, sambil menatap ke arah sawah. Matahari sudah mulai turun. Lahan sawah di depannya memantulkan cahaya kuning keemasan.
“Meratapi nasib,” kata Bibi setengah bercanda sambil memandang sawah. “Merenungi gaji yang tidak cair-cair.”
Menjual Tandon Hingga Menunggu Dana ‘Kampanye’

PAGI HARI, pekik dan cekikikan anak-anak telah terdengar dari gerbang masuk sekolah tempat Bibi mengajar. Di sebuah ruangan kelas, ada sekitar 30 anak sedang duduk melingkar. Orangtua mereka duduk menunggu di teras depan kelas.
Sambil mengajak anak-anak bernyanyi, seorang guru juga memberikan pengetahuan dasar tentang anatomi tubuh. Ia mengangkat kedua tangannya ke hadapan anak-anak, lalu bertanya ke mereka,
“Tangan ada berapa?”
Seorang anak dengan lantang menjawab, “Sepuluh!”
Si guru tersenyum dan mengoreksi dengan sabar, “Itu jari. Kalau tangan ada…?”
“Lima!”
Di luar ruangan, beberapa anak sedang berlari-larian, bermain ayunan, jungkat-jungkit, dan perosotan. “Adri, nggak usah laju-laju!” seru Bibi ke seorang anak yang mengayun dengan tinggi dan cepat.
Butuh sabar dan kekuatan lebih untuk menjadi guru pra-sekolah. Tugas mereka tak lantas selesai begitu sekolah bubar pada pukul 10 pagi.
Bibi dan guru-guru lain akan merapikan kelas dan membersihkan sampah-sampah bekas kegiatan. Mereka lalu menyusun rencana kegiatan untuk keesokan hari.
Mereka juga harus menunggu di sekolah hingga seluruh anak pulang. Terkadang, ada saja 1-2 anak yang tak dijemput orangtuanya hingga siang hari.
“Gimana ini kalau nggak dijemput? Aku nggak tahu di mana rumahnya.”
“Mamanya kerja. Tadi yang antar tantenya.”

Percakapan-percakapan semacam itu kerap terjadi. Bibi dan guru-guru lain dengan sabar menemani si anak, mengajak mereka berbicara, bermain, atau menyuapi mereka makan.
“Harus jaga di luar terus. Kejar sana-sini. Belum yang dia [si anak murid], naik-naik tangga. Jangan sampai terjadi celaka-celaka. Jatuh-jatuh gitu. Bahaya,” tutur Bibi.
Dari pengalamannya, menjaga anak-anak adalah pekerjaan yang, “Menghabiskan tenaga luar biasa.”
Di tengah mengawasi anak-anak yang sedang berlarian di taman, Bibi dan seorang guru memperbaiki perosotan yang rusak. Kaki perosotan lepas dari tanah, mereka perlu menanamnya kembali. Bibi mengambil palu dan mengetok-ngetok salah satu kaki perosotan sampai masuk lagi ke tanah.
Untuk urusan-urusan perbaikan “minor” seperti itu, para guru biasa mengandalkan diri mereka sendiri.

Susah-susah gampang bagi para guru di PAUD tempat Bibi mengajar untuk mencari pendanaan bagi sekolah.
“Jangan lihat kepsek. Kepsek nggak bisa ngegaji,” kelakar Bibi ke guru-guru lain ketika mereka sedang berkumpul bersama.
* * *
Bibi dan lima guru lain di PAUD itu berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY). Gaji mereka bersumber dari dana hibah pemerintah daerah dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Ia dulu mendaftarkan sekolahnya sebagai sebuah yayasan semata untuk memudahkan urusan administrasi. Jika bukan yayasan, perizinan perlu ia perbarui setiap satu tahun sekali. Kini, dengan status yayasan, izin operasional lembaga berlaku untuk selamanya.
Tetapi, mendaftarkan sekolah mereka sebagai sebuah yayasan justru mempersulit mereka mendapatkan dana dari pemerintah.
“Yayasan kami bukan seperti yayasan di kota-kota. Yayasan di kota, kan, bisa menghasilkan dana. Ada donatur. Kalau kami, yayasannya kami sendiri yang buat, kami yang ketuai, kami juga yang cari dana. Kami bikin buat formalitas izin saja,” ujar Bibi.
Untuk dukungan operasional, seperti memenuhi kebutuhan penyediaan alat tulis maupun makanan tambahan, sekolah bisa memanfaatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dari pemerintah pusat. Tapi BOP tidak mencakup anggaran untuk gaji guru.
Ini bagai buah simalakama bagi Bibi. Di satu sisi, mereka tak dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di sisi lain, pendapatan mereka bergantung sepenuhnya dari pemerintah daerah.
“Jadi, kita ini seolah-olah dijebak. Berapapun dia [pemerintah daerah] kasih gaji, Rp500 ribu pun, kami terima. Ndak bisa berontak, karena sudah terikat sama yayasan itu tadi,” terangnya.
Sementara, di saat yang sama, mereka mendapat kabar bahwa BOSDA hendak dihapus.
Padahal dulu, anggaran BOSDA juga bisa dialokasikan untuk pelatihan bagi para guru ke luar kota. Mereka sempat kebagian pergi ke Jakarta. Ada juga yang pergi ke Malang.
Bibi ingat ia sampai menjual tandon di rumahnya, seharga Rp500 ribu, demi punya pegangan uang saku selama pelatihan di Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan Kak Seto.
Ketika orang-orang sudah punya ponsel pribadi untuk berfoto dengan Kak Seto, Bibi tak punya. “Ada, tapi handphone yang masih hitam-putih. Nokia tipe berapa waktu itu. Orang-orang sudah jepret sana-sini, aku tidak. Hanya dapat hasil cetak foto kenang-kenangan dari pemandu foto. Masing-masing orang diberikan foto kenang-kenangan.”
Dana BOSDA untuk pelatihan di luar kota itu ditiadakan setelah pemerintahan berganti. “Katanya, jalan-jalan itu hanya buang-buang uang. Menurut mereka, guru ke sana bukan belajar, tapi cuma jalan-jalan.”
Sementara untuk biaya perawatan gedung, Bibi terkadang mau tak mau mengandalkan uang apa saja yang bisa ia dapatkan, seperti uang kampanye ketika masa-masa pemilihan kepala daerah. Belajar dari pengalaman, Bibi paham betul uang akan dengan mudah cair jika itu berkaitan dengan urusan politik.
Pada 2012, seorang anggota partai politik mendekatinya. Ia meminta Bibi untuk membantu mencarikan suara untuk seorang kandidat bupati.
“Ibu minta apa?” tanya orang tersebut ke Bibi.
“Saya minta bangunan [sekolah],” jawab Bibi.
Si pihak partai berjanji untuk membantu memuluskan pencairan proposal anggaran ke pemerintah daerah. Dalam waktu seminggu, uang sebesar Rp112 juta cair. Bibi mengambilnya langsung di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).
Uangnya kini telah berbentuk bangunan baru. Posisinya ada di depan, tak jauh dari plang nama sekolah.

Ada dua bangunan sekolah di PAUD Bibi mengajar. Bangunan yang lebih tua terletak di pojok, terpisah dengan bangunan baru oleh taman bermain anak-anak. Bangunan baru itu kini jadi lokasi utama kegiatan belajar-mengajar. Ruang kepala sekolah dan pantry tempat menyimpan makanan dan minuman untuk para siswa juga berada di sana.
“Itulah, Mbak,” keluh Bibi kepada kami. “Kalau ada imbal baliknya begitu, cair cepat. Sementara kalau kita ndak gajian begini, bilangnya ndak ada uang.”
Enam guru, termasuk Bibi, kini mendapatkan gaji sama rata. Rp1,1 juta setiap bulan. Tidak ada perbedaan upah antara kepala sekolah, guru, atau pegawai administrasi. Kadang mereka mengandalkan keuntungan dari penjualan buku atau seragam yang besarnya tidak seberapa dan baru terakumulasi pada akhir tahun ajaran.
‘Sekolah Cuma Nyanyi-nyanyi’
BELUM banyak orangtua di sekitar tempat tinggalnya yang punya kesadaran akan pentingnya kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia dini. Kebanyakan dari orangtua memilih langsung mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar.
“PAUD itu ndak penting. Cuma nyanyi-nyanyi, bayar sekian.” Bibi mengulang kata-kata yang kerap diucapkan warga setempat, termasuk kakak-kakaknya.
Anggapan serupa juga diakui dinas pendidikan. Mereka pernah hendak menekan nominal gaji guru PAUD menjadi Rp500 ribu per bulan. Alasannya sama, “Pekerjaan guru PAUD hanya bernyanyi-nyanyi.”
Kebijakan yang saat ini berlaku juga tidak berpihak pada guru seperti Bibi. Undang-undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen; dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mengakui pendidik seperti Bibi sebagai guru, sebab tempat mereka mengajar masuk klasifikasi PAUD nonformal.
Implikasinya, Bibi tidak dapat mengikuti sertifikasi guru dan tidak mendapatkan upah yang berkaitan dengan profesi, seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan lainnya. Dalam kasus lain, seorang guru PAUD juga telah menggugat UU Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas ke Mahkamah Agung pada 2019 dengan alasan yang sama.
Bibi tertawa miris. “Padahal, golden age itu usia 1-5 tahun,” terang Bibi. “Kelihatan jelas perbedaan anak yang dari PAUD sama yang langsung ke SD. Nggak lagi diantar mamaknya, pede-nya sudah dapat, pegang pensil nggak kayak orang bunuh.”
“Bukan saya menghina,” tambah Bibi. “Karena, kalau orangtua sendiri yang mengajar, anak-anak biasanya susah menurut.”
Bibi masih bisa memahami alasan orangtua yang enggan menyekolahkan anaknya di PAUD. Bagi kebanyakan orangtua di daerahnya yang bekerja sebagai buruh harian, menyekolahkan anak di PAUD jadi beban finansial tambahan. Meski biaya PAUD Bibi relatif terjangkau, Rp50 ribu per bulan, tetapi masih ada biaya tambahan yang perlu orangtua keluarkan seperti pembelian buku pelajaran.

Selain itu, program Keluarga Berencana (KB) di daerahnya terbilang tak sukses. Banyak keluarga memiliki banyak anak. Seringkali, anak-anak mereka masuk sekolah berbarengan: ketika anak paling bungsu masuk PAUD, kakak-kakaknya secara bersamaan hendak naik tingkat ke SD, SMP, sampai SMA. Pengeluaran semakin membengkak.
Orangtua menunggak SPP jadi kabar yang biasa bagi Bibi. Ia memilih tak ambil pusing. Ia tetap membiarkan anak-anak yang belum membayar SPP untuk masuk kelas. Ia hanya mewajibkan para orangtua untuk membayar biaya paket buku sebesar Rp200ribu, yang dapat mereka cicil selama yang mereka butuhkan.
“Ntah dia mau kreditkan berapa kali, terserah. Kalau SPP ndak bayar, ya sudah. Saya biarkan saja, sudah.”
Ini jadi upayanya untuk turut serta meningkatkan taraf pendidikan warga keturunan suku asli di daerahnya. Bibi mendorong mereka, yang kebanyakan masih memiliki ikatan darah atau memiliki hubungan keluarga dengan dirinya, untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Sebab, ada ketimpangan akses pendidikan yang mereka rasakan. Masyarakat suku asli (indigenous peoples) tidak dibesarkan dengan edukasi tentang pentingnya pendidikan formal.
Mereka ketinggalan jauh dari para pendatang dari Jawa, Bugis, dan daerah-daerah lain. Sehingga, tak banyak warga asli yang memiliki pekerjaan formal, atau menjabat pekerjaan-pekerjaan strategis seperti di pemerintahan daerah.
“Mumpung saya masih kepala sekolah. Sekolah, memang, meski ndak punya uang.” Bibi mewanti-wanti keluarganya.
Berjibaku Mengurus Sekolah dan Rumah Tangga

BIBI biasa pulang dari sekolah pukul 12. Di rumah, Bibi berpakaian santai. Ia mengucir kuda rambutnya, memakai kaos hitam bertuliskan cannabis, dan celana panjang longgar. Gaya itu berbeda dengan tampilannya di sekolah: memakai jilbab, kemeja tangan panjang, dan rok panjang.
“Saat pertama kali jadi guru, saya pakai Levi’s (celana jin) terus. Pakai kaos kaki warna hijau, karena warna kesukaan saya hijau. Tapi, lama-kelamaan tidak boleh,” ceritanya. “Katanya, jadi guru PAUD itu harus pakai baju yang sopan, tidak boleh ngepres-ngepres.”
Di sebelah kiri tempat Bibi duduk, terletak ruang dapur. Tanpa sekat, ruang itu menyatu dengan ruang tamu. Piring-piring kotor menumpuk di sudut ruangan, di sebelah bak air.
“Aku cuci besok, sudah.”
Selain piring kotor, hal lain yang Bibi paling malas sentuh adalah baju kotor. “Kalau betul-betul ndak ada pekerjaan, baru saya kerjakan. Kalau ndak, ya, sudah. Seberantakan-berantakannya. Saya tumpuk sampai penuh seperti gunung,” katanya santai.
Kertas-kertas dokumen kurikulum sekolah berceceran di sekitar Bibi. Satu toples plastik berisi kerupuk ada di samping Bibi. Ia akan bekerja sambil sesekali mengambil dan mengunyah kerupuk.
Di tengah pekerjaannya, ia meminta Alesha untuk menyuruh kakaknya mandi. Namanya Raka. Ia baru pulang sekolah.
Sehari-hari, Bibi memulai aktivitasnya pada pukul lima pagi. Ia akan terbangun oleh suara azan Subuh dari masjid yang terletak di seberang rumahnya. Ia langsung bergegas menyiapkan sangu untuk anak-anak sekolah. Raka baru saja masuk SMP.
“Kalau lagi MOS (Masa Orientasi Sekolah), biasanya kita terlambat sedikit kena hukum. Jadi aku siasati, bawain bekal makan dan air dari rumah.”
Setelah itu, jika masih sempat, ia akan membersihkan rumah, “Selayaknya yang bisa aku simpun (sapu), lah.”

Pekerjaan rumah tangga itu biasa Bibi kerjakan sendiri. “Makanya ndak pernah rapi,” katanya. Dengan rumah tanpa dinding, piring dan baju kotor berceceran, ia bilang rumahnya sudah seperti ‘kandang babi.’
Ia tak bisa mengandalkan suami atau anak-anaknya. Sebagai buruh sawit, suaminya biasa berangkat pukul 8 pagi, lalu pulang pukul 6 sore.
“Panen sawit itu berat, lho, Mbak,” sebut Bibi. Ia ikut kasihan dengan suaminya. Bibi bisa berkata begitu karena ia dulu juga pernah merasakan bekerja panen sawit ketika masih sekolah.
Harga sawit juga sempat terjun bebas. Suami Bibi ikut kena imbasnya. Kelompok panen sawitnya terdiri dari 5-6 orang. Mereka mendapatkan bayaran Rp300 ribu/ton brondolan sawit yang dikumpulkan ketika panen.
Jika dapat 10 ton, misalnya, para buruh akan mendapatkan imbalan senilai Rp3 juta dan dibagi berenam. Jika sedang mujur, suaminya bisa mendapatkan Rp1 juta dalam dua hari.
Tetapi, buah lebih sering seret. Paling-paling suaminya hanya dapat Rp50 ribu dalam satu minggu. Upah yang, kata Bibi, tak cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan rokok suaminya. “Dua bungkus rokok dia habis satu hari. Kalau saya ndak bantu-bantu [kerja], ndak bisa.”
Ketika gaji Bibi tak juga turun dan pemasukan suaminya tak seberapa, tak banyak yang bisa mereka lakukan selain mengirit pengeluaran.
Alesha mulai mengeluh. Ia minta dibelikan sepatu. “Mama kapan, sih, gajiannya? Sepatuku sudah bolong.”
“Nanti, sabar. Kalau Mama sudah gajian, nanti Mama bawa ke Balikpapan.”
Dipaksa Belajar Berenang Tanpa Pelampung

TAHUN INI, Bibi berusia 35 tahun. Ada beberapa guru di PAUD itu yang sepantaran dirinya, ada juga yang sudah 50 tahun. Ada satu guru paling muda, biasa disebut Bunda Suci, kelahiran 1997.
“Itu, yang paling glowing,” sebut Bibi tentang Suci.
Semuanya lulusan S1. Tetapi, hanya Bibi yang mampu dan terbiasa menggunakan komputer. Ia sempat mendorong guru-guru lain untuk belajar memakai komputer. Terutama mereka yang masih muda. Tetapi mereka enggan. Mereka bilang, “Ndak usah. Masih ada Bunda Bibi, kok.”
Bibi geleng-geleng kepala. “Ku bilang, kalau suatu saat saya pindah, atau saya ikut suami ke Jawa, nanti kalang kabut kamu. Nggak ada yang bisa komputer.”
Di saat yang sama, pemerintah daerah mulai mewajibkan agar setiap tenaga pengajar menguasai komputer.
Bibi mengerti pentingnya kemampuan menggunakan komputer, setidaknya kemampuan mengetik di Microsoft Word. Apalagi sekolah terkadang harus menyetor proposal dan laporan ini-itu ke pemerintah daerah. Belum lagi urusan-urusan administrasi lain yang berkaitan dengan operasional sekolah.
Kendati begitu, Bibi mafhum mengapa guru-guru lain tak bersemangat meningkatkan kemampuan mereka. Berbagai tuntutan dan persyaratan dari pemerintah tak sebanding dengan jaminan kesejahteraan bagi guru.
“[Pemerintah] nggak bisa menuntut begitu kalau gaji ndak sesuai. Gaji, lho, cuma Rp1,1 juta. Dituntut harus bisa ini, itu. Ya, ndak mau, lah,” kata Bibi.
Bibi kembali mengeluh. Ia lagi-lagi menyorot soal gaji yang sudah kecilpun masih tak dibayar berbulan-bulan. “Dari bulan satu sampai tujuh ndak ada gajian. Hanya dijanji dan dijanji.”
Di tengah ketidakpastian soal gaji, mereka masih mesti mengeluarkan dana untuk kebutuhan sekolah. Yayasan mengeluarkan uang dari kocek sendiri untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan para guru. Besarnya Rp330.000 untuk enam orang setiap bulannya. Ada juga biaya internet yang akhirnya tak lagi mereka bayar.
“Akhirnya kami putus,” cerita Bibi.
Guru-guru di tempatnya juga minim mendapatkan pelatihan dan bimbingan. Mereka seolah-olah seperti orang-orang yang tak bisa berenang dan diceburkan ke laut tanpa pelampung.
Pada 2013, Bibi pernah diminta menyetorkan data sekolah ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Saat itu, koneksi internet masih barang langka di kampung Bibi. Ia lalu berangkat diantar suami menuju sebuah warung kopi dengan Wi-Fi yang berjarak sekitar 10-15 kilometer (km).
“Dari sana langsung bilang, ‘kerjakan ini, download ini, link-nya ini.’”
Sementara, sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA, mendapatkan pelatihan langsung yang diselenggarakan di hotel-hotel di kota besar, seperti di Samarinda atau di Jakarta. “Kami tidak. Kadang alasannya karena tidak ada anggarannya,” kata Bibi.
Tinggal di Kandang Ayam Demi Ikut Ujian
PERJUANGAN BIBI di dunia pendidikan tak pernah mudah.
Ia ingat pernah bekerja harian memukul dan memecah batu di hutan demi menebus ijazah SMA-nya. Kala itu, usia orangtuanya sudah lebih dari 75 tahun. Saudara-saudaranya juga sudah berumah tangga, dan tergolong tidak mampu secara ekonomi.
Bibi berangkat naik truk pukul 06.00 dan menempuh satu jam untuk sampai ke hutan. Di sana, ia bertugas memecah batu hingga ukuran 23 mm. Pekerjaan itu ia lakukan selama satu bulan. Ia mendapatkan upah Rp300 ribu. Sementara, biaya menebus ijazah sebesar Rp150.000.
“Memang aku yang berniat. Saya ingin sekolah tinggi. Masa aku tidak sekolah, sudah saudara-saudaraku tidak ingin sekolah?” katanya.
Selama SMA, Bibi ikut berangkat dengan anak tetangga untuk pergi ke sekolah. Rumah dan sekolahnya berbeda desa. Ia perlu kendaraan bermotor untuk ke sana.
Untuk uang jajan selama di sekolah, Bibi berjualan keripik pisang. Ia akan menyiapkan jualannya pada hari sebelumnya. Bibi akan pergi mencari pisang sepulang sekolah. Ia mengiris-iris pisang, kemudian ia goreng dan kemas. “Saya jual di sekolah. Nanti uangnya untuk sangu,” katanya.
Untuk membayar SPP, Bibi sering mengikuti berbagai perlombaan di sekolahnya, dari bernyanyi sampai cerdas cermat. Sekolah juga biasanya akan memotong langsung hadiah lomba untuk biaya sekolah. Sisanya, sekitar Rp20 ribu sampai Rp30 ribu akan disimpan Bibi.
Bibi juga akan menggunakan waktu libur untuk bekerja. Bibi bersama kakak perempuannya akan berangkat ke KM 12 Balikpapan untuk bekerja mengolah sampah. Botol-botol bekas, kertas, hingga buku ia pilah dan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap 1 kilogram hasil pemilahan, ia akan mendapatkan upah Rp100. Kala itu, ia bisa mendapatkan sekitar Rp500 ribu selama satu bulan bekerja.
Sembari menunggu ijazah SMAnya keluar, Bibi bekerja sebagai buruh harian di hutan tanaman industri. Ia bekerja selama dua tahun: membawa parang untuk merintis hutan, menyemprotkan racun tanaman, melakukan pemupukan, menanam, melakukan singling. “Singling itu menggunting dahan yang bercabang. Pakai gunting rumput,” jelas Bibi.
“Kalau diingat-ingat, saya dari SD sudah kerja. Keliling hutan, menghampiri orang yang sedang bekerja di hutan tanaman industri, bawa 300 biji kue setiap hari Minggu,” kenang Bibi.
Selama menjadi buruh harian itu pula, Bibi belajar menggunakan laptop. Ia belajar dari atasannya.
“Bibi ini katanya lulusan SMA. Tapi, kok, tidak bisa komputer?” Atasannya heran.
“Ya, tidak bisa, lah, Pak. Namanya juga sekolah di kampung. Mau belajar komputer dari mana?”
Kemampuan menggunakan laptop itu yang membuat Bibi mendapatkan tawaran kerja sebagai kepala sekolah PAUD. Saat itu, jumlah orang yang bisa menggunakan laptop bisa dihitung jari. Bahkan, hingga saat ini, lulusan S1 di daerahnya bisa tidak memiliki kemampuan mengetik.
Sejak itu, ia mulai paham sedikit-sedikit cara menggunakan laptop. Ketika suaminya yang berasal dari Jawa pulang kampung, ia sekalian membelikan Bibi laptop. Pada saat yang sama, seorang keponakan Bibi yang menempuh sekolah administrasi perkantoran di Balikpapan ikut mengajarkan Bibi ketik-mengetik.
“Alhamdulillah. Sedikit-sedikit nyantol,” kata Bibi.
* * *
Menjadi guru mendorong Bibi untuk mengenyam S1. Pada 2013, ia mengambil jurusan sarjana PAUD di sebuah universitas di Samarinda. Anak pertama Bibi, Raka, sudah berusia 4 tahun.
Suaminya ikut mendukung, bahkan turut menanggung biaya pendidikannya. Ketika itu, suami Bibi masih berprofesi sebagai pembawa alat berat yang upahnya lebih besar ketimbang saat ini.
Perguruan tinggi tempat kuliah Bibi menerapkan sistem belajar daring. Namun, bila ujian, mahasiswa tetap diminta melaksanakannya secara luring di sebuah kecamatan yang berjarak sekitar 50 km dari rumahnya.
Biasanya Bibi akan menginap selama dua malam di kecamatan tersebut. Tetapi, biaya menginap di hotel mahal.
“Jadi, saya cari penginapan yang hanya Rp25 ribu/malam,” ceritanya. “Tidurnya di samping kandang ayam. Baunya tidak karuan. Saya tahan-tahanin saja.”
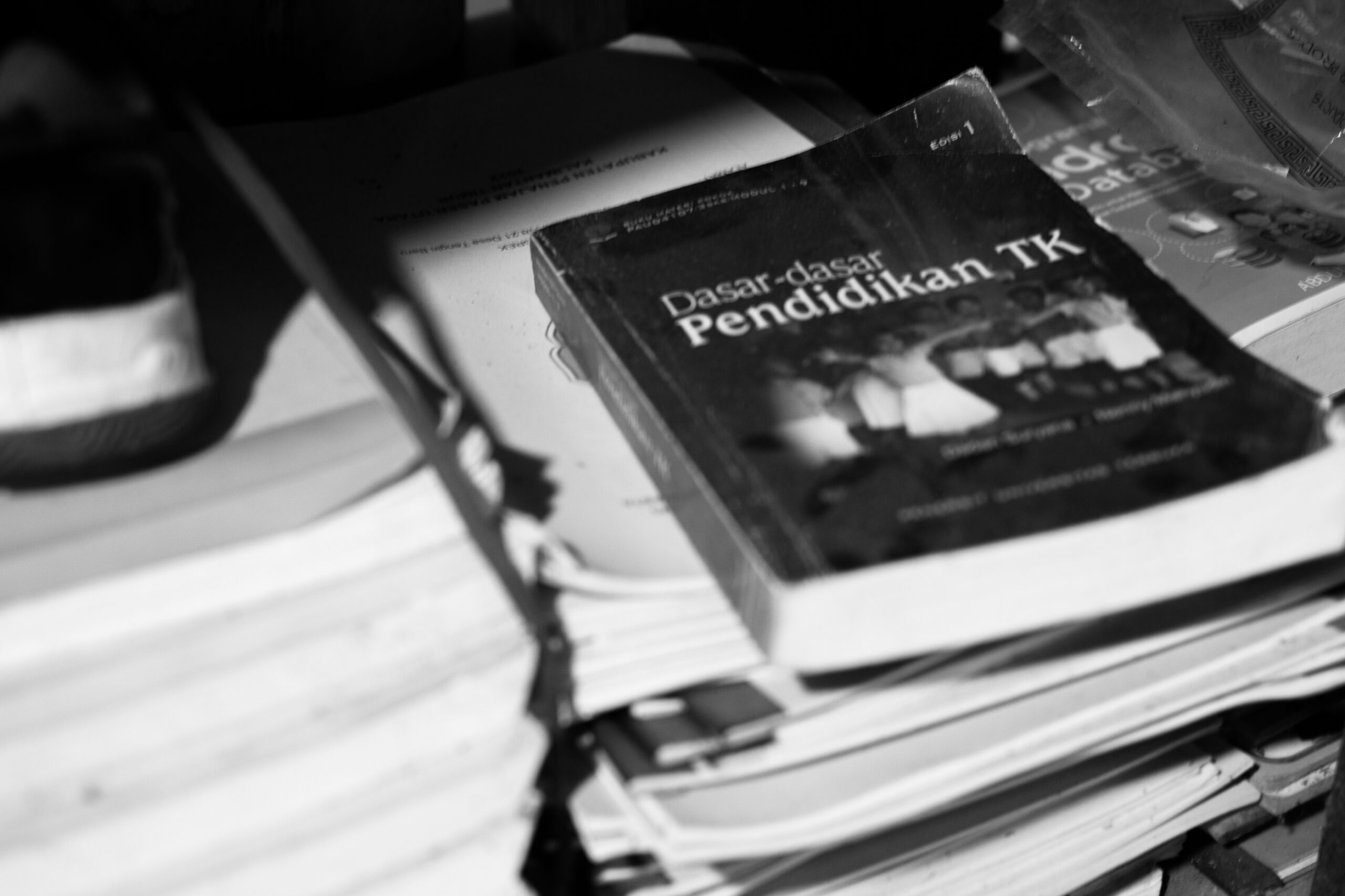
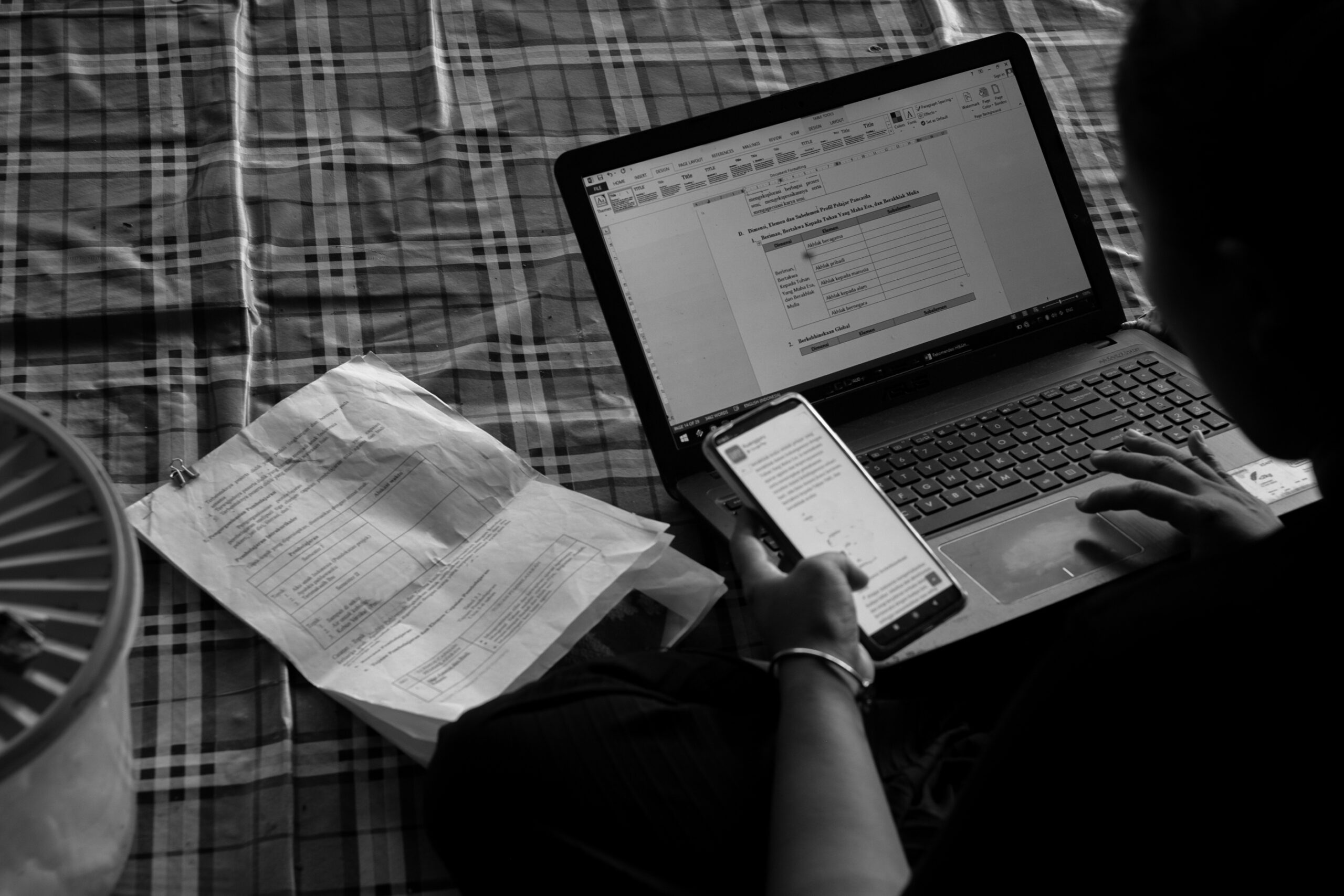
Hingga kini, Bibi masih memiliki pekerjaan-pekerjaan sampingan. Ia sempat menawarkan jasa ketik, mengerjakan tugas kuliah dan skripsi, hingga administrasi lembaga. Pasalnya, banyak mahasiswa atau pekerja di sebuah lembaga pendidikan di daerahnya yang tidak bisa menggunakan komputer.
Kadang, dalam waktu lima hari, ia bisa mengerjakan urusan administrasi untuk sembilan lembaga.
Bibi tak masalah jika klien yang menggunakan jasanya berutang atau baru membayar pada akhir tahun. Suatu waktu, ia pernah mendapatkan bayaran dari beberapa lembaga sekaligus secara bersamaan. Totalnya sampai Rp29 juta. Sebagian uangnya ia gunakan untuk pulang ke kampung suaminya sekeluarga dan memberikannya ke sang mertua.
Jika pekerjaannya sedang padat, Bibi bisa lembur hingga pukul 3 pagi. Bibi juga punya mesin fotokopi di rumahnya. Ia sekadar melayani orang-orang fotokopi dokumen, menyusun, atau menjilid buku.
Selama pandemi ini, Bibi mengambil kerja tambahan demi membeli biaya paket data untuk mengajar. Ia ikut lomba bernyanyi yang kerap diadakan di aplikasi Smule. Para pemenang biasanya mendapatkan hadiah pulsa telepon, paket data, atau pulsa listrik.
Bibi menunjukkan kain hitam di sudut rumahnya yang biasa dijadikan latar belakang ketika ‘rekaman.’
“Kemarin saya juara tiga. Dapat Rp200 ribu,” katanya.
Bibi biasa menyanyikan bermacam-macam lagu, mulai dari yang bergenre folk, hingga lagu-lagu lokal seperti dari Sunda, Jawa, atau Banyuwangi.
“Yang saya ndak bisa cuma genre bahasa Inggris,” katanya, sambil melanjutkan, “Padahal kalau bisa bahasa Inggris lebih lumayan. Juara satunya bisa dapat sampai Rp20 juta atau liburan ke Singapura. Tapi bahasa Inggrisku kan biasa-biasa saja, nanti malu-maluin.”
Biasanya, pelaksana lomba tersebut adalah orang Indonesia yang bermukim di luar negeri, misal para pekerja migran atau TKW. Bibi menduga mereka menyelenggarakan lomba-lomba itu karena kerinduan mereka akan Tanah Air.
Bibi menunjukkan salah satu videonya. Di video itu, Ia bernyanyi dua lagu sekaligus, medley, berdurasi lima menit. “Sepotong lagu Banyuwangi, sepotong lagu dangdut,” kata Bibi.
Video yang lainnya, Bibi bernyanyi medley pop dan dangdut. Ia masuk final, tetapi belum ada pengumuman pemenang.
Ia biasa merekam video-videonya di malam hari. “Aku setor lagunya setelah salat Isya,” cerita Bibi. “Karena kalau siang, kan, banyak suara. Kalau videonya ada noise, kita di-dis[kualifikasi].”

Kini, pulsa Bibi berlimpah. Nominalnya sampai Rp2 juta. Ia akan mengisikan pulsa dan paket data ponsel suami dan anaknya. Kadang, ia jual pulsanya ke orang lain. Bibi tak pernah lagi mengisi pulsa sendiri selama dua tahun terakhir.
Di tengah seluruh kesibukannya itu, Bibi tadinya masih berharap untuk membantu tetangganya menggarap sawah. Imbalannya lumayan, kata Bibi. Tetangganya akan membagikan padi dengan rasio 1:7. Untuk setiap tujuh kaleng padi yang berhasil dipanen, Bibi akan mendapatkan satu kaleng.
“Cuma, tidak boleh sama suami. Dilarang,” katanya.
“Kenapa?”
“Nanti kalau mengeluh capek, minta diurut, siapa yang mau urut? Suami juga capek.”
Berkaca dari masa kecilnya, Bibi ogah punya anak banyak seperti orangtuanya. Saudara-saudara kandung Bibi lain paling mentok adalah lulusan SMP. Ada juga yang tidak lulus SD.
Bibi bilang cukup dua anak, sehingga ia bisa fokus menyekolahkan mereka hingga pendidikan tinggi. Suaminya terkadang ikut parno Bibi hamil lagi. “Aku kalau sedang pusing sedikit, disuruh periksa. Takut hamil lagi. Saking tidak maunya punya anak lagi.”
Bibi juga ingin anak-anaknya dapat menikmati masa kecil mereka, tak seperti dirinya yang sudah mesti bekerja sejak kecil.
“Makanya aku bilang ke anakku: Jangan sampai kamu seperti Mamak. Cukup Mamak yang kerja keras sejak kecil.”
* * *
Bibi masih menyimpan angan-angan untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pascasarjana.
Angan-angan itu sempat nyaris terwujud, ketika gajinya sempat naik menjadi Rp3,4 juta/bulan.
Ia sudah bilang ke suaminya, dan si suami menjawab, “Silakan jika mampu.” Ia lalu membayangkan suaminya antar-jemput jika ia lanjut S2 di Samarinda.
Tidak ada kata tidak mampu bagi Bibi yang usianya masih relatif muda. “Yang penting, aku sudah tidak hamil lagi.”
Bibi berniat untuk mengambil jurusan kesenian. Tidak lagi PAUD. Setelah lulus S2, Bibi ingin menjadi dosen di bidang kesenian. Sebab, sedari kecil, cita-cita Bibi memang bergerak di bidang tersebut. Ia aktif mengikuti kegiatan bernyanyi dan menari.
Sewaktu lulus SMA, kepala sekolahnya merekomendasikan agar ia kuliah di perguruan tinggi seni di Yogyakarta. Ia berkomitmen untuk membantu mencarikan dana beasiswa untuk Bibi. Tetapi, orangtua Bibi tidak memberikan izin baginya bersekolah jauh.
Terbersit rasa penyesalan di diri Bibi. Ketika masih sekolah, Bibi termasuk siswa berprestasi. Ia selalu mendapatkan ranking dan kerap memenangkan lomba.
Tetapi ia tidak menyalahkan orangtuanya. Ia sadar tidak mudah bagi mereka untuk menanggung keperluan hidup anak-anaknya. Tidak sedikit biaya yang perlu mereka keluarkan.
“Orang ndak mampu juga, kan. Saudara ada delapan. Saya sudah yang terakhir.”
Mimpi Bibi untuk sekolah kembali mesti ia tunda dulu.
Gaji Rp3,4 juta hanya berlangsung selama dua bulan. Kini ia masih menunggu pemerintah daerah membayarkan gajinya, yang turun menjadi Rp1,1 juta, dan belum juga cair sejak Januari tahun ini. Sementara, biaya S2 di universitas impiannya cukup mahal baginya. Rp5 juta per semester.

Tidak apa-apa, kata Bibi. Sembari memandangi bangunan rumah dan sepatu anaknya yang sama-sama bolong, ia berkata, “Mudah-mudahan nanti ada rezeki.”
*Demi keamanan narasumber, Bibi dan nama-nama lain di artikel ini bukanlah nama sebenarnya.
Artikel ini adalah serial liputan Project Multatuli mendokumentasikan lika-liku #DuniaPendidikan.










