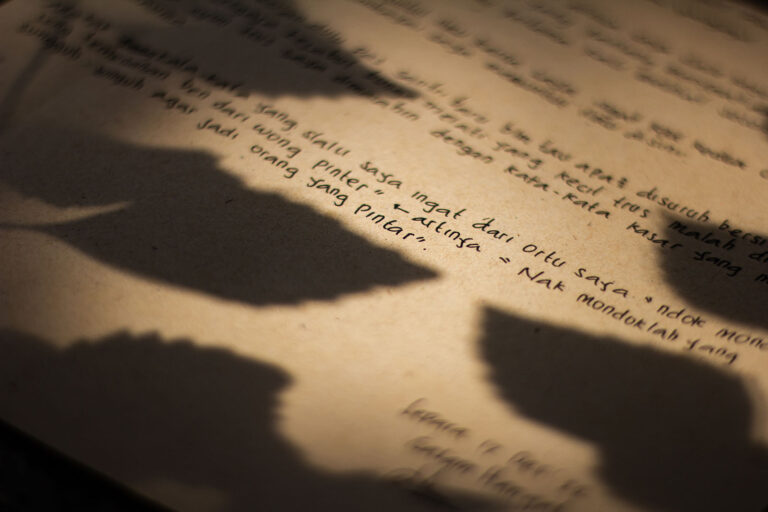Kisah tentang tiga sekolah swasta yang hidup segan mati tak mau, dengan jumlah murid kurang dari 20 siswa, dengan upah guru honorernya Rp20 ribu per mata pelajaran.
Suasana kompleks Sekolah Yayasan Dr. Wahidin di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tampak landai. Meski kompleks sekolah itu terdapat SMP dan SMA Dr. Wahidin, tapi terlihat tak berpenghuni. Sesekali tampak guru yang keluar masuk ruang kelas setelah mengajar. Sementara peserta didik nyaris tak terlihat.
Sekolah ini memang beda dari sekolah pada umumnya. Jumlah peserta didik hanya ada 14 orang. Rinciannya, 3 siswa di kelas X, 6 siswa di kelas XI, dan 2 siswa di kelas XII. Kondisi ini bukan karena sekolah ini eksklusif, tapi memang kekurangan siswa.
“Setelah ada kebijakan (sistem) zonasi, kami mulai kesulitan mendapatkan siswa atau surut jumlahnya. Terlebih ada sekolah di sekitar membuka program baru,” kata Kepala SMA Dr. Wahidin, Suwajirah, pada awal Maret 2024.
SMA Dr. Wahidin pernah mencapai masa jaya dengan memiliki 5 rombongan belajar dengan dua jurusan, IPA dan IPS. Setiap grupnya saat itu diisi 20 hingga 25 siswa. Itu terjadi pada 1996-2005. SMA itu juga bekerja sama membuka kelas pariwisata.
Namun, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan signifikan, terlebih saat pandemi COVID-19. Siswa yang mendaftar hanya 2 atau 3 anak setiap tahun ajaran baru. Beberapa siswa memutuskan pindah sekolah karena terlalu sepi.
“Kemarin (2022) sekolah sudah mau ditutup, enggak mau melanjutkan, tapi yayasan masih ingin mempertahankan tetap dibuka,” katanya.
Hidup segan mati tak mau. Siswa yang sedikit merembet ke keuangan sekolah, termasuk guru honorer yang gonta-ganti karena sekolah tak mampu memberi upah layak.
Persoalan lain, dalam tiga tahun terakhir, tidak ada lulusan SMP di sana meneruskan ke SMA satu yayasan, ujar Suwajirah. “Sekitar 80 persen siswa SMP Dr. Wahidin sekarang memilih ke SMK,” lanjutnya.
Para guru SMA Dr. Wahidin sudah berupaya menjaring siswa dengan mendatangi berbagai SMP negeri maupun swasta di kawasan Mlati dan sekitarnya. Tapi cara itu terasa semakin sulit. Banyak sekolah setingkat SMA tumbuh dan berkembang lebih baik dibandingkan SMA Dr. Wahidin, termasuk dari aspek kualitas.
Mereka lantas bersiasat dengan menerima siswa pindahan, meski hasilnya sama saja.
Suwajirah berkata persoalan finansial sekolah sangat memprihatinkan. Memang ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, tapi nominalnya sangat kecil karena berbasis jumlah siswa, tambahnya.
Di sisi lain, kewajiban siswa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) juga macet. Ada dua kategori SPP di sekolah itu, Rp250 ribu/bulan bagi siswa kategori mampu dan Rp150 ribu/bulan untuk siswa tak mampu. Rata-rata, siswa hanya membayar saat awal masuk, kemudian tak membayar lagi bahkan hingga lulus.
“Rata-rata siswa dari keluarga tak mampu, kesadaran membayar sangat sulit. Sangat kesulitan membayar operasional,” ujarnya.
Keuangan sekolah yang sulit berimbas pada kemampuan membayar honor yang layak. Guru honorer dibayar Rp20 ribu/satu jam pelajaran. Selain itu, ada honor tambahan berdasarkan jabatan berkisar Rp50 ribu-Rp300 ribu. Praktis, guru honorer tanpa jabatan hanya mendapatkan upah rendah.
Sudahlah upahnya rendah, guru-guru di sana pernah tidak menerima honor pada 2020-2022 saat pandemi COVID-19.
“Khususnya membayar honor guru, kami tidak bisa tertib karena orangtua siswa tidak membayar kewajibannya. Kadang enggak ada pemasukan. Jadi kami harus menanggung semua itu,” ujar Suwajirah.
“Yayasan hanya memberikan lahan atau tempat untuk [guru honorer] mengejar karier, cari pengalaman. Untuk fasilitas honor yayasan tidak bisa membantu apa-apa. Jadi apapun keadaannya dikelola mandiri [oleh sekolah]. Banyak berkorban kepala sekolah.”

Suwajirah berkata seandainya menutup sekolah, ia kasihan dengan keberadaan siswa yang memerlukan pendidikan, khususnya ijazah, untuk kelanjutan masa depan peserta didik. Apabila tetap lanjut, dana terbatas membuat hampir segala pekerjaan di sekolah seakan dibayar ucapan terima kasih saja.
“[Untuk mencukupi dana] operasional kami sudah menyerah. Tidak bisa [mencukupi] untuk operasional. Mereka [guru SMA Dr. Wahidin] harus rela, berbakti, dan sabar,” ungkapnya.
Dari 14 siswa, hanya 6 siswa memiliki atau tinggal bersama ayah dan ibu. Sisanya, dibesarkan orangtua tunggal, ada pula yang hidup bersama kakek dan nenek.
Salah seorang guru honorer SMA Dr. Wahidin, Galih Janur Safitri, mengisahkan pahit dan getir menjadi pengajar di sekolah ini sejak Juli 2022.
“Saya menjadi guru Bahasa Indonesia dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 12 dalam sebulan,” ujar alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta ini.
Galih diberi honor Rp20 ribu per jam pelajaran. Selain itu, karena jadi bendahara sekolah, ia menerima tambahan Rp150 ribu. Sehingga, ia menerima honor Rp390 ribu/bulan. Mengelola keuangan sekolah, Galih bercerita pernah cuma mengurus dana Rp2 juta dalam sebulan.
“Persoalannya kadang pengeluaran dan pemasukan tidak tercatat dengan baik,” katanya. “Semoga ke depan sekolah ini dapat lebih berkembang dengan struktur yang bagus dan tertata.”
Selain di sekolah ini, Galih menambah jam pelajaran di SMP Hamong Putera, Kecamatan Ngaglik. Di sana ia memiliki 18 jam pelajaran dengan honor Rp35 ribu. Dalam sebulan, di sekolah itu, ia memperoleh honor Rp630 ribu.
Defvi Rahmawati, guru SMA Dr. Wahidin, merasakan hal serupa. Menempuh 22 km dari rumahnya menuju sekolah setiap hari, Defvi mengajar mata pelajaran Biologi, Kimia, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di sekolah ini sejak Oktober 2023.
Total semuanya, Defvi memiliki 14 jam pelajaran, dengan kata lain hanya menerima upah bulanan Rp280 ribu. Defvi kini menggantikan Galih sebagai bendahara sekolah.
Mengandalkan upah sebagai guru honorer saja tidak cukup, alumnus Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma mencari tambahan dengan berbisnis thrifting atau menjual pakaian bekas layak pakai.
“Semoga sekolah ini menjadi lebih baik dalam mengelola dan diurus kembali dalam struktur sekolah,” katanya.
Remuk karena Konflik Internal
Situasi SMA 17 Yogyakarta serupa dengan SMA Dr. Wahidin. Meski SMA 17 berada di pusat Kota Yogyakarta, jumlah muridnya hanya 15 siswa, terdiri dari 5 siswa kelas X, 7 siswa kelas XI, dan 3 siswa kelas XII.
Kepala SMA 17 Yogyakarta, Bambang Eko Jati, yang mengajar di sekolah ini sejak 1989, mengisahkan konflik internal yayasan membuat lahan gedung sekolah yang lama diambil alih.
“Dahulu siswa kami banyak, meski terus berkurang sampai ada sekitar 80-an. Ada jurusan IPA dan IPS. Setidaknya ada 6 kelas,” kata Bambang.
Setelah terusir, kegiatan sekolah ini berpindah-pindah. Pernah menumpang di SMP 12 Yogyakarta, lalu pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra, kemudian berbagi tempat dengan SMP 17 “1” dan SMP 17 “2” sampai sekarang.
“Sejak pindah, fasilitas sekolah berkurang. Ruang kelas terbatas dan sekarang harus berbagi dengan SMP di sini,” ujar Bambang.

Saat COVID-19 tahun 2020, kondisi SMA 17 Yogyakarta makin terpuruk. Setiap awal tahun ajaran baru, hanya menerima 2 siswa baru. Pada tahun 2023 hanya menerima 5 siswa.
“Kami diuntungkan SMP 17 “1” dan “2”, ada yang masuk ke sini. Ada siswa yang melanjutkan ke sini. Kalau dari sekolah lain harus mencari,” katanya.
Imbas lainnya adalah tenaga kerja guru. Banyak guru yang enggan lama-lama mengajar di sekolah ini. Pihak sekolah pontang-panting mencari guru pengganti. Guru mata pelajaran Kimia dipinjam dari SMA Gajah Mada, guru mata pelajaran Fisika dari SMA Sang Timur.
“Ngajar 1 anak dengan 100 anak itu bebannya sama. Murid banyak, pemasukan banyak, murid sedikit pemasukan sedikit. Tiga tahun terakhir kita buka [jurusan] IPS semua,” ujar Bambang.
Sumber keuangan SMA 17 tak bisa hanya mengandalkan SPP siswa, sebab selain siswanya cuma 15 anak, lebih sedikit lagi yang membayar tertib karena mereka dari keluarga miskin. Pihak sekolah tidak berani menagih keras-keras sebab berisiko kehilangan peserta didik.
“Ada yang membayar, tapi tak rutin. Awal bayar Rp300 ribu, setelah itu tidak lagi,” ucap Bambang.
Maka, operasional sekolah sepenuhnya menggantungkan dana BOS. Dana BOS terakhir yang diterima sekolah sekitar Rp24,9 juta per tahun. Sekitar Rp6 juta-Rp7 juta untuk membayar honor. Sisanya untuk operasional dan kebutuhan siswa.
Itu berimbas pada upah guru honorer yang cuma mendapatkan Rp20 ribu per mata pelajaran.
Upah segitu kecil, kata Bambang mengakui, tapi ia “terpaksa” menerapkannya karena keuangan sekolah yang minim.
Di sisi lain, ia bersyukur pihak yayasan tidak meminta uang setoran. “Pihak yayasan bilang kalau siswanya 100, silakan setor berapa. Kalau kurang dari 100 siswa, silakan dikelola. Tapi, kalau enggak kuat, gimana caranya bertahan,” ujarnya.

Bambang tak pernah berpikir menutup sekolah Selain itu, ia merasa berutang budi pada sekolah. Ia sempat merasakan masa jaya sekolah ini karena itu ia tetap bertahan.
Pada 1980-an, SMA 17 Yogyakarta memiliki 45 kelas dengan 40 siswa per kelas. Para guru yang merasakan masa itu dan masih hidup masih rela berjuang membantu kelanjutan kehidupan sekolah.
Nasib Sekolah Pinggiran
Kondisi SMK Darma Bhakti di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, juga tidak lebih baik. Saat ini hanya memiliki 4 siswa terdiri dari 2 siswa kelas X dan masing-masing 1 siswa kelas XI dan XII.
SMK dengan program studi Keperawatan Sosial ini menjadi satu dari tiga sekolah di Yogyakarta yang memiliki program keahlian serupa. Sayangnya, peminatnya semakin rendah.
Kondisi sekolah di Jalan Wates KM. 14 ini tampak seperti sekolah yang sudah mati. Pagar sekolah berubah jadi tanaman jagung. Di bagian lain, sebuah bangunan dipakai untuk Taman Kanak-kanak.
“Siswa di sini memang minim tapi warga sekolah semangat membangun kemajuan sekolah,” kata Kepala SMK Darma Bhakti Sedayu, Hadianto Saputra.
Empat siswa yang masih bertahan itu dididik sembilan guru. “Kendalanya memang jumlah siswa karena tergolong sekolah kecil,” ucapnya.

SMK ini pernah memiliki 20 peserta didik per kelas pada 2000, tapi terus merosot. Hadianto cukup menyayangkan anak-anak saat ini kurang tertarik pada program Keperawatan Sosial meskipun gratis ditanggung BOS.
“Kalau ujian praktik industri, biaya sendiri. Guru dari yayasan digaji yayasan,” katanya.
Saat ini Hadianto dan para guru SMK Dharma Bhakti berjuang agar sekolah tidak ditutup. “Kami berupaya sekolah tetap eksis dalam kondisi apapun,” ucapnya.
Di Yogyakarta, ada 137 SMA terdiri 69 SMA negeri dan 104 swasta, berdasarkan Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu ada 206 SMK dengan 50 negeri dan 156 swasta.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Didik Wardaya, mengatakan pengelolaan sekolah swasta tetap menjadi kewenangan yayasan yang menaunginya. Meskipun, Dinas Pendidikan setempat juga melakukan pemantauan atau kontrol.
“Terkait jumlah siswa dan segala macam, tergantung strategi masing-masing sekolah. Kita mencoba supaya sekolah itu tetap bisa mendapatkan siswa,” ujar Didik.
Ia mengetahui sejumlah sekolah swasta itu pernah menapaki kejayaan dengan memiliki banyak peserta didik. Dengan terjadinya penurunan jumlah siswa itu, Didik menilai pihak sekolah dan yayasan harus kerja keras untuk menarik minat masyarakat.
“Seharusnya sekolah berusaha memberikan layanan terbaik supaya masyarakat tertarik,” katanya.
Menurut Didik, jumlah ideal per rombongan belajar di sekolah sekitar 20 hingga 30 siswa. Apabila jumlahnya di bawah itu, sekolah itu masuk kategori perlu digabungkan sekolah lain.

Didik menyatakan tiga sekolah itu sebaiknya digabungkan dengan sekolah lain dengan tujuan agar manajemen dan pembelajaran lebih efektif.
“Kalau jumlah peserta didik sedikit tidak efektif juga. Tidak mungkin sekolah mampu menggaji honor guru. Misal, jumlah siswa 4, diberikan dua guru dengan berbagai mata pelajaran, enggak efektif juga,” tambahnya.
Proses menggabungkan sekolah harus sepengetahuan gubernur dan rekomendasi Dinas Pendidikan DIY. Sebab, wewenang SMA/SMK berada di bawah Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Betapapun itu menjadi opsi terakhir apabila pihak sekolah dan yayasan tidak mampu mengelola lagi.
“Tetapi untuk menutup sekolah, kita harus melihat perkembangan. Memang ada sekolah sebelum ditutup menyarankan untuk bergabung. Yayasan satu dengan yayasan lain bisa merger. Siapa tahu dengan cara itu, dengan perbaikan manajemen bisa menjadi lebih besar. Tapi ada kadang yayasan berpikir tidak mau bergabung,” ucapnya.
Laporan ini adalah bagian dari serial #DuniaPendidikan yang mengangkat beragam kekusutan sistem pendidikan Indonesia. Serial ini didanai oleh Kawan M.