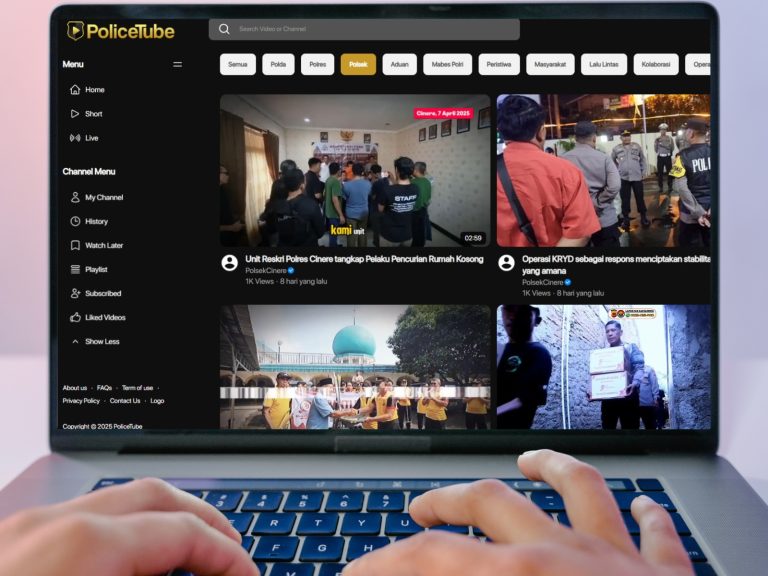Empat akar masalah Polri: warisan cara kerja Orde Baru, penggelembungan tugas dan wewenang, minimnya pengawasan, dan impunitas.
Pasca aksi menolak RUU Pilkada, dalam gelombang protes #PeringatanDarurat dan ‘Darurat Demokrasi’ yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa, tagar #DaruratKekerasanAparat dan #PolisiBrutal menggema di media sosial X. Kemunculan tagar ini disertai berbagai video dan foto yang menunjukkan kekerasan aparat di berbagai daerah dalam “mengamankan” aksi massa tersebut.
Dokumentasi foto dan video kekerasan aparat yang tersebar mengindikasikan ada korban luka parah di antara para demonstran. Aparat diduga menyiksa demonstran di Makassar dan menembaki mahasiswa dengan gas air mata di Palu dan Semarang. Seorang mahasiswa di Semarang bahkan menyebut tindakan beberapa aparat “seperti iblis”. Bahkan ada mahasiswa yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan hingga menjalani operasi akibat tindak kekerasan oleh polisi.
Rentetan kekerasan ini menunjukan kepolisian telah melanggar kode etik mereka sendiri, sebagaimana diatur dalam aturan pelaksanaan tugas kepolisian yang mengharuskan anggota Polri memperhatikan prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas.
Selain berbagai tindak kekerasan, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) juga menemukan penangkapan ratusan mahasiswa. Polisi bahkan menghalang-halangi pendampingan hukum untuk para demonstran yang ditangkap. Jurnalis pun tak luput dari kekerasan dan intimidasi polisi; beberapa jurnalis dilaporkan mengalami luka saat meliput.
Sewenang-wenang, Berulang-ulang
Kekerasan aparat terhadap peserta demonstrasi merupakan kelakuan berulang. Aksi ‘Reformasi Dikorupsi’ 2019 dan ‘Tolak Omnibus Law’ 2020 menjadi contoh betapa tindakan kekerasan terhadap penyampaian pendapat di muka umum polanya sama. Warga menggunakan istilah “brutalitas polisi” untuk menggambarkan kekerasan ini, termasuk juga kasus penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, sepanjang 2020 hingga 2022, kepolisian menjadi aktor kekerasan yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Pelanggaran hak memperoleh keadilan menjadi yang paling banyak diadukan terkait polisi.

Brutalitas kepolisian ini mendorong masyarakat menggaungkan tagar #DaruratKekerasanAparat dan #PolisiBrutal sebagai bentuk keresahan dan kemarahan pada institusi ini. Rakyat mengharapkan institusi kepolisian yang profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Publik terus disuguhi berbagai peristiwa kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara terbuka tanpa malu-malu seolah tindakan itu sudah normal dan wajar bagi kepolisian.
Kekerasan yang saat ini terjadi sangat mirip dengan peristiwa Kanjuruhan yang membunuh 135 orang dan melukai lebih dari 600 orang. Boro-boro reformasi kepolisian, setelah tragedi tersebut, korban-korban bahkan merasa tidak mendapatkan keadilan dan jalan mereka mendapatkan keadilan pun diwarnai ancaman dari “pihak-pihak tak dikenal”.
Masih ingat kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo?
Setelah pembunuhan itu, sejumlah petinggi kepolisian melakukan berbagai tindakan obstruction of justice (dengan merekayasa peristiwa kejadian dan menghilangkan bukti CCTV) untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan tersebut yang pada akhirnya terungkap di persidangan. Tak lama berselang muncul kasus keterlibatan Teddy Minahasa dalam pusaran narkotika.
Kasus-kasus tersebut, selain menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang juga dapat dilakukan oleh pejabat polri, sekaligus puncak gunung es atas berbagai permasalahan dalam tubuh institusi Bhayangkara.
Kekecewaan mayarakat terhadap kelakuan polisi itu sudah diungkapkan sejak saat itu lewat tagar #PercumaLaporPolisi dan ‘No Viral No Justice’. Sayangnya, suara itu tidak pernah dianggap serius.
Upaya perbaikan serius dari pemegang otoritas yang seharusnya mengawasi dan memperbaiki polisi juga tidak berjalan. Meski Presiden Joko Widodo pada akhir 2022 pernah memanggil para perwira ke istana negara, namun perbaikan secara fundamental terhadap institusi Polri belum diimplementasikan, terbukti dengan pertunjukan kekerasan oleh polisi belakangan ini.

Kekerasan Jadi Cara Polisi ‘Menjaga’
Hasil pemantauan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada periode Juli 2023-Juni 2024 mencatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Peristiwa kekerasan tersebut terdiri dari antara lain 36 kasus pembubaran paksa, 33 peristiwa intimidasi terhadap warga sipil, 52 peristiwa penganiayaan dan 37 penyiksaan. Tercatat pula 35 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang menyebabkan 37 korban jiwa.
Berdasarkan pemantauan yang sama, mayoritas peristiwa kekerasan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, menjadikan upaya penegakan hukum pidana sebagai penyebab tertinggi terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan. Angka kekerasan yang dicatat oleh KontraS mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada periode Juli 2022-Juni 2023, tercatat 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian.
Angka ini menunjukkan penggunaan kekerasan merupakan pendekatan utama yang digunakan oleh kepolisian dalam “menjaga” keamanan.
Dalam konteks penegakan hukum, berbagai peristiwa penyiksaan seperti yang diduga dialami oleh Afif Maulana, seorang remaja di Padang, menjadi bukti bahwa penegakan hukum masih umum dilakukan dengan mengedepankan tindak kekerasan, padahal UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan kepolisian Indonesia gagal memahami Hak Asasi Manusia (HAM) saat di lapangan, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kultural dan reformasi institusi di Polri, dengan kata lain reformasi total.
Empat Akar Masalah Polri
Tim kami memetakan empat aspek utama akar permasalahan dalam institusi Polri: warisan cara kerja Orde Baru, penggelembungan tugas dan wewenang (menggurita dan melebar ke mana-mana), minimnya pengawasan, dan budaya permisif terhadap kekerasan yang cenderung melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.
Warisan budaya Orde Baru masih menghantui institusi kepolisian yaitu berkarakter seperti tentara (bukan pengayom) dan menjadi alat pemerintah. Praktik kekerasan yang sudah mengakar ini terlihat jelas dalam berbagai tindakan Polri selama pengamanan aksi massa, seperti penggunaan senjata berat secara berlebihan yang kerap mengakibatkan korban jiwa.
Tragedi seperti peristiwa Kanjuruhan dan kasus kekerasan lainnya di Rempang dan Papua mencerminkan kegagalan Polri dalam melindungi warga sipil dan menunjukkan kecenderungan Polri sebagai alat kekuasaan daripada pengayom rakyat.

Setelah reformasi, Polri dipisahkan dari TNI melalui dua ketetapan MPR tahun 2000 dengan harapan dapat menjadi institusi yang demokratis dan berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM), sesuai UU kepolisian tahun 2002. Namun, sifat otoriter dalam pemolisian tetap ada. Polri cenderung bertindak berdasarkan kepentingan institusi daripada publik. Polri malah menganggap HAM sebagai hambatan dalam tugas mereka.
Kedua adalah penggelembungan tugas dan wewenang. Amandemen UUD 1945 memandatkan Polri sebagai “alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
Dalam UU 2/2002 total terdapat 36 kewenangan polisi termasuk memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Wewenang yang terlalu luas membuat Polri rentan memiliki konflik kepentingan selain menjadi tidak fokus pada tugas utamanya.
Akar permasalahan lain adalah minimnya pengawasan atas kewenangannya. Secara teoritis, semakin besar wewenang, semakin ketat pengawasannya.
Idealnya, pengawasan terhadap kepolisian dijalankan secara berlapis (multi-layered oversight) dan demokratis (democratic oversight) mulai dari pengawasan internal hingga pengawasan eksternal oleh lembaga negara lain, serta dengan menciptakan transparansi agar pengawasan oleh publik dapat berjalan.
Sayangnya, pengawasan internal kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta mekanisme akuntabilitas melalui Komisi Kode Etik Kepolisian seringkali tidak berjalan efektif. Bahkan, pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, kepala Divisi Propam justru menjadi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan keji.
Lebih jauh, kepolisian saat ini sebenarnya tidak memiliki pengawasan eksternal. Kompolnas tidak dapat disebut sebagai pengawas eksternal karena tiga orang berasal dari pemerintah. Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
Klaim kerap dibuat dengan mengatakan ada pengawasan eksternal melalui hubungan dengan berbagai lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komnas HAM.

Sayangnya, hubungan dengan berbagai lembaga dalam rangka pengawasan tidak efektif. Mereka hanya memberi rekomendasi dan catatan tanpa pernah berhasil menyentuh dan memperbaiki akar masalah. Tanpa pengawasan eksternal dan internal dan tanpa transparansi publik, maka berbagai kasus pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terus berulang dan menjadikan para anggota polisi menikmati impunitas.
Maka, jika ingin menghentikan #PolisiBrutal, dibutuhkan perbaikan kultural, institusional, dan instrumental, dengan kata lain reformasi total.
Mirisnya, alih-alih memperbaiki akar permasalahan kepolisian, muncul wacana untuk melakukan revisi terhadap UU kepolisian yang malah membuka peluang polisi makin sewenang-wenang. Walaupun pada akhirnya wacana ini batal dilakukan oleh DPR periode ini, tapi masih membuka kemungkinan dibahas lagi. Jika DPR melanjutkan pembahasan dengan menggunakan draf versi terakhir, maka perbaikan dan reformasi polisi akan semakin jauh dari harapan.
Asfinawati adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Ia merupakan advokat hak asasi manusia yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang tertindas dan pencari keadilan.
Hans G. Yosua adalah peneliti HAM pada Divisi Riset KontraS.
Artikel ini adalah opini perdana dari serial opini yang akan dirilis di platfrom kami oleh koalisi masyarakat sipil untuk reformasi Polri. Ikuti akun Instagram sekretariat reformasi kepolisian untuk ikut mengawasi polisi agar tidak ugal-ugalan.