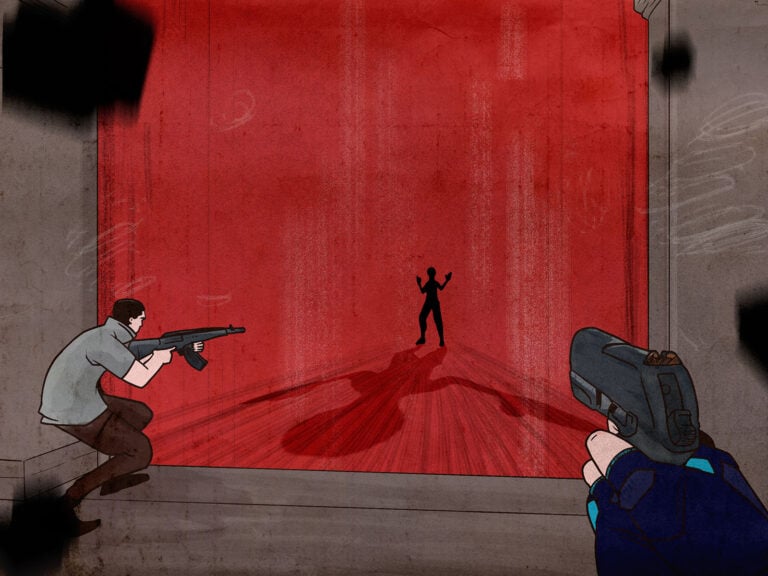ANDI AMIR baru saja tidur pada bakda subuh minggu pertama bulan Ramadan tahun 2005, ketika ia tersentak oleh koor teriakan dari seberang kali.
“Api-api, kebakaran-kebakaran.”
Di perkampungan seperti Kerapu, tempat tinggalnya, juga seperti di Lodan, kampung tempat teriakan berasal, kebakaran adalah peristiwa yang bisa sewaktu-waktu berubah menjadi tragedi kolosal. Sehingga, tidak ada alasan bagi Andi untuk melanjutkan tidurnya. Semula ia mengira kebakaran itu sedang terjadi di kampung tetangganya, namun Andi keliru. Ternyata api justru berkobar-kobar melalap rumah Rohani tepat di samping rumahnya.
Panik, Andi lintang pukang melakukan semua cara yang mampir di kepalanya untuk mematikan api yang mulai menggila. Ia menadahi air ledeng yang keluar sebanyak air kencing, lalu melalui usaha setengah sia-sia menyiramkannya pada api yang hampir melalap rumahnya. Merasa konyol, ia mengambil air dari kali sebanyak yang ia bisa bersama warga, namun api terlalu berkuasa untuk ditundukkan air dalam ukuran baskom. Dalam pikirannya terlintas pemadam kebakaran di pelabuhan yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya.
Andi berlari secepatnya menuju kantor pelabuhan Sunda untuk meminta bantuan. Tapi atas nama birokrasi dan prosedur, pihak pelabuhan lebih memilih berhemat air ketimbang memadamkan api yang menghancurkan kehidupan Andi dan tetangga-tetangganya.
Andi lantas pulang, berdiri di atas Jembatan Kampung Kerapu sembari memandang matahari yang terlihat samar-samar dari di belakang rumahnya yang remuk dilalap api, sampai ia teringat bahwa ia melupakan satu hal: ia meninggalkan istri dan kedua anaknya.
Andi sedikit beruntung hari itu. Kebakaran yang pada akhirnya meratakan nyaris seluruh harta benda warga Kampung Kerapu itu tidak meminta tumbal keluarganya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Andi mendapati istrinya yang masih memakai mukena dan kedua anaknya yang hanya bercelana dalam dan berkaus kutang tertunduk lesu di sudut taman di samping Museum Bahari dengan raut ketakutan.
* * *

Bagi Sukaidah (58), kebakaran hebat yang terjadi pada pertengahan 2005 itu lebih dari sekadar kehilangan harta benda. Ia memang kehilangan semua harta benda. Irda (25), putri bungsunya, bercerita bahwa tidak hanya harta bendanya yang habis dilalap api, tetapi juga semua dokumen-dokumen penting, termasuk ijazah-ijazah miliknya dan saudara-saudaranya. Namun bagi Sukaidah dan keluarganya, Kerapu adalah denyut kehidupan mereka, bila Kerapu habis terbakar, itu berarti kehidupan mereka pun ikut remuk.
Sukaidah ingat bahwa kebakaran serupa yang juga pada akhirnya membawanya sampai di Kerapu. Itu terjadi pada Maret 1980—masa ketika ia masih menjadi pengantin baru. Kebakaran hebat menghanguskan semua rumah di daerah tempat ia dan suaminya mengekos di Mangga Besar, melumat habis semua harta benda tak seberapa yang ia kumpulkan bersama suami. Trauma atas kebakaran itu membuat ia gentar untuk kembali. Ia kerap di kos sendiri. Suaminya seorang pelayar yang terkadang tidak pulang selama berbulan-bulan.
Seorang saudara membawa keluarga Sukaidah pindah ke Kampung Kerapu. Di kampung inilah kemudian Sukaidah dan suaminya mulai membangun mimpi. Pada mulanya mereka mengontrak rumah panggung sederhana milik seorang warga, berbagi kamar dengan satu keluarga lain dari Sukabumi. Setahun kemudian, mereka membeli rumah itu.
“Kami membelinya secara patungan dengan keluarga yang dari Sukabumi itu. Masing-masing membayar Rp175 ribu,” kata Sukaidah. Dua tahun kemudian, Sukaidah akhirnya menebus separuh hak milik keluarga serumahnya itu setelah mereka memutuskan pindah dari Kerapu untuk kembali ke kampung halaman. “Kami membelinya dengan harga yang sama.”
Bisa dikatakan, bahwa di Kampung Kerapu Sukaidah mulai membangun kehidupannya yang sebenarnya. Di tanah ini ia dan suaminya mulai mengumpulkan harta benda sedikit demi sedikit, merancang masa depan keluarga dan anak-anaknya. Di tempat ini pula ia mendapatkan apa yang begitu ia butuhkan pascatrauma hebat akibat kebakaran di tempat tinggalnya sebelumnya, yakni keamanan; di sini ia bertemu banyak keluarga yang menenangkan dalam wujud tetangganya.
Setelah kebakaran besar 2005 itu, warga berangsur-angsur menata kembali kehidupannya di Kerapu. Tercatat hanya ada satu warga pemilik rumah yang pindah dari Kerapu, yakni Rohani, setelah kebakaran itu. Warga tetap bertahan dengan cara nyaris ajaib dan dengan keteguhan seperti batu.
Mereka membangun bedeng-bedeng di atas puing-puing reruntuhan rumah, tidur di musala-musala, sampai menyewa petakan ala kadarnya sembari pelan-pelan menata kembali kehidupan. Andi memerlukan waktu setahun untuk membangun rumahnya kembali, sekadar bisa ditempati. Sampai beberapa tahun setelahnya ia dan keluarganya masih berbenah, menambal sulam bagian rumah yang masih bolong, dengan pendapatan yang disisihkan mati-matian setiap hari. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, atau dari siapa pun dalam usaha panjang itu.
* * *
Kerapu, dilihat dari sejarahnya barangkali memang pantas disebut sebagai tanah harapan. Kampung itu adalah harapan terakhir bagi orang-orang yang tersingkir oleh pembangunan dan konsentrasi kekayaan yang tidak seimbang; harapan bagi orang-orang yang betapapun telah dimiskinkan secara struktural oleh banyak hal—konsentrasi kekayaan, politik, dan sistem ekonomi—layak memperjuangkan hidupnya sehingga tidak dihinakan. Orang-orang seperti Suminem—penduduk pertama wilayah ini.
Sejarah kampung ini memang tidak bisa dilepaskan dari Mbah Nem, panggilan Suminem. Perempuan sepuh yang sudah 12 tahun mengalami kelumpuhan akibat osteoporosis yang menggerogoti kakinya ini seolah menjadi legenda hidup bagi warga Kerapu sendiri.
“Sewaktu saya pertama kali bertemu, beliau ya sudah terlihat setua sekarang,” kata Djumaing, (52), seperti menegaskan bahwa perempuan tua itu memang pantas menjadi pendiri kampung yang sekarang ia tempati.
Djumaing adalah generasi pertama penduduk Kerapu yang datang ke sana pada tahun 1969, beberapa tahun setelah kedatangan Mbah Nem. Usianya masih 4 tahun ketika orang tuanya memutuskan menguruk rawa-rawa di sisi timur pangkalan bambu Mbah Nem. Bagi anak-anak muda yang terpaut dua generasi dengan Djumaing, cerita soal Mbah Nem adalah kisah tentang Kerapu itu sendiri.
Bagi anak muda Kampung Kerapu seperti Puji, 27, suatu kisah tentang sudut bersejarah di kampung, misalnya reruntuhan bangunan tua di bibir sungai di depan rumah Andi, belum sahih jika belum diverifikasi Mbah Nem.
Pula dengan kabar simpang siur soal Jembatan Kampung Kerapu yang konon dulu bisa dibuka-tutup, atau riwayat kapal-kapal yang dulu pernah memenuhi Anak Kali Ciliwung yang memisahkan Kampung Kerapu dengan Kampung Lodan.
Beberapa deskripsi warga soal Suminem sebagian besar meragukan, kecuali bahwa Suminem lah manusia pertama yang meletakkan denyut kehidupan di Kampung Kerapu. Kisah Djumaing soal perempuan sepuh ini misalnya, kemungkinan besar meleset, karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Mbah Nem sekarang berusia 82 tahun. Artinya, Mbah Nem baru berusia 34 tahun ketika pertama kali Djumaing datang ke kampung ini.
Kerapu sebelum Mbah Nem adalah wilayah tak berpenghuni dan tak ternamai. Orang-orang sebelumnya hanya mengenal tempat ini sebagai tempat kosong di sisi selatan Kampung Japat (sekarang Kampung Lodan). Tanah kosong yang tepat berada di timur Menara Syahbandar dan bekas Weistzijdsche Pakhuizen (Gudang Barat) tempat penyimpanan rempah milik VOC. Jarak kampung ini dengan kedua tempat itu memang hanya dipisahkan oleh kawasan pintu air Penjaringan dan jalan raya.
Wilayah ini, sebelum tahun 1962, tahun kedatangan Mbah Nem, hanya dimanfaatkan oleh satu orang, Pak Jani, sebagai pangkalan bambu. Dengan bantuan Pak Jani lah Mbah Nem kemudian menjadi penduduk pertama yang menetap di wilayah ini.
“Mulanya saya ditawari oleh Pak Jani membeli pangkalan bambunya.”
Ia membelinya dengan harga Rp125 dengan cara mencicil. Mbah Nem tidak tahu persis siapa sebenarnya Pak Jani ini, kecuali bahwa dia orang yang sangat tua dan sehari-hari tinggal di Kampung Japat.

Di atas lahan pangkalan bambu itu kini sudah berdiri Musala Al-Idzhar. Kala itu, pangkalan bambu itu adalah satu-satunya petak tanah tanah yang bisa didirikan bangunan di atasnya. Selebihnya rawa-rawa.
Perlu waktu bertahun-tahun bagi Mbah Nem dan Karyat, suaminya, membangun kehidupan yang stabil dan layak di Kerapu. Setiap ada kelebihan rezeki, mereka mencicil menguruk lahan di sekitar pangkalan bambu dengan serutan kayu gergaji yang ia beli dari orang Semarang bernama Oerip dengan harga 20 perak satu gerobaknya. Kala itu ekonomi Mbah Nem cukup lumayan.
Kerapu sebelum tahun 1970-an adalah wilayah yang ramai. Menurut Mbah Nem, sebelum masa-masa itu, Jembatan Kampung Kerapu bisa naik dan turun laiknya Jembatan Ampera di Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sisi Anak Kali Ciliwung yang membelah Kampung Kerapu dan Lodan adalah tempat persinggahan perahu berukuran kecil dan sedang, terutama perahu-perahu yang rusak dan perlu perbaikan. Di Kampung Lodan, di seberang rumah Andi, dahulu terdapat dermaga kecil yang terhubung dengan dok kapal—anak usaha milik Kantor Pemuliaan Ikan yang terletak di dekat Pintu Air Penjaringan. Dari para nelayan itulah Mbah Nem mengais rezeki. Para nelayan membutuhkan bambu jualannya untuk membuat rumpon—alat penangkap ikan.
Betapapun nampak manis, lantaran penghasilan yang cukup baik dari pangkalan bambu, pilihan tinggal di Kerapu sesungguhnya bukan pilihan yang ideal. Pada awal ia pindah sama sekali tidak ada kepastian kalau segalanya akan berjalan mudah, termasuk soal ekonomi. Pindah ke Kerapu, tinggal sendirian di wilayah yang masih kosong dengan bentang rawa-rawa yang luas, dengan membawa Sunerti, putri sulungnya yang kala itu masih berusia 6 bulan pun bukan perkara yang gampang. Belum lagi usaha berdarah-darah bertahun-tahun untuk menguruk rawa dengan jumlah besar kayu limbah gergaji. Tapi bagi orang seperti Mbah Nem, pilihan dalam hidup seringkali tidak banyak.
“Saya tidak punya uang, melarat, mau ke mana lagi?”
Sebelum sampai di Kerapu, kehidupan Mbah Nem dan keluarganya memang tak ubahnya para peziarah; berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bedanya, Mbah Nem dan keluarganya terkungkung di kamar-kamar kos. Sebelum tinggal di Kerapu, ide soal rumah sama sekali tidak ada dalam bayangan Mbah Nem. Meskipun lahir di wilayah pedesaan di Yogyakarta, ia besar di Jakarta dengan hidup menumpang bude-nya di Luar Batang sampai menikah.
Lantaran itu, begitu mendapatkan sebidang tanah di Kerapu untuk menopang kehidupannya yang sederhana, Mbah Nem bertekad mempertahankannya. Pernah suatu ketika, Rukiyat, saksi jual beli tanah antara dia dan Pak Jani, berniat membeli tanah yang baru dibelinya selama setahun. “Saya ndak mau, terlalu kecil [harganya],” kata Mbah Nem. Tentu saja persoalan harga itu hanya salah satu siasat Mbah Nem untuk menghindari tawaran itu. “Lagipula saya ingin tinggal di sini, saya akan mewariskan tanah kepada anak saya.”
Bagi Mbah Nem dan warga lainnya Kerapu semesta yang menyediakan harapan akan kehidupan lebih baik, betapapun pahitnya keadaan mendera.
* * *
Kisah hidup Elang Junaidi (66) menyimpan cerita lain perihal bagaimana Kampung Kerapu menjadi tempat terbaik bagi warganya dalam menjalani kehidupan di kota seperti Jakarta. Lelaki Bugis itu datang dan kemudian menetap di Kerapu pada tahun 1977 dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang pernah jatuh cinta.
Pada waktu itu Elang adalah seorang pelayar di salah satu kapal Pinisi yang sedang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Mbah Nem saat itu sudah beralih profesi menjadi pedagang gado-gado di pelabuhan setelah Jembatan Kampung Kerapu mati, tak lagi membuka dirinya, sehingga perahu tak bisa datang dan pergi dan menggulung perekonomian keluarga Mbah Nem.
Sunerti, sudah berumur 25 tahun dan lebih muda dua tahun dari Elang, hampir setiap hari membantu emaknya berjualan. Nasib mempertemukan Elang dan Sunerti dalam sebuah perkenalan singkat berujung pernikahan tanpa didahului ikatan cinta.
“Saya mengenalnya cuma tiga hari,” tutur Elang mengenang almarhumah istrinya.
Ceritanya waktu itu Sunerti sudah memiliki seorang tunangan. Namun, karena suatu pertengkaran, sang tunangan mengucapkan satu perkataan tolol dengan berikrar bahwa dia tidak akan menikahi anak Mbah Nem. Sunerti murka dan memutuskan pertunangan itu seketika.

Elang yang tertarik sejak pertemuan pertama dengan Sunerti tiga hari sebelumnya nekad mengajukan lamaran. Ajaib! Mbah Nem yang mulanya membenci orang Bugis karena kenangan pribadi di masa lalu mau menerima Elang sebagai menantunya. “Mau bagaimana lagi,” kata Mbah Nem. “Mereka saling suka.” Tiga hari kemudian mereka menikah.
Pernikahan membuat Elang terikat sepenuhnya dengan Kampung Kerapu. Enam tahun setelah menikah, Elang berhenti berlayar dan bekerja di Kantor Pemuliaan Ikan. Dua tahun kemudian ia beralih profesi menjadi tukang batu lalu di tahun 1995 memutuskan berjualan air bersih. Sepuluh tahun kemudian ia menjalani operasi pengangkatan ginjal yang membuat fisiknya melemah hingga akhirnya dia berhenti berjualan.
Tinggal di Kerapu memang tidak membikin Elang menjadi kaya. Sejak pernikahannya sampai ia akhirnya berhenti bekerja, ia harus berjuang mati-matian menafkahi keluarganya. Meskipun demikian ia selalu bersyukur telah memutuskan hidup di Kampung Kerapu karena di sinilah ia memperoleh kebahagiaan.
Kebahagiaan memang satu hal yang nampaknya mudah didapat oleh warga Kerapu. Sukaidah, misalnya, mengaku tidak akan mau pindah dari Kerapu, bahkan seandainya ia dan keluarganya memiliki tempat yang lebih baik secara fisik seperti tempat tinggalnya sekarang. “Susah mencari tempat sehangat Kerapu. Kami semua keluarga di sini, sudah saling percaya,” katanya.
Pengakuan Sukaidah ini bukannya tanpa alasan. Kebakaran tahun 2005 membuat ia percaya bahwa Kampung Kerapu adalah tempat terbaik yang pernah, sedang, dan akan ia tempati selama hidup. Ia akan selalu mengingat semua kebaikan tetangganya dengan penuh haru ketika mengingat bagaimana tetangganya yang sama-sama tertimpa pulung membantu kehidupannya selama setahun penuh dalam salah satu periode hidupnya yang paling susah itu.
“Beberapa hari setelah kebakaran, para tetangga membantu saya mendirikan tenda, membantu kehidupan keluarga kami selama setahun sampai kami mampu membangun rumah lagi secara sukarela.” Sukaidah tidak yakin ia akan mendapat bantuan semewah itu sebagai seorang istri yang lebih banyak merawat ketiga anaknya seorang diri jika ia tinggal di tempat lain di manapun di sudut kota Jakarta.
Hubungan antar-tetangga di Kampung Kerapu memang demikian dekat. Contoh paling unik dari hubungan itu adalah kisah di balik hubungan saudara sepersusuan antara Puji dan Irda. Menurut Sukaidah, segalanya terjadi kebetulan belaka. Suatu ketika Puji yang berusia 2 tahun dititipkan ibunya yang tengah keluar ke suatu tempat dalam waktu cukup lama. Puji yang memang masih menetek ketika itu ngambek sebelum kepulangan ibunya. Sukaida, waktu itu baru beberapa bulan melahirkan Irda, kemudian menyusui Puji supaya bocah itu lekas diam.
Perkara kedekatan antar warga Kerapu, Puji memiliki penjelasan yang lebih ekstrem. “Di sini,” katanya, “Hampir semua rumah sudah seperti rumah saya sendiri.” Puji tidak asal ngecap. Karena sehari-hari ia memang bisa tinggal di hampir semua rumah di Kerapu, sesukanya.
Tentu saja kekeluargaan bukan satu-satunya alasan kenapa hidup di Kampung Kerapu bisa demikian membahagiakan bagi warganya.

Bagi Andi, hidup di Kampung Kerapu membuat segalanya tampak mudah karena lokasinya yang dekat dengan tempat kerja, pasar, stasiun dan sekolah anaknya. Andi memang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa di salah satu perusahaan di sana sebagai pegawai administrasi. Namun, bagi Andi, faktor kekeluargaan lah yang membuat Kampung Kerapu menjadi tempat pulang yang selalu dirindukan, sehingga tidak pernah ada bayangan di benaknya untuk pindah dari sini.
“Di sini, masyarakatnya gotong-royong, dan punya solidaritas yang tinggi,” katanya sambil menunjukkan layar gawainya yang berisi grup Whatsapp aktif yang menghubungkan warga Kerapu.
Berbagai hal yang dimiliki Kampung Kerapu inilah yang membuat warganya mampu bertahan melewati serangkaian bencana yang mengintai sewaktu-waktu seperti kebakaran atau banjir. Tetapi ada satu bencana yang paling mereka takuti: penggusuran.
* * *

“Kabar soal penggusuran masuk di Kerapu sejak tahun 1975,” kata Djumaing.
Sejak saat itu warga Kerapu tidak pernah benar-benar tenteram hidupnya. Penggusuran bisa berarti kiamat karena semua kehidupan mereka ada di kampung ini. Sialnya, penggusuran ini, sebagai sebuah sampar mustahil bisa diatasi tanpa melawannya.
Dalam sejarah Kampung Kerapu, penggusuran pertama kali baru benar-benar terjadi pada tahun 1990. Penggusuran kala itu terjadi ketika gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Wiyogo Atmodarminto, seorang serdadu mantan Pangkostrad periode 1978-1980 yang memerintahkan pelebaran sungai. Perintah itu benar-benar dilaksanakan 2 tahun kemudian di akhir jabatan Wiyogo.
Penggusuran ini menyapu bersih seluruh rumah yang menjorok ke sungai. Banyak warga Kampung Kerapu terpaksa pindah setelah peristiwa itu.
Pada tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melalui sejumlah media, mengultimatum akan melakukan penggusuran besar-besaran, terutama di kawasan pinggiran Sungai Ciliwung. Kabar itu makin santer pada awal 2015. Pemerintah provinsi menegaskan akan menggusur semua rumah yang berdiri 15 meter dari bibir Anak Kali Ciliwung. Itu artinya, seluruh wilayah Kampung Kerapu harus diratakan dengan tanah. Warga bakal dipaksa pindah ke rusunawa tanpa uang ganti sepeserpun.
“Setidaknya di zaman Gubernur Wiyogo tanah kami dihargai, bangunan kami dihargai, bahkan bangunan WC pun dihargai,” ujar Djumaing kesal mengingat kejadian itu. Uang itu digunakan sebagian warga yang masih selamat dari penggusuran (dengan syarat memangkas rumah sejauh 5 meter dari bibir sungai) untuk membenahi rumah mereka. Hal yang sama tidak terjadi pada 2015.
Penggusuran kali ini, dilawan oleh warga. Pada Selasa 26 Mei 2015 warga tiga kampung di Jakarta Utara (Lodan, Tongkol, dan Kerapu) bersolidaritas atas rencana eksekusi Kampung Kunir dan Kencur di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Ratusan warga tegang menunggu proses negosiasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjalan alot. Warga bersikeras menolak rencana penggusuran. Negosiasi buntu dan berakhir pada keputusan spontan untuk mendatangi rumah pribadi Ahok, meminta kesempatan bicara dan negosiasi.
Malam itu iring-iringan ratusan motor menuju Pantai Mutiara, perumahan dengan penjagaan berlapis di Jakarta Utara, tempat Ahok tinggal. Warga memaksa masuk ke kediaman rumah Ahok dan hampir merobohkan pagar perumahan.
“Sebenarnya waktu itu kami hanya ingin bertemu Pak Ahok dan meminta keadilan.”
Aspirasi warga rupanya disalahpahami. Sejam kemudian, 50-an aparat gabungan bersenjata lengkap datang membubarkan aksi warga. Andi masih mengingat momen memilukan itu.
“Mereka (aparat gabungan) berteriak kepada massa, ‘Bubar tidak, kalau tidak bubar kami tembak.’ Mereka membentak kami dengan menanyakan, ‘siapa pemimpin demonya?’ Ya kami jawab, ‘kami semua!!’”
Suasana demikian panas malam itu dan bentrokan mungkin tidak akan bisa dihindarkan seandainya Guntoro Muhammad, salah satu pimpinan warga, gagal melakukan negosiasi dengan Kapolres Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kemarahan warga Kerapu terhadap rencana penggusuran bukannya tanpa alasan. Sedari awal mendengar rencana penggusuran itu, mereka telah mengorganisasi diri, lalu mengajukan dua tuntutan. Pertama, mereka ingin Pemerintah DKI Jakarta kembali pada kesepakatan yang pernah dibuat bersama warga di era Gubernur Wiyogo; yakni mensterilkan bangunan apapun di sepanjang 5 meter dari bibir sungai. Untuk ini mereka rela melakukan pemotongan rumah.
Kedua, mereka ingin rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk mengubah Kampung Kerapu menjadi “Jalan Inspeksi” diganti dengan “Desa Inspeksi”. Mereka menolak disebut liar oleh Ahok dan dianggap merusak ekosistem sungai dan untuk itu mereka siap diajak bekerja sama oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga Anak Kali Ciliwung secara komunal.
Pertengahan Juni, tanpa kesepakatan tertulis yang terikat secara hukum, pihak kecamatan akhirnya memberi jaminan bahwa warga boleh melakukan pemotongan rumah sampai 5 meter dari bibir sungai. Warga percaya dengan izin lisan tersebut setelah Dinas Tata Air Jakarta Utara melakukan pengukuran rumah mereka, dan wakil gubernur saat itu Djarot Saiful Hidayat dalam satu aksi demonstrasi warga memberikan izin. “Lanjutkan,” kata Djarot, sebagaimana diingat oleh Andi.

Bagi Andi, peristiwa ini justru menjadi awal dari keresahan yang tidak pernah dia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di Kampung Kerapu. “Ramadan tahun itu [2015] benar-benar menjadi Ramadan paling meresahkan buat saya,” kata Andi.
Ia tidak terlalu resah memikirkan bagaimana cara menutupi ongkos perbaikan rumah meskipun ia mesti berjibaku sendirian menanggung ongkos pemotongan rumah itu. Tanpa bantuan pemerintah, Andi pontang-panting mencari uang untuk membenahi rumahnya yang porak poranda karena terpotong separuh, menguras semua tabungan, dan berutang sebesar Rp20 juta kepada keluarga besarnya di Sulawesi untuk pertama kali dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi kenyataannya pemotongan rumah itu ternyata bukan ancaman terakhir kampung mereka dari penggusuran. Ia makin gusar.
Ramadan tahun itu, di akhir Juni tepatnya, Yusuf Majid, Camat Pademangan, mengatakan kepada warga bahwa meskipun warga sudah memotong rumahnya, perintah pembersihan bangunan sepanjang 15 meter dari bibir sungai akan tetap dilakukan di Kerapu dan kampung-kampung lainnya. Warga marah ketika itu. Dua bulan kemudian, di kantor Kelurahan Ancol, bentrok nyaris pecah. Warga yang murka mendamprat Camat Pademangan karena dianggap tidak bisa dipegang janjinya. “Saya sampai membentak dia dan menunjukkan rekaman pembicaraan dia kepada kami di awal bulannya,” kata Andi yang masih emosi jika mengingat kisah itu.
Bagaimanapun, warga sudah mempertaruhkan semuanya. Mendengar rencana penggusuran setelah mereka melakukan serangkaian usaha habis-habisan membuat mereka gemetar. Itu artinya mereka akan menyaksikan kematian semua harapan dan kebahagiaan yang mereka pupuk secara kolektif sejak pertama kali Mbah Nem menurunkan urukan pertama serbuk gergaji seharga 20 perak.
Bagi Nurhayani, istri Andi, masa depan gelap jika kampung tetap digusur. “Entahlah, tidak ada tempat yang aman di Jakarta buat kami selain di Kerapu. Mungkin kami akan pulang kampung di Bone,” katanya.
Reporter: Irda Syani dan Pujiono (relawan muda Kampung Kerapu)
Tulisan ini adalah satu dari serial #SejarahKampungKota yang ditulis dalam kurun waktu 2017-2019 oleh para relawan di Kampung Kota Merekam (KKM), upaya mengedepankan kisah kampung kota di Jakarta yang sedapat mungkin datang dari perspektif warga kampung kota sendiri, demi menandingi narasi-narasi lain yang kerap bias kelas. Mengenai apa itu KKM dan latar belakang dari upaya ini, bisa dibaca di Ide dan Esai. Pembaca bisa mengunduh buku Kampung Kota Merekam di sini.