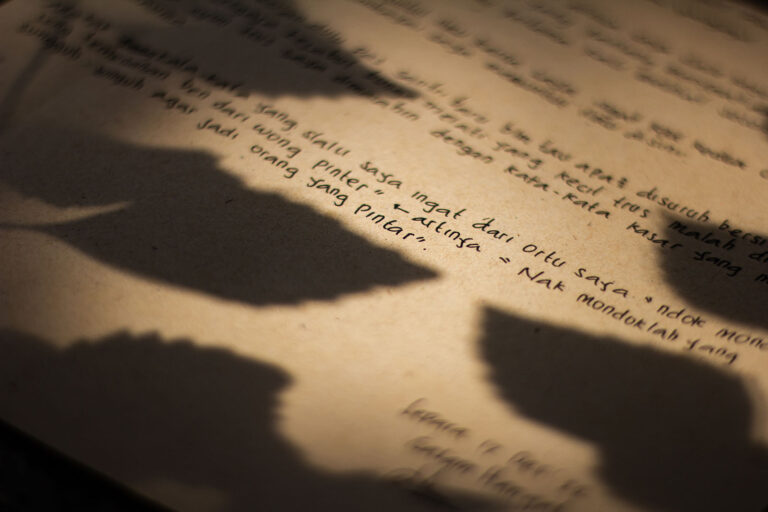Kaluding, 74 tahun, adalah seorang veteran nelayan. Sejak datang di Jakarta tahun 1960, hidupnya ditimang ombak. Ia nyaris tak mengenal daratan. Pria yang akrab disebut Daeng Kalo itu berlayar ke Banjarmasin, Pontianak, Makassar, hingga Surabaya.
Lima tahun setelahnya, Daeng Kalo menyaksikan orang-orang membangun rumah panggung di Muara Baru, Jakarta Utara. Kerangka rumah dibuat dari kayu dolken. Satu meter di bawah lantai dasar rumah itu masih lautan. Samping rumah mereka tak terparkir motor atau mobil, melainkan perahu.
Jalan Muara Baru Raya, masih dikepung alang-alang yang tingginya lebih dari tubuh manusia. “Makanya di daerah sini banyak diketemuin orang, badannya ada tapi kepalanya enggak ada,” ungkap Daeng Kalo. Tetapi warga tak peduli soal itu.
Pada tahun 1978, barulah Daeng Kalo menetap di Muara Baru. Tepatnya di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Gang Kelinci, bagian dari Kampung Marlina. Bersama istrinya, Rohani, 63 tahun, mereka membangun rumah panggung dengan atap alang-alang. Kayu dolken tiga hingga empat meter mereka silangkan ke dasar laut.
“Kami bangun dulu untuk sementara. Daripada kami tidur pinggir jalan,” ucapnya.
Dua tahun setelah kepindahannya, Selasa (11/11/1980), api merambati rumah warga Muara Baru. Rohani terjungkat. Dia dikagetkan jeritan warga saat tengah menidurkan anak pertamanya yang masih berusia tiga bulan.
Kalang kabut. Suaminya masih berlayar di lautan.
Rohani bergegas menggendong anaknya. Hanya memakai bra dan celana pendek, ia lari menjauh dari kampungnya. Dia terobos orang-orang yang sibuk memadamkan api.
Amarah Si Jago Merah tak bisa dibendung. Banyak rumah di Muara Baru terbakar, termasuk kediaman Daeng Kalo dan Rohani.
Setelah kehancuran rumah mereka, Daeng Kalo dan Rohani lalu mengungsi di sebuah tanah becek di tepi tanggul—yang sekarang dikenal dengan nama Gang Elektro.
Solidaritas Jadi Kunci Mitigasi Bencana
Warga saling bahu-membahu menguatkan satu sama lain. Apa yang luluh lantak dibangun kembali. Tjokropranolo, Gubernur DKI Jakarta saat itu, ikut mendukung dengan mengerahkan pasukan tentara (dulu ABRI).
Namun api berganti rupa. Ketika rumah sudah ditempati, berdatangan sekelompok orang mengetuk rumah-rumah warga. Mereka mengaku mewakili pengembang.
Orang-orang itu memaksa warga membongkar rumahnya sendiri. Jelas desakan diiringi ancaman pembongkaran paksa itu ditolak. Bagi warga, tanah adalah bagian dari nyawa mereka.
Daeng Kalo heran. Pemerintah daerah mendukung, tetapi kalangan swasta berlaku sebaliknya. Peristiwa itu membuat kebersamaan warga makin matang. Mereka melawan.
Daeng Kalo memerintahkan anak buahnya, sekitar 200 orang, untuk mengasah bambu runcing. Selanjutnya, bambu itu dijajar di pekarangan setiap rumah. Jika ada yang datang untuk merampas, mereka akan memakainya sebagai senjata untuk menangkal.
Bendera merah putih juga dikibarkan di setiap atap rumah warga. Rutinitas baru warga: berdemo dan melakukan mediasi di kantor gubernur hingga DPR RI. Daeng Kalo terbiasa mengabaikan ancaman yang kerap diulang saat itu: jika protes akan diculik.
“Saya bukan orang politik, Pak. Yang saya bicarakan ini kandang saya dan istri saya. Kandang anak saya,” kenang Daeng Kalo kala itu nyaris pada tiap mediasi.
“Kalau hujan, kehujanan. Panas, kepanasan,” lanjutnya. “Dia mau berlindung di mana? Sedangkan saya bangun kembali rumah ini dapat dukungan dari gubernur langsung.”
Perjuangan berbuah manis. Kampung Muara Baru urung dibongkar. Hingga kini mereka masih bertahan di tanah yang sama.
Namun tahun 2018, ancaman penggusuran paksa kembali datang. Semangat perlawanan menyala kembali di masing-masing warga.
Berebut Tanah Muara Baru
Di ruang tamu rumah Daeng Kalo, seorang pria tampak gelisah. Ichwan, 64 tahun, bercerita soal orang-orang yang datang untuk merampas tanah mereka.
“Rencananya, dia akan,” kata Ichwan memberikan jeda menghisap rokok dalam-dalam, lalu mengembuskan asap. “Berikan tanah kita ke pengembang.”
Orang-orang itu, kata Ichwan, mengaku sebagai ahli waris Tommy Abdullah, mantan ketua RW3 Luar Batang. Dia juga menunjukkan verponding yang menjadi bukti kepemilikan. Tanah yang ia klaim cukup luas, mencakup sebagian kawasan Kampung Elektro hingga Kampung Marlina.
Tiga bulan setelahnya, seorang pria bernama Siman bin Tilan ikut mengaku sebagai ahli waris sah tanah di Muara Baru. Ia juga memiliki verponding.
Merespons kejadian itu, beberapa RT di Kampung Elektro membuat surat pernyataan sikap: tidak akan menjual tanah dan bangunan ke pihak manapun. Surat itu telah sampai ke tangan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Verponding juga ikut ditunjukkan ke gubernur—yang Anies hanya balas dengan senyum.
“Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu biasa mafia tanah, cuma kerikil saja,” komentar Anies seperti diceritakan Ichwan.
Ichwan menjadi yakin untuk beradu di peradilan, “Kalau mau sidang, ya sidang!”
Ichwan percaya warga akan menang kembali. Tanah yang mereka tinggali, telah dikelola secara mandiri lebih dari 40 tahun. Mereka tak pernah luput membayar pajak. Sedangkan ahli waris tersebut terakhir membayar pajak pada tahun 1954.

Empat dekade memang bukan waktu yang pendek. Banyak rintangan yang harus mereka lalui untuk mempertahankan semuanya. Mulai dari ancaman penggusuran, kebakaran, banjir rob, hingga merelakan sebagian kampung mereka ditelan kenaikan air laut.
Sebanyak tujuh RT bahkan rela memisahkan diri secara administratif dari Kampung Muara Baru, dan terlahir kembali dengan nama Kampung Elektro. Semua dilakukan agar bisa bergabung dalam daftar 16 kampung yang tercantum dalam kontrak politik bikinan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang disodorkan pada Anies Baswedan saat Pilkada 2017.
Alasan pemilihan namanya sederhana saja. Letak kampung mereka ada di sepanjang Gang Elektro, sebuah nama yang diteguhkan dari gudang barang elektronik yang ada di sisi barat kampung. Gudang itu telah berdiri jauh sebelum kampung ini ada. Akhirnya identitas gudang itu tumbuh bersama warga, menjadi saksi budaya yang terus berkembang.
Taufik, 66 tahun, seorang saksi hidup terbentuknya Kampung Elektro berujar, “Awal tahun 1970-an, cuma ada beberapa rumah di tepi gudang, bukan di belakangnya.”
Area belakang gudang saat itu, masih berupa tanggul dan kawasan empang yang sepi penghuni. Namun kondisi geografisnya perlahan berubah pada tahun 1976.
Saat itu, pemerintah berinisiatif untuk mengeruk lautan di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa supaya lebih dalam. Aksi serupa juga terjadi di Waduk Pluit. Lumpur hasil pengerukan lalu dibuang ke sisi luar tanggul Muara Baru, memenuhi empang dan menjadi landasan tumbuhnya Kampung Elektro.
Sebelum datang ke sini, Taufik mengontrak rumah di area Pabrik Kaleng. Dia lalu digusur karena tanahnya dibutuhkan untuk pergudangan.
Sebagai kompensasi, Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Pluit memindahkan Taufik dan beberapa keluarga lain ke tanah baru hasil reklamasi lumpur di tahun 1978. Dua tahun sebelum kedatangan Daeng Kalo. Setiap keluarga saat itu mendapat lahan seluas 12×15 meter.
Di samping tiap petak, selalu disisakan jalan sebesar 1,5 meter, untuk menghubungkan ke kawasan pesisir pelabuhan. Jalan-jalan tersebut kini nyaris seluruhnya tertelan oleh pemekaran rumah-rumah warga.
Taufik tidak tahu siapa pemilik lahan baru yang mereka tempati saat itu. Ketika ia menagih surat legal ke pihak BPL Pluit, mereka menolak memberinya. “Mereka khawatir nanti dikira jual tanah kepada saya. Mereka yang kena. Selama tanah itu tidak dibutuhkan, kami bisa pakai katanya,” jelas Taufik.

Berbeda dengan Taufik, Daeng Kalo pindah ke Muara Baru atas inisiatifnya sendiri. Tidak mudah baginya untuk menggarap tanah endapan lumpur. “Di atasnya memang kering, tapi di bawahnya masih basah semua,” ujarnya.
Daeng Kalo membangun rumah di atas lumpur yang menimbun lautan. Dia menanam kayu dolken sepanjang 4 meter sebagai tulang dasar rumah papan. Bekas kandang ayam hingga potongan kulit limbah pabrik alas kaki Carvil, ditimbun untuk memadatkan lumpur. Butuh hitungan tahun untuk menunggu endapan lumpur mengeras.
Setelah mengeras, Daeng Kalo memasang cerucuk dan menanam batu kali. Itu bahan dasar untuk mendirikan pondasi rumah. Cara Daeng Kalo juga dilakukan beberapa warga lain.
“Dulu engga ada istilah tuan tanah,” kata Daeng Kalo.
“Orang-orang yang rumahnya dibongkar di tempat lain datang ke sini [Kampung Elektro],” imbuhnya.
Penghuni baru terus berdatangan, termasuk Kadir, 72 tahun, yang saat ini menjabat sebagai ketua RT 7. Pada tahun 1985, ia memutuskan pindah ke Kampung Elektro karena ajakan seorang kawan. Kadir membangun rumah dari sepetak tanah yang masih becek di sisi utara Gudang Elektro.
“Terus terang saja. Waktu itu, saya cuma bosen bayar kontrakan di Pasar Lama,” kelakar Kadir menjelaskan alasan pindah.
Sewaktu rumah mulai ditempati, Kadir dikunjungi perwakilan RT 15. Mereka mengajaknya mengurus surat-surat terkait rumahnya. “Saya dibikinin kartu kuning yang ada gambar garudanya, disertai stempel RT dan RW,” ceritanya.
Lima tahun kemudian, Ichwan menyusul. Ia membeli tanah yang teksturnya gembur seharga Rp2 juta, tepat di belakang Gudang Elektro. Butuh sekitar tiga bulan baginya untuk selesai mengurug, supaya rumah yang dibangun tak mudah ambrol.
Meski ada kebebasan, ambisi untuk menguasai tanah seperti absen dari warga saat itu. Penghuni baru pun terus berdatangan, tanpa ada yang melarang atau memonopoli lahan.
“Kalau mau main patok-patokan mungkin sudah banyak rumah saya, karena masih sepi. Tapi ya, saya dilahirkan enggak membawa tanah. Saya mati juga masuk ke tanah. Itu saja,” terang Ichwan.
Saat ini, Kampung Elektro sudah menjadi rumah untuk lebih dari 700 keluarga. Letaknya yang dekat Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadikannya populer di kalangan pelaut luar Jawa.
Keberagaman etnis mulai dari Bugis, Serang, Padang, Flores hingga Papua membuat Kampung Elektro menjadi kaya. Namun di sisi lain, keberagaman itu menumbuhkan berbagai gesekan yang memicu konflik sosial di masa lalu.

Jiwa Keras Muara Baru
Pada kurun waktu tahun 1980 hingga 1990-an, Muara Baru terkenal di seluruh Jakarta sebagai kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi. Ichwan menuturkan, kala itu ia sering naik taksi dari stasiun kereta untuk ke rumahnya. Namun sopir taksi kerap menolak mengantarkannya.
“Saya sampai ngomong. Pir, engga usah khawatir. Nanti ada yang macem-macem saya kempesin kepalanya. Baru dia mau,” gelagaknya.
Kehidupan pelaut yang keras menempa karakter penghuni Muara Baru. Sirkulasi uang yang deras di Pelabuhan Sunda Kelapa yang luput dari pengawasan pemerintah, menyuburkan tindakan premanisme.
Di sisi lain, pertikaian antar ras sering terjadi. Daeng Kalo menuturkan, dulu orang Serang dan Makassar saling membenci. Amarah mereka mudah tersulut. Terutama jika berkaitan dengan berebut ladang pekerjaan.
“Apalagi waktu ada lelang ikan,” ujar Daeng Kalo. “Gara-gara ikan satu keranjang saja, bisa bunuh-bunuhan.”
Namun perlahan kebersamaan dipupuk melalui perkawinan. Sekitar akhir tahun 1980-an, banyak perempuan Makassar menikah dengan laki-laki Serang, atau sebaliknya. Mereka mulai membaur dan memutus mata rantai warisan konflik.
Akan tetapi hal itu tak membuat Muara Baru berhenti jadi sumber masalah bagi tetangganya. Wilayah ini tetap dikenal sebagai sarang preman. Banyak dari mereka beraksi di area pergudangan dan kawasan pelabuhan.
Tak hanya itu, Muara Baru dikenal angker karena banyaknya mayat tanpa nama yang dibuang di sini.
“Sekitar tahun 1983 di dekat [Kampung] Marlina kan ada telepon koin. Kalau subuh sudah ada 2-3 mayat ditaruh di situ,” cerita Taufik.
“Di pinggir laut juga sering. Di sekitar alang-alang,” imbuhnya.
Pada kurun waktu yang dimaksud, memang marak aksi penembakan misterius (Petrus) yang menyasar para pembuat onar, atau penghuni dengan catatan kriminal. Banyak dari mereka yang dihakimi begitu saja, tanpa proses pengadilan.
“Warga di sini ada juga yang hilang. Namanya Maroya, Raja Rampok yang sering beraksi di pelabuhan. Dia ditangkap, dikejar, masuk kebun, ditembak. Ada beberapa sih, warga yang lain juga,” tambah Taufik.
Tak jarang, warga tak bersalah juga diberantas hanya karena bertato. Hal itu membuat beberapa warga bersusah payah menghapus tato dengan cara seadanya.
Seperti almarhum Tono yang rela menggosok tatonya dengan setrika panas, atau beberapa warga lain yang menusuk tato mereka dengan jarum berisi sabun. Cara terakhir tak sepenuhnya berhasil. Tato masih cukup terlihat. Yang berbeda hanya ada luka mirip bekas koreng.
Pada pertengahan tahun 1980-an, peristiwa Petrus berhenti. Preman Muara Baru kembali merajai kawasan Sunda Kelapa dan sekitarnya, meski tak lama. Pada sekitar tahun 1991, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) masuk Pelabuhan Sunda Kelapa dan mulai memberantas premanisme.
Seiring waktu, cap sarang preman terhapus dari Muara Baru. Saat ini, warga Kampung Elektro lebih ingin dikenal lewat kegiatan keagamaannya yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja memiliki komunitas pengajian sendiri. Musala selalu ramai setiap harinya. Berbagai ustaz diundang ceramah, termasuk eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab.
Sekolah Alternatif dan Keberagaman
Pada tahun 2019, rumah Ichwan kerap dipenuhi suara anak-anak. Sekitar dua puluh bocah memenuhi ruang tamu yang sudah disulap menjadi kelas kecil. Para ibu mengawasi dari dekat pintu. Sebagian duduk di sebelah anak mereka. Menemani menulis atau mengajari berhitung.
Mereka sedang mengikuti Kelompok Belajar Anak (KBA) asuhan Herdayati, 46, istri Ichwan. Sebuah inisiatif yang lahir dari kegelisahan Herdayati akan pendidikan anak di Kampung Elektro. Ketika anaknya berusia 4 tahun, ia tak bisa menyekolahkan mereka di bangku TK, karena biaya yang terlalu tinggi. Dia semakin resah ketika sadar banyak ibu lain di kampungnya bernasib serupa. Anak mereka lebih gemar bermain jauh dari rumah.
Herdayati lalu mengutarakan usulannya pada Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC). Inisiatif itu direspons hangat dalam bentuk bantuan dana dan pelatihan.
“Saya bilang, Mbak Wardah, di kampung saya banyak anak-anak, tapi enggak ada biaya,” kata Herdayati.
Herdayati menghimpun siswa sekolah di kampungnya, termasuk anak dan keponakannya sendiri, untuk menjadi guru bagi murid yang lebih muda.
Tahun 2004, sekolah nonformal itu menjaring 60 murid tetap. Setiap murid awalnya tidak dikenakan biaya sama sekali. Namun, perlahan kebutuhan mereka naik. Kini setiap murid hanya membayar Rp2 ribu tiap pertemuan.
“Kami kan juga harus ngebayar gurunya,” jelas Herdayati.

Herdayati juga aktif menjadi paralegal LBH Apik. Banyak kasus KDRT terjadi di kampungnya yang diselesaikan dengan diskusi baik-baik. “Denger suara ribut bak-buk-bak-buk, saya ketok pintunya. Assalamualaikum, ada apa sih, Pak?”
Ia mencoba menjembatani pembicaraan antara suami dan istri. Seringkali mereka lalu membuat kontrak seadanya untuk tidak mengulangi kejadian serupa. Namun tak jarang, ada yang lanjut melapor ke polisi.
Herdayati tak kenal lelah berjuang, meski keselamatannya pernah terancam. Pernah seorang pria yang geram karena pelaporan ke polisi, datang ke rumahnya dan mengintimidasi. “Ibu kalau saya cegat di pinggir jalan bagaimana? Kalau pulang, perut ibu sudah terburai?” teriaknya sembari membanting belati ke lantai rumah Herdayati.
“Tapi diancam seperti itu saya malah tak gentar!” sambungnya.
Herdayati adalah contoh kecil bagaimana warga siap bergerak untuk memajukan kampungnya. Mereka selalu berusaha memberi apa yang mereka punya. Majelis dan musala mereka bangun sendiri. Sebulan sekali, gotong royong rutin diadakan. Di kala hajatan, para ibu juga selalu siap membantu tanpa perlu diundang.
Kebanyakan warga Elektro adalah perantau. Mayoritas sadar mereka butuh satu sama lain untuk bertahan dari kerasnya Jakarta.
“Setiap ada yang sakit, pasti ada yang ngetok pintu dan ngabarin. Meski jam 2 atau 3 pagi pasti kami langsung sigap,” tuturnya.
Dukungan bak keluarga itu juga menjangkau lintas agama. Dalam perayaan keagamaan seperti Isra Miraj dan Maulid Nabi, warga non muslim kerap turut menyumbang dana dan membantu perayaan. Begitu juga sebaliknya.
Warga Kampung Elektro juga menopang bersama-sama beban setiap warga yang ditinggal keluarganya. Mereka rutin menghimpun dana kematian. Di RT 14, warga sepakat mematok iuran Rp5.000 per bulan.
Semua itu adalah inisiatif swadaya warga. Sudah empat dekade warga Kampung Elektro membangun rumah, budaya, hingga relasi sosial. Hasilnya bukan hanya dinikmati sendiri oleh mereka, melainkan seluruh warga DKI Jakarta.
Kampung Elektro dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perekonomian pendatang yang tidak menetap. Para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa dan area industri Muara Baru banyak menyewa rumah di sini. Selain itu, kampung ini juga menyuguhkan fasilitas seperti area parkir hingga warung makan bagi para pekerja kerah biru.
Namun semua itu dipandang sebelah mata oleh pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kampung Elektro dianggap sebagai penyakit yang harus disingkirkan demi mewujudkan visi metropolitan bak Singapura.
Ahok melayangkan ultimatum akan menggusur Kampung Elektro. Tak peduli meski mereka memiliki KTP DKI Jakarta, membangun kampung secara mandiri, dan rutin membayar PBB.
“Itu yang bikin warga merasa kecewa kenapa waktu Ahok kok PBB dibebaskan. Waktu itu bongkaran merajalela. Kami was-was apa karena tidak membayar pajak? Warga lebih seneng bayar,” ujar Ichwan.
KTP mereka diblokir. Mereka juga tidak bisa mengurus Kartu Keluarga. Namun mereka tetap memilih bertahan.
“Ancaman itu juga yang jadi alasan kami ikut kontrak politik untuk memenangkan Anies Baswedan,” tegas Ichwan.
Keputusan mereka berbuah positif. KTP mereka sudah aktif kembali. Anies juga terbukti berusaha mewujudkan poin-poin janjinya di kontrak politik. Salah satunya adalah revitalisasi 16 kampung, termasuk Kampung Elektro.
Oleh karena itu, dalam beberapa bulan terakhir, sebagian warga Elektro sibuk mengerjakan Community Action Plan (CAP) Mandiri bersama RUJAK Center for Urban Studies. Di dalam kegiatan itu, mereka berusaha merumuskan aspirasi akan masa depan kampung mereka. Sebuah proses yang rumit dan butuh waktu lama.
Namun kompleksitas diskusi bukanlah hambatan utama bagi para penggiat CAP. Tantangan terbesar adalah menyatukan langkah warga untuk menyukseskan CAP.
“Banyak dari mereka yang ingin hasil cepat dan konkret. Tapi kan proses CAP ini engga bisa seperti itu,” tuturnya.
Warga terpecah menjadi tiga kubu dalam menyikapi CAP. Ada yang pro, apatis, dan kontra. Jumlah penduduk yang tinggi dan keberagaman etnis menjadi tantangan besar dalam pengorganisasian. Banyak dari mereka bersikap acuh tak acuh. Sedangkan mereka yang menolak CAP kebanyakan karena terhasut isu bahwa CAP adalah penggusuran terselubung.
Tak dipungkiri, pada saat proses penataan kampung pasti ada yang dikorbankan. Entah dinding yang digeser, jalan yang harus dilebarkan, atau saluran yang harus diperdalam. Namun semua keputusan itu tentu kembali pada persetujuan warga.
“Kalau misalnya kampung kita sudah bersih dan rapi, kan tidak dianggap kumuh lagi sama pemprov. Harapan jangka panjangnya ya semoga bisa membantu meraih legalitas tanah,” tegas Ichwan.
Ichwan berharap warga untuk lebih proaktif terhadap CAP. Semuanya harus siap berjuang bersama, agar nantinya bisa menikmati hasil bersama. Segelintir orang saja akan kewalahan untuk mewujudkan masa depan yang warga harapkan. “Kalau aktif, yang menentukan masa depan kampung nanti ya warga. Kalau engga, ya nanti pemprov. Padahal kan warga yang paling tahu apa yang mereka mau,” tambahnya.
Sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi para pejuang kampung Elektro. Mereka harus dapat meyakinkan warga bahwa harapan untuk kampung sejahtera sudah dekat dengan genggaman tangan warga. Oleh karena itu, warga harus bergerak cepat. Karena kesempatan menata kampung dengan dukungan Pemprov Jakarta, mungkin tidak akan datang untuk yang kedua kalinya.
* * *
Catatan Editor: Tulisan ini terbit pada awal 2019 di situs Kampung Kota Merekam (yang sudah tutup) dan merupakan hasil liputan sejak 2018 ketika proses CAP belum selesai. Saat tulisan ini diterbitkan ulang pada Maret 2022, proses CAP di Kampung Elektro telah selesai.
Tulisan ini adalah satu dari serial #SejarahKampungKota yang ditulis dalam kurun waktu 2017-2019 oleh para relawan di Kampung Kota Merekam (KKM), sebuah upaya mengedepankan kisah kampung kota di Jakarta yang sedapat mungkin datang dari perspektif warga kampung kota sendiri, demi menandingi narasi-narasi lain yang kerap bias kelas. Mengenai apa itu KKM dan latar belakang dari upaya ini, bisa dibaca di Ide dan Esai ini. Pembaca juga bisa mengunduh buku Kampung Kota Merekam di sini.