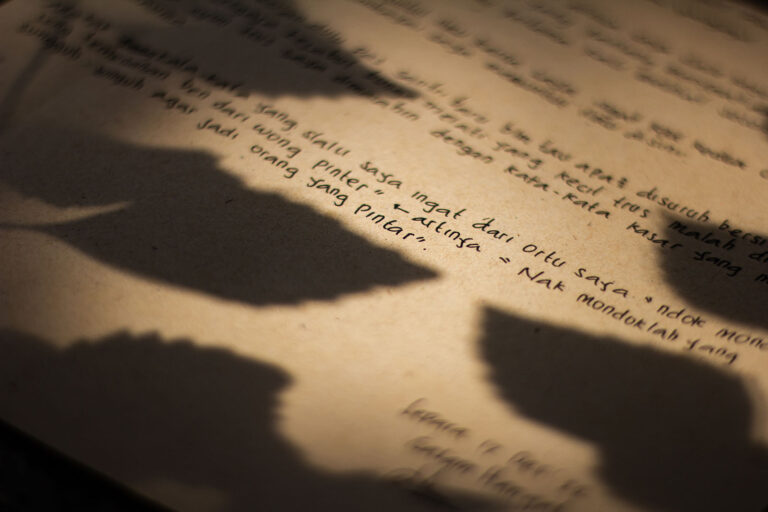RASA SESAL dan sakit hati tak pernah benar-benar hilang dari diri Cahaya. Perasaan itu kerap berubah menjadi air mata setiap ia mengingat dan membicarakan sang ibu yang telah berpulang, dua tahun silam.
November 2020, ibunya mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif selama lima hari melawan virus korona.
Cahaya tak ada di sana, di ruang perawatan maupun di pemakaman. Kala itu, ia juga tengah terbaring, berbalut selang-selang oksigen di ruang perawatan rumah sakit tanggap COVID-19 yang berbeda dari ibunya.
Ia baru bisa mengunjungi makam almarhumah ibunya Februari 2021. Hari itu, ia menangisi kuburan ibunya yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus pasien COVID-19 di Cikadut, Bandung, Jawa Barat.
Cahaya bersimpuh sambil berkali-kali mengucapkan kata maaf.

***
Cahaya, anak bungsu dari tiga bersaudara, adalah lulusan ilmu keperawatan di salah satu kampus negeri di Bandung tahun 2001. Saat wabah merebak, tempatnya bekerja menjadi salah satu rujukan rumah sakit yang menangani pasien COVID-19.
Cahaya sebetulnya tidak pernah ditugaskan merawat pasien COVID-19. Namun dari pengalamannya, ruang perawatan pasien umum itu justru yang paling rentan tertular virus.
“Itu area abu-abu yang tidak jelas apakah dia pasien [COVID-19] atau bukan, kan tidak semua diswab PCR. Kalau swab antigen kan bisa berapa persen kemungkinan false negatif,” kata Cahaya.
Belum lagi penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang perawatan umum cenderung tidak setebal dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien COVID-19.
Cahaya sadar ia bisa sewaktu-waktu tertular. Mendiang ibunya juga menyimpan kecemasan yang sama. Cahaya beberapa kali memergoki ibunya menangis kala mendengar lagu “Demi Raga yang Lain” karya musisi Eka Gustiwana yang mengisahkan perjuangan nakes pada masa pandemi.
Hingga pada November 2020, apa yang dicemaskan mendiang ibu pelan-pelan jadi nyata.
Cahaya mulai merasa nyeri di badannya. Gejala itu ketika ia sedang bertugas dan sempat menghadiri rapat dengan sejumlah rekan kerja. Selang satu hari, gejala lain bermunculan, dari mulai batuk, demam, dan berkurangnya sensitivitas indra penciuman (hiposmia).
Akan tetapi, hasil tes PCR menunjukkan negatif COVID-19. “Kabayang mamah waktu itu senang pisan,” kata Cahaya dengan suara terisak.
Sebelum tes, Cahaya sempat melakukan isolasi ketat di rumah, berjaga-jaga agar ibunya tidak tertular penyakit sama. Setelah hasil tes keluar, isolasi melonggar. Sesekali, Cahaya mengingatkan ibunya untuk menjaga jarak karena khawatir tertular sakitnya.
Hanya saja sang ibu tak pernah absen merawat. Saban pagi, ibunya mengantarkan minum dan telur rebus, membelikan obat serta makanan minuman yang menyehatkan.
Tapi kondisi Cahaya terus menurun. Ia mulai sesak napas, diare, dan mudah lelah (fatigue). Rekannya menyarankan Cahaya dites ulang. Hasil tes keduanya menunjukkan positif terinfeksi COVID-19.
Pada saat yang sama, ibunya mulai mengeluhkan demam, sakit kepala, dan batuk.
Jumat, 21 November 2021, Cahaya semakin kesulitan bernapas. Saturasinya turun ke angka 80. Cahaya akhirnya dilarikan ke rumah sakit, diantar kakak dan ibunya.
“Jumat, saya sudah gak kuat, sudah sesak banget. Tapi saya juga sudah mulai lihat mama sakit,” tutur Cahaya sambil bercucuran air mata, mengingat hari terakhir ia bertemu fisik dengan ibunya.
Setibanya di rumah sakit, petugas langsung membawa Cahaya ke ruang HCU (High Care Unit), menerobos keramaian rumah sakit yang tengah ramai pasien COVID-19.
Pada momen itu, di atas brankar, Cahaya menengok dan berteriak ke ibunya, “Mah, duluan, yah, nanti Mamah nyusul.”
Akan tetapi, sang ibu tak kunjung menyusulnya.
“Saya pikir mamah ngikutin. Ternyata mama gak mau. Jadi mama gak ikut ke IGD. Ternyata, kata kakak, mamah gak mau karena takut diswab, jadi cuma saya sendiri,” kata Cahaya.
***
Di luar pengawasan Cahaya, gejala yang dirasakan ibunya memburuk. Sang ibu menyusul dirawat, tetapi ke rumah sakit berbeda. Sama seperti Cahaya, hasil tes ibunya semula menunjukkan negatif terinfeksi COVID-19. Selang beberapa hari dirawat, hasil tes berubah menjadi positif.
Pada titik itu, rasa sesal dan bersalah mulai membuncah di diri Cahaya. Ia yakin telah menulari ibunya.
“Sudah kita jaga-jaga orang yang kita cintai, malah tertular dari kita,” kata Cahaya.
Pada saat yang bersamaan, ia menerima kabar bahwa lima rekan kerjanya juga dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Lagi, ia merasa itu semua karena dirinya.
“Jadi selain mama, saya juga menulari lima orang teman saya. Lima orang yang ditulari saya sudah masuk rumah sakit. Mereka juga menulari lagi ke keluarganya. Jahatnya COVID-19! Sampai ada yang keluarganya masuk ke HCU juga karena faktor usia,” kata Cahaya, dengan emosi.
Di tengah kegundahan karena merasa bersalah menularkan COVID-19 ke banyak orang, Cahaya mendapat kabar ibunya akan dirujuk ke rumah sakit tempatnya dirawat. Ia begitu menantikan momen ini, berharap bisa bertemu dengan ibu yang selama ini terpisah.
Harapannya pupus. Maut lebih dulu menjemput perempuan yang dikasihinya itu.
Sang ibu hanya bertahan selama tiga jam setibanya di rumah sakit. Mendiang bahkan tidak sempat dipakaikan alat bantu pernapasan.
“Jadi cepat banget. Saya lihat hasil laboratorium, saturasinya 60 persen. Kebayang sesaknya,” kata Cahaya.
“Saya sempat video call mama gak jawab (bicara). Mungkin lagi sesak. Kami cuma saling mandang saja. Itu video call terakhir.”
Pada perbincangan terakhir itu, Cahaya sempat berucap kata saling menguatkan meski sang ibu tak menjawab, ‘kita berjuang bersama-sama ya, Mah. Kita lawan COVID-nya.’
“Kami sempat saling bilang I love you lewat WhatsApp,” ujar Cahaya dengan suara tercekat.

Di Antara Lelah dan Amarah
Di balik hazmat tiga lapisnya, Moza Asri Fitriani (24), menyimpan lelah fisik dan mental yang luar biasa. Moza baru selesai mengetes usap puluhan orang kontak erat dan suspek COVID-19.
Pada Mei 2021 itu, berbarengan dengan mulai merebaknya COVID-19 varian Delta, ia sudah mengetes nyaris 100 orang dalam tiga jam.
Moza bertugas sebagai Kepala Tim 3T (tracing, testing, treatment) Puskesmas Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ia bertugas dalam tim penanganan COVID-19 kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan think tank kesehatan, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).
Hari itu, ia tengah bertugas di lokasi pengetesan di Puskesmas Cimenteng Sehat, sekitar enam menit berkendara dari Cipageran.
Saat ramai penyebaran varian Delta, ia bisa bekerja selama hampir 24 jam, setiap harinya. Antrean orang-orang berstatus suspek COVID-19 tak putus. Tubuhnya lelah luar biasa, tetapi tak ada yang bisa dilakukan.
“Sampai keluar kata-kata, kayaknya harus positif dulu biar bisa ada waktu istirahat. Kalau enggak, gak mungkin,” kata Moza, menceritakan kembali masa-masa itu pada akhir September 2022.
Harapannya terkabul. Ia terkonfirmasi positif COVID-19 sekitar awal Juli 2021. Beruntung gejala yang ia rasakan ringan. Ia bisa mengambil jeda selama 10 hari untuk memulihkan diri dari lelah dan sakit.
Bagi Moza, periode Delta adalah yang terparah, dibandingkan Alpha dan Omicron. Saat varian Alpha merebak, sekitar Oktober hingga akhir 2020, ia lebih banyak disibukkan dengan kegiatan sosialisasi kepada warga tentang pandemi.
Sementara saat Delta, ia mulai kewalahan dengan pasien yang membludak. Sebagian besarnya mengalami sesak napas. Tabung oksigen langka. Kematian datang silih berganti.
Di titik itu Moza mengalami burnout syndrome yang ditandai dengan kewalahan dan lelah baik fisik, mental, dan emosional. Ia juga mengalami gangguan tidur.
“Karena benar-benar 24 jam itu waktu kita untuk pasien. Sampai kadang saya tidur saja mimpi, tuh. Mimpi nge-tracing pasien saking terus-terusan melakukan tracing, testing,” ujar Moza seraya tertawa mengingat momen tersebut.
Namun kejadian yang memukul jiwanya, ketika pasien yang ditangani meninggal dunia. Perasaan bersalah bercampur kesedihan menyelusup ke batinnya.
“Mau dirujuk, tapi rumah sakit penuh, harus rebutan,” kata Moza.
“Saya nangis-nangis, merasa bersalah.”

Perjuangan menjaga fisik dan kewarasan juga harus dijalani Intan Nila, nakes dengan latar belakang pendidikan gizi, Koordinator Tim 3T di Puskesmas sama dengan Moza, selama masa pandemi. Ia harus banyak-banyak bersabar karena sering menjadi pelampiasan amarah keluarga pasien yang meninggal dunia.
Suatu ketika, ia pernah diancam dilaporkan ke media dan aparat karena menolak membantu menyediakan ambulans puskesmas untuk menjemput salah satu pasien terkonfirmasi COVID-19.
“Katanya puskesmas gak mau bantu, ‘gimana kalau mati…’ Marah-marah di telepon, sampai saya gak bisa berkata-kata. Padahal kita mau bantu cari ambulan yang lain,” kata Intan.
Bukan hanya itu. Ia juga sering dimarahi warga ketika melakukan penelusuran kontak erat berstatus suspek COVID-19.
“Sedih sih. Niat baik kita dianggap apa. Disangkanya kami cuma minta-minta data aja,” kata Intan.
Belum lagi berkali-kali menghadapi pasien dengan kondisi di antara hidup dan mati membuatnya jadi mudah merasa resah, hingga sulit tidur.
Situasi tersebut membuat Intan gampang marah dan melampiaskannya ke adiknya. Padahal, intensitas pertemuannya dengan keluarga sudah sangat berkurang semenjak bertugas di Satgas COVID-19.

Penelitian Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (MKK FKUI) 2020 menunjukkan fakta sebanyak 83% nakes di Indonesia mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat. Secara psikologis, kondisi tersebut berisiko mengganggu kualitas hidup dan produktivitas kerja dalam pelayanan kesehatan.
Selain itu, sebanyak 41% nakes mengalami kelelahan, 22% mengalami kehilangan empati, serta 52% mengalami kurang percaya diri selama pandemi.
Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa dokter umum di Indonesia yang menjalankan tugas pelayanan medis di garda terdepan selama pandemi COVID-19 memiliki risiko dua kali lebih besar mengalami burnout syndrome.
“Tingginya risiko menderita burnout syndrome akibat pajanan stres yang luar biasa berat di fasilitas kesehatan selama pandemi ini dapat mengakibatkan efek jangka panjang terhadap kualitas pelayanan medis karena para nakes ini bisa merasa depresi, kelelahan ekstrim bahkan merasa kurang kompeten dalam menjalankan tugas,” tutur Ketua Tim Peneliti Dewi Soemarko, dikutip dari situs FKUI, Januari 2023.
Menghadapi Stigma dan Trauma
Pandemi COVID-19 menjadi masa-masa yang sulit bukan hanya dalam lingkup profesi tetapi juga kehidupan sosial para nakes.
Ganjar Wisnu Budiman, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bandung mengatakan banyak perawat mendapat stigma dari lingkungan sekitar mereka. Pada beberapa kasus, sejumlah perawat bahkan diusir dari tempat tinggalnya karena warga khawatir tertular.
“Dampak negatifnya stigma masyarakat, kami merawat pasien-pasien COVID-19 di rumah sakit, berjuang untuk kehidupan mereka, tapi di masyarakat malah diperlakukan seperti itu,” kata Ganjar.
“Hal itu yang membuat kami trauma, kenapa sampai seperti itu.”

Hal lain dialami Carissa Wityadarda, seorang nakes di Puskesmas Rusunawa Kota Bandung. Ia mengaku pernah dijauhi oleh teman-temannya saat awal pandemi COVID-19 menjangkit. Kehidupan sosial Carissa, seorang dengan kepribadian ekstrover ini, terganggu.
“Pernah geng saya, mereka renang semua, terus saya dilewatkan. Oh, mungkin memang takut bareng orang yang kerjanya di situ (tim COVID-19),” kata Carissa.
Menurut Carissa teman-temannya sebetulnya tidak perlu khawatir tertular karena selama bertugas, nakes menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. “Padahal mereka lebih berpotensi menularkan ke saya karena prokesnya mereka pasti lebih rendah dibanding saya,” katanya.
Soal penanganan pasien COVID-19, Carissa mengaku tidak ingin terbawa empati terlalu dalam. Carissa berprinsip pekerjaannya harus dijalankan secara profesional. Terlebih menurutnya pandemi tidak terjadi setiap saat dan terus-menerus.
“Kalau saya sih selalu pengin jadi bagian dari sejarah. Maksudnya kapan lagi membantu, menjadi bagian paling depan,” kata Carissa, di salah satu kafe di Bandung, Oktober 2022. “Kalaupun saya gugur saat itu, memang bukan karena covid, tapi karena takdir saya untuk berpulang.”

Data LaporCOVID-19, koalisi sipil yang menjadi wadah pelaporan warga, mencatat sebanyak 2.087 nakes Indonesia meninggal dunia sejak pandemi pertama kali diumumkan pada Maret 2020 hingga 30 Januari 2023.
Dari jumlah tersebut, 751 di antaranya adalah dokter, 670 perawat, dan 398 bidan. Angka kematian tertinggi terjadi pada Juli 2021, saat varian Delta merebak dan menyebabkan lonjakan angka kematian harian tertinggi hingga melebihi 100 ribu nyawa.
Sementara, laporan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) per November 2022, menyebut 755 dokter meninggal dunia karena COVID-19. Kementerian Kesehatan belum pernah merilis data keseluruhan angka kematian nakes secara resmi.
Adapun jumlah kematian nakes tertinggi terjadi di Jawa Timur, disusul Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
***
Sesak yang Membekas
Kematian ibu dan pengalaman sesak napas karena COVID-19, membuat hidup Cahaya tak lagi sama. Hingga kini, Cahaya tidak bisa berlama-lama diam di rumah karena pasti akan teringat almarhumah ibunya.
Setelah keluar dari rumah sakit, Cahaya masih terus melakukan terapi penyembuhan COVID-19. Di rumah, ia masih mengecek saturasi oksigennya dengan oksimetri.
“Tabung oksigen pun gak mau lepas. Saya sewa oksigen tabung besar sama kecil. Pernah yang tabung kecil habis sampai si kakak beli subuh-subuh nyari. Waktu itu saturasi 90 persen. Padahal gak sesak, tapi trauma dengan saturasi rendah,” kata Cahaya.
“Saya kayak orang sakit jiwa.”

Semasa dirawat di rumah sakit, Cahaya pernah dikunjungi oleh psikolog. Namun, hanya sebatas itu. Cahaya tidak melanjutkan pemeriksaan psikisnya karena merasa bisa menanganinya dengan berjalan-jalan bersama teman-teman. Ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya, terlebih ia tidak mengalami gangguan tidur dan makan.
Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran terhadap 200 responden nakes di Jawa Barat selama Mei hingga September 2020, menunjukkan pekerja di rumah sakit rujukan COVID-19 memiliki status kesehatan mental lebih rendah.
Penelitian bertajuk Kesehatan Mental, Kepuasan Kerja, dan Kualitas Hidup Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Sampel Indonesia menemukan profesi dokter lebih rentan mengalami gejala gangguan stres pasca-trauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD) yang lebih parah. Profesi setelahnya adalah perawat, apoteker, spesialis medis, dan asisten laboratorium.
Studi yang dilakukan Aulia Iskandarsyah dkk tersebut menemukan lima kondisi yang memperburuk kondisi psikis para nakes: kekhawatiran menularkan virus ke keluarga terdekat, kematian dan isolasi, tertular virus COVID-19, dan stigma sosial.
Elvine Gunawan, pakar kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Limijati di Bandung mengingatkan trauma yang dialami para nakes karena pandemi tidak bisa diabaikan karena erat berkaitan dengan gangguan stres.
“Kalau dalam enam bulan masa duka dan bersedih belum hilang artinya sudah jatuh ke dalam gangguan sehingga memerlukan bantuan lebih lanjut,” kata Elvine.
“Makan, jalan-jalan, ga akan cukup. [Bila dibiarkan] Berkembang mulai mengganggu kualitas hidup dan perawatan diri, lalu berkembang lagi dengan masalah relasi, dan ujungnya gangguan produktivitas.”
*Cahaya adalah nama samaran.
Laporan ini adalah bagian dari serial reportase #KamiSesakNapas.