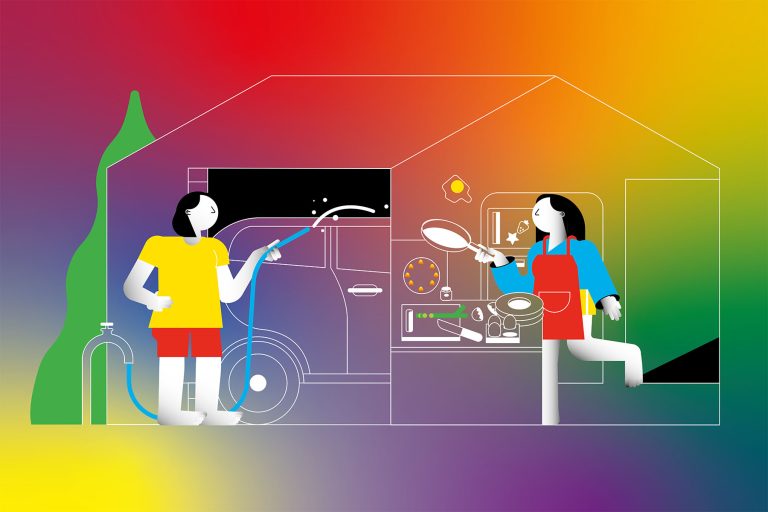I — BERKAT
Sudah dua minggu ini Berkat tidak leluasa menggerakkan badan. Punggung dan pundaknya sakit. Ia tak bisa menolehkan kepala. Ini bukan sakit tua. Usia Berkat masih 26 tahun. Ia yakin sakitnya karena mengangkat berkarung-karung pakan ternak babi berbobot sekitar 50 kg per karung.
“Sehari harus selesai 60 ton,” katanya.
Berkat mengambil tawaran kerja itu setelah 1,5 tahun menganggur. Ia pikir tak ada salahnya mencoba bekerja di bidang baru.
“Itu kayak usaha rumahan. Semua proses dikerjakan manual. Ngangkut bahan, nyampur, ngemas, angkut lagi ke truk untuk dijual. Ada mesin tapi tetep aja kita awasin,” katanya.
Berkat hanya kuat bekerja sehari.
Ia bilang para pekerja di sana terbiasa mengonsumsi minuman berenergi dan jenis suplemen lain agar kuat bekerja keras dari pagi hingga malam. Bagi Berkat, itu tidak masuk akal. Ia tidak mau merusak badan. Jika itu terjadi, tidak terbayang bagaimana ia bisa menghidupi ibu, bapak dan adiknya, sebab ia yang diandalkan untuk menafkahi mereka.
Di rumah, Berkat mesti menjaga adik dan ibu yang kondisinya belum benar-benar pulih setelah terdiagnosis tuberkulosis (TBC) pada 2021.
Salah satu rutinitas harian Berkat selama menganggur adalah mengantar adiknya, Iman, ke Puskesmas untuk disuntik. “Sudah nggak mempan kalau pakai obat doang.”
Bila tidak diantar, kecil kemungkinan Iman datang ke Puskesmas meski lokasinya dekat dari rumah mereka di Kampung Tongkol, Jakarta Utara. “Pernah saya suruh berangkat sendiri. Kasih motor. Eh, malah nggak tahu dia kabur ke mana. Bandel!”
Berkat tahu Iman kabur karena petugas Puskesmas pasti datang ke rumah bila adiknya ogah-ogahan berobat.
Tidak ada seorang pun menyangka Iman bakal terserang penyakit cukup serius. Berkat bercerita, ia sempat prihatin melihat tubuh Iman semakin kurus. Bobot tubuh adiknya turun puluhan kilogram. Nyaris tanpa daging.
Ia membawa Iman ke Puskesmas setelah melihat tubuh adiknya begitu lemas, tidak bisa beraktivitas normal, dan batuknya memburuk. Satu hal yang membuat Berkat sedikit lega: semua pengobatan ditanggung pemerintah. Katanya, pelayanan dari Puskesmas cukup baik. Puskesmas memberi banyak obat, tugas Berkat harus memastikan adiknya menenggak sekitar 12 butir obat setiap hari.
Masalah tidak selesai di situ. Ibunya tertular TBC. Kondisinya lebih tidak stabil dibandingkan Iman. Sang ibu sempat dirawat beberapa minggu di rumah sakit.
“Repot banget waktu itu COVID-19 lagi naik. Nggak bisa gantian jaga sama bapak,” kata Berkat.
Sepulang dari rumah sakit, kondisi ibunya tak kunjung membaik. Kakinya lumpuh. Entah apa penyebabnya. “Katanya sih ‘diisengin’ orang.”
Berkat tak sanggup bila harus menjaga dua orang sakit. Maka, diputuskan ayahnya harus berhenti bekerja agar mereka bisa berbagi tugas.
Berkat bersyukur saat ini kebutuhan primer keluarga masih bisa terpenuhi. Katanya, saudara-saudara yang tinggal berdekatan dengannya suka membantu.
Rumah Berkat bersebelahan dengan rumah para paman dan bibinya. Rumah mereka merupakan salah satu proyek percontohan penataan kampung Tongkol pada 2015. Pada masa itu, Pemprov DKI Jakarta berencana menggusur permukiman di Kampung Tongkol. Kemudian, warga dan komunitas Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta bergerak menata ulang kawasan itu dan bernegosiasi untuk tidak menggusur permukiman.
Jalan tengahnya, area rumah warga “dipotong” lima meter agar tak terlalu dekat dengan sungai. Jalan aspal dibangun; model rumah ditata ulang dengan material dan bentuk baru.
“Tadinya kali rata sama rumah. Orang buang air di kali seenaknya. Banjir setiap lima tahun. Sekarang udah nggak,” lanjut Berkat.
Kami berbincang di bawah pohon rindang yang membuat sengatan sinar matahari siang terasa hangat dan nyaman di badan. Suara dedaunan tertiup angin bikin sejenak lupa bahwa kami ada di Jakarta yang bising. Tempat kami duduk tadinya hunian bantaran kali.
“Tiap hari gini-gini ajalah, nggak ngapa-ngapain,” kata Berkat, memecah hening. “Paling nanya-nanya teman info kerjaan.”
Kini Berkat menghabiskan banyak waktu di rumah. Berkat dan Iman berbagi kamar di lantai dua rumah mereka. Di ruang itu Berkat tidur di atas kasur kapuk di atas lantai. Mungkin Berkat begitu sering ada di kasur itu sampai-sampai tercetak lekuk tubuhnya di kasur itu.
Bila ditotal, Berkat sudah bekerja selama 14 tahun. Pada usia 12, pekerjaan pertamanya sebagai pengemas kaset bajakan di kawasan Glodok. Waktu itu ia masih SMP, tapi memutuskan berhenti sekolah karena harus membantu kebutuhan finansial keluarga. Tidak mungkin mengandalkan upah ayahnya yang dulu bekerja sebagai kernet truk.
Gaji pertama Berkat Rp50 ribu/hari, dipakai untuk kebutuhan rumah sementara sisanya untuk membeli rokok. Pada masa itu, Berkat sempat nyambi bekerja sebagai buruh angkut.
Beberapa tahun kemudian, Berkat pindah kerja di perusahaan jasa angkut barang. Ia juga pernah bekerja kernet truk seperti ayahnya. Upahnya sekali jalan saat itu Rp150 ribu.
“Lumayan banget bisa kirim ke rumah Rp500 ribu-Rp600 ribu.”
Setelah itu ia pindah kerja demi gaji lebih tinggi. Ia kembali bekerja di perusahaan ekspedisi. “Langsung ambil (beli) motor. Umur saya udah 17 tahun saat itu.”
Kini motor itu ibarat kenang-kenangan berharga hasil kerjanya ke sana kemari. Kenangan berharga lain: ia berhasil melunasi cicilan biaya renovasi rumah. Ia bangga dengan pencapaian ini, meski kini tak sepenuhnya bahagia karena belum tahu kapan bisa mendapatkan pekerjaan lagi.
Pekerjaan terakhirnya adalah petugas kebersihan atau biasa disebut “pasukan oranye”. Statusnya pekerja kontrak.
“Tolong dicariin kerjaan dia,” teriak bibi Berkat dari seberang jalan sambil menyimpul tali untuk dibuat gelang. Pekerjaan menganyam gelang ini kerap dilakukan para ibu, termasuk ibu Berkat, di Kampung Tongkol, dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per minggu. Sesekali Berkat membantunya selagi masih mencari kerja lain.
Berkat merasa sekarang susah mendapatkan pekerjaan, tidak semudah dulu, karena “apa-apa sekarang serba teknologi.” Sementara, tambahnya dengan nada kesal, “pendidikan saya terbatas.”

II — BAPUL
“Takut diambil sama yang lain,” kata Bapul, 18 tahun, mengenai alasannya ingin cepat menikah.
Rencana menikah muncul pada hari ketiga pacaran. Saat kami bertemu, Bapul baru mengenal pacarnya selama seminggu. Perkenalan via Facebook.
“Halo, ini siapa? Boleh kenalan nggak?” Bapul tersipu malu mengulangi kalimat pertama dari perempuan yang kini jadi pacarnya. Wajah Bapul terus berseri tiap mengingat pertemuan kedua dengan si pacar.
Bapul menunjukkan foto wajah pacarnya via layar ponselnya yang retak dan redup. Ponsel itu rusak setelah dibanting karena kalah bertarung permainan Mobile Legend.
Ponsel itu belum lama kembali ke tangan Bapul setelah sekian lama ada di konter ponsel. “Habis diservis ini,” katanya. Kondisi ponselnya dililit lakban hitam.
Bapul menyebutnya sebagai ponsel jelek yang dibelinya dari hasil bekerja konveksi. Meskipun buruk, ponsel itu pernah berjasa. Dulu, Bapul pernah menyewakan ponsel ke teman-temannya. Biaya sewa Rp5000 per jam. Dipakai untuk main gim. Dalam sehari, Bapul bisa mendapatkan Rp25 ribu. Ini disebutnya sumber penghasilan sampingan.
Bapul tidak ingat persis kapan mulai bekerja di perusahaan konveksi; yang masih bisa ia ingat adalah keputusan tidak meneruskan sekolah setelah sekolah dasar. Orangtua Bapul membiarkan keputusan ini. Kakak Bapul juga lulusan SD.
Satu hari, saat kelas enam SD, Bapul melihat kakak temannya bekerja sebagai kurir. Ia minta si teman mencari tahu cara agar bisa menjadi kurir. Tapi, pekerjaan ini mustahil dilakukan karena usia Bapul terlalu muda. Ia belum bisa mengendarai motor. Meski demikian, kakak temannya bilang Bapul bisa jadi petugas pengemas barang di kantornya, sebuah perusahaan e-commerce. Ternyata perusahaan ini tidak melarang pekerja anak. Bapul diterima bekerja sebagai petugas pengemas barang. Kerja harian.
Maka, Bapul bekerja dari jam 8 pagi sampai 5 petang, dengan upah Rp75 ribu/hari. Uang ini dipakainya untuk membeli rokok, membayar cicilan ponsel pertama (yang kini hilang dan sudah diganti dengan “ponsel jelek”). Tapi ia hanya tahan bekerja dua pekan. “Bos galak banget. Kalau bungkus nggak rapi dikit, dimarahin.”
Setelah itu, Bapul pindah kerja ke perusahaan konveksi, usaha rumahan bordir di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tugasnya menjahit logo berbagai model baju, dari baju anak hingga dewasa. Jam kerjanya dari 7 pagi hingga 9 malam; upahnya Rp430 ribu setiap pekan.
“Buat bayar utang warung, utang warteg, ngasih Ibu. Paling sisa Rp50 ribu atau Rp100 ribu buat (beli) paketan (internet),” katanya.
Penghasilan ayah Bapul sebagai penarik becak tak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk keperluan bapaknya membeli rokok. Akhirnya, Bapul bertugas melunasi tunggakan-tunggakan belanja rokok di warung langganan.
Ibu Bapul adalah ibu rumah tangga. Bila ada uang lebih, ia berjualan mi instan dan minuman kemasan di depan rumah. “Dulu Indomie, lalu mie Sakura yang murahan. Sekarang nggak jualan. Modalnya habis,” ujar Bapul.
Bapul sering tidak bisa tidur nyenyak. “Saya nggak bisa tidur ngebayangin disamperin orang nagih utang. Pusing!”
Utang yang harus dilunasinya bukan cuma utang rokok bapaknya, tapi juga utang ongkos main. Ada kalanya Bapul main bareng teman-teman ke tempat agak jauh dari rumah. Kawasan Dukuh Atas, contohnya. Ada kala ia perlu ngapel ke tempat pacarnya di Jakarta Timur. Untuk perjalanan jauh ini, Bapul perlu ongkos tambahan.
“Biasanya minjem saudara. Gocap (Rp50 ribu) atau pego (Rp150 ribu).”
Rasa pusing bisa hilang sebentar saat ia bermain. Setelah bekerja, Bapul berkumpul bersama para tetangga yang masih sepantaran. Kebanyakan teman Bapul masih sekolah. Mereka biasa nongkrong hingga subuh di trotoar depan bangunan sekolah.
Di situlah mereka bermain gim online, bernyanyi, berselancar media sosial, bertaruh slot judi online. Ponsel mereka terhubung dengan Wifi sekolah. Kadang mereka ditegur Ketua RW agar jangan berisik pas tengah malam.
“Sekarang udah jarang dan nggak main (slot judi online). Duitnya nggak ada,” kata Bapul. “Cuma pernah menang gopek (Rp500) doang. Buat bayar utang.”
Sekarang Bapul sedang kasmaran. Ia tak punya keinginan apa-apa selain cepat menikah.
Mendengar keinginan itu, otot-otot wajah Ibu Bapul langsung kaku. “Enggak! Masih kecil,” kata ibunya.
Bapul tertunduk melihat ponsel setelah mendengar perkataan ibunya.
Underprivileged Gen Z Ibu Kota: Hidup Miskin, Woke, dan Punya Gangguan Mental
* * *
Berkat dan Bapul, dan mereka yang sepantaran dan senasib dengannya, adalah bagian dari Generasi Z, sebutan bagi mereka yang lahir pada 1996-2010.
Realitas Berkat dan Bapul sangat bertolak belakang dengan representasi Gen Z yang dicitrakan di media sosial. Berkat dan Bapul dilupakan dalam riset pasar Gen Z.
Publik lebih familiar akan citra Gen Z yang melek pendidikan, pengetahuan, dan teknologi, demikian hasil riset-riset terbuka maupun yang dinyatakan pejabat pemerintah.
Salah satu contohnya riset pasar dari UMN Consulting, yang menjelaskan bahwa para responden, mayoritas usia SMA dan kuliah, menyadari diri sebagai Gen Z. Riset ini menyimpulkan Gen Z masih bergantung pada orangtua; ingin memiliki karier gemilang, tinggal di rumah layak, memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia; mengisi waktu luang di mal dan kedai kopi, serta hobi mencoba kuliner baru.
Contoh potret Gen Z berikutnya adalah generasi yang percaya diri, demikian riset dari Tim Penelitian Pusat Karier di Universitas Andalas dan Tanoto Foundation. Riset ini menyebut rasa percaya diri tinggi membuat Gen Z mampu mendapatkan pekerjaan idaman meski persaingan kerja semakin ketat; mereka percaya memiliki pengalaman relevan dengan bidang pekerjaan, keterampilan sesuai kebutuhan industri, dan bisa melalui sesi wawancara kerja dengan baik.

Kenyataannya, banyak Gen Z berada di luar kategori di atas. Para Gen Z di kampung kota Jakarta adalah cerminan dari berbagai permasalahan struktural.
Di ibu kota masih ditemukan anak-anak putus sekolah, yang langsung menjadi bagian dari angkatan kerja. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut pada 2020-2021, ada 181 anak SD putus sekolah; jenjang SMP ada 126 anak; SMA ada 24 anak; SMK ada 92 anak.
Total di Indonesia sepanjang 2020-2021, ada 14.430 anak putus sekolah dasar; 7.417 anak putus sekolah menengah pertama; 4.780 anak putus sekolah menengah atas; dan 5.620 anak putus sekolah menengah kejuruan.
Tim Litbang Kompas pernah menelusuri penyebab anak putus sekolah, di antaranya merawat atau menjaga adik; menikah; orangtua berpikir menghentikan pendidikan anak; tidak ada pemantauan dari guru, kepala sekolah atau pemerintah desa.
Putus sekolah pada usia dini membuka pintu permasalahan berikutnya: pekerja anak.
Berkat dan Bapul adalah contoh nyata. Keduanya putus sekolah, lalu terpaksa bekerja layaknya orang dewasa sejak masih usia anak-anak. Topik pekerja anak kerap jadi perbincangan tapi jarang jadi perhatian.
Data KPPA pada 2020 menyebut lebih dari separuh pekerja anak bekerja lebih dari 15 jam per minggu; yang seharusnya mereka tidak boleh bekerja lebih dari tiga jam dalam sehari.
“Menurut aturan, anak tidak boleh bekerja dalam situasi membahayakan mereka. Anak juga tetap bisa mendapatkan hak pendidikan,” kata Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Namun, aturan semacam ini lebih banyak diabaikan. Retno meyakini jumlah pekerja anak lebih banyak ketimbang yang tercatat pemerintah karena mayoritas pekerja anak bekerja di sektor informal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mempublikasikan Profil Anak Indonesia Tahun 2021. Dokumen ini menyebut persentase pekerja anak di DKI Jakarta di bawah rata-rata. Jumlah tertinggi pekerja anak ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sejak 2015-2017, jumlah anak usia 10-17 tahun meningkat menjadi 7,23%. Jumlah ini turun pada 2018-2019 (6,35%), tapi kembali meningkat drastis pada 2020 menjadi 9,34% karena kemiskinan Indonesia memburuk, menurut KPPA.
Masalah putus sekolah, pekerja anak, hingga kemiskinan berkelindan bak lingkaran setan. Kondisi inilah yang menjerat Bapul dan Berkat sejak anak-anak hingga akhirnya menjadi bagian dari Gen Z, tapi bukan Gen Z yang ingin dicitrakan pemerintah dan para pemangku pasar.
III — TAKWA
Tidak semua ibu langsung mengekspresikan kegembiraan saat berjumpa dengan anak bungsunya yang kembali pulang usai beberapa hari menghilang.
Ipah, ibu Takwa, seketika marah melihat anaknya. “Begitu kelakuannya. Pulang pergi suka-suka dia. Dipikir orang tua nggak khawatir?”
Nada tinggi suara Ipah mengalahkan suara mesin kendaraan lalu-lalang di atas tempat kami berbincang. Amarah Ipah menarik perhatian beberapa tetangga untuk mendekat.
Takwa duduk menunduk. Semua mata tertuju pada Takwa dan Ipah yang duduk bersebelahan.
Ipah masih mengeluarkan keluh kesah. Takwa semakin jarang pulang setelah mengamen di jalan; Takwa bisa-bisa ditangkap lagi dan mengalami penyiksaan di tempat tahanan sementara.
Keduanya tak bisa saling berkabar karena keduanya tak punya ponsel.
Ipah tinggal di kolong jalan tol. Pintu tempat tinggal mereka tak pernah terkunci. Bila didorong sedikit, orang bisa melihat ruangan dengan dua buah kasur berdempetan, beberapa kipas angin menempel dinding tripleks, beberapa stop kontak, penanak nasi di samping pintu. Tidak ada ruang untuk berjalan; tidak ada lemari menyimpan barang.
“Namanya tinggal di tempat kayak gini ya rentan dicolong kalau nggak hati-hati banget jagain,” kata Ipah.
Ada empat orang tinggal di sana. Ipah dan Takwa dan keponakan Takwa yang masih anak-anak dan balita. Setiap bulan keluarga ini harus mengumpulkan Rp300 ribu untuk membayar biaya sewa tempat tinggal.

Takwa dan Ipah sama-sama bekerja sebagai pengamen. “Saya jalan setiap hari, biasanya sore sampai malem. Bawa ini (menepuk balita di gendongan).”
Sebagian uang mengamen untuk melunasi biaya kontrakan. Sebagian lagi untuk biaya keperluan mandi, cuci dan kakus, serta makan.
Ipah berkata hidupnya semakin sulit setelah ayah Takwa meninggalkan dia dan anak-anak. Dan, katanya, mustahil ia bisa membiayai keperluan sekolah Takwa. Letak sekolah negeri jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Selain itu, ia tidak mengerti caranya bisa mendapatkan bantuan pemerintah.
Takwa hanya menuntaskan jenjang pendidikan dasar. Usianya saat ini 14 tahun.
Saya dan Takwa sempat sebentar mengobrol ketika Ipah menjauhi kami untuk membeli rokok dan menghibur cucu balita di gendongannya.
Takwa bercerita menikmati pergi naik kereta ke Bogor dan mencari uang di sana bersama teman-teman. Seorang temannya biasa menyewa speaker untuk mengamen keliling.
“Kalau ke Bogor bisa dapat duit agak banyak, Rp100 ribu-Rp200 ribu,” kata Takwa. Selesai mengamen, ia lebih suka tidur di tempat teman.
Ia bilang, uang mengamen itu kadang diberikan ke ibunya, kadang dipakai sendiri, sebagian untuk patungan biaya sound system, makan, minum, dan rokok.
Saat masih sekolah, Takwa pernah bercita-cita menjadi dokter, kini berubah menjadi pekerja di bengkel, katanya lebih realistis.
Ipah kembali mendekati kami dan terlihat gusar melihat anaknya berbincang dengan saya. Takwa kembali terdiam.
Saya dan Takwa sepekat bertemu di lain hari tanpa sepengetahuan Ipah.
Di hari seharusnya kami bertemu, Takwa tak kunjung tiba. Saya mencarinya ke rumah, ke lokasi tempat tinggalnya di balik truk-truk dan timbunan karung-karung plastik dan sampah.
Beberapa warga sekitar, salah satunya ternyata kakak Takwa, menanyakan siapa yang saya cari. Jawaban mereka sama: “Dia mah susah, jarang pulang.”
Takwa hari ini mungkin sudah terjebak dalam jejak pahit Gen Z yang pernah dan sampai sekarang dijalani Bapul dan Berkat: Putus sekolah, jadi pekerja anak, terjerat kemiskinan.
Berkat, Bapul, dan Takwa bukan nama sebenarnya. Irma Garnesia membantu riset data dalam tulisan ini.
Laporan ini adalah bagian dari serial reportase #UnderprivilegedGenZ. Serial ini didukung oleh Kawan M.