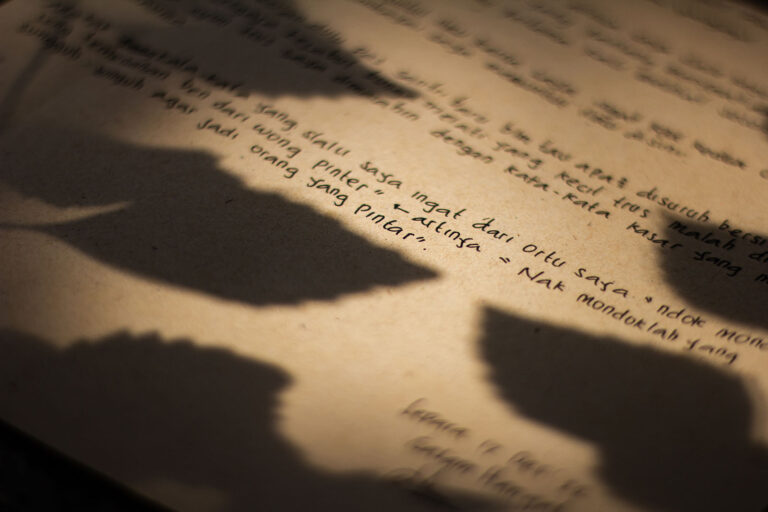Perampasan tanah ulayat, pemaksaan agama dan kepercayaan, eksklusi sosial, hingga pemiskinan dan kelaparan yang mematikan: itulah kisah-kisah suram yang kerap kita dengar tentang masyarakat adat. Selama ratusan tahun, secara sistematis, silih berganti penguasa telah meminggirkan masyarakat adat Nusantara, pertama-tama dengan propaganda bahwa mereka adalah kaum terbelakang yang perlu dijadikan modern.
Padahal masyarakat adat menyimpan sejarah panjang pengetahuan yang menjadi fondasi dari keberagaman budaya Nusantara.
Ketika manusia saat ini menghadapi kombinasi krisis iklim dan kemanusiaan, masyarakat adat justru memiliki ketangguhan, kearifan, dan siasat yang bisa menawarkan solusi dan kritik atas resep pembangunan yang abai terhadap lingkungan hidup.Click To TweetProject Multatuli, yang diluncurkan di minggu ketiga Mei 2021, memulai karya jurnalisme kami dengan serial reportase tentang masyarakat adat. Serial reportase ini bertujuan membuka fakta-fakta tentang situasi masyarakat adat di Indonesia saat ini, sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk bersuara. Tema liputannya, mulai dari soal pandemi, kedaulatan dan krisis pangan, perempuan di masyarakat adat, gerakan anak muda adat, lingkungan, hingga konflik tanah dengan perusahaan atau pemerintah. Peliputan ini bukan hanya menampilkan masalah yang menghimpit mereka, namun juga berupaya menampilkan pengetahuan lokal, kebijakan, dan solusi mereka terhadap berbagai masalah yang kita hadapi saat ini, termasuk di kala pandemi.
Ruang Hidup Menyempit
Konflik seputar ruang hidup masyarakat adat menjadi perhatian kami, karena peristiwa-peristiwa ini terus terjadi.
Pada 26 Agustus 2020, siang, petugas kepolisian datang ke rumah Ketua Adat Komunitas Laman Kinipan di Lamandau, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing. Polisi kemudian menangkap Effendi atas tuduhan pencurian alat milik perusahaan sawit, PT Sawit Mandiri Lestari, perusahaan yang telah lama berkonflik lahan dengan Komunitas Adat Kinipan.
Video penyeretan Effendi oleh tiga polisi, yang diiringi teriakan keberatan dari istri ketua adat itu, mengundang kemarahan publik. Effendi akhirnya dilepas, namun konflik antara masyarakat adat Laman Kinipan yang mempertahankan hutan ulayat mereka dengan perusahaan sawit tidak berhenti di situ.
Kasus Laman Kinipan ini juga hanya puncak gunung es, dari sederet konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang didukung oleh negara. Laporan Perkumpulan Huma Indonesia, mayoritas dari total 326 konflik sumber daya alam dan agraria pada tahun 2018 terkait dengan masyarakat adat. Dari sengketa yang melibatkan areal seluas 2.101.858 hektare dengan korban total mencapai 186.631 jiwa itu, sebanyak 176.637 di antaranya berasal dari masyarakat adat.
Masyarakat adat telah ada di negeri ini sebelum terbentuknya Indonesia. Mereka hidup di wilayah ulayat masing-masing dan mengembangkan jalan pangan yang adaptif terhadap lingkungan spesifik.
Mereka adalah penjaga alam dan fondasi dari keberagaman kebudayaan kita. Namun, keberadaan mereka semakin terpinggirkan, bahkan sebagian telah hilang, karena model pembangunan kita yang mengizinkan perampasan hak ulayat dan sumber daya alam yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.Click To TweetProgram Merendahkan Masyarakat Adat
Ketegangan antara adat dan negara terus berlanjut setelah terbentuknya Indonesia, di antaranya dengan peninjauan aliran kepercayaan di masyarakat. Dengan aturan ini, kelompok masyarakat adat yang tidak berafiliasi dengan agama yang diakui negara tidak mendapat hak kewarganegaraan.
Di masa Orde Baru, penyangkalan dan peminggiran terhadap hak masyarakat adat ini ditutupi dengan narasi pembangunan yang di awal Orde Baru berfokus pada empat isu sentral yaitu pertumbuhan, akumulasi kapital, transformasi struktural, dan peran pemerintah. Tak hanya penyangkalan terhadap hak atas tanah dan sumber daya, pada era ini, masyarakat adat bahkan dianggap sebagai masalah sosial yang harus diatasi. Mereka dianggap sebagai penghambat kemajuan dan modernitas. Sejarah, tradisi, dan pengetahuan masyarakat adat tidak diakui negara, bahkan diberangus dengan dalih persatuan, keseragaman, dan kesesuaian.
Stigmatisasi masyarakat adat sebagai masalah sosial itu tercermin dalam buku yang menjadi pegangan Kementerian Sosial, Sistem Pelayanan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (1981). Untuk mengatasi “masalah sosial” ini pemerintah membuat berbagai program pembangunan, di antaranya Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT).
Sekalipun terus berevolusi, namun hingga saat ini peminggiran masyarakat adat masih tercermin dalam definisi yang dibuat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mereka mendefinisikan masyarakat adat sebagai sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Mereka menyebutnya sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Konsep tentang kesejahteraan itu dirumuskan dan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah dengan berbagai indikator yang cenderung merendahkan jalan hidup masyarakat adat. Misalnya, mereka yang hidup nomaden sebagai pemburu dan peramu seperti Punan di Kalimantan, Orang Rimba di Jambi dan Sakai di Riau, dianggap tak berbudaya. Mereka yang mempraktikan perladangan secara berotasi seperti berbagai etnis Dayak di Kalimantan dianggap sebagai perusak hutan.
Untuk mengatasi “masalah sosial” ini, pemerintah Indonesia membuat proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT), dulu PMT. Merumahkan masyarakat adat ini dianggap sebagai pintu masuk untuk “membudayakan” mereka. Karena itu, indikator lain dari kesuksesan PKMT—selain merumahkan—adalah jumlah warga yang memeluk agama resmi yang diakui pemerintah dan berbagai indikator lain yang ditentukan oleh pemerintah.
Sebuah buku bacaan untuk anak sekolah dasar, yang diterbitkan pada 2018 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, misalnya menyebut bahwa keputusan seorang warga komunitas adat untuk ikut PKMT sebagai keputusan yang cerdas.
Bah Langai, bapakku, orang Sakai yang ikut program pemerintah PMT atau Pemukiman Masyarakat Terasing. Alhamdulillah, bapakku orang yang pandai mendengar dan menurut apa yang dikatakan pemerintah.Click To TweetKatanya, kalau orang mau maju, mau tidak tertinggal, harus rajin berladang. Jangan hidup berpindah-pindah di hutan,” demikian dua penggal kalimat di buku tersebut.
Sebagaimana terjadi sejak era kolonial, peminggiran budaya, kepercayaan dan ruang hidup ini kemudian diikuti dengan penguasaan sumber daya alam. Hutan-hutan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal masyarakat adat kemudian diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada perusahaan untuk dieksploitasi, sebagaimana terjadi di Kalimantan dan Sumatera sejak akhir 1960-an, dan belakangan di Papua serta di berbagai pulau lain. Inilah yang kemudian menjadi sumber utama berbagai konflik agraria di Indonesia.
Dampaknya, bukan hanya pemiskinan masyarakat adat, namun kehancuran lingkungan secara masif, yang menghadapkan kita dengan krisis iklim dan krisis kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi langganan tiap tahun, selain banjir besar yang melanda Kalimantan pada awal tahun 2021 menjadi indikator nyata dari merosotnya daya dukung lingkungan karena salah tata kelola.
Tak hanya menyimpan pengetahuan lokal untuk kebaikan mereka sendiri, masyarakat adat ternyata berperan penting dalam menjaga keberagaman hayati di Bumi yang kini mengalami tekanan hebat. Meskipun 370 juta masyarakat adat di dunia berjumlah kurang dari 5 persen dari total populasi manusia, mereka mengelola lebih dari 25 persen permukaan tanah dunia dan melindungi sekitar 80 persen keanekaragaman hayati global.
Maka, pengambilalihan sumber daya alam dari tangan masyarakat adat seperti menyingkirkan penjaga terakhir atas kelestarian alam. Melindungi masyarakat adat dan hak-hak ulayat mereka berarti juga melindungi keberagaman hayati yang menghidupi Bumi.
Perubahan Jalan Pangan
Seperti dikemukakan Kementerian Sosial dengan KAT-nya, masyarakat adat di Indonesia saat ini memang identik dengan keterbelakangan, kemiskinan, bahkan juga kelaparan. Pada 2018 masyarakat di pedalaman Asmat mengalami gizi buruk yang menyebabkan 72 anak meninggal. Pada awal Juli 2018 sekitar 170 orang warga suku Mausu Ane di Pulau Seram, Maluku Tengah kekurangan pangan dan tiga orang di antaranya meninggal dunia. Sebelumnya pada Maret tahun 2015, sedikitnya 11 Orang Rimba di Jambi meninggal dalam enam bulan. Kematian beruntun itu terjadi pada rombong (kelompok) Terap dan Serenggam yang beranggota sekitar 150 orang. Mereka hidup nomaden di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun. Orang Rimba yang meninggal itu umumnya memiliki gejala batuk dan demam. Sekitar 60 warga lainnya, sebagian besar anak balita, memiliki gejala serupa.

Kajian Ahmad Arif dalam buku Masyarakat Adat & Kedaulatan Pangan menunjukkan, masyarakat adat yang masih menjalankan sistem pangan tradisional, yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, cenderung lebih berdaulat. Mereka mampu memenuhi kecukupan pangan dan memiliki kualitas nutrisi lebih baik dibandingkan yang telah beralih ke sistem pangan modern yang berorientasi pada pasar. Contohnya, masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dan masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Sebaliknya, masyarakat adat yang dipaksa mengubah jalan pangannya justru mengalami kerentanan pangan. Selain terjadi di Asmat, Papua, fenomena ini juga terjadi di Kasepuhan Cilebang, Kabupaten Lebak, Banten dan Desa Meorumba dan Mauramba di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Kebijakan pangan di Indonesia seharusnya memperhitungkan keberagaman karakteristik masyarakat dengan menjadikan kedaulatan pangan yang berbasis pada keragaman budidaya tanaman pangan lokal sesuai konteks ekoregionnya sebagai indikator keberhasilan. Hak masyarakat adat terhadap pangan ini tidak bisa dipisahkan terhadap hak mereka terhadap lahan, teritori, sumber daya alam, dan kedaulatan diri.
Meliput Masyarakat Adat
Serial reportase masyarakat adat Project Multatuli, yang direncanakan akan berjalan paling tidak selama satu tahun, mengupayakan ruang bicara bagi masyarakat adat. Kami menyediakan diri untuk melayani mereka dan memastikan suara mereka didengar.
Dengan reportase jangka panjang ini kami berkeinginan menyediakan narasi untuk menandingi yang selama ini dominan, bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang perlu diubah alam pikirnya demi kemajuan pembangunan.Click To TweetKami ingin mencari tahu apa yang terjadi di kampung-kampung mereka dan mencatat serta mengabarkan ketangguhan, siasat, dan kearifan mereka dalam menghadapi masalah demi masalah, termasuk pandemi Covid-19.
Ketika kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan dan lingkungan, sesekali kita perlu melihat ke dalam dan belajar dari masyarakat adat. Kami yakin mereka bisa membuka mata kita dan membantu kita merenungi lagi hubungan kita dengan Bumi.
Tulisan ini adalah bagian dari serial reportasi #MasyarakatAdat dan Lingkungan Hidup.